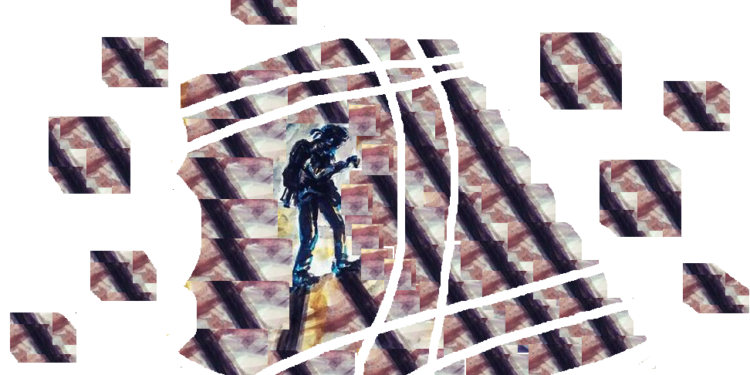Saya menerima sepotong surat dari Mama pada suatu hari Minggu
Setelah subuh menjemput tubuh yang pasrah di ruang rindu
Isinya demikian:
“Nak, jika kau merindu, pergilah ke sudut kapel.
Temui Mama di sana dan duduklah dekat kaki Bunda.
Kita bisa bercerita dari hati ke hati
Dalam hening dan beningnya doamu.”
Salam dari keabadian.
***
INI tentang kehilangan, suatu perihal mengikhlaskan. Tak sedikit orang mengatakan “Tingkatan tertinggi dari mencintai seseorang adalah mengikhlaskan ia pergi.”
Lebih baik ia pergi daripada disakiti berulang-ulang kali. Maka, teriring doa yang tak pernah lapus, semoga setiap air mata yang pernah jatuh dari mata lelahmu demi aku dan orang yang kau cintai, Mama, menjadi sungai untukmu di surga.
***
Pukul 12.00 Wita, sebelas jam sebelum peristiwa kehilangan.
“Halo, Kaka di mana?” Telepon dari adik perempuanku.
“Masih di Mataloko, Nona, baru saja selesai urus ijazah. Nona apa kabar?”
“Kapan pulang? Kaka cepat pul…”
Belum juga menjawab pertanyaan singkatku, aku malah kembali diserang sebuah pertanyaan, beriringan dengan sepenggal kalimat yang tidak ingin diteruskan. “Sudahlah mungkin ia hanya sekadar bertanya kabar atau telanjur rindu pada kakaknya ini,” timpalku dalam hati.
“Besok saya pulang.”
“Oke, Kaka.”
“Ya, Nona, salam bu…”
Aku hendak menyampaikan salam buat Mama, tetapi telepon lebih dulu dimatikannya. “Anak ini, apa dia tidak tahu sopan santun!” ungkapku kesal.
Udara Mataloko selalu sama. Dingin tetapi selalu bikin kangen. Aku menyusuri lorong-lorong sepi itu sendirian, sambil kutarik nafas dalam-dalam, menikmati udara yang bertiup dari Bukit Sasa. Dan beberapa menit kemudian, aku melewati pekuburan yang letaknya tepat di belakang kapela agung St. Alfonsus Maria de Ligouri.
Aku berhenti sejenak memandang makam para imam. Lantas aku teringat pada Bapak. Aku membayangi wajah Bapak yang meninggal setahun lalu karena sakit.
Kabut perlahan-lahan menutupi sebagian pekuburan, dan aku pun beranjak pergi. Aku sendiri heran mengapa wajah Bapak terlintas dalam benakku. “Ah… sudahlah. Toh nantinya, setiap orang pun akan menemukan ajalnya masing-masing. Siapakah yang mampu luput dari kematian?”
Tak lama berselang, handphone-ku berdering lagi, beberapa menit setelah berusaha mencerna pertanyaan tadi.
“Halo,..”
Lagi-lagi pembicaraanku dipotong. Aku sedikit kesal. “Untung saja kau adik perempuanku satu-satunya,” gumamku ngawur.
“Kaka harus pulang hari ini. Mama sakit lagi. Mama makin kritis.”
Bibirku dingin terbius kaku. Tak pernah kusangka Mama sakit lagi. Padahal beberapa hari lalu, sebelum aku ke Mataloko Mama masih sehat-sehat. Malam sebelum berangkat pun Mama sempat berpesan, “Hati-hati di jalan. Jangan tunda-tunda lagi urus ijazah biar studi aman dan lancar.”
Apa artinya pesan ini, toh semua ibu pasti akan memberikan pesan yang sama jika anaknya bepergian jauh. Namun, ketika aku mengabaikan pesan mama, aku justru terjebak dalam kesalahan dan rasa penyesalan yang tak bertepi. Siapa sangka, itulah suara sekaligus pesan terakhir yang keluar dari mulut Mama sebelum peristiwa kehilangan.
Pukul 23.00 Wita, tentang kepergian dan mengikhlaskan
Senja perlahan-lahan ditelan malam. Mega merah di ufuk barat sedikit lagi lenyap. Induk ayam dan anak-anaknya sudah sedari tadi naik ke sangkar. Pukul 19.00, suasana di rumah kolong benar-benar sepi, yang terdengar hanyalah tangisan Mama karena menahan sakit.
Semenjak melahirkan adik kembarku, Mama sering sakit-sakitan. Sampai pada akhirnya sebulan sebelum kepergiannya, Mama divonis dokter mengalami gagal ginjal. Ah, Tuhan, hati ini terlalu sakit melihat orang tercinta harus menanggung penderitaan seberat ini.
Hari kian larut, kira-kira pukul 23.00 Wita. Keadaan Mama tak lekas membaik, malah sebaliknya tangisan dan rintihan kesakitan terdengar semakin kuat dari mulut yang tak mampu berucap sepatah kata lagi itu. Suasana sepi berubah menjadi gaduh, bukan saja karena tangisan Mama, tetapi juga karena tangisan adik-adikku.
Aku memang tak berupaya bernazar pada Tuhan. Namun, di dalam hati kecil tertulis sepotong doa dari anak yatim ini, “Tuhan semoga hal terburuk tidak terjadi malam ini. Jikalau Engkau berkenan biarkan mama sembuh dan hidup bersama kami lebih lama lagi.”
Kutatap mata Mama dalam-dalam. Persis setelah kuucapkan kata-kata itu dalam hati, Mama perlahan-lahan menutup mata, pergi untuk selama-lamanya. Mama pergi dalam pelukan anak-anaknya, meninggalkan setetes air mata, tanpa kata-kata perpisahan.
Malam kedukaan malam perpisahan. Aku menangis sejadi-jadinya. Air mata yang sedari tadi kubendung kini mengalir dan membasahi seluruh wajah. Kudekap wajah Mama, tak henti-hentinya kucium keningnya. Bertubi-tubi kata-kata penyesalan dan pertanyaan lahir dari bibirku.
“Apakah semua bentuk cinta selalu berakhir dengan mengikhlaskan? Apakah setiap kenangan selalu tentang kematian?”
Mama tetap terbujur kaku. Ia pergi diiringi tangis pada gelap malam. Ingin aku mengadu tetapi pada siapa. Bapak aku tak punya. Anak yatim ini kini menjadi yatim piatu karena yang dicintai hilang satu persatu.
“Ah Tuhan, seberat inikah salib yang harus kupikul?”
*Mengenang mama, 2024
- BACA cerpen lain di tatkala.co