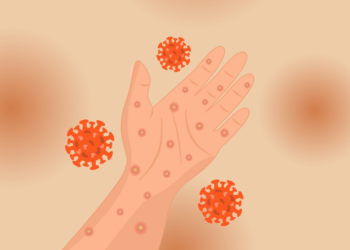DI kamar kotrakan saya ada tiga buku Anton Chekhov. Dua kumpulan cerpen (Matinya Seorang Buruh Kecil dan Pengakuan) dan satu naskah lakon (Tiga Saudari—terjemahan Trisa Triandesa). Saya tidak tahu asal-usul ketiga buku tersebut. Saya merasa tidak pernah membelinya. Tapi dugaan saya, ketiga buku ini saya ambil—untuk tidak mengatakan mencurinya—dari sebuah perpustakaan yang saya lupa itu di mana.
Tapi terlepas dari mana ketiga buku itu berasal, khusus kumpulan cerpen Matinya Seorang Buruh Kecil sudah saya baca berulang-ulang. Itu karena, selain saya menyukainya, juga tak banyak buku baru yang tersedia di rak kecil di kamar saya. (Kalau merasa tak cukup punya uang saya tidak membeli buku baru.)
Matinya Seorang Buruh Kecil di kamar saya ini tampaknya cukup klasik. Diterbitkan oleh Melibas tanpa tahun terbit. Sampulnya berwarna biru tua dengan foto Anton Chekhov dengan judul buku yang melingkarinya—lebih tepatnya berbentuk oval seperti telur.
Ada 13 cerpen dalam buku tipis ini, yang oleh penerbitnya disebut unik, “selain meng-‘KO’ kan, ia juga bisa membuat pembacanya tersenyum simpul dan senang. Tanpa beban, tapi membuat penasaran, juga mengejutkan.”
Ungkapan tersebut benar adanya. Semua cerpen Chekhov dalam buku ini memang memiliki ending yang mengejutkan, tak tertebak. Cerita-cerita Chekhov yang lekat akan realitas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial itu—cerita-cerita khas sastrawan Rusia—, ditulis dalam bahasa sederhana yang dipenuhi dengan unsur humor dan olok-olok, cerita-cerita dalam buku ini seperti menelanjangi sifat asli manusia.
Sejak cerpen pertama dalam buku ini, Peristiwa di Pengadilan (hlm. 17), saya sudah dibikin geleng-geleng kepala. Ketika seorang pengacara ternama harus membela terdakwa yang berdasarkan bukti dan fakta-fakta telah dinyatakan bersalah; tapi di penghujung cerita sungguh tak dapat saya kira. Satire. Sungguh membuktikan kata-kata si penulis di awal cerita yang menggambarkan bahwa sang tokoh, si pengacara, adalah orang yang penuh kharisma dan disegani oleh banyak orang.
Atau cerita yang menjadi banner kumpulan cerpen ini, Matinya Seorang Buruh Kecil (hlm. 25). Karena Chekhov berasal dari Rusia, awalnya saya mengira cerita ini akan dipenuhi dengan narasi yang heroik-heroik tentang buruh, perlawan kelas sosial, yang mengundang simpati dan gelombang protes dari aktivis demokrasi layaknya kematian Marsinah.
Tapi seketika saya geleng-geleng kepala sambil mengumpat kecil sembari tak percaya setelah tahu bahwa penyebab kematian buruh kecil itu, Kreepikov namanya, boleh dibilang sangat “sepele”—karena si buruh tidak sengaja bersin tatkala menonton opera yang tanpa sepengetahuannya semprotan bersinnya bersarang di jidat seorang petinggi tentara.
Dan lebih tak saya sangka lagi, buruh kecil itu mati bukan karena dibunuh oleh tentara tersebut, tapi karena tak mendapat maaf, “pengampunan” dari sang tentara. Kreepikov merasa, ketiadaan maaf adalah maut. Dan benar, sepulang dari kantor tentara itu ia mati terduduk di atas sofa. Titik. Sampai di situ saja cerpennya. Jancuk, Chekhov!
Cerpen Barang Antik (hlm. 43) dan Peti Mati (hlm. 67) juga tak kalah asyiknya. Dua cerpen ini membuat saya tertawa, selain terkejut. Kisah keduannya benar-benar tak dapat saya tebak. Di awal saya dibuat penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya; tapi mendekati akhir cerita, dengan semena-mena Chekov memberi jawaban—atau mematahkan asumsi saya sejak awal—begitu saja, “KO”.
Dan kisah Di kota Ada Surga (hlm. 117), ya Tuhan, air mata saya keluar karena terpingkal-pingkal. Cerpen ini bercerita tentang rahib-rahib yang menderita, katakanlah, shock culture. Rahib-rahib itu pada awalnya tinggal nyaman di tempat terpencil, jauh dari peradaban, terisolir. Namun ketika mereka mendengar kabar tentang kehidupan kota—oleh seorang yang tersesat dan pengalaman kepala biara—yang serba aduhai dan menggiurkan, mereka berbondong-bondong menyambanginya.
Meskipun kepala biara menggambarkan kota dengan penuh rayuan iblis, cantik moleknya dosa, menggiurkannya tubuh perempuan, tapi para rahib justru terpaku di tempatnya. Mereka menelan setiap kata yang diucapkan kepala biara dan hampir-hampir tak bisa bernapas karena keranjingan. Dan ketika esok harinya sang kepala biara keluar dari kamarnya, ia tak melihat seorang pun rahib tertinggal di biara. Mereka semua lari ke kota.
Humor dan Tak Ada Agitasi
Meski besar di Rusia, di mana dulu struktur masyarakat yang seluruh darah dagingnya dikenal oleh dunia sebagai masyarakat sosialis, tepatnya komunis, tapi tak satu pun cerpen Chekhov dalam antologi ini yang mengandung ajakan-ajakan agitasi pembangkangan seperti yang selalu dijunjung tinggi oleh rabi-rabi sejarah mereka, atau bercerita tentang soal-soal yang berbau semacam-semacam itu.
Membaca antologi cerpen “Matinya Seorang Buruh Kecil” memberi tahu saya bahwa Anton Chekhov ternyata bukan pribadi yang selalu suka pada cerita-cerita yang besar (grand naratives), semacam angan-angan internasionalisme atau universalisme, sebagaimana cita-cita adiluhung komunisme.
Ketiga belas cerpen dalam buku ini justru berkisah tentang hal-hal biasa, keseharian, kesederhanaan, kesahajaan, kemanusiaan, dan tentang orang-orang kecil dengan cara karikatural dan parodikal, humor. Ya, sangat humoris. Namun, meski terkesan “main-main”, lucu, parodis, di setiap cerita berkelebatan sindiran (satire) yang tajam atas sebuah struktur totalitarianisme komunis. Dalam wacana postkolonial, ingat, humor tidak sekadar dianggap remeh-temeh.
Seorang Cicero gemar melempar joke saat berbicara dan berargumen di depan orang banyak. Dianggap terlalu humoris untuk seorang pejabat publik di zamannya, seperti kata Ulwan Fakhri, Cicero pun dipandang bak badut. Wajar, kala itu, pendapat Plato dan Aristoteles bahwa tertawa cenderung terasosiasi dengan aktivitas kaum tak terhormat masih sangat dominan. “Humor,” kata Cicero, “bisa meruntuhkan perbedaan antara seorang orator dan komedian.”
Bagi saya, seperti Cicero, ketika humor digunakan dengan kadar yang pas dan bijak di muka umum, kuasa sosial hingga politik bisa dimenangkan. Tetapi saat humor digunakan dengan sembrono di hadapan orang-orang, kita bisa saja dicap sebagai badut seperti Cicero─tanpa prestasi yang selevel dengannya.
Humor, kata Ulwan Fakhri, “pada dasarnya hanya sebuah alat, sama seperti pisau. Mau dipakai untuk memasak makanan kesukaan orang yang ingin Anda bahagiakan, bisa. Mau ditodong-todongkan ke orang lain sembari tertawa puas menari-nari bahagia melihat muka tak nyaman mereka, bisa pula. Yang penting, mari lebih melek dan sadar dalam berhumor. Minimal, tahu apa yang sedang ingin Anda sendiri capai, meraup simpati atau untuk mengekspresikan diri.”
Dalam sistem kekuasaan totalitarian atau otoriter yang kerap membungkam kebebasan termasuk kreativitas dan memandulkan perayaan kebebasan berpikir, gaya-gaya humoris dan parodis menjadi kekuatan efektif untuk mencemooh identitas pongah penguasa.
Memang, humor—apalagi yang bersifat protes sosial—sangat digemari akhir-akhir ini. Orang-orang yang risau dan tidak puas terhadap keadaan masyarakat maupun polah-tingkah birokrat, demi menjaga keseimbangan jiwa, menumpahkan perasaan ketidakpuasan itu melalui tulisan-tulisan yang terkesan tidak serius tapi sebenarnya serius, adalah sebuah jalan lain—dan penting.
Beberapa pengeluaran energi agresif yang bersifat primitif memang tidak bisa dituangkan begitu saja karena adanya batasan dalam masyarakat, maka desas-desus yang hendak disebarluaskan itu diubah dahulu ke dalam lelucon. Begitu pun dengan cerpen-cerpen dalam Matinya Seorang Buruh Kecil—yang membuat saya geleng-geleng kepala itu.[T]
Judul asli: Chekhov The Early Stories
Penulis: Anton Chekhov
Penerbit: Melibas
Tebal: 164