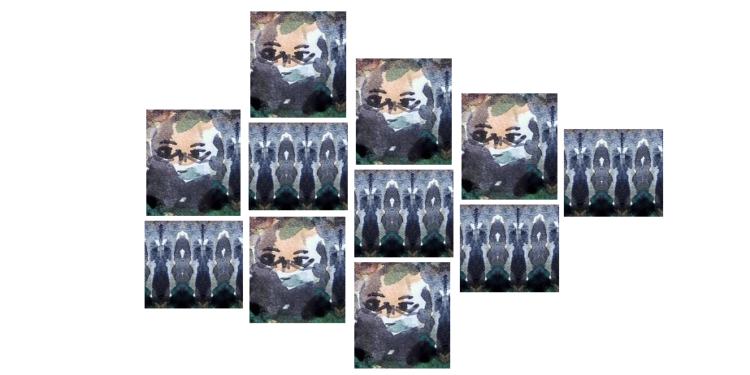KAMI menyebutnya leluhur, sesuatu yang ada dan menempel pada diri, pada raga dan mungkin juga jiwa. Yang kadang muncul menjadi bisikan lembut di dada, belaian sayang yang membayang. Atau memantul dan berbicara lewat bibir yang tersenyum di dalam cermin. Ya,, kami, aku dan dia menyebutnya leluhur, sesuatu yang dekat, sangat dekat, tetapi kadang tak terjangkau bahkan oleh kecerdasan pikiran.
Aku dan dia, memandang, memahami dan menanggapi leluhur secara berbeda, bahkan nyaris bertolak belakang. Aku, seperti namaku, Pertiwi, Bumi yang mematri semua yang di dalam, statis, diam tak kemana-mana, memahami, dan memandang leluhur sebagai manusia-manusia nyata dengan segala aturan tradisi tetek bengeknya yang membelengu, dan mengganggu.
Dia, namanya Dian, Agni,, seperti api terlempar dan menggelepar di luar lingkaran, menggapai-gapai kedalaman, mencari akar untuk bahan bakar, memandang dan memahami leluhur sebagai spirit yang selalu membantu dan menguatkan.
Maka, jadilah kami dua sosok berbeda yang bertolak belakang, tetapi disatukan dalam konteks “leluhur”.
Hentah siapa yang benar dan siapa yang salah menjadi tak penting lagi. Yang menarik adalah sesuatu yang kami sepakati yang kami sebut leluhur yang wajib dan mesti dihormati.
Bagi Dian rasa hormat dan kewajiban itu ditunjukkan dengan mengikuti semua semua arahan leluhur, karena selalu benar, dan memang merupakan kebenaran itu sendiri.
“Aku dibuang, dipisahkan dari ayah, ibu, saudara-saudara dan lingkunganku. Nenek yang mengajak, menjaga, memelihara dan mendidikku. Nenek menjadi perantara kasih sayang leluhur-leluhurku. Bahkan saat nenek sudah meninggalpun, kasih sayangnya yang hadir dalam batinku, menyelamatkanku dari tiga kematian. Aku dihidupkan dari nafas kasih nenek dan leluhurku. Maka kujalani hidupku untuknya, untuk leluhurku!” Mata Dian berkaca-kaca, ada kenangan indah masa silam yang melintas-lintas dalam geraknya yang tanpa batas.
Aku terpana, merasa berbeda dan sangat berbeda.
Aku menghormati leluhur, karena kuanggap lebih tua. Ibu mengajariku untuk menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda dan menghargai sesama.
Jadi rasa hormatku pada leluhur, lebih pada rasa hormatku pada nasehat ibu, yang kuyakini benar dan kebenaran itu sendiri.
Pada ibu, rasa hormatku tak kutunjukkan dengan mengikuti semua perkataannya, untuk yang kuanggap krusial aku sering membantah ibu, justru karena rasa hormatku padanya.
Ketika ibu sakit, beliau melarangku memijat kakinya, karena menganggap aku anaknya memiliki derajat yang lebih tinggi darinya.
“Lebih tinggi dari mana, sudah jelas aku lahir dari rahimnya, jangankan memijat kaki, kepalakupun akan aku serahkan dengan senang hati agar bisa berada di bawah telapak kakinya!” Pendapatku itu tidak saja melawan permintaannya, tapi juga membuat keluarga lain tidak suka.
Membuat orang yang lebih tua tidak suka, marah bahkan benci, bukan berarti aku tak menghormati, tetapi rasa hormatku diletakkan pada keyakinan yang kuanggap benar.
“Kamu tahu kenapa sampai sekarang kamu belum mendapatkan pasangan, itu karena aku pasang tembok yang sangat tinggi untuk mengurungmu.., ” kata sebuah suara di dalam dadaku. Ya, aku tahu itu suara bagian dari diriku, dalam darah, DNA leluhurku.
Aku terkekeh, bersilat lidah dengan yang ada di dalam diriku.
“Ya, tidak apa-apa, berarti pasanganku nanti adalah orang hebat, peloncat tinggi yang bisa meloncati tembok tinggi yang kalian buat.”
“Sejak dari dalam kandungan, dari kecil kau kujaga, selalu kujaga, agar kau bisa melahirkan keturunan, yang mewarisi keagungan dan keluhuran leluhur kita!” Suara itu tegas dan jelas, sedikit marah.
Aku terkekeh.
“Ya, silahkan saja, kalau mau lahir dari aku silahkan saja, mau suamiku siapa kek ya lahir, lahir sajalah, mau orang asing atau siapa saja.”
Suara di dadaku kurasakan makin marah. Kemudian dia memberikan gambaran suami yang dijodohkan untukku. Seorang lelaki muda dan tampan, masih saudara yang juga teman SMA ku. Tentu saja aku makin terkekeh, yang membuatnya makin marah.
“Oke, oke, gini aja, aku hanya akan menikah dengan orang yang kucintai dan mencintai aku. Jadi kalau kau ingin aku menikah dengannya, tolong buat aku mencintainya dan dia mencintai aku, ” kataku akhirnya.
Suara di dadaku makin marah, mengumpat-umpat dan mengancam-mengancam, mengatakan apa saja yang sudah dilakukan untukku selama ini, yang dianggapnya percuma karena aku tak mau mengikuti perintahnya.
Setelah itu sungguh kurasakan sangat tidak nyaman. Seminggu aku merasakan jiwaku tak berada di dalam ragaku, hidupku serasa kosong. Tapi saat seperti itu, pikiran-pikiran nakalku tentang kematian berlompatan. Kalau seandainya aku mati, aku ingin teman-temanku sedikit tahu tentang cerita kematianku. Maka ku telpon teman-teman dekatku, kunikmati berbagai jawaban yang mereka berikan.
“Aduh, jangan seperti itu, jangan melawan leluhur, minta maaflah, ” kata seorang teman yang dikenal sangat ahli dalam adat dan budaya Bali.
“Wah Kingkong lu lawan,” kata teman satunya yang terkenal santai.
“Wah gitu ya, hati-hati,” kata teman sedikit cuek
Berbagai jawaban teman-teman mampu sedikit meredakan debar di dadaku,sekaligus memberiku pemahaman yang lebih dalam tentang teman-temanku.
Ketika kemudian adikku meninggal, aku masih berusaha melupakan perdebatan dengan yang kuanggap leluhur itu, dan berkeyakinan bahwa persoalan hidup dan mati ada dalam kemahakuasaan Tuhan, juga jodoh dan cinta.
Jalanku menghormati leluhur adalah jalan pembangkangan dan pemberontakan terhadap apa yang kunilai keliru. Kupahami kini, leluhur atau, siapapun, atau apapun itu yang hadir sebagai penghalang, penghambat, pengganggu bahkan pengancam, hadir semata untuk menguji keyakinan kita, pada Tuhan, pada kebenaran yang satu, yang sebenar-benarnya.
Leluhur menjadi salah satu jalan menuju hakekat. Hentah jalan darat, laut maupun udara.
Di udara bagi Dian, diri adalah ketelanjangan yang memerlukan baju-baju duaniawi dari leluhur untuk perlindungan dan rasa aman.
Sampai bisa menemukan baju-baju keyakinan pada Tuhan untuk menjadi benar-benar telanjang dan menyatu dengan semesta. Menjadi semesta.
Di Bali, tubuh kita seperti pohon pisang, yang hatinya diselubungi berlapis-lapis pelepah, yang menjadi pelindung inti. Lapis-lapis yang menjadi batang pohon pisang itu seperti lapis-lapis keluarga, leluhur, lingkungan, adat dan tradisi yang menutupi kesejatian yang kita cari. Hanya dengan melepas kelopak pisang satu-satu, melewati perih luka dan koyakan, akan mendapatkan inti. [T]