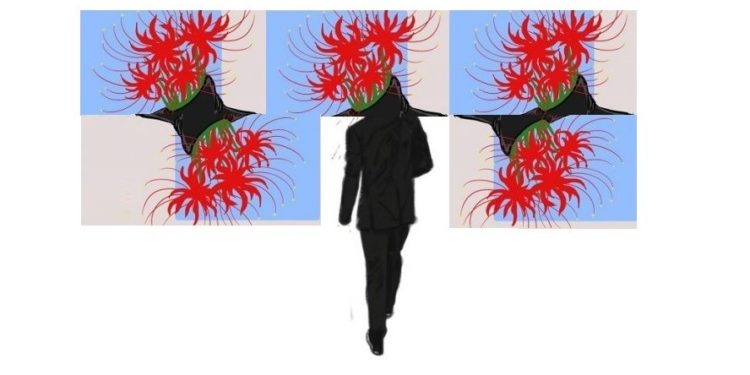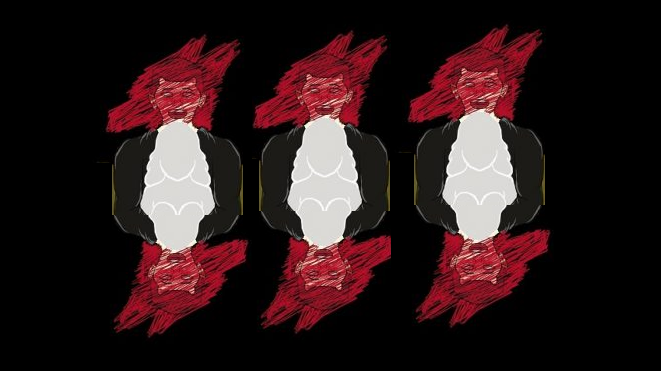Rumah sakit di kabupaten kecil itu heboh. Seorang dokter, suatu malam, tidur dan bermalam di ruang pasien. Ia bercerita bersama penunggu pasien, dan sesekali ngobrol bersama pasien. Ia tidur di bangsal. Dan besoknya, ia bangun pagi seperti biasa, sarapan nasi bungkus bersama staf rumah sakit, seperti penunggu pasien, lalu ngopi.
“Itu dokter gila!” kata seorang perawat, bukan dengan nada mengejek, justru ada kesan takjub di sela-sela suaranya,
***
“Dokter tidak perlu sampai harus tidur di ruang pasien!” kata Direktur Rumah Sakit pada malam sebelumnya.
Saat itu dokter gila itu minta izin secara baik-baik untuk tidur dan menginap di ruang pasien.
“Silakan langsung saja sampaikan apa masukan Dokter untuk manajemen?” sambung sang direktur.
Dibandingkan sebagai sebuah pertanyaan, suara Direktur Rumah Sakit itu lebih terdengar seperti memberi perintah atau larangan kepada dokter gila.
“Masukan saya sudah sangat jelas sejak dulu. Tidak manusiawi satu ruangan bangsal dihuni oleh 16 orang pasien. Meskipun obat yang kita berikan sudah sesuai standar, secara psikologis situasi tersebut akan menghambat penyembuhan pasien. Saya yakin Pak Direktur pasti paham soal ini!” kata si dokter.
“Saya paham sekali!” Nada suara Direktur semakin tinggi dan emosional.
Seorang kepala ruangan dan wakil direktur yang berada dalam ruangan saat itu hanya diam seperti patung.
“Kita tidak bisa seideal seperti yang Anda pikirkan. Kita pun tak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh kementrian kesehatan!”
Kali ini kedua patung mulai mengangguk-angguk, meski jelas sekali itu sekadar basi-basi dan tampak ragu-ragu, entah bagaimana sikap mereka yang sebenarnya. Si dokter gila bergeming, mungkin tersenyum geli dalam hatinya.
Pertemuan dokter gila dan sang direktur itu jelas tidak menghasilkan apa-apa. Namun sikap si dokter sudah jelas. Ia ingin tidur di ruang pasien. Untuk itu, ia tak memerlukan diskusi lagi. Ia meninggalkan ruangan yang masih diliputi suasana tegang itu.
“Terimakasih, saya sudah minta izin!” kata dokter gila itu.
Malam pada hari setelah pertemuan di ruang direktur itu ia, diizinkan atau tidak, tetap tidur di salah satu bangsal perawatan. Ia di situ hingga pagi. Dan hingga pagi ia bersama pasien yang menjalani rawat inap saat itu.
Sebelumnya, kepala ruangan menawarkan si dokter untuk tidur di salah satu ruangan kelas dua yang kebetulan kosong.
“Maaf, Dokter. Apakah tidak lebih baik malam ini dokter tidur di ruang Lily yang kebetulan kosong?”
“Oh nggak apa-apa, Pak Yoga, izinkan saya semalam saja tidur di bangsal,” sahut si dokter. Seperti biasa suaranya datar, dan Pak Yoga, kepala bangsal itu, tidak bisa berbuat apa-apa.
Keesokan harinya ia meminjam toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Entah bagaimana, pagi itu, suasana di ruang perawat justru menjadi cair, jauh dari ketegangan.
“Saya boleh minta tolong ya? Belikan nasi bungkus duabelas bungkus dan air mineral. Oh ya, saya biasa ngopi setelah sarapan, jadi tambah satu kopi krim ya!”
Dokter itu menyerahkan sejumlah uang kepada salah seorang staf, lalu duduk di salah satu kursi di depan meja lebar. Meja itu biasa digunakan untuk rapat perawat, dan di situ si dokter bersiap untuk sarapan sambil merapikan tas ransel setelah mandi dan berganti pakaian.
Beberapa perawat yang bertugas pagi mengikuti si dokter. Mereka duduk mengelilingi meja. Pak Yoga yang baru datang, duduk pada posisi paling dekat dengan si dokter. Beberapa di antaranya terkesima, dokter itu tepat menghitung jumlah staf duabelas orang sehingga meminta beli nasi duabelas bungkus. Dari mana dokter gila tahu persis jumlah staf yang bertugas pagi itu?
Hidangan nasi bungkus telah tersedia di atas meja, uap kopi panas pun masih mengepul, aroma kopi krim memang sangat menggugah.
“Ayo, teman-teman, sarapan dulu. Siapkan diri dulu dengan baik sebelum melayani pasien!”
Ajakan hangat dokter gila itu mengundang lebih banyak perawat untuk ikut duduk sarapan sebelum pergantian tugas. Salah seorang dari mereka tak bisa menahan diri untuk menyampaikan sesuatu yang sangat sentimentil dan emosional.
“Dokter, terimakasih telah mengajari kami banyak hal dengan cara-cara yang bagi kami tak masuk akal. Namun kami semakin meyakini, itu semua ada benarnya.”
Salah satu perawat perempuan muda yang tampak lebih gaul dan selama ini suka ceplas-ceplos ikut nimbrung.
“Tahu gak, Dok? Selama ini dokter dijuluki dokter gila, lho!”
Perawat muda itu mengucapkan kata-katanya sambil menutupi wajahnya yang bulat dengan kedua telapak tangan. Tawa seisi ruangan pecah. Ruangan jadi riuh.
“Ha ha… Mungkin tetap lebih baik menjadi dokter gila ketimbang pasien waras!” kata dokter gila itu santai.
***
Dokter itu kemudian makin terkenal dengan sebutan dokter gila. Sebutan, bukan panggilan tentu saja. Mungkin saja ia sudah tahu dirinya disebut sebagai dokter gila, namun tak akan ada yang berani memanggil atau menyapanya saat bertemu misalnya dengan sapaan, “Selamat pagi, dokter gila. Apa kabar?”
Orang gila, atau sekarang disebut dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), mungkin saja tidak suka disebut gila. Apalagi orang normal. Lebih-lebih, ini seorang dokter yang bekerja, salah satunya, justru untuk mengobati ODGJ.
Tetapi, meski ia mungkin tahu telah disebut dokter gila oleh orang-orang di sekitar tempatnya bekerja, di rumah sakit, sepertinya ia tak peduli. Jangan-jangan, ia memang sudah tahu, tapi hanya menanggapi dengan tersenyum dalam hati.
Jika saja ia tak terima, sekali waktu pastilah salah seorang perawat atau petugas lain di rumah sakit itu telah dipanggil ke ruangannya, untuk diajak bicara, atau dimarahi, atau untuk sekadar menanyakan hal-ikhwal sebut gila itu. Namun kenyataannya ia tak pernah memanggil siapa pun untuk urusan itu.
Seperti biasa ia datang pagi-pagi sekali. Ia melakukan tugas biasa, mengunjungi pasien di ruang perawatan. Dan seperti biasa juga, ia tak pernah menggunakan jas dokter saat bertugas. Sehari-hari ia datang ke rumah sakit memakai kemeja lengan pendek, kaos berkerah bahkan kadang hanya T-shirt dengan bawahan lebih sering celana jeans ketimbang celana kain biasa.
Sepatunya, sejak datang pertama kali ke rumah sakit tetap itu-itu saja. Belum pernah diganti. Warna sepatu yang coklat buram, lecet di sana-sini. Semua hapal merknya: Rockport. Soal pakaian ini ia pernah ditegur pihak manajemen rumah sakit. Namun dengan enteng ia menjawab dengan pertanyaan balik, khas orang gila yang susah diatur.
“Saya ke rumah sakit untuk memeriksa dan mengobati pasien. Bukan untuk fashion show. Coba tanya, ada nggak pasien saya yang keberatan dengan penampilan saya?”
Pihak manajemen buru-buru angkat tangan dan tak mau memperpanjang perkara ini.
Pagi itu si dokter gila memasuki bangsal pasien penyakit infeksi didampingi seorang suster senior. Kepala ruangan sebelumnya sudah wanti-wanti, jika dokter gila yang visite, maka ia harus didampingi perawat-perawat senior. Maksudnya tentu saja agar perawat itu bisa mengimbangi kemauan dokter gila yang sulit diprediksi arahnya bicara dan tindakannya.
Dan betul saja, pagi itu, ketika masuk ruangan pasien, alih-alih memeriksa pasien, ia justru menyeret suster memeriksa kamar mandi pasien terlebih dahulu.
“Ayo, Suster, kita cek kamar mandi dulu!” ajaknya tegas.
Berpasang-pasang mata di ruangan itu pun kebingungan. Ada empat tempat tidur pasien yang terisi penuh dengan masing-masing pasien ditunggu satu atau dua orang penunggu.
Suster senior hanya bisa menuruti namun refleks bertanya, “Maaf, Dokter ke toilet untuk apa?”
“Sudah. Ikut saja saya sebentar!” Suaranya diikuti gerakan kepala ke arah kamar mandi.
Suster pun bergerak mengikuti langkah si dokter.
“Nah, itu, coba Suster lihat, ada genangan di washtafel. Itu, apa lagi di bawah, pasti bekas muntahan. Tolong panggil dulu bagian sarana dan petugas cleaning service untuk membereskan. Setelah itu baru saya mau memeriksa pasien!” kata si dokter.
Intonasi kata-kata dokter gila itu datar. Pandang matanya terus menyisir dengan teliti seluruh keadaan di kamar mandi. Kejadian itu terasa begitu cepat dan singkat, namun dirasakan begitu berbobot oleh suster senior yang mendampinginya. Seakan-akan keadaan kamar mandi yang demikian itu sudah diketahui oleh dokter gila sejak dari rumahnya.
Pada dasarnya, dokter gila tidak pernah marah. Namun hal-hal tak biasa yang dilakukannya memang mudah ditafsirkan sebagai kemarahan.
“Oh ya, baik, Dokter, akan saya hubungi bagian sarana dan petugas kebersihannya sekarang!” Suster senior mengalah.
Dalam perjalanan ke nurse station, dokter gila itu menjelaskan teori penyakit infeksi yang ditentukan oleh faktor kuman, tubuh pasien dan lingkungan. Kamar mandi pasien adalah salah satu aspek lingkungan yang sangat penting.
Ia menjatuhkan tubuhnya di salah satu kursi di ruang perawat untuk lalu meneruskan ceritanya. “Jika keadaannya buruk seperti itu, mana mungkin pasien bisa cepat sembuh. Jangan-jangan, antara pasien nanti dapat saling menulari penyakit atau kepada para penunggunya. Syukur-syukur Anda nggak ikut tertular. Muntahan atau sisa air kencing maupun feses merupakan media penularan kuman penyakit. Genangan air sudah tentu bisa menjadi sarang jentik nyamuk demam berdarah!”
Beberapa perawat dan petugas yang kebetulan ada di ruangan itu terpaksa ikut menyimak kuliah pagi yang tak dijadwalkan itu. Tentu saja para perawat dan petugas lain mendengar sembari tetap mengerjakan tugas mereka masing-masing. Suara pesawat televisi yang sedari tadi membahana menyampaikan berita gosip seakan tenggelam oleh suara dokter gila yang padat dan tak putus-putus.
Ada yang buru-buru menutup kembali nasi bungkusnya, padahal baru dimakan setengahnya. Untunglah suster senior tiba-tiba muncul dengan berita baik. Kamar mandi pasien sudah beres dan pasien sudah menunggu untuk diperiksa. Sang dokter gila pun beranjak menuju ruangan pasien.
***
Cerita itu belum seberapa. Dokter gila pernah datang pagi-pagi ke bagian dapur rumah sakit atau instalasi gizi. Ia minta seporsi makan yang biasa diberikan kepada pasien.
“Maaf, Dok. Kalau Dokter belum sarapan pagi, biar saya minta CS-nya untuk membelikan nasi bungkus!?”
Kepala dapur memohon dalam keadaan bingung.
“Oh, nggak usah repot, Bu Lisa, izinkan saya minta seporsi makanan yang pagi ini akan dibagikan kepada pasien untuk sarapan pagi. Boleh, ya, Bu?” balas dokter gila itu sembari tersenyum.
Tanpa berani berdebat lebih panjang, Bu Lisa langsung mengambilkan satu paket sarapan pagi yang biasa ia berikan untuj pasien. Paket sarapan itu diberikan kepada dokter gila. Si dokter menolak makan di ruang kepala dapur, maka Bu Lisa mengantarkannya ke ruang administrasi.
Setelah mengucapkan terimakasih, ia duduk santai, bersandar di salah satu kursi di ruang administrasi instalasi gizi. Ia menikmati hidangan makan yang sebetulnya disiapkan untuk pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tentu saja ini membuat semua staf dapur yang bertugas saat itu menjadi kikuk dengan tingkah laku dokter gila itu.
Bahkan ada juru masak yang tak mau beranjak dari dapur dan masih menunggu panci di atas kompor, padahal air dalam panci sudah mendidih sejak tadi. Ini lantaran juru masak itu enggan bertatap muka dengan si dokter gila yang lagi asyik melahap makanan pasien.
Belum habis keheranan Bu Lisa dan juru masak, dokter gila tiba-tiba membagikan nasi bungkus kepada Bu Lisa dan semua juru masak yang bertugas saat itu. Maka terjadilah peristiwa unik. Dokter gila makan nasi pasien, sementara juru masak makan nasi bungkus pemberian si dokter. Juru masak makan, sementara hatinya terus bertanya-tanya. Apa maksud si dokter gila itu?
Nasi bungkus yang dibawa dokter gila adalah salah satu nasi bungkus terkenal yang selalu menjadi pilihan sehari-hari warga kota sejak dulu. Tentu karena harganya sangat terjangkau dan rasanya sangat enak dengan porsi yang pas. Siapapun menikmatinya, dijamin tak akan pernah menyisakannya. Dengan begitu, staf dan juru masak di bagian dapur rumah sakit diharapkan paham apa yang ingin disampaikan dokter gila itu. Ia memang tak bicara secara langsung, namun maksudnya begitu jelas dan gamblang.
Raciklah makanan yang lebih enak untuk dinikmati oleh orang-orang sakit. Itu tak selalu memerlukan biaya yang besar. Yang penting adalah kepekaan sebagai pelayan masyarakat. Orang sakit butuh nutrisi yang baik, artinya ia perlu hidangan yang menggugah selera dan rasanya nikmat, sehingga makanan dilahap habis dan tidak tersisa dengan sia-sia.
***
Rumah sakit heboh lagi. Dokter gila menghilang.
Dokter gila itu bernama lengkap dr Satyagraha SpPD. Ia seorang ahli penyakit dalam atau internist. Orang-orang di rumah sakit tak banyak mengetahui kehidupan pribadinya. Sepertinya orang sudah cukup mengenalnya sebabagai dokter gila meskipun ia bukan seorang dokter ahli jiwa atau psikiater. Kini rumah sakit tempatnya bekerja menjadi rumah sakit favorit di masyarakat. Alasannya bukan karena ada dokter gila di situ, namun karena sikap kegilaan si dokter itu terjadilah banyak perubahan di rumah sakit, salah satunya kebijakan yang lebih mementingkan pasien. Ruangan yang lebih layak, makanan pasien yang lebih enak, kebersihan ruangan dan lingkungan yang lebih baik seta asri. Banyak lagi alasan kenapa rumah sakit itu menjadi pilihan warga untuk berobat. Manajemen rumah sakit pun telah menambah berbagai sarana medis yang lebih canggih, yang dibutuhkan pasien.
Tapi, sejak sebulan ini dokter gila menghilang. Ia tak pernah kelihatan di rumah sakit. Perawat, petugas kebersihan, petugas medis lain, tukang taman, kehilangan dan kebingungan. Apalagi banyak pasien meminta agar mereka dirawat oleh dokter gila.
“Dokter Satya, sudah minta izin kepada direktur untuk tidak memperpanjang kontrak kerjanya di RS kita.” Itu berita yang dibawa Pak Yoga.
Pak Yoga duduk di sisi meja yang biasa digunakan untuk rapat dan makan nasi bungkus bersama dokter gila. Ia di kelilingi oleh rekan-rekan dan beberapa orang dokter.
Ia bercerita dengan nasa sedih. Suaranya lirih dan semua yang hadir menahan napas mendengarkannya dengan khidmat.
“Bukan karena beliau tidak betah di sini. Itu karena anak semata wayangnya harus menjalani pengobatan ke luar negeri!”
Suasana hening. Tak ada yang bertanya.
“Anak beliau harus mendapatkan tindakan medis canggih yang kita belum miliki di Indonesia. Karena dirasa pengobatannya akan memakan waktu yang cukup lama, beliau merasa lebih baik sementara waktu memutuskan kontraknya agar beliau bisa fokus mendampingi anandanya. Dokter Satya menitipkan salam untuk kita semua, mohon didoakan untuk kesembuhan anandanya!” kata Pak Yoga. Suaranya makin parau.
Semua yang mendengar, tanpa sadar, meneteskan air mata. Air mata doa. Air mata rindu. [T]
______