SEWAKTU film GIE (2005) aku ingin putar di rumah, ayah angkatku terlihat tidak suka. Soe Hok-Gie dianggapnya sebagai tokoh penyebab kejatuhan Sukarno, yang kala itu adalah presiden Republik Indonesia. Meski begitu, film itu tetap aku tonton bersama keponakanku; berharap ia melek sejarah, betapa pentingnya buku-buku dan kebiasaan menulis. Dari sana ia terinspirasi untuk kuliah di Yogyakarta. Selanjutnya dia mendapat beasiswa studi ke luar negeri.
Ayah angkat saya pengagum berat Sukarno. Tidak aneh kemudian, ia membenci segala hal yang ‘anti-Sukarno’, termasuk film GIE yang berhasil dan sangat baik menggambarkan tokoh mahasiswa dan aktivis muda Soe-Hok Gie. Ayah tidak mau tahu. Mungkin beliau tahu melalui buku atau bacaan tentang kekecewaan Soe-Hok Gie—meskipun telah turut berhasil menumbangkan Orde Lama, Orde Baru kemudian tidak kalah ‘rusak’, bobrok, dan buruk juga.
Dari ayah, aku mengetahui banyak cerita masa lalu, termasuk soal tragedi 1965/66 yang mana Jembrana, kampung halamanku, korban ‘genosida’ paling banyak di Bali. Aku yang saat itu masih duduk di sekolah dasar bergidik ngeri mendengar cerita pembunuhan orang-orang tidak bersalah yang karena hasutan dituduh anggota maupun simpatisan partai yang berhalauan ‘kiri’.
Keluarga besar kami bukan bagian dari partai tersebut, tidak juga terlibat dalam huru-hara politik masa itu. Salah seorang paman yang menjadi kepala desa waktu itu, bahkan banyak “menyelamatkan” warga yang masuk daftar orang yang “kena garis”—pantas dihabisi, tanpa pengadilan, apalagi kesempatan untuk membela diri di depan hukum.
Dengan setengah berbisik, ayah angkat saya seperti takut untuk berbicara tentang tragedi 1965/66. Itu pula yang saya rasakan saat beliau diwawancarai oleh kakak kelas saya pada jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Sastra Universitas Udayana, yang melakukan penelitian tentang kekerasan di Bali untuk tugas akhirnya. Saya pun waktu itu mengantarnya bertemu beberapa informan yang telah berusia lanjut untuk diwawancarai perihal tragedi yang dalam hitungan ‘kasar’ telah menewaskan sebanyak 80.000 orang di Pulau Bali.
Secara tidak langsung, ayah angkat saya banyak menyematkan pemikiran-pemikiran ‘kiri’. Tentu yang dimaksud tidak selalu berkonotasi misalnya pada komunisme atau sosialisme. Ayah seperti ingin mengajarkan saya sejak dini tentang nilai-nilai keadilan, yang perlu terus untuk diperjuangkan dalam hidup manusia.
Meski tidak menyebut nama penulis atau pemikir seperti Pramoedya Ananta Toer atau Karl Marx, saya tahu kemudian hari apa yang sering ayah ceritakan pada saya agaknya bersumber dari buku-buku yang pernah beliau baca. Seperti pendongeng, beliau mengambil intisari pemikiran untuk kemudian diolah dan diceritakan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. “Kiri” yang tidak terdengar berat, berbahaya, apalagi perlu diwaspadai karena salah dan “jahat”.
Ayah angkat saya pernah menjadi tenaga administrasi di kantor kelurahan. Beliau juga editor bagi tulisan-tulisan kakaknya yang dikenal sebagai penulis sejarah di Jembrana. Sebelum mengirim tulisan ke koran, paman memperlihatkan pada ayah jikalau ada tanda baca, kata atau kalimat yang perlu diperbaiki, tentu dengan tanpa mengubah isi tulisan.
Pengetahuan beliau luas. Kegemaran membaca dan mendengar radio siaran luar negeri punya andil sehingga beliau selalu tahu apa yang terjadi pada banyak belahan dunia. Lalu menyampaikannya dengan gaya bicara yang meyakinkan dan menarik. Sehingga kami, anak dan cucu-cucunya, selalu ingin tahu apa kelanjutan yang beliau sedang bicarakan.
Generasi “lama” dan kini telah hilang yang hidup pada beberapa zaman bisa jadi hanya tinggal cerita; bagaimana sistem pendidikan di masa lalu berhasil membentuk pribadi yang kritis juga cerdas. Pola pendidikan Belanda turut berperan menghasilkan generasi yang berpikiran terbuka, suka akan pengetahuan baru, dan kerelaan serta kesukaan untuk berbagi ilmu.
Hal-hal tersebut yang kini sulit ditemui pada generasi sekarang di Indonesia. Minat baca buku menurun, kecanduan media sosial, kemampuan analisa yang rendah menjadi PR bersama tidak hanya bagi pendidik tapi juga para orang tua di rumah.
Hidup di dunia digital menjadi pilihan anak-anak dan remaja kita. Pengetahuan bahkan “banjir informasi” membuat berbagai penyakit mental menghantui seperti overthinking, stress, gangguan panik/cemas, depresi bahkan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia kini kian menjadi biasa.
Meski demikian, terdapat harapan jika kita melihat konten-konten baik itu teks atau video tentang ilmu dan buku-buku filsafat yang disajikan oleh anak-anak muda di media sosial. Itu akan menjadi bekal yang baik sehingga generasi muda kita mampu berpikir dan bersikap kritis tentang hal-hal yang ada di sekitar kehidupan mereka, misalnya saja tentang identitas, krisis jiwa, atau kesadaran akan hidup yang lebih berarti sebagai manusia. Filsafat juga bahkan akan mempertanyakan apa yang kita pikirkan karena ia berangkat dari keraguan. Sehingga, orang tidak mudah melabeli mereka yang membaca buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer sebagai “orang kiri” apalagi “komunis” hanya karena buku-buku tersebut pernah dilarang di Indonesia. Tuduhan dan hasutan yang bercampur sentimen pribadi dan kelompok, hanya akan membawa duka dan air mata; sesama saudara saling tikam dan bunuh, seperti tragedi 1965/66. Semoga kita semua mau belajar dari kejadian masa lalu. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis ANGGA WIJAYA


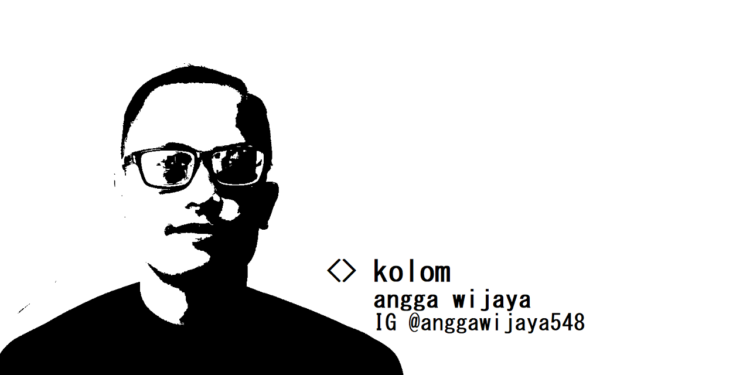
![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-75x75.jpg)



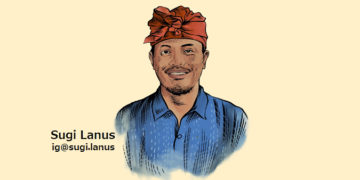













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











