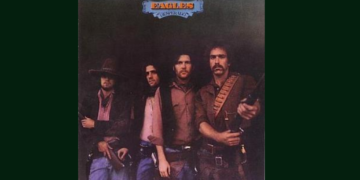TEMPAT pementasan di atas sungai itu kecil saja. Bahkan nyaris tak berjarak dengan penonton. Anyaman ulatan bambu di bawah atapnya tampak seperti liukan terasering di daerah Jatiluwih dan sekitarnya. Barangkali karena itulah tempat pementasan tersebut dinamai: Subak.
Itu salah satu tempat pementasan dalam gelaran Sthala Ubud Village Jazz Festival (UVJF) 2024 yang berlangsung di Sthala Hotel, Ubud, Gianyar. Di sana ada tiga tempat pertunjukan, memang. Di dekat pintu masuk festival ada Panggung Padi; di tengah berdiri Panggung Giri; dan di paling bawah, di dekat sungai dan beringin besar itu, terpacak Panggung Subak.
Dan di Panggung Subak inilah, Noé Clerc Trio—grup musik beraliran jazz asal Prancis—membawakan repertoar berjudul “Canson”, pada hari pertama festival, Jumat (2/8/2024) sore.

Noé Clerc Trio dari Prancis saat pentas di Panggung Subak UVJF 2024 | Foto: tatkala.co/Son
Noé Clerc Trio adalah band beraliran jazz yang digawangi oleh Noé Clerc sebagai pemain akordeon, Clément Daldosso pemain kontrabas, dan Elie Martin-Charrière yang bertugas menjaga ritme permainan mereka bertiga dengan drum-nya.
Menurut beberapa sumber dari internet, band ini dibentuk pada tahun 2018 dan langsung memenangkan kompetisi internasional sekelas “Leopold Bellan” (2018), lalu “Jazz à St Germain des Près” (2019), dan “Prix d’instrumentiste du festival Jazz à la Défense” (2021). Sebuah lesatan yang tak main-main.
Trio ini menelurkan album perdana berjudul ”Secret Place” yang diproduseri oleh seorang maestro akordeon asal Prancis, yang dijuluki Sun King of the Accordion, Vincent Peirani. Sebagai musisi jazz international, Vincent kerap pula menggelar konser turnya di Indonesia beberapa waktu lalu.
Menurut Vincent, ia tak lagi sendirian saat menebarkan kebahagiaan dengan menarikan jari-jemari di atas tuts mutiara akordeon. “Selamat datang, Noé!” seru Vincent yang, tentu saja, membuat bungah Noé Clerc Trio.
Tahun ini, Noé Clerc Trio termasuk band yang kerap kali riwa-riwi di festival-festival jazz di Indonesia. Pada Juli kemarin, mereka petas di Jazz Gunung Bromo yang digelar di Jiwa Jawa Resort, Probolinggo. Lalu berlanjut ke Surabaya untuk menggelar workshop dan sharing session bersama musisi jazz lokal.
Setelah itu, mereka tampil pada pertemuan jazz di Jakarta yang bertajuk “Bernama Jazz Summit” yang diselenggarakan di Auditorium IFI Thamrin. Kemudian mereka terbang ke Yogyakarta untuk konser dan jamming di Jazz Mben Senen di Bentara Budaya Yogyakarta.
Konser mereka ditutup dengan sangat menyenangkan sekaligus menenangkan di dalam suasana pedesaan di UVJF kemarin—yang membuat saya terdiam dan membayangkan banyak hal.
Interpretasi “Canson”
Noé Clerc memainkan harmonikanya—yang memiliki tuts seperti akordeon. Dia berdiri. Clément dan Elie terpaku menunggu momentum.
Suara alat musik yang baru kali pertama saya lihat itu, melengking, melambat secara tiba-tiba, merintih, dan tak jarang mendayu panjang. Suara instrumen tersebut saya pikir sangat cocok dengan suasana sore dengan paduan arus sungai, angin yang berkesiur, dan senja yang keemasan yang mendaulat Lodtunduh.

Noé Clerc saat memainkan harmonikanya | Foto: tatkala.co/Jaswanto
Ada perasaan yang belum ternamakan sebelumnya yang tiba-tiba saya rasakan saat mendengar Noé Clerc Trio membawakan repertoar mereka, “Canson”—salah satu dari sekian repertoar yang mereka bawakan di UVJF hari itu.
Bersama sore yang hangat, suara-suara setiap instrumen Noé Clerc Trio itu mengalir bagai mengikuti suatu garis penunjuk, tapi mereka juga seperti tidak betul-betul selalu mengikuti garis itu, kadang-kadang mereka berbelok entah ke mana—kontrabass ke mana, drum ke mana, dan harmonika ke mana.
Tiba-tiba harmonika, kontrabass, dan drum menghilang lantas kembali lagi, meloncat-loncat, menari, jungkir balik—semuanya tampak seperti improvisasi tapi tidak saling merusak. Bila tiba saatnya harmonika ditonjolkan, ketika Noé Clerc mendemonstrasikan kepiawaian individualnya, yang lain secara otomatis tahu diri untuk tidak mengacaunya.
Sebagaimana kata Seno Gumira Ajidarma, tentu saja permainan dengan kekacauan ini hanya bisa dilakukan para musisi yang sudah beres urusannya dengan ketertiban, tapi yang merasa segenap kaidah musikal tak cukup menyalurkan kebutuhannya untuk bicara lewat instrumennya.
Mendengar Canson, saya dapat membayangkan rintihan para minstrel sekuler—yang mencoba melawan “tangan besi” Katolik—Abad Pertengahan di Prancis yang keliling membawakan lagu-lagu bermuatan kisah tempat-tempat yang jauh atau tentang peristiwa sejarah.

Clément Daldosso dengan kontrabass-nya | Foto: tatkala.co/Jaswanto
Saya juga membayangkan sebuah tempat di mana penjajahan dan perbudakan masih berlaku. Tapi tiba-tiba, oh, ada suatu saat saya hanya cukup mendengarkan saja tanpa berpikir macam-macam, seperti kata John Fordham: “Anda tidak usah tahu musiknya untuk memahami rasanya….”
Menurut orang-orang yang bergelut di jazz, ini bukannya saya sok tahu, selain improvisasi, interpretasi adalah unsur penting dalam jazz. Dan Canson tentu saja sangat multitafsir. Bisa saja saat mendengar repertoar ini saya membayangkan seorang seniman musik tua Abad Pertengahan yang membawakan sebuah nyanyian atau musik narasi (balada) sambil keliling Prancis. Tapi bisa jadi bayangan Anda tidak demikian. Dan itulah jazz.
Canson bagi saya merupakan repertoar yang berkisah—entah apa, tergantung imajinasi masing-masing itu tadi. Ia seperti musik balada (ballad) berbentuk puisi yang mengisahkan sebuah cerita. Aspek repetisi bunyi yang terwujud dalam bentuk nada-irama sangat kuat dan terdapat banyak unsur refrain seperti pada sebuah nyanyian.
Berdialog Tanpa Kata
Jika diperhatikan betul suara instrumen Noé Clerc Trio satu per satu, maka kita akan mendengar betapa akordeon dan harmonika Noé Clerc saling kejar-mengejar dengan double bass (kontrabas) Clément Daldosso dan drum-nya Elie Martin-Charrière.
“Dengarkanlah apa saja dalam jazz maka kita akan mendengarkan instrumen yang berdialog. Itulah beda jazz dengan jenis musik lain. Jazz adalah suatu percakapan akrab yang terjadi dengan seketika, spontan, dan tanpa rencana,” kata Seno Gumira dalam salah satu roman urbannya.

Elie Martin-Charrière dengan drum-nya | Foto: tatkala.co/Jaswanto
Noé Clerc Trio seperti tidak ingin memainkan sebuah repertoar, tapi ingin mengungkapkan kata hatinya. Tapi karena bahasa kata seolah tak pernah cukup mewakili kata hatinya itu, maka dengan terampil mereka menyampaikan kata hati itu lewat suara instrumennya—seperti kata Seno Gumira tentang musisi jazz pada umumnya.
Ya, berbicara musik jazz, sekali lagi dalam sebuah roman metropolitan berjudul Jazz, Parfum, dan Insiden (2017) yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma, terdapat sebuah kutipan yang menarik. “Jazz isn’t music. It’s language. Communication.” Kutipan tersebut disampaikan Enos Payne—musisi asal Brooklyn, New York.
Apa yang dikatakan Enos tentu saja bukan sekadar cuap-cuap kosong yang nyaring bunyinya. Coba buka lembaran sejarah musik jazz, maka Anda akan menemukan riwayat kemanusiaan orang Afrika-Amerika yang tertindas. Dan inilah yang membuat penulis F. Scott Fitzgerald menyatakan datangnya Abad Jazz pada tahun ‘20-an menjabarkan suatu sikap.
Mengenai hal tersebut, Seno Gumira menulis, “… tentu Fitzgerald menyatakan pendapatnya dalam konteks pembebasan sebuah sub-kultur dari rasa rendah diri, yakni sub-kultur budak-budak hitam dari Amerika keturunan Afrika.”
Jazz, bagi sastrawan penulis Sepotong Senja untuk Pacarku itu, seperti hiburan, tapi hiburan yang pahit, sendu, mengungkit-ungkit rasa duka. “Selalu ada luka dalam jazz, selalu ada keperihan. Seperti selalu lekat rintihan itu—rintihan dari ladang-ladang kapas maupun daerah lampu merah.”
Lagu “Berta, Berta” dalam album Branford Marsalis, I Heard You Twice The First Time, tulis Seno lagi, sebuah nyanyian bersama tanpa iringan instrumen, tanpa bermaksud menjadikannya suatu paduan suara yang canggih, diiringi suara rantai terseret.[T]
BACA artikel lain tentang UBUD VILLAGE JAZZ FESTIVAL
Editor: Adnyana Ole