“Ini yang paling ramai sejak hari pertama,” ucap Erma yang berdiri di samping saya. General Manager UWRF ini harus berdiri dengan saya di sisi luar Alang-Alang Stage karena kursi yang disediakan sudah penuh.
Penonton terus berdatangan, mereka yang tidak mendapatkan tempat duduk akan berdiri seperti saya dan Erma. Kami menonton film “Eksil” yang diputar pada film program di acara Ubud Writer and Readers Festival (UWRF) 2024, Sabtu malam, 26 Oktober 2024.
Film dokumenter Indonesia karya Lola Amaria itu menjadi salah satu film atau bahkan satu-satunya film yang membuat Alang-Alang Stage seperti sebuah bioskop alternatif. Malam itu penonton penuh, dan yang menarik lagi banyak orang Indonesia yang hadir—biasanya setiap sesi acara UWRF ini didominasi oleh orang asing (bule), termasuk pemutaran film. Tapi, kali ini pemandangannya berbeda.
Jangankan kursi di dalam area Alang-alang Stage, di sisi luarnya pun, jika tidak rebutan posisi, maka sulit menonton dengan nyaman—karena layar di depan akan ketutupan tiang atau badan orang lain yang lebih tinggi.


Penonton memenuhi Alang-alang Stage pada pemutaran film Eksil di UWRF 2024 | Foto; tatkala.co/Rusdi
Kami menonton dengan senyap, bahkan orang-orang yang hadir menahan untuk berbisik-bisik. Selama pemutaran masih ada yang tiba-tiba berdatangan dan menyela barisan untuk mendapat posisi terbaik di hadapan layar.
Sepertinya ada semacam panggilan batin yang membuat orang-orang antusias memenuhi sesi nobar (nonton bareng) malam itu. Mereka tidak mendadak muncul dan ikut nonton begitu saja. Ada banyak rasa penasaran yang dibawa oleh mereka, termasuk saya pribadi.
Sejak kemunculannya pertama kali di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2022, film yang berdurasi 120 menit itu langsung mendapat penghargaan kategori best film. Setelah itu menjadi pembicaraan banyak orang, sampai soal desa-desus pelarangan pemutarannya.
Sesuai dengan namanya, Eksil merupakan film yang menyorot kisah yang dialami oleh para ‘eksil’ atau orang buangan—pelajar indonesia yang terdampar di luar negeri pasca konflik 1965. Kisah mereka—orang buangan—selama ini layaknya mitos yang jarang terdengar atau menjadi perhatian, kisah ini tidak akan pernah didapatkan di bangku sekolah maupun kelas-kelas perkuliahan.
Situasi pasca 1965 menggeser paradigma sosial kala itu. Apapun yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah bola api yang selalu dihindari, temasuk siapapun yang dianggap terafiliasi dengan itu. “Generasi pasca 65 dididik untuk membeci PKI, lewat propaganda film dan lain sebagainya.” Demikian petikan ungkapan dalam Film Eksil malam itu.
Bahkan orang yang pernah memiliki hubungan dengan Soekarno ikut terseret, karena Soekarna dianggap berpihak kepada PKI. Maka diambil kesimpulan siapa pun yang mendukung Soekarno harus dilenyapkan juga.
Sepuluh narasumber yang menjadi subjek Film Eksil adalah orang-orang yang dulunya pelajar atau mahasiswa yang dikirim oleh Presiden Soekarno untuk studi ke luar negeri.
Tetapi, setelah 65 mereka mengalami skrining dan dicap PKI, menjadi eksil; tidak bisa kembali ke bangsanya sendiri; kewarganegaraanya dicabut; dan luntang-lanting di negeri orang.
Bisa dibayangkan bagaimana perasaan para eksil kala itu; kesal bercampur rindu kampung halaman, kecewa dan kehilangan semua yang telah mereka bangun dan impikan. Perasaan mereka itulah yang berusaha ditangkap oleh Lola dalam filmnya—yang membuat saya dan peserta UWRF lainnya harus berkaca-kaca pada mata saat menonton malam itu.
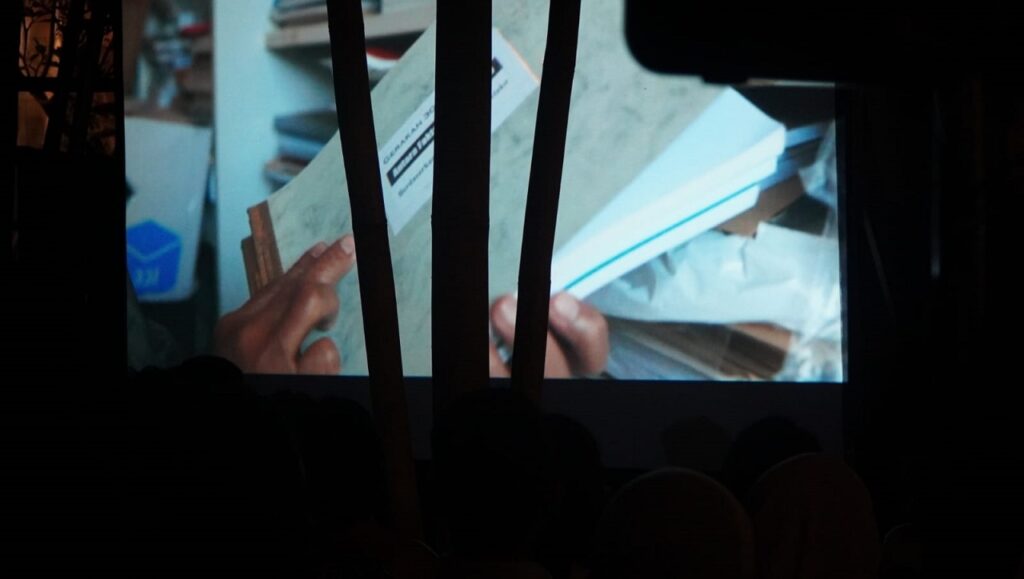
Pemutaran film Eksil di UWRF 2024 | Foto; tatkala.co/Rusdi
Kali ini saya beruntung, UWRF 2024 tidak hanya menggelar pemutaran film “Eksil”, tetapi mendatangkan juga Lola Amaria sebagai narasumber dan Eni Puji Utami sebagai moderator untuk sesi diskusi setelah pemutaran,.
Produser film Eksil itu datang menggunakan drees motif bunga yang memadukan antara warna putih dan ungu. Lola bercerita soal proses produksi hingga distribusi filmnya yang sampai 10 tahun, melalui jalan panjang yang bekelok-kelok.
“Ini bermula dari rasa penasaran dan takut,” ucap Lola Amaria saat sesi diskusi. Dua hal itu telah memicunya menggali tentang kejadian 65, yang kala itu masih tabu untuk diperbincangkan.
Lola yang melewati hidup di era 1990-an, menurutnya sedari zaman sekolah telah diberi tontotan wajib setiap tanggal 30 September, sebuah film berjudul Penumpasan Penghianatan G30S/PKI.
Ia tidak pernah punya kesempatan untuk bertanya seperti apa kejadian sebenarnya. Masa sekolahnya penuh dengan dokrin kebecian terhadap komunisme.
Dalam waktu yang bersamaan ia malah berpikir kenapa komunisme atau PKI itu bisa bersalah; kenapa mereka harus takut dengan PKI—banyak pertanyaan kritis tentang 65 yang muncul di kepalanya saat dulu.
Hanya saja situasi kala itu, guru dan orang-orang di sekitarnya membuat Lola takut untuk terus terang mempertanyakan konflik 65. Ia tidak bisa bertanya ke siapapun, kecuali mencari tahu sendiri.
Dalam penelusurannya, Lola menemukan banyak hal tentang PKI, mulai dari soal pembunuhan/pembantaian massal, buruh, gerwani sampai soal eksil yang menggelitik pikirannya dan kemudian mencari tahu lebih dalam tentang kisah eksil.
“Mereka tidak dibunuh atau tidak dipenjara tetapi mereka tidak boleh pulang, mereka dituduh, padahal mereka bukan PKI atau komunis. Mereka hanya mahasiswa yang dipilih Soekarno untuk dapat beasiswa dan nggak tau apa-apa,” terang Sutradara film Eksil itu di depan puluhan orang yang menonton malam itu.
Lola merasa heran kenapa aset negara yang sebenarnya para intelektual seperti itu malah menjadi korban karena dikaitkan dengan Soekarno yang mengirim mereka ke luar negeri. Mereka malah dikhianati oleh bangsanya sendiri.
“Mereka 32 tahun di negara orang, badannya aja di Eropa tapi hati mereka itu di sini (Indonesia),” lanjut Lola.
Di balik kaca mata beningnya, kedua mata Lola sedikit memerah dan berair. Sepertinya emosional Lola terpantik karena ia telah menampung seluruh perasaan dan cerita yang begitu bermakna dari para eksil—selama ia mengunjungi mereka di luar negeri kala itu.
Lola Amaria Sempat Dikira Intel Oleh Para Eksil dan Hampir Putus Asa
Lola adalah seorang produser film dan sutradara, sekitar tahun 2012-2013 ia mendapat undangan screening film di Jerman. Selama satu minggu di sana, lalu bertemu seorang teman yang memperkenalkannya ke seorang bapak, yang ternyata adalah seorang eksil.
Lewat pertemuan itu, Lola terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada bapak itu dan bagaimana nasib para eksil lainnya. Dan ia keget, di tahun 2013, kata bapak itu, ada lebih dari 200 orang yang dikenal sebagai eksil di Eropa, yang tersebar dari eropa barat dan timur.
Saat itu juga Lola meminta kontak para eksil dan menghungi mereka, “Ada sekitar 50-an orang yang saya dapatkan kontaknya,” ucap Lola.
“Kemudian saya ke Belanda dan bertemu beberapa dari mereka, saya bermodal HP aja, lalu saya rekam dan tanya mereka,” lanjutnya.

Lola Amaria dalam diskusi usai pemutaran film Eksil di UWRF 2024 | Foto; tatkala.co/Rusdi
Beberapa dari eksil yang ia temui ada yang awalnya dikirim ke Tiongkok lalu pindah ke Uni Soviet (sekarang Rusia) dan berakhir di Belanda; ada juga dari Swedia berakhir di Belanda; dan statusnya bermacam-macam.
Saat menelusuri para eksil itu ia sempat dimarahi, ditolak dan dikira intelegen. “Kamu ini siapa? Siapa yang mengutusmu? Berapa kamu dapat dana? Siapa di balik organisasi kamu ini, kata mereka ke saya,” ucap Lola.
Kecurigaan itu tentu hadir karena para eksil punya pengalaman traumatis yang tidak pernah kita bayangkan. Bahkan salah satu eksil di filmnya Lola memberikan keterangan pernah memiliki pacar saat di Belanda yang ternyata adalah seorang intel yang dikirim pemerintah.
Lola sempat berada di titik di mana ia ingin berhenti. Penerimaan eksil terhadap dirinya tidak semulus rencana film yang ia susun. Satu tahun ia terhambat melanjutkan projectnya. Sampai ia mencoba menghubungi temannya di Amsterdam untuk membantunya.
“Saya minta tolong untuk meyakinkan para eksil kalau saya bukan intel, saya tidak berbahaya, dan saya kasih film-film yang pernah saya buat agar mereka tau kalo saya ini hanya pembuat film,” terangnya.

Diskusi usai pemutaran film Eksil di UWRF 2024 | Foto; tatkala.co/Rusdi
Berkat bantuan temannya itu ia berhasil meyakinkan sekitar 30 eksil dan diantaranya adalah perempuan. Hanya saja, cuma 10 orang yang mau terlibat dalam produksi film dokumenternya. Para eksil lain merasa takut untuk lebih jauh muncul di permukaan. Menurut Lola, mereka masih takut dan tidak tahu siapa yang akan menjamin mereka beserta keluarganya yang ada di Indonesia jika mereka muncul ke publik.
Lola akhirnya syuting tahun 2015 dan hanya memiliki tim lima orang termasuk dirinya. Narasumber yang terpilih antara lain Asahan Aidit (alm), Chalik Hamid (alm), Djumaini Kartaprawira (alm), Kuslan Budiman (alm), Sardjio Mintardjo (alm), Sarmadji (alm), Hartoni Ubes, I Gede Arka, Tom Iljas, Waruno Mahdi, Herutjagio Mintardjo, dan Nurkasih Mintardjo.
Keluarga dan Kerabat Eksil Ikut Hadir di UWRF 2024
Sebelum menutup ceritanya, Lola memanggil seorang pria berbaju kuning dengan badan yang kekar dan warna kulit sawo matang seperti saya. Ia melangkah ke depan dan duduk di sebelah kanan Lola.
“Nama saya Manto dan bapak saya eksil yang tidak bisa kembali ke Indonesia,” ucap pria itu.
Manto adalah anak seorang eksil yang hidup di Tiongkok sejak kecil, lalu sekitar umur 6 tahun ia bersama ayahnya pindah ke Belanda. Kini ia telah menjadi seorang bapak.
Ia tumbuh dan besar di luar negeri, tapi entah bagaimana saat berbicara Manto begitu fasih berbahasa Indonesia. Suaranya bulat mengucapkan setiap kata dan kalimat Bahasa Indonesia. Saya tidak mau heran sebenarnya, tapi umumnya orang yang tumbuh dan besar di luar negeri tidak akan selancar itu berbicara dalam Bahasa Indonesia.
Kebetulan saat itu, Manto sedang berlibur di Bali dan langsung dikontak oleh Lola untuk ikut nonton “Eksil” di acara UWRF.
Manto pertama kali ke Indonesia umur 30 tahun, dan merasa sedih atas apa yang dilakukan oleh bangsanya, terhadap ayahnya.
“Di Belanda kami dikasih passport stateless person, khusus untuk orang yang tak berkewarganegaraan. Dan bapak saya, sampai ia meninggal, tidak pernah mau mengambil status kewarganegaraan Belanda,” ucap Manto dengan mata yang sedikit berkaca-kaca.
Badan Manto memang besar dan kekar tetapi saat ia bercerita perasaannya tidak bisa menipu
Ayahnya selalu meyakinkan Manto bahwa mereka adalah orang Indonesia, sampai kapan pun. Dan ayahnya selalu merasa ia adalah Soekarnois, bukan PKI.
Persis seperti itu juga yang dirasakan oleh para eksil di film, mereka mengakui bahwa dirinya utusan Soekarno dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan ideologi atau partai politik manapun kala itu.

Lola Amaria berincang dengan penonton | Foto: tatkala.co/Rusdi
Diskusi malam itu semakin menyita perhatian saya, seorang ibu tiba-tiba mengacungkan tangan untuk menyampaikan sesuatu. Saat diberi kesempatan oleh moderator, ia tidak ingin berdiri, hanya duduk. Seolah tidak ingin disorot oleh kamera, bahkan tidak sempat memberitahu namanya.
“Adik bapak saya juga seorang eksil,” katanya. Ibu itu hadir dengan seorang anak perempuan. Dan ia tidak pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi terhadap pamannya.
Belum sampai tiga kalimat yang ia ucapkan, ibu itu tiba-tiba meneteskan air mata. Baginya setelah menonton eksil seperti diingatkan kembali dengan pamannya dulu. Tidak banyak yang ia ceritakan, tapi ia sangat berterima kasih terhadap Lola untuk film yang menyentuh perasaan itu.
Saya merasakan hal yang sama, film Eksil menyita emosional. Puncaknya ada di akhir film ketika Lola Amaria dan tim pamit kepada para eksil di luar negeri. Mereka melambaikan tangan kepada Lola seolah itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dan benar saja, beberapa eksil telah meninggal, sesaat setelah Lola di Indonesia dan film itu tayang saat ini.
Karena ingin lebih dekat mendengarkan cerita Lola, saya memutuskan menyerobot kerumunan penonton dan mencari posisi yang memungkinkan kaki tidak cepat keram atau pegal. Kebetulan saat itu juga ada seorang yang minggalkan kursinya di depan, tentu tanpa pikir panjang langsung saya duduki.
Tepat di kursi sebelah saya, duduk seorang perempuan dengan kaca mata dan baju hitam yang dipadukan dengan rok putih bermotif bunga. Rambutnya diikat ke belakang dan menggunakan tas kulit coklat, tentunya bukan kulit buaya. Kalung yang ia pakai memiliki permata hitam seukuran biji nangka. Saya pikir ia kolektor batu akik.
Awalnya saya tidak begitu memperhatikannya, sampai ia menyatakan hal yang mengejutkan bagi saya bahkan orang-orang di sana saat itu.
“Waktu di Jogja saya bersama suami cepat-cepat harus menonton film ini, jaga-jaga film ini akan di-breakdown. Tapi, bukan karena kami ingin tercerahkan soal 65, kami sudah tercerahkan oleh film-film sebelumnya,” ungkapnya.
Lalu tiba-tiba ia mengatakan, “Kami kangen dengan Pak Min. Saya dan suami adalah dua dari mahasiswa yang selalu mendatangi Pak Min atau Pak Kuslan.”
Seketika itu ia langsung menjauhkan mic dari mulutnya, sedikit gemetar seperti tersendak. “Aduh jangan,” ucapnya pelan.
Ia hampir saja meneteskan air mata, seorang ibu yang duduk di sebelah langsung memegang pundaknya dan menguatkannya. Saya menunggu air matanya menetes, barangkali tisu di dalam totebag yang saya bawa akan berguna.
Ia mengatur napas dan lanjut berkata “Saya bukan keluarga tapi mereka seperti bapak bagi kami mahasiswa-mahasiswa di Belanda,” ucapnya soal Pak Min atau yang bernama asli Sardjio Mintardjo, salah satu narasumber film Eksil itu.

Penonton tampak puas usai menonton film Eksil di UWRF 2024 | Foto: tatkala.co/Rusdi
Tidak ada respon dari Lola atas apa yang diucapkan perempuan itu. Hanya senyuman singkat tetapi tampaknya amat bermakna. Barangkali Lola sadar perempuan itu hadir bukan untuk bertanya atau menginginkan jawaban darinya. Melainkan hanya ingin mengatakan ke semua orang tentang apa yang ditayangkan malam itu adalah kebenaran yang terabaikan selama ini. Sebab, ia sendiri pernah menjadi saksi kisah hidup para eksil itu di negeri orang.
Perempuan itu bernama Rhomayda, dari Jogja sengaja datang untuk menonton film Eksil yang diputar pada UWRF 2024. Dulu selama di Belanda ia dan mahasiswa lain sering mengadakan acara diskusi atau hanya sekadar ngumpul di rumah Pak Min. Dan bagi Pak Min sendiri, kehadiran mereka adalah obat untuk kerinduannya terhadap bangsa.
Bertemu dengan mahasiswa Indonesia bagi Pak Min sama saja dengan ia merasa berkumpul dengan keluarganya di kampung.
Sejak di Belanda, Rhomayda baru tahu soal-soal tentang 65. Awalnya ia tidak tahu apa-apa, bahkan sempat tidak mengetahui kalau Pak Min adalah orang yang dibuang bangsa Indonesia. Baru ketika sering mendengar cerita seniornya di Belanda-lah yang mendorong Rhomayda kembali membaca sejarah kelam bangsanya sendiri.
Saat berbincang dengan saya setelah sesi diskusi, Rhomayda mengatakan salah satu kekuatan film ini adalah sisi humanity-nya. Berbeda dengan film lain yang lebih menampilkan sisi yang keras dan mengerikan. Menurutnya filmnya Lola Amaria berhasil menyentuh hati setiap orang yang menonton.
Saya memahami betul apa yang disampaikan perempuan Jogja itu. Beberapa kali rasa-rasanya mata saya seolah-olah berair ketika khusuk menonton. Sungguh, semakin mendekati menit-menit akhir film ini semakin memancing sisi cengeng semua orang.
Haru demi haru menguar di Alang-alang Stage, dan sekitarnya, di UWRF 2024 ini, dengan tetes air mata atau tanpa tetes air mata.
Apalagi ketika momen seorang eksil yang dikubur dengan diiringi lagu Indonesia Pusaka. Sepertinya bukan hanya saya, semua orang mulai berkaca-kaca saat menyaksikkan momen itu di layar. Betapa seorang yang rindu bangsanya, di sisa hidupnya pun berwasiat untuk diiringi pemakanannya dengan lagu Indonesia Pusaka, walau dirinya dikubur di tanah orang asing. [T]
Reporter/Penulis: Rusdy Ulu
Editor: Adnyana Ole





























