KEMARIN, saat duduk di bangku depan sebuah warung seusai mengantar tunangan saya bekerja, seorang ibu berhenti tepat di dekat saya. Dari atas sepeda motor, dia menanyakan tentang keberadaan saya; bekerja apa, tempat kerja saya di mana, dan pertanyaan ringan lainnya yang mungkin bertujuan untuk mencairkan suasana di antara kami.
Awalnya saya tidak merasa curiga, tapi seiring percakapan mengalir, saya merasa ibu itu hanya ingin didengarkan. Dia menyampaikan tentang kakinya yang bengkak dan berhubungan dengan penyakit dalam, antara sakit ginjal dan sakit jantung. Saya lebih banyak menyimak apa yang ia sampaikan, kemudian menyarankan untuk berobat rutin ke dokter; apalagi sejak lama ada jaminan kesehatan nasional (JKN) dimana banyak jenis penyakit bisa diobati secara gratis.
Di tengah kehidupan kini yang bergerak pada individualisme, ruang-ruang percakapan dan dialog memang semakin hilang. Jika dulu masyarakat punya kebiasaan mengobrol dengan tetangga, saudara, guru atau para tetua adat, sekarang apalagi sejak adanya ponsel pintar, kesempatan untuk berinteraksi di dunia nyata semakin jarang kita temui sehari-hari.
Orang-orang lebih memilih asyik sendiri dengan ponsel pintar mereka, hingga tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Bahkan, ketika ada acara bersama misalnya pertemuan atau acara ngopi bersama rekan kerja, perhatian mereka lebih banyak pada layar ponsel; entah menjawab pesan, melihat media sosial atau saling membalas komentar dari sebuah kiriman/posting.
Kondisi inilah kemudian membuat orang-orang yang rentan secara psikologis atau istilah resminya orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) kehilangan tempat untuk berbagi, bahkan untuk sekadar ‘curhat’ pun sulit. Seperti cerita seorang ibu di awal tulisan ini, bisa jadi ia termasuk ODMK, walau jika dilihat secara sepintas ia normal-normal saja; berpakaian wajar, mengendarai sepeda motor dengan lancar, namun ada “sesuatu” pada dirinya.
Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Bali memang tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi pengidap skizofrenia atau psikosis tertinggi di Indonesia. Prevalensinya mencapai 11,1 per 1.000 rumah tangga. Ini berarti, dari setiap 1.000 rumah tangga di Bali, terdapat sekitar 11 rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan skizofrenia atau psikosis. Sebagai perbandingan, prevalensi skizofrenia/psikosis secara nasional pada tahun 2018 adalah 6,7 per 1.000 rumah tangga.
Saya sendiri adalah penyintas skizofrenia, pertama kali didiagnosa oleh psikiater pada 2009. Sejak itu pula saya berobat secara rutin, menginiasi berdirinya komunitas kesehatan mental di Denpasar, Bali, bersama kawan-kawan senasib berkumpul secara rutin untuk mendapat informasi dan pengetahuan tentang skizofrenia. Juga, saling menguatkan satu sama lain dalam proses pengobatan dan pemulihan. Selain itu juga memberi edukasi kepada masyarakat luas.
Dulu, saya sering merasa menjadi ‘pesakitan’ — orang ‘khusus’ yang berbeda karena pengaruh stigma yang masih kental di masyarakat, termasuk di Bali yang mana gangguan mental sering dihubungkan dengan hal-hal gaib seperti terkena black magic, kutukan leluhur atau bahkan karena karma phala atau buah dari perbuatan di masa lalu atau masa kehidupan terdahulu.
Padahal, sejatinya, gangguan mental adalah murni karena penyakit pada organ otak. Terdapat ketidakseimbangan zat kimiawi atau neurotransmitter yang bisa diobati dengan obat-obatan psikiatri, selain dengan psikoterapi dan metode pengobatan medis modern yang semakin maju.
Sekarang, rasanya saya tidak perlu lagi menyampaikan pada orang banyak bahwa saya penyintas skizofrenia, kecuali dalam konteks dan tempat yang tepat; misalnya untuk memotivasi sesama penyintas gangguan mental untuk rajin minum obat dan tetap semangat menjalani proses jatuh-bangun dalam perjalanan mereka untuk pulih, kembali berkarya dan berdaya.
Masalah kesehatan mental kini telah menjadi hal yang umum. Ada yang sadar mereka ‘sakit’ lalu mencari pertolongan psikolog/psikiater, ada yang memilih pengobatan secara religi/budaya/tradisi, lebih mendekatkan diri pada tuhan dengan juga misalnya menekuni meditasi dan atau yoga.
Ada pula yang tidak sadar, bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka. Kondisi terakhir ini yang perlu mendapat perhatian. Agar tidak membebani diri sendiri dan keluarga, bahkan membahayakan; lari pada hal-hal negatif yang malah memperburuk kondisi mereka. Alih-alih meredakan gejolak atau tekanan yang dihadapi, ‘pelarian’ itu justru malah membuat mereka semakin jauh dari kesempatan untuk mengenal diri, dan mencari pertolongan dan support system yang mampu mendukung pemulihan dari gangguan mental maupun gangguan kepribadian.
Peran negara, komunitas adat, pemerintah daerah, sekali lagi amat penting. Program konsultasi dan pengobatan kesehatan gratis belum menyentuh kesehatan mental; hanya kesehatan fisik saja. Padahal, kesehatan jiwa-raga secara holistik penting. Tidak hanya sehat fisik saja, atau sehat mental saja. Keduanya sebagai satu-kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Pada pemahaman saya kini, yang telah menjalani enam belas tahun pengobatan skizofrenia, bahwa setiap orang pernah terluka dan sakit. Jadi, tidak perlu menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami. Seorang anak yang telah banyak membaca atau mengkonsumsi konten-konten kesehatan mental di media sosial, kemudian menyalahkan orang tuanya sendiri karena pada sebuah titik ia mengalami depresi, misalnya, sebenarnya adalah keliru dan kurang bijaksana.
Saya setuju jika ada yang mengatakan setiap orang tua telah melakukan hal terbaik bagi anak-anak mereka. Jika pun terdapat kekeliruan misalnya pada pola asuh, hal tersebut juga merupakan ‘hasil” dari orang tua-nya orang tua kita, semacam pengulangan yang tanpa sadar dilakukan.
Orang tua kita pada zaman dahulu tidak tahu atau punya sedikit informasi tentang kesehatan mental. Banyak dari mereka yang juga tidak mengenyam pendidikan tinggi. Berhenti untuk saling menyalahkan dan fokus serta kembali pada diri sendiri merupakan langkah maju untuk bisa pulih dari berbagai jenis gangguan mental, baik itu depresi, skizofrenia, bipolar, dan lainnya. Hidup mesti terus berlanjut, bukan? Tidak menutup kemungkinan ketika kita menjadi orang tua nantinya juga tidak melakukan kekeliruan pola asuh pada anak-anak kita. Ya, semua orang pernah sakit dan terluka. Jika melihat dari sudut pandang itu, rasanya seberat apapun penderitaan dari sakit yang kita alami, pasti akan mampu kita hadapi dengan penuh semangat dan optimisme. Salam. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis ANGGA WIJAYA


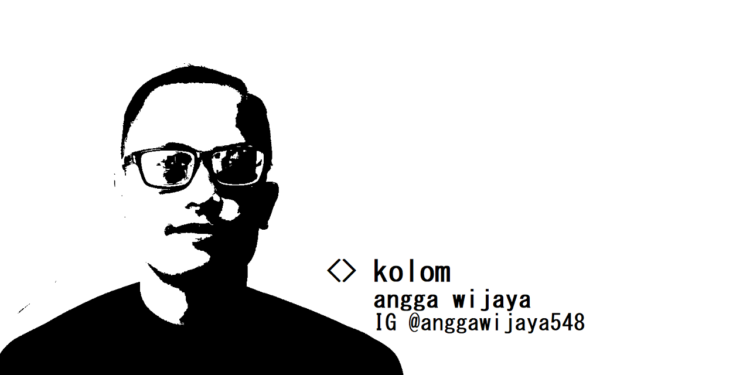



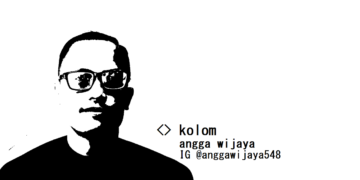













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











