BEBERAPA KEKELIRUAN
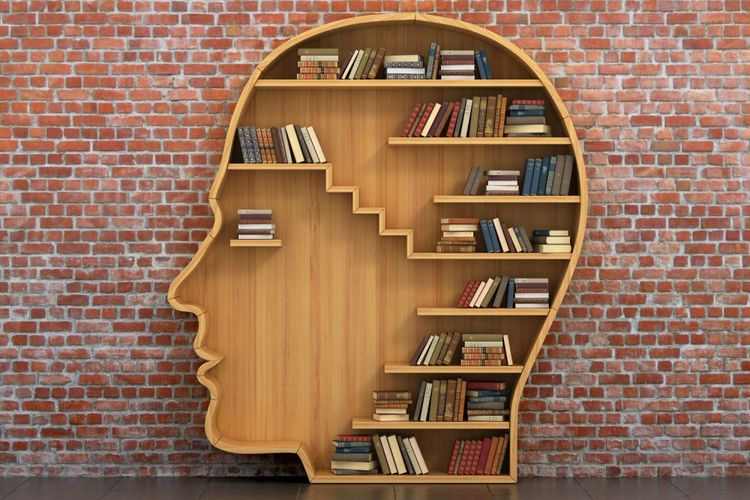
.
Foto di atas adalah ilustrasi tulisan yang membahas literasi dasar di kompas.com (4/4/2021). Sebuah rak buku yang menempel di tembok bata yang sangat indah. Rak ini berbentuk kepala manusia. Yang ditonjolkan adalah otak, identik dengan isi terpenting kepala manusia. Buku mengandung makna pengetahaun. Hal ini masih sejalan dengan ungkapan bahwa buku adalah Gudang ilmu. Sebagai tempat menyimpan pengetahuan, buku pada rak tersebut menunjukkan isi otak manusia ada;ah berbagai pengetahuan. Tapi, otak manusia tidak hanya terisi pengetahuan.
Pada saat membicarakan literasi, foto di atas dapat memberi definisi literasi dengan sederhana dan mudah dipahami. Literasi adalah pengetahuan manusia. Telah dipahami sejak Barat melewati abad gelap, pengetahuan disimpan di dalam buku. Para penulis menyusun pengetahuan di dalam buku-buku mereka. Wallace menulis pengetahunnya mengenai anggrek kantong semar dalam Sejarah Nusantara. History of Java karya Rafles juga demikian.
Di seberang penulis buku ada pembaca. Mereka membaca untuk mendapat pengetahuan. Manusia membaca adalah tahap selanjutnya ketika masyarakat lisan ditinggalkan semenjak diciptakan aksara, ditemukan teknologi awal tulisan hingga mesin cetak dan berujung pada abad kapitalisme cetak.
Sejak itu manusia di dunia memasuki budaya baca. Mereka amendapat pengetahuan dengan membaca. Ketika literasi adalah membaca (membaca 15 menit) maka ini dapat dipastikan merujuk pada aktivitas membaca.
Mengatakan literasi sebagai atau sama dengan membaca adalah kekeliruan. Sejak GLN, literasi disamakan dengan membaca buku. Dan, sejak itu pula, terjadi demam literasi. Kata ini sangat populer dan bisa dipasangkan dengan apa saja, seperti visual, musik, lingkungan, budaya, politik, dll. Hampir seluruh kata dalam kamus, nyaman dan enak dikombinasikan dengan kata literasi.
Karena itu, literasi sejatinya adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Pengetahaun yang memberi kecakapan hidup. Pengetahuan sebagai kekuatan (knoledge is power). Pengetahuan sebagai senjata (saking tuhu manah guru). Semua khazanah pengetahuan manusia adalah literasi.
Tapi, apa sebabnya, literasi diartikan dengan membaca?
Kembali kepada hubungan aksara, buku dengan (sebagai) tempat menyimpan pengetahuan. Aksara dan pustaka hanyalah teknis atau teknologi semata untuk membantu ingatan manusia yang terbatas. Manusia tidak lagi harus mengingat sejumlah besar pengetahuan karena kemampuan yang terbatas karena telah disimpan dalam tulisan/buku. Tapi manusia harus memiliki budaya baca. Membaca dapat meringankan kerja otak dalam mengingat.
Beberapa bangsa di dunia memang tidak bernasib baik seperti barat dan sejumlah negara di timur. Bangsa yang malang itu tidak memiliki budaya baca atau ada politik pengetahuan lokal untuk sengaja mebuat mereka buta aksara. Aksara Bali dan orang Bali menjadi contoh yang menarik. Ironisme yang tidak disadari. Hal ini tentu disebabkan oleh faktor-faktor politik, sosiologis, dan ekonomi. Sampai dunia memasuki kelisanan kedua dengan ditemukannya televisi, bangsa-bangsa yang malang itu, bemum memasuki fase baca.
Maka definisi literasi di kalangan bangsa-bangsa yang belum memiliki budaya baca adalah literasi disamakan dengan membaca. Definisi ini merujuk aktivitas yang terjadi di negara-negara maju. Difinisi literasi di kalangan bangsa yang malang selesai pada aktivitasnya dan tidak sampai kepada tujuan: mengumpulkan pengetahuan untuk memenuhi hasrat ingin tahu.
Definisi yang keliru ini masih digunakan di kalangan GLN. Berbagai program atau gerakan literasi fokus pada membaca. Bahkan lebih keliru lagi ketika membaca adalah tujuan. Dalam literasi, membaca adalah jalan untuk mencapai tujuan. Hasrat ingin tahu manusia dipenuhi dengan cara membaca karena membaca adalah jalan untuk mencapai tujuan itu.
Di tengah kekeliruan memilih definisi literasi, maka politik literasi nasional dan jaringan kerja yang dibangun di seluruh Indonesia berkubang dalam memecahkan persolan bahan bacaan, distribusi buku, buku murah, donasi buku, dan entah apa lagi yang selalu terkait dengan buku. Maka di seantero negeri muncul berbagai gerakan amal buku. Di bawah payung GLN, menyumbangkan buku adalah amal yang mulia. Buku ternyata tidak menyelesaiakan perkara literasi bangsa. Inti persoalan literasi belum disentuh; hasrat pengetahuan masyarakat! Seakan buku mampu menyelesaikan persoalan literasi!
Definisi yang keliru juga berdampak pada pandangan bahwa manusia hanya mendapat pengetahuan dengan membaca. Bagi bangsa yang lisan, pengetahuan didapat dengan cara lisan. Pandangan ini menimbulkan kekeliruan kedua. Seolah hanya lewat membaca, pengetahuan itu diperoleh. Orang-orang Tibet memanen madu. Pengetahuan ini didapat bukan dengan cara membaca buku. Petani di Bali tidak membaca buku pertanian sama sekali.
Dengan berpijak pada konsep “literasi adalah pengetahuan” maka ada dua jalan besar untuk mendapatkannya: membaca dan lisan. Karena itu, literasi tidak hanya identik lagi dengan buku dan membaca. Literasi juga adalah lisan.
Gerakan-gerakan literasi yang masif juga mengantongi kekliruan lain. Literasi hanya membaca. Lalu buku katanya tidak ada! Karena itu, literasi baru terjadi ketika sudah ada buku. Bentuk nyata kekeliruan ini adalah pada GLS. GLS banyak mengembangkan program dekorasi sekolah dengan pojok baca, pohon literasi, membaca 15 menit. GLS dan gerakan literasi komunitas/masyarakat/keluarga tidak pernah membalik arah relasi dari buku dan membaca ke menulis dan buku. Sehingga literasi juga bisa dimulai dengan kegiatan menulis. Jika buku tidak ada, kenapa tidak nulis buku? Bukankah titik awal atau sejarah pengetahuan dari menulis yang melahirkan buku? Sebagian buku memang memindahkan ingatan sosial yang penuh oleh khazanah pengetahuan. Sejarah pengetahuan selanjutnya di era modern, setelah Eropa keluar dari abad gelap tentu saja konstruksi. Mendel suntuk mengkonstruksi, mengkaji, meneliti perkara genetika di tengah keheningan kebun anggur biaranya. Clifford Geertz menghasilkan tiga varian masyarakat Jawa ketika mengkonstruksi agama Jawa (religion of Java): abangan, santri, priyayi.
EVOLUSI
Manusia mulai hidup lisan dan sedikit visual dinding gua, tanpa aksara. Tapi konstruksi pengetahuan tidak terbendung sama sekali. Otak satu-satunya tempat menyimpan pengetahuan dengan cara mengingat. Resep atau ramuan obat dihafal oleh para tabib. Epos diceritakan setiap malam. Memori kolektif bekerja seperti perpustakaan umum atau ensiklopedi terbuka (Wikipedia). Siapa saja dalam dunia lisan bisa melakukan penyuntingan ketika menyimpan pengetahuan atau saat menuturkannya. Di tengah masyarakat lisan selalu lahir episentrum-episentrum ingatan, seperti kaba, tukang cerita, dalang, juru pantun. Khusus di tengah keluarga, episentrum ingatan itu adalah nenek dan cerita pengantar tidur.
Aksara ditemukan lebih awal puluhan abad ketimbang teknologi tulis. Namun kelak menjadi fondasi bagi kebudayaan cetak. Setelah teknologi kuno tulis ditemukan di berbagai pusat peradaban dunia, kerja manusia dalam mengingat khazanah pengetahuan, menjadi lebih ringan. Ada otak baru atau ada memori baru yakni naskah-naskah dari bahan alam (kulit kambing, bambu, daun tumbuhan, dan kulit kayu) tempat pengetahuan disimpan pada kode aksara. Pengetahuan ditulis.
Produk teknologi naskah-naskah kuno tersedia terbatas dan ada di bawah ancaman serangga, perang, dan musim yang basah. Hal ini dalam rentang sejarah yang panjang, baru ditanggulangi dengan tumbuhnya skriptorium. Di sini naskah disalin dan diubah oleh kuasa para penyalin yang tekun!
Pengetahuan semakin menjanjikan menjadi komoditas setelah mesin cetak ditemukan. Ketika pada masa naskah, episentrum-episentrum pengetahuan dikelilingi oleh kelisanan yang sangat luas. Lewat episentrum ini, pengetahuan disebar secara lisan. Artinya, periode naskah tidak sanggup membawa umat manusia memasuki era baru: membaca atau melek aksara. Hal ini baru tercapai sejak mesin cetak dan perkembangan pesat teknologinya (mesin tik, offset, foto kopi, percetakan, mesin tik elektrik, hingga computer tanpa jaringan) serta dibangunnya sekolah di seluruh dunia.
Inilah era baru umat manusia, dengan penegcaualian bangsa-bangas terjajah di Asia dan Afrika. Kapitalisme cetak. Industri buku, koran, majalah, tabloid, teka-teki silang, komik, novel, buku pelajaran, peta, panduan wisata, referensi, kamus, ensiklopedi, novel cabul, buku judi, buku ilmu hitam dan racun, hingga resep masakan. Semua itu dihasilkan lewat proses yang dijelaskan pada kutipan di bawah ini.
Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Percetakan merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan. (Wikipedia)
Manusia mengalami era cetak ternyata hanya selama 500 tahun. Kini telah berakhir. Era cetak membangun dua kutub yang salah satunya menjadi subordinat. Yang satu kutub lagi menguasai. Penerbit, toko buku besar, pers, tumbuh kuat dan meraih keuntungan besar. Kuasa modal atau kapital di industri percetakan dan penerbitan juga menimbulkan kuasa poltiik dan kuasa sosial. Dengan ini, kuasa cetak mengendalikan arah dan konsumsi pengetahuan masyarakat. Di sana bekerja para monster redaktur penjaga pengetahuan yang dikanonkan. Mereka menguasai distribusi atau jaringan kekuasan dan pasar informasi/pengetahuan.
Kutub-kutub yang saling bertentangan misalnya tampak pada oposisi penulis dan masyarakat pembaca; koran atau pers dengan massa. Kuasa mereka yang berkembang terlalu besar menyebabkan masyarakat bergantung. Bahkan kekuatan pemerintah atau politik pun tidak bisa menandingi dan ini terbukti dari terjadinya persekongkolan di antara mereka. Reproduksi dan distribusi pengetahuan dikendalikan oleh kekuatan kapitalisme cetak.
Kini kekuatan itu telah diruntuhkan oleh era disrupsi. Kuasa cetak tidak ada lagi karena teknologi baru dan dampak pandangan baru itu pada mindset masyarakat. Teknologi baru ini lengkap dengan generasinya. Generasi cetak sudah mentok. Diskontinyuitas sejarah terjadi pada kaum tua. Teknologi ini seolah mengubur potongan sejarah yang sangat penting. Masa 500 tahun semenjak mesin cetak ditemukan. Jika ada persambungan maka hal ini hanya datang dari sejarah yang sudah jadi masa lalu. Tidak diperlukan lagi oleh generasi teknologi digital.
Sejalan dengan literasi, yang dari lima abad lalu dan kini telah beralih karena revolusi disrupsi; mencoba merangkul era baru, dengan memunculkan literasi digital. Sebelum era ini, umat manusia ada pada literasi kertas atau cetak. Sejarah pengetahuan manusia terentang dalam periode panjang yang hanya terdiri atas tiga fase besar: (1) lisan, (2) tulis, dan (3) digital. Literasi digital memang muncul dalam gerakan literasi. Kehadiran buku sebagai kelanjutan kehidupan lisan, tidak menimbulkan guncangan yang berarti di dunia. Seakan tulisan adalah berkah bagi lisan. Bukan ancaman dan kemunduran. Tetapi pencapaian baru yang lebih hebat. Disrupsi dan digitalisme sebaliknya! Bahkan dalam politik literasi pun digitalisme mendapat ruang yang sangat penting untuk mengatasi ancaman-ancaman digital. Atau gilasan revolusi. Buktinya nyata dengan pencetusan literasi digital sebagai salah satu dari enam literasi dasar.
Literasi digital dikaitkan dengan teknologi informasi atau internet adalah segalanya. Dunia yang menjadi oposisi terhadap kertas, buku, dan perpustakaan. Ruang pengetahuan manusia beralih dari kertas/cetak ke digital, drive, internet, ke berbagai mesin pencari kata. Mesin pencari kata adalah cara baru untuk mendapatlan berbagai pengetahuan. Misalnya perusahan Google dipandang telah menutup pintu-pintu perpustakaan. Demi digitalisme, sumber pengetahuan analog/kertas/cetak bermigrasi ke virtualisme digital.
Tetap saja literasi digital berurusan dengan pengetahuan sebagai bukti esensi literasi bergeming. Relasi-relasi antara manusia dan pengetahuan berlangsung di dalam dunia digital. Walaupun terjadi peralihan besar abad ini, esensi literasi tetap: pengetahuan.
Sebagai akibat 500 tahun manusia hidup dalam teknologi cetak (tinta, kertas), teknologi digital memberi rasa tidak nyaman di tengah paksaan untuk melakukan migrasi digital. Paksaan yang tidak bisa ditolak! Sementara itu digitalisme melahirkan generasinya sendiri, yakni para digital native. Literasi dari perspektif kaum digital migran memandang literasi digital bukan sebagai literasi. Alasannya hanya soal infrastruktur fisik literasi, kertas! Kaum digital migran memandang bahwa literasi digital rendah. Mereka tampak keliru. Literasi adalah buku cetak. Tidak demikian, literasi tetap saja berperkara pada hubungan manusia dengan pengetahuan. Hubungan ini terbangun pada dua kutub, yakni konstruksi pengetahuan dan konsumsi.
Infrastrutur digital berurusan dengan keduanya (konstruksi dan konsumsi pengetahuan). Jadi, digital bukanlah soal konten literasi (pengetahuan). Digital adalah teknologis, adalah infrastruktural. Sama dengan teknologi lisan dengan formula-formula ucapan yang dibangun agar mudah mengingat pengetahuan dan mereproduksinya secara berulang. Sama dengan huruf dan ejaan.
LITERASI DASAR
Politik literasi Indonesia, dengan GLN yang memayungi tripusat gerakan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) mengenalkan enam literasi dasar. Digital merupakan salah satunya. Hal ini mencerminkan sikap pemerintah yang antisipatif terhadap terjadinya perubahan infrastruktur yang mendasar dalam relasi manusia dan pengetahuan, baik pada kutub konstruksi dan konsumsi.
Enam literasi dasar terdiri atas (1) baca tulis, (2) numerasi, (3) sains, (4) finansial, (5) digital, dan (6) budaya, kewarganegaraan. Keenam jenis literasi dasar ini berkaitan dengan persoalan pokok literasi, yaitu (a) infrastruktur pengetahuan, (b) konstruksi dan konsumsi pengetahuan, (c) dunia kata dan dunia angka, dan (d) standar pengetahuan dasar.
Bisa dikatakan bahwa politik literasi dengan wujud enam literasi dasar dilandasi oleh ide besar mengenai standar dasar pengetahuan yang harus dikuasi, seperti (1) numerasi yang dipahami sebagai matematika, (2) bahasa, (3) sains, dan (4) uang (lebih luas adalah ekonomi), dan (5) budaya.
Enam literasi dasar juga dapat dipahami dari aspek infrastruktur literasi, yaitu membaca dan menulis kertas atau digital. Di dalam infrastruktur ini manusia mengembangkan relasi abadi antara dirinya dan pengetahuan dalam dua kutub, yakni konstruksi dan konsumsi pengetahuan.
Dalam forum ini, saya mengenalkan satu pandangan untuk memahami enam literasi dasar. Pandangan ini dibangun dalam prinsip yang mendasar literasi; atau sebagai pengertian dasar yang sampai saat ini belum ada kesepakatannya. Pandangan dasar yang dimaksud adalah konstrulsi dan konsumsi pengetahuan.
Prinsip dasar ini terdiri atas unsur manusia yang selalu menjadi pusat, sejak di dalam agama hingga di dalam pengetahuan. Pada prinsip ini manusia menempati posisi penting sebagai episentrum pengetahuan, baik ketika ada di kutub konstruksi dan di kutub konsumsi.
Baca tulis dalam relasi manusia dan pengetahaun dapat dimengerti sebagai hubungan-hubungan manusia dengan peralatan menulis dan membaca, yang tentu saja baru muncul setelah manusia memiliki teknologi menulis (kertas, mesin cetak, tinta). Baca tulis adalah dunia baru manusia pascalisan. Manusia tergiring ke dalam dunia aksara. Untuk ini terjadi transformasi besar dalam sejarah umat manusia, dari dunia lisan ke dunia aksara yang sering dipertentangkan. Para ibu yang terlalu optimis berlomba-lomba sejak sedini mungkin, memasukkan anak-anak mereka ke dalam dunia calistung (baca, tulis, dan hitung). Kemampuan calistung anak-anak, bagi ibu-ibu yang terlalu optimis itu dipandang sebagai prestasi. Memang benar baca tulis adalah jalan masuk dunia aksara. Ini semakin penting ketika gudang pengetahuan manusia berpindah dari ingatan sosial ke pustaka. Benar bahwa perpustakaan itu gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Jadi, baca tulis berkaitan dengan usaha manusia mendapat penegtahuan dalam dunia aksara dengan jalan satu-satunya, yaitu membaca.
Transformasi anak-anak dari dunia lisan ke dunia aksara mendapat perhatian dan kerja keras pada proses pengenalan huruf dengan berbagai pendekatan dan model belajar baca tulis permulaan. Akhirnya anak-anak sukses memasuki dunia baca tulis. Tapi tujuan sejatinya baca tulis kurang dikenalkan kepada anak-anak. Sehingga, mereka tidak paham untuk apa kemampuan baca tulis itu? Apakah hanya untuk pelajaran di sekolah?
Pada literasi digital (juga dimasukkan literasi dasar) konstruksi dan konsumsi pengetahuan manusia terjadi secara digital. Bukan pada digital-nya tetapi pada relasi manusia dan pengetahaun di dalam dunia digital. Entah di dalam kertas atau digital, manusia hanya berurusan dengan pengetahuan.
Telah terjadi kekeliruan dalam transformasi ini. Anak-anak tidak digiring lebih jauh bahwa guna baca tulis adalah untuk konstruksi dan konsusmi pengetahuan. Inilah yang harus diberi tekanan. Orang tua dan guru sudah puas ketika siswa di kelas rendah sudah lancar calistung.
Literasi baca tulis merupakan ruang bagi manusia dalam mengkonstruksi dan mengkonsumsi pengetahuan untuk kecakapan hidup atau berbagai tujuan dengan segala kebaikan dan nilai-nilai. Membaca dan menulis adalah jalan untuk sampai kepada pengetahuan. Di sini dapat lebih ditekankan bahwa episentrum literasi bukan pada aktivitas membaca dan menulis tetapi pada pengetahuan itu sendiri. Pada satu kutub manusia mengkonstruksi pengetahaun mereka. Darwin adalah sebuah contoh konstruksi pengetahuan evolusi yang disimpan dalam dunia tulis The Origin of Species. Para komponis mengkonstruksi karya musik di atas buku partiture. Anthony de Mello menulis ulang dongeng-dongeng dari seluruh dunia dalam Doa Sang Katak. Hawking mengkonstruksi sejarah waktu, Riwayat Sang Kala. Revolusi kognitif yang menjadi kekuatan manusia Sapien dikonstruksi oleh Noah Harari dalam Sapien.
Pada kutub lain, lahir para pembaca. Mereka membaca dan mengkonsumsi pengetahaun dari banyak buku. Literasi sering mengambil kutub ini sebagai satu praktik baik. Sehingga, adalah kegiatan membaca untuk memetik buah dari buku pohon-pohon pengetahuan yang ditanan dan dikembangkan oleh para pengarang (ilmuawan, pemikir atau filsuf, petualang, juru cerita, rahib, sastrawan, dll.)
Dengan memandang digital bukan sebagai ilmu teknik komunikasi dan informasi, maka literasi dasar ini hanya beda karakter dengan literasi baca tulis. Baca tulis sejatinya tetap terjadi di dunia digital, ditambah gerak (video, animasi) dan rekaman suara. Dunia digital adalah gudang baru yang bentuk dan besarnya tidak terbayangkan, tempat menyimpan pengetahuan manusia. Literasi digital tetap berurusan dengan relasi manusia dengan berbagai pengetahuan yang secara aksiologis bahwa pengetahuan apapun itu bernilai pragmatis dan hal ini berarti bahwa karena manfaatnya manusia membutuhkan pengetahuan.
Literasi sangat disayangkan hanya sampai pada membaca. Pandangan baru bahwa pengetahuan itu berguna untuk kecakapan hidup manusia, maka literasi ada pada ranah aksiologis. Hal ini didasari oleh prinsip ilmu pengetahuan bahwa ilmu itu harus memberi manfaat. Hal ini selalu menjadi tuntutan para peneliti. Soal untuk apa ilmu pengetahuan.
Dalam perincian enam literasi dasar juga muncul satu pokok mengenai dunia komunikasi manusia. Manusia berkomunikasi dengan menggunakan dua bahasa, yaitu (1) bahasa kata (leksikal) dan bahasa angka (matematika). Dalam hidup sehari-hari, matematika sangat praktis karena berhubungan dengan tindakan. Pada semua bidang digunakan bahasa angka. Numerasi tentu saja bukan matematika tetapi bahasa angka dalam kehidupan sehari-hari. Manusia melakukan perbandingan berbagai hal. Manusia mengukur panjang tiang rumah mereka. Manusia menghitung berapa jumlah ternaknya. Manusia melakukan pembagian hasil panen. Manusia memiliki berbagai jenis alat ukur untuk berbagai kepentingan, seperti jual beli, mencampur, atau membagi. Manusia melakukan urutan-urutan.
Jadi numerasi bukanlah pengetahuan itu sendiri tetapi bahasa angka dalam kehidupan sehari-hari dan sangat praktis. Keliru jika numerasi disamakan dengan pelajaran matematika. Numerasi memang diasah oleh pelajaran matematika.
Dalam kehidupan sehari-hari bahasa angka tidak berupa angka secara nyata. Hal ini sering ditemukan untuk ukuran pakaian, cukup dinyatakan dengan S, M, L atau slim fit atau basic. Ada pula ungkapan “sejauh mata memandang” atau “sepanjang malam” dan ”tiga purnama”. Masih terkait dekat dengan numerasi adalah finansial atau keuangan. Ini merupakan wilayah matematika yang sangat khusus untuk transaksi. Selalu berhubungan dua kondisi: untung atau rugi. Tidak jelas apa alasan pemerintah memasukkan finansial sebagai literasi dasar. Pengetahuan finansial selalu hanya berhubungan dengan menabung atau investasi, menghemat uang, penghasilan kerja dan belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Literasi finansial akan mendukung mansusia untuk kerja keras agar menghasilkan banyak uang sehingga kaya raya.
Literasi sains dan literasi budaya/kewarganegaraan berhubungan dengan konten atau muatan pengetahuan. Dengan masuknya sains dan budaya/kewarganegaraan di dalam literasi dasar dimaksdukan untuk mengembangkan dua kategori dasar ilmu pengetahuan, yakni IPA dan IPS. Lewat berbagai praktik literasi dasar sains dan budaya/kewarganegaraan, seseorang akan memiliki pengetahuan ilmu alam dan ilmu sosial.
IMPLEMENTASI
Masifnya GLS telah mencipta stigma bahwa literasi hanya untuk anak-anak atau siswa. Padahal literasi untuk siapa saja. Implementasi enam literasi dasar pun terjadi hanya pada sekolah. Sejalan dengan itu, akan diuraikan implementasi enam literasi dasar di dalam sekolah. Catatannya adalah, masih sangat mungkin diimplementasi di luar sekolah, keluarga dan masyarakat.
Implementasi literasi selalu berhubungan dengan relasi pengetahuan dan manusia. Pada relasi ini terdapat dua kutub yakni konstruksi dan konsumsi. Siswa sebagai unsur manusia dalam literasi lebih diposisikan pada kutub konsumsi pengetahuan. Implementasi literasi dasar pun lerupa kegiatan membaca buku dan kini secara digital. Maka diperlukan model-model praktik baik dalam membaca. Praktik membaca di tengah masyarakat yang tidak kuat fondasi budaya bacanya menjadi hambatan yang berat. Ini sudah umum diketahui. Gerakan literasi putus asa menghadapi masalah minat baca.
Implementasi baca tulis dapat dilakukan dengan pengembangan bebagai model membaca. Secara konvensional, membaca bertujuan mengumpulkan pengetahuan yang mungkin dapat berupa catatan, ringkasan, atau bagan, sebatas alat bantu ingatan dan pemahaman. Tapi membaca di era digital harus menekankan pada produk membaca. Produk digital jauh lebih menarik dalam literasi dasar baca tulis. Lewat produk yang dihasilkan, pengetahuan berhasil dipetik dari sumber yangberupa bahan bacaan (kertas/digital).
Beberapa produk bacaan seperti grafis, ilustrasi, tabel, daftar kata, video buku, buku suara, web, vlog, daftar pertanyaan untuk wawancara, naskah film, komik digital, dan lain-lain.
Pengalaman selama melakukan gerakan literasi akar rumput menunjukkan literasi dengan kegiatan membaca sangat tidak direkomendasi sampai pada suatu tahap subjek sasaran telah mencapai tahapan kesadaran membaca mandiri. Sebelum tahap ini dicapai, enam literasi dasar ini hanya bisa diimplementasi dengan literasi praktis dan berorientasi kepada tindakan /aksi produk atau karya. Literasi praktis adalah praktik baik yang tidak hanya membaca tetapi membaca yang diintegrasikan dengan kegiatan lain. Diintegrasikan dengan kegiatan memasak dalam suatu proyek memasak. Di sini ada cerita yang dibaca sambil masak atau di sela-sela kegiatan dan langsung dilakukan di dapur. Bahan yang dibaca bisa digital atau daftar menu yang ditempel di dinding dapur atau sejumlah resep lengkap dengan takaran atau ukuran serta perbandingan bahan.
Dengan kegiatan kemah di desa bagi siswa urban yang dari kota. Bahan-bahan bacaan dapat disiapkan. Sejarah gunung di desa tempat kemah bisa dipahami dengan konsep geopark, seperti misalnya Gunung Batur. Peserta diajak menyusun deskripsi singkat berhubungan dengan alam desa. Ketinggian desa bisa ditulis di satu lokasi. Untuk hal ini, peserta akan bertemua dengan ”berapa meter” dan singkatan MDPL. Peta desa lokasi kemah bisa dibuat dengan sederhana dan membandingkan juga dengan peta digital. Mengutip beberpa lokasi mata air dari peta digital dan mengunjungi secara langsung adalah praktik literasi yang nyata karena berupa tindakan. Dari sini dapat diturunkan sejenis peta atau denah yang menjelaskan jumlah mata air yang ada dan berapa jarak di antaranya?
Integrasi lainnya, mungkin masih bisa memanfaatkan peta atau denah mata air. Manfaat air sudah diketahui bersama. Demikian pula sifat-sifatnya. Tapi membicarakan sifat-sifat air dalam kondisi yang nyata, belum, lebih-lebih untuk literasi dasar. Masuk ke ruang literasi budaya, mengenai makna air dan manfaatnya bagi warga desa setempat. Bagi warga desa bersangkutan, air digunakan tentu saja untuk kepentingan yang paling umum dan pokok. Memasak, mencuci, mandi, mengairi sawah. Tapi ada fungsi air di luar itu. Air suci untuk upacara. Karena air memiliki makna khusus dan memiliki dewa, dicari satu cerita soal air dan mungkin ada ritual sucinya. Di mana saja air berjalan atau mengalir di suatu desa? Bisa dibuat peta jalan air. Peserta juga baik sekali jika langsung menelusuri jalan air. Pasti berjumpa pohon, batu-batu, ikan kecil, semak bambu, sarang burung di tebing, dan tidak lupa sampah plastik. Lantas ada diskusi masalah air dan sampah plastik. Apa hubungan sampah plastik pembungkus diterjen atau sampo di aliran air ini? Sangat menarik, setelah dibuktikan satu jawaban dengan menemukan pancuran. Pada saat ini disampaikan teks pendek (lagi-lagi digital atau kertas) soal kapan plastik busuk. Lantas diberi tabel kategori, sampah plastik yang ditemukan itu masuk yang kategori mana. Di sini juga disediakan dengan singkat bacaan deskripstif berbagai jenis plastik. Peserta menyocokkan informasi dalam bacaan dengan fakta di lapangan.
Lewat air, peserta juga dapat memahami transformasi sosial di desa. Hampir semua desa telah memiliki instalasi air bersih. Perubahan perilaku warga desa berubah semenjak ada pipa-pipa yang mengalirkan air ke rumah-rumah. Pancuran desa tidak terurus karena warga tidak mandi dan mengambil air di pancuran. Sebagai akibat pembangunan desa dalam bidang air bersih. Sawah kekurangan air karena mata air bagi sawah dialirkan lewat pipa hingga ke rumah-rumah. Air jadi rebutan! Perssoalan kekuarangan air membuat ekonomi pertanian subak berhadapan dengan persoalan yang lebih berat. Pemuda desa tidak berminat menjadi petani. Mereka kerja di kota atau berlayar. Kerja di kapal pesiar. Subak dan tradisinya benar-benar terancam.
Model praktik literasi dasar seperti ini belum banyak dilakukan. Literasi masih berupa rutinitas yang gagal untuk memaksa sasaran membaca. Aktivitas membaca ditonjolkan. Karena literasi adalah membaca! Gerakan literasi dan implementasi literasi dasar secara praktis jangan menonjolkan membaca. Membaca adalah beban. Para pegiat komunitas literasi jangan terlalu mengagungkan membaca. Model implementasi yang dibutuhkan adalah yang dapat mengubah pandangan subjek bahwa literasi bukan kegiatan membaca konvensional (duduk, diam, kening berkerut). Pandangan pengantinya adalah membaca sebagai salah satu variabel tindakan.
Model implementasi literasi dasar terdiri atas beberapa komponen, seperti aktivitas, produk, pengetahuan, dan membaca. Implementasi model ini didasari oleh konteks yang nyata, asli (autentik). Dengan ini literasi dasar tidak sebatas membaca di atas halaman buku atau layar. Implementasi literasi dasar diterjadikan dalam tindakan di dalam suatu konteks yang autentik untuk menghasilkan produk di atas halaman-halaman buku kehidupan. Literasi tidak sebatas pengalaman membaca atau memasuki belantara aksara. Literasi dijadikan pengalaman dan diintegrasikan ke dalam kegiatan, konteks.
Di samping model di atas, implementasi literasi dasar juga dapat dilakukan dengan pendekatan tematika. Selama ini belum ada praktik literasi dasar dengan model yang diturunkan dari tema. Pendekatan tema juga tidak fokus pada satu kegiatan membaca. Saat ini banyak sekali materi literasi yang memiliki tema yang berdekatan. Dunia digital menyediakan materi yang sangat melimpah. Ada berbagai jenis, seperti bacaan, video, resensi buku, grafis, wawancara, foto, berita, peta, ilustrasi, vlog, web, dll.
Materi implementasi Batur Geopark sebagai tema, dapat menggunakan
video,

.
foto,

.
sains,
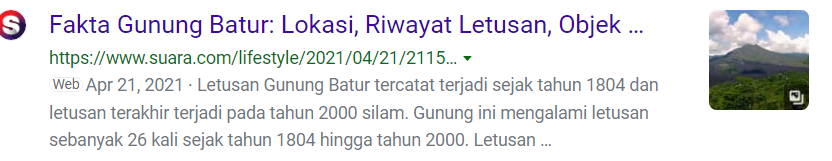
.
legenda/cerita rakyat,
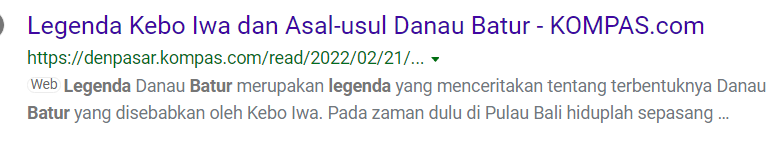
.
penelitian,
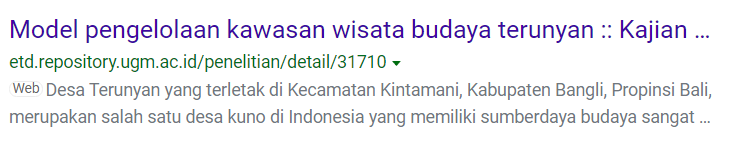
.
vlog,

.
SIMPULAN
Literasi dasar berkaitan dengan ruang tempat manusia menyimpan pengetahuannya dalam berbagai format sesuai dengan infrastruktur pengetahuan yang dikembangkan, sehingga ada literasi baca tulis dan literasi digital. Numerasi berhubungan dengan dunia bahasa-berpikir dasar manusia. Manusia berpikir menggunakan bahasa kata dan bahasa angka. Literasi dasar sains dan budaya berhubungan dengan konten pengetahuan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan konten-konten pengetahuan dasar yang paling pokok, seperti sains dan budaya/kewarganegaraan.
Literasi dasar dengan demikian mengandung tiga pokok, seperti (1) Gudang pengetahuan, (2) bahasa kata dan Bahasa angka, dan (3) konten pengetahuan (sains dan budaya/kewarganegaraan). [T]
- BACA artikel lain dari penulis I WAYAN ARTIKA


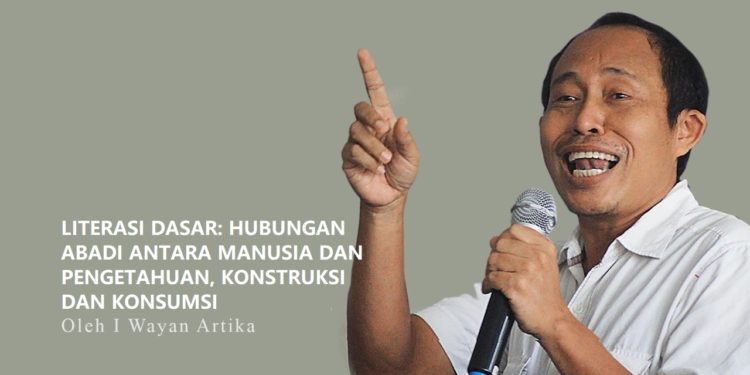
![Persepsi Lintas Budaya yang Sering Keliru | Catatan dari Inggris [1]](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2023/06/lintas-budaya-75x75.jpg)



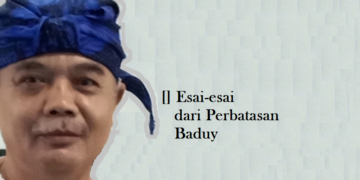













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











