MENJELANG Hari Suci Kuningan, nasi kuning menjadi bagian sajen yang wajib ada. Secara tradisional, nasi kuning untuk sajen dapat dibuat dari kunyit yang dilumatkan, dicampur minyak dan diaduk bersama nasi. Berbeda lagi dengan nasi kuning untuk nasi yasa atau nasi pradnyan yang biasanya juga dicampur bumbu-bumbu khusus agar lebih gurih dan sedap di lidah.
Perkembangannya, dua per tiga masyarakat belakangan ini mungkin lebih praktis menggunakan pewarna makanan guna membuat nasi kuning untuk sajen, selain juga ada yang lebih praktis lagi dengan membeli tumpeng dan penek kuning yang dijual di pasaran.
Cara membuat nasi kuning dengan bahan kunyit, asal-muasalnya secara tersirat saya simak dalam segmen cerita di lontar berjudul Tantu Panggelaran. Jika dipikir-pikir, mitos sederhana ini punya kupasan makna yang berelasi dengan dinamika hidup kita saat ini.
Alkisah, dalam narasi mistikal ini ada empat jenis burung yang merupakan wahana Bhatari Sri. Bhatari Sri kita kenal sebagai dewi padi, dewi sawah dan dewi kemakmuran. Empat burung itu adalah titiran ‘perkutut’, puter ‘puter’, wuru-wuru sepang ‘dara merah’, dan dara wulung ‘dara hitam’. Masing-masing burung membawa empat jenis biji (lebih tepatnya benih), perkutut membawa biji putih, puter membawa biji kuning, wuru-wuru membawa biji merah dan dara hitam membawa biji hitam.
Suatu ketika, ada lima orang anak kecil yang memburu burung-burung itu. Para burung ditembak jatuh. Keempat tembolok burung itu dilukai dan ternyata berisi empat jenis biji. Biji berwarna kuning yang dibawa puter ternyata yang paling menggiurkan. Biji itu berbau harum semerbak. Aromanya menggoda anak kecil ini untuk memakan habis biji kuning, hingga yang tersisa hanya kulit bijinya. Ketiga biji yang masih tersisa lalu ditanam sehingga tumbuh menjadi padi. Oleh sebab itu ada beras berwarna putih, merah dan hitam. Tidak ada beras berwarna kuning.
Dalam teks disebutkan: kang wija kuning kulitnya pineṇḍemnira matĕmahan kunir ‘biji kuning itu kulitnya mereka tanam sehingga menjadi kunyit’. Kulit dari biji yang hanya tinggal kenangan, setelah ditanam ternyata menjelma menjadi kunyit. Semenjak itu, orang yang ingin membuat beras maupun nasi berwarna kuning menggunakan ekstrak kunyit sebagai pewarnanya.
Kita yang Kehilangan Biji Kuning
Biji kuning yang harum semerbak, mewujud bukan hanya sekadar warna, tetapi makna. Kuning diamini sebagai warna yang mewakili kemakmuran, kesejahteraan dan kekayaan. Secara tak langsung kuning adalah simbol kenikmatan hidup. Kenikmatan ini, oleh lima anak kecil tadi sebatas dimaknai sebagai kenikmatan rasa. Kelimanya bisa saja mewakili lima indra, lima unsur diri manusia yang paling rakus pada yang paling menggiurkan. Mungkin karena itu, biji kuning tak tersisa untuk ditanam. Apa yang terlalu dinikmati, seringkali justru gagal diwariskan.
Sebuah sindiran filosofis tersirat dalam fragmen ini, bahwa kekayaan yang hanya dikonsumsi akan musnah dan berubah dengan substitusi yang lain. Biji kuning sebagai simbol kekayaan tak bisa diabadikan jika hanya dikejar untuk dinikmati. Biji putih, merah, dan hitam yang bisa dimaknai sebagai kesucian, darah semangat, dan wibawa masih tersisa untuk ditanam, justru biji kuning yang mewakili nilai tertinggi yang berusaha kita capai selagi hidup tak sempat tumbuh.
Biji kuning tersubstitusi sebagai kunyit, yang juga bertindak sebagai rempah penyembuh dan zat pewarna. Kunyit tak hadir sebagai tanaman pokok, melainkan sebagai esensi pengingat bahwa sesuatu yang pernah ada, kini dijaga dalam wujud lain. Kunyit bukan makanan utama, melainkan pemberi warna dalam makanan. Mungkin inilah petunjuk bahwa biji kuning harus ditemukan dalam pengalaman batin, bukan ladang duniawi belaka.
Narasi ini seakan mengajak kita merenungi ulang apa yang kita buru dan telan habis dalam hidup. Apakah kita terlalu tergoda dengan aroma biji kuning tanpa berpikir bahwa yang harum itu bisa musnah jika tidak diwariskan? Di era konsumsi cepat dan pencarian kenikmatan instan, cerita ini memberi jeda maknawi bahwa yang seolah paling nikmat tidak selalu bijak untuk dihabiskan sekaligus.
Jika tembolok burung menjadi lambang alam, maka biji yang tersimpan di dalamnya ialah benih-benih makna yang hendak dititipkan alam pada manusia. Warna-warni dalam biji itu bukan sekadar visual, tetapi mengandung resonansi kosmologis dan psikologis. Putih untuk kesucian dan permulaan (purwa), hitam untuk gelap dan kedalaman batin, merah untuk semangat dan keberanian, dan kuning yang paling harum dan paling cepat habis ialah lambang kekayaan yang menggoda dan yang paling sulit dijaga karena disukai semua.
Mengapa biji kuning dimakan sampai habis, sementara yang lain mampu ditanam ulang? Anak-anak dalam cerita itu tidak menanam apa yang mereka sukai, justru menanam apa yang tersisa. Kunyit, sebagai jelmaan kulit biji kuning, hanyalah sisa dari esensi biji itu. Maka tak heran jika dalam kehidupan sehari-hari, kunyit juga identik dengan obat penawar luka. Ia pernah terluka dan menyembuhkan dirinya sendiri.
Biji kuning menjadi perumpamaan untuk segala hal yang kita habiskan tanpa berpikir panjang. Tanah subur yang kita jadikan akomodasi pariwisata, hutan yang kita bakar, air tanah yang kita sedot nyaris habis, tanaman upakara yang kita pakai besar-besaran tanpa budidaya atau bahkan investasi yang dihabiskan di generasi ini tanpa benih untuk masa depan. Cerita ini mengingatkan bahwa kebahagiaan yang tidak disemai takkan bisa dituai. Kegembiraan kelima anak itu seperti pesta panen tanpa menabur benih. Gairah sesaat itu kemudian melahirkan kekosongan panjang karena aroma semerbak yang dinikmati satu lahapan itu tidak ada lagi saat ini.
Tafsir maknawi yang lebih luas, membuat cerita ini menyuguhkan renungan tentang kebijaksanaan dalam memilih keseimbangan antara memakan dan menanam, antara menikmati dan menyisakan, antara hasrat dan warisan, antara konsumsi dan produksi. Apakah kita tengah menjadi anak-anak yang gembira memakan biji kuning, atau kita tengah berusaha menanam makna dari sisa yang tertinggal? [T]
Penulis: Abdi Jaya Prawira
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:







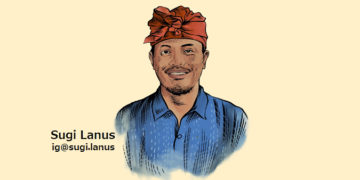













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











