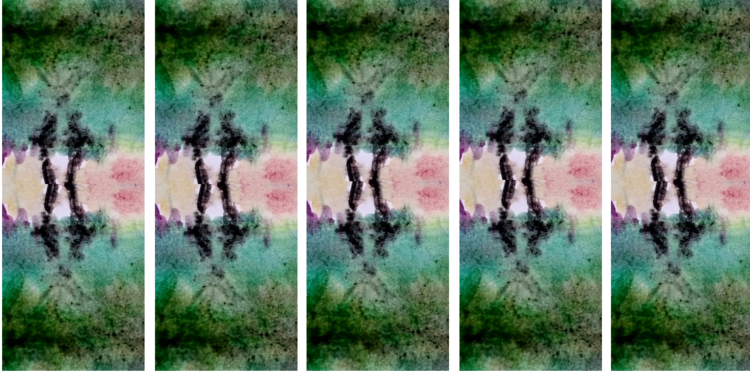BEJO baru saja tiba sesaat setelah Kasdi mengumpat dan menyumpahserapahi anjing gudis yang hampir menerkam kakinya. Pemuda itu kagum melihat cara lelaki paruh baya itu menghindar dari gigi ganas penuh kuman itu. Anjing itu cepat, tapi Pak Di Kopok [tuli]—begitu ia akrab dipanggil, meski sebenarnya ia hanya setengah tuli—tentu lebih cepat. Melihat caranya menghindar, rumor yang beredar bahwa Pak Di adalah pendekar pilih tanding itu tampaknya bukan bualan semata.
Bahkan, dan ini yang membuat mata Bejo berbinar dengan dada sedikit berdebar, tanpa ampun Pak Di menendang makhluk kurap itu dengan penuh dendam-kejengkelan. Anjing tegalan itu mental, sebelum tubuhnya terguling-guling dan membentur pohon nangka depan musala. Kaingannya sampai memekakkan telinga.
“Jancuk! Asu!” umpat Pak Di, berkali-kali, sambil mengelus-elus kaki kanannya dengan kasar.
Beberapa orang yang sedari tadi menyaksikan adegan konyol sekaligus heroik itu tertawa terpingkal-pingkal dan kagum secara bersamaan. Lainnya diam-diam kasihan kepada hewan kurap yang sekarang jalannya sempoyongan seperti habis menegak berbotol-botol ciu itu—bobot kepalanya sepertinya bertambah lebih berat setelah membentur pohon nangka.
Tapi kejadian itu berlalu begitu saja, setelah seorang pemuda yang duduk di depan TV tabung 80-an ukuran 14 inci, yang harganya hampir sebanding dengan harga motor bebek bekas keluaran setahun sebelumnya, mengumpat dengan nada putus asa. “Jancuk!PKI jancuk!” Pemuda itu berdiri dan membanting putung rokok lintingannya setelah tim yang dibelanya kebobolan untuk kedua kalinya.
Pak Di, yang tampak masih kesal, bertambah kesal setelah melihat Ahn Jung-Hwan—yang berduel dengan Maldini, bek terhebat Italia sepanjang masa itu—berhasil menyundul bola melewati Gianluigi Buffon tiga menit sebelum perpanjangan waktu kedua berakhir. Ia mengamini orang yang mengumpat “PKI jancuk!” tadi.
(Orang-orang Pundung Gede dengan ngawur dan semena-mena memang menganggap orang Korea Selatan itu PKI, dulu. “Lihat saja, mata dan nama-namanya seperti orang Cina-PKI,” kata mereka, tentu dengan dasar pengetahuan akademik yang bobrok.)
Bejo ikut mengumpat walau dalam hati. “Taik, kok bisa masuk? Padahal saat 12 pas tadi nggak masuk,” ucapnya kemudian, nyaris kepada diri sendiri.
Performa tim azzurri sepanjang Piala Dunia 2002 sebenarnya memang tak bagus-bagus amat, kalau tak bisa dibilang busuk, meski diperkuat nama-nama besar seperti Maldini, Cannavaro, Totti, Del Piero, Nesta, Inzaghi, Materazzi, Buffon, Vieri, dkk. Cara mereka kalah dari timnas Negeri Ginseng itu—terlepas dari dugaan pihak Korea Selatan melakukan kecurangan—tetap menorehkan luka mendalam di hati publik sepakbola Italia—bahkan bagi pendukungnya di seluruh dunia, termasuk orang-orang Pundung Gede.
Namun, malam itu, bukan hanya kekalahan Italia saja yang membuat heboh dan keget orang-orang; tapi juga seorang pemuda yang duduk di pojok dekat pintu keluar kedai kopi kecil—tempat orang-orang menonton pertandingan yang mengecewakan itu—tiba-tiba berteriak kesakitan.
Sambil memegangi dada sebelah kiri, ia terus berteriak. “Sakit… Sakit… Mati aku… Mati…” Ia terbatuk dan mengeluarkan semua isi perutnya sebelum pingsan dan tak sadarkan diri.
Orang-orang mengerubunginya dan saling bertanya satu sama lain. Kejadian ini begitu cepat. Orang-orang seperti belum siap mendapati kejadian aneh itu di depan mata kepala mereka. Pak Di, yang sedari tadi terpaku, menerobos kerumunan dan memperhatikan sekujur tubuh pemuda yang tak berdaya itu. Ia memegang kepalanya. Lalu telapak tangannya. Dan ia terpejam. Dari mulutnya terdengar kata-kata purba yang tak dimengerti siapa pun. Orang-orang saling pandang. Bejo, yang melihat adegan tersebut, semakin yakin bahwa Pak Di memang orang sakti.
“Supri kenapa Pak Di?” pemilik warung bertanya, lebih kepada ingin tahu alih-alih prihatin. Dan sepertinya semua orang juga demikian.
Pak Di bergeming. Matanya masih terpejam. Seorang pemuda dengan luka sayatan di wajahnya diminta istri pemilik warung untuk segera memberi tahu keluarga Supri. Pemuda itu melesat dengan kaki tanpa alas.
“Piye, Pak Di?” seorang bertanya dengan sedikit berteriak, tidak sabar di tengah kasak-kusuk.
Pak Di membuka mata dan melepaskan genggamannya yang sedari tadi melekat di pergelangan tangan kanan Supri. Dengan debar semua orang menanti jawaban lelaki paruh baya setengah tuli itu. Pak Di mengedarkan pandangan kepada orang-orang. “Supri disantet!” katanya tegas dan serius. Tapi tak satu pun orang percaya dengannya, kecuali satu, ya, Bejo.
***
Lelaki paruh baya bertelanjang dada berjalan setengah berlari dengan kelewang di tangan kanannya. Benda tajam tanpa sarung itu berkilat-kilat, siap menumpas apa saja. Lengannya yang berurat gemetar dengan keringat yang mengucur, membasahi mata senjata yang dibawanya. Mata lelaki itu nyaris merah, giginya bergemeletuk menahan amarah yang memuncak. Ia menebas pelepah pisang yang menghalangi jalannya dengan sekali ayunan. Seperti orang kesurupan, Rajimin mengumpat, berteriak memanggil satu nama: Kasdi.
“Di mana kau bajingan? Wong tua kopok keparat!” Semua nama binatang yang hidup di Pundung Gede tumpah dari mulut Rajimin. Ia mendatangi rumah Kasdi, tapi di sana hanya ada istri dan anak-anaknya. Dan ia ternyata masih cukup waras untuk tidak berbuat macam-macam kepada mereka. Bejo, bersama beberapa orang yang melihatnya, memilih menyingkir dari pandangan Rajimin.
Pundung Gede senyap saat Rajimin menghunus pedang pusaka warisan buyutnya yang dipercaya bertuah itu. Amarahnya memuncak saat anak laki-lakinya tewas dengan cara mengenaskan—apalagi tak satu pun orang mengetahui penyebabnya. Supri, anak semata-wayang Rajimin, meninggal secara tiba-tiba saat ikut menonton pertandingan Piala Dunia malam itu. Setelah sesak napas, muntah, dan pingsan beberapa kali, tubuh Supri melepuh seperti terbakar, mengeluarkan nanah dengan bau yang tak dapat dijelaskan. Dan Rajimin yakin, bahkan hakulyakin, bahwa Kasdi-lah pembunuhnya.
Sementara itu, di ujung setapak, Pasih berteriak memanggil-manggil nama suaminya sambil berkali-kali menyebut nama Tuhan. Air matanya tak berhenti tumpah. Suaranya serak dan rambutnya awut-awutan—sangat mengibakan. Sebenarnya orang-orang yang melihatnya memiliki keinginan untuk menenangkannya, tapi ketakutan mereka lebih besar daripada kepeduliannya. Mereka takut berurusan dengan Rajimin, suami Pasih, yang barangkali sudah gelap mata itu.
“Duh Gusti, duh Biyung. Min, berhenti Min! Eling, Min! Eling!” ratap Pasih berusaha mengejar suaminya yang kini telah lenyap ditelan semak-gerumbul tegalan. Ia jatuh terjerembab, bersimpuh dengan tangis yang memilukan. Saat Rajimin sudah benar-benar tak terlihat batang-hidungnya, beberapa perempuan memberanikan diri untuk menghampiri Pasih yang bermandikan keringat terik siang hari.
Orang-orang berusaha menenangkan Pasih, lainnya diam seribu bahasa. Dengan suara lirih Pasih memanggil-manggil nama suaminya dan sesekali nama anaknya yang pagi hari dikuburkan. Ia terdiam sejenak dengan napas yang tersengal. Ingatan membawanya ke masa silam saat Rajimin menikahinya dengan mahar setengah hektare tanah tegalan.
Rajimin adalah anak dari Sunandar bin Karmijo, mantan Kepala Desa Pundung Gede di masa Orde Baru. Ia sombong dan merasa paling berkuasa—karena dekat dengan birokrasi dan aparat pemerintah. Keluarganya sangat feodal dan pelit. (Meski kaya mereka tak rela membelanjakan uangnya untuk membeli TV.) Dan bapaknya memiliki banyak pengawal dari kalangan pendekar sampai preman ketengan. Begejil-begejil itu dipelihara oleh Sunandar untuk mengukuhkan status quo-nya di Pundung Gede. Meski begitu, tak sedikit orang berani melawannya, meski nasibnya sudah dapat ditebak bahkan sebelum benar-benar melakukan perlawanan.
Sunandar dan Kasdi sebenarnya sahabat karib sebelum Kasdi mengetahui bahwa Karmijo, kakek Rajimin, yang telah membunuh Kaeran, bapak Kasdi, pada masa kelam 1965. Karmijo adalah jagal. Dan ia membunuh Kaeran, begitu menurut keterangan paman Kasdi—adik dari bapaknya. Kaeran yang malang itu dituding Karmijo sebagai PKI yang pantas dibumihanguskan—walaupun tuduhan itu benar-benar tak dapat dibuktikan, sebagaimana banyak kisah serupa di banyak tempat pada masa itu.
Menurut paman Kasdi, terlepas apakah kakanya seorang PKI atau bukan, pembunuhan itu jelas karena ada motif lain. Dan ia percaya itu urusan tanah setengah hektare yang belakangan hari dijadikan mahar Rajimin saat menikahi Pasih.
Tanah tegalan setengah hektare itu bertengger di lereng bukit kapur yang sebenarnya tidak terlalu produktif. Tanah itu, menurut paman Kasdi, dibabat oleh bapak Kaeran, kakek Kasdi, pada zaman dulu semasa tanah itu masih belantara. Tapi karena musim paceklik, tanah tersebut digadaikan, katakanlah begitu, kepada Wiji, bapak Karmijo—buyut Rajimin—dengan jagung dan singkong beberapa kampil. Belakangan, pada saat perekonomian keluarga Kaeran mulai membaik, karena perjanjiannya gadai, Karean berusaha menebusnya.
Tapi dasar malang, sebelum tanah itu tertebus, Wiji sudah meninggal, dan Karmijo tak sudi mengembalikan tanah tersebut kepada keluarga Kaeran. Meski begitu Kaeran tetap berusaha menebus tanah tegalan itu—karena ia merasa itu warisan bapaknya. Tapi, seperti yang Anda pikirkan, Karmijo tetap bergeming. Hingga peristiwa mengerikan itu meletus. Kaeran tewas ditebas Karmijo dengan kelewang yang dibawa Rajimin itu.
Karmijo dianggap pahlawan oleh negara. Maka anaknya, si Sunandar, pada kisaran tahun 80-an, diangkat, lebih tepatnya ditunjuk, menjadi kepala desa—karena keluarga mereka juga dinilai sangat berjiwa beringin. Jadilah Sunandar kepala desa sumur hidup, sampai ia digantikan adiknya pada awal tahun 90-an.
Pada saat pembunuhan itu terjadi, Kasdi sudah berumur sekitar 28 tahun, seumuran dengan Sunandar. Tapi ia tak tahu bapaknya dibunuh. Pada saat itu ia tinggal di desa istrinya. Ia hanya mendapat kabar bahwa bapaknya hilang, muspra, sebagaimana orang-orang lain yang mengalami nasib serupa. Dan Kasdi tak berani mempertanyakan perihal tersebut. Waktu itu, orang-orang juga memilih menutup mulut rapat-rapat. Tak satu pun orang berani berurusan dengan jagal maupun aparat. Tapi menjelang kematiannya, paman Kasdi menceritakan kejadian yang sebenarnya.
“Karmijo menanam jasad bapakmu di tanah tegalannya sendiri. Orang Pundung Gede tahu itu,” terang paman Kasdi sebelum meninggal dunia di pertengahan tahun 80-an. Kisah ini telah ia pendam cukup lama. Dan Paman Kasdi begitu benci saat Kasdi berteman dengan Sunandar, anak Karmijo, semasa Kasdi masih remaja, dulu.
Beberapa bulan setelah mendengar kesaksian pamannya, Kasdi pergi dari Pundung Gede, meninggalkan istri, kedua anaknya, dan ibunya. (Beberapa bulan setelah bapaknya dinyatakan hilang, Kasdi memang memutuskan pindah ke tanah kelahirannya, menempati rumah tinggalan bapaknya, dan merawat-menemani ibunya yang gila.)
Sebagian warga Pundung Gede mengatakan ia merantau ke Malaysia bersama beberapa orang. Lainnya, termasuk ibu Bejo, percaya Kasdi berangkat berguru kepada seorang pertapa sakti yang menghuni Gua Gunung Rupit. Tapi kedua asumsi itu jelas sulit untuk dibuktikan. Selain hanya karena katanya-katanya, pada awal tahun 2000-an, Kasdi muncul dengan perilaku yang aneh, alih-alih membawa brono picis untuk keluarganya. Dan lebih aneh lagi, sejak menghilang bertahun-tahun, saat muncul dan mengegerkan warga Pundung Gede, Kasdi sangat senang jika berbicara tentang sepakbola. Oh, dari mana pengetahuannya tentang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia itu? Tak satu pun orang Pundung Gede dapat menjawab pertanyaan itu.
Dan Kasdi menjadi lelaki paruh baya setengah tuli yang jarang berbicara dan memilih hidup di sebuah gubuk kecil di bawah pohon randu yang menjadi pembatas antara tanah tegalan sisa warisan bapaknya dan tanah tegalan setengah hektare di lereng bukit kapur itu—yang menurut pamannya di situlah jasad Kaeran, bapaknya, dikubur oleh Karmijo. Istrinya, yang telah lama ia tinggalkan, sudah setengah mati membujuknya untuk tinggal di rumah, tapi Kasdi tetap bergeming.
Sampai saat Pabrik Semen menambang secara paksa tanah tegalan sisa warisan bapaknya dan tanah tegalan setengah hektar itu, barulah Kasdi beranjak dari sana. Ia pulang ke rumahnya, tanpa protes, bahkan nyaris tanpa gumam, berkumpul kembali bersama istri dan anak-anaknya. Ia tahu, kedua tanah itu diam-diam telah dijual adik Sunandar, Kepala Desa Pundung Gede, kepada Pabrik Semen. Tak hanya kedua tanah miliknya, tapi juga milik beberapa warga. Para warga Pundung Gede yang tanahnya telah dirampas, termasuk Kasdi, tak bisa berbuat apa-apa, karena pihak Pabrik Semen mengantongi sertifikat tanah mereka.
***
“Darah itu menggenang dan melumuri leher hingga kepalanya. Lehernya keroak, mengangga, dan mengerikan. Aku melihatnya sendiri. Meski sudah mati, tapi matanya tetap terbuka—bahkan melotot seperti ingin keluar—dan mulutnya mengangga seperti hendak mengumpat. Rajimin, anak Sunandar, cucu Karmijo, tewas oleh kelewangnya sendiri. Sejata yang kata orang-orang bertuah itu masih menancap di lehernya saat seorang pengais sisa panen jagung menemukan jasadnya,” Sajam memungkasi ceritanya.
Aku menghela napas. Lalu menandaskan setengah cangkir kopi yang disajikan istri Sajam saat aku bertandang ke rumahnya. Aku mendatangi Sajam karena urusan tugas akhir kuliah. Sebagai mahasiswa sejarah, aku tertarik untuk meneliti huru-hara sengketa tanah antara warga Pundung Gede dengan Pabrik Semen pada kisaran tahun 2000-an.
Menurut warga setempat, Sajam merupakan saksi hidup peristiwa tersebut. Oleh sebab itu aku mewawancarainya. Tapi di luar dugaan, Sajam malah mengisahkan tentang Bejo, Kasdi, Rajimin, dan nama-nama yang terdengar kuno lainnya. Dan aku benar-benar tak percaya dengan ucapannya. Apalagi, menurut salah satu anaknya, Sajam memang rada-rada ngelantur kalau bercerita.
“Bapak itu, dulu, kebanyakan mendengar sandiwara radio, menonton wayang dan sinetron, Mas. Jadi, jangan didengarkan dengan serius!” seru anak Sajam.
Tetapi kisah Sajam ini aku akui cukup detail dan terstruktur meski masih banyak lubang di sana-sini. Ah, aku jadi berpikir, apa aku tuliskan saja kisah ini menjadi cerpen atau bahkan novel dengan mengembangkan dan menambal-sulamnya dengan kisah-kisah silat, ilmu kanuragan, dan sedikit bumbu percintaan? Tampaknya menarik. Tapi sebentar, siapa yang membunuh Rajimin? Dan ke mana perginya Kasdi?
Sajam sialan! Sebelum memberi keterangan kepadaku bagaimana kisah selanjutnya, ia sudah mengurung diri di kamarnya. “Tak bisa diganggu,” kata istrinya.
Hari sudah sore. Aku beranjak dari kursi penjalin tua di ruang tamu rumah Sajam. Saat hendak berpamitan, betapa jantung dan mataku seperti keluar dari kelopaknya, saat melihat sebuah foto usang yang menampakkan sosok lelaki dengan kumis dan alis tebal, sorot mata tajam, dan rahang yang kokoh, tertempel di dinding kayu, terselip di antara foto-foto keluarga Sajam lainnya. Tubuhku gemetar. Ya, aku yakin, bahkan hakulyakin, sosok di dalam foto itu memiliki ciri-ciri yang sama persis seperti lelaki yang dikisahkan secara berbuih-buih oleh Sajam tadi. Sejenak napasku seperti berhenti.
“Siapa bapak berkumis di foto itu, Bu?” Dengan terbata aku bertanya kepada istri Sajam sambil menunjuk foto yang kumaksud.
“Yang mana, Mas? Oh, yang ini. Ini foto mertua saya, Mas.”
Aku pamit meninggalkan rumah Sajam. Dan aku baru sadar bahwa nama yang tertulis di kolom narasumber dalam kertas pertannyaanku itu ialah: Sajam Bejo.
GS45, Singaraja, 2024
- BACA cerpen lain di tatkala.co