Pendahuluan
Lalu lintas perdagangan rempah pada abad ke-17 hingga ke-19 yang menghubungkan kepulauan Malaku ke Batavia dan Banten hingga Malaka sehingga membuka jalur alternatif bagi pelabuhan transit seperti di Buleleng, baik sebagai persinggahan karena cuaca maupun mengisi perbekalan atau mencari kebutuhan selain rempah. Walaupun Bali terletak di jalur perdagangan antar-Pulau Sumatra, Jawa, dan Maluku yang masing-masing terkenal dengan penghasilan beras dan rempah-rempah itu, masyarakat Bali tidak sepenuhnya terlibat dalam kegiatan niaga maritim (Reid, 2000).
Akan tetapi, Bali utara semakin penting sebagai pelabuhan transit alternatif yang mengundang pedagang-pedagang asing dan Nusantara yang membuka arena perekonomian dengan memaksimalkan komoditi dari Bali yang disuplai daerah penghasil pertanian Bali selatan (Tabanan, Badung, dan Gianyar) dan daerah penghasil perkebunan dari Mengwi dan Bangli.
Diantara para pedagang Nusantara ini sebagian adalah pedagang dari berbagai daerah, seperti Bugis, Makasar, Madura, dan Jawa serta pedagang Arab dan India (muslim) yang bersaing dengan pedagang Tionghoa di Bali utara. Eksistensi ekonomi dan meningkatnya transaksi ekspor dari Bali dalam jaringan jalur rempah yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Nusantara sehingga mendorong orang-orang Bali termasuk dari kalangan bangsawan atau kerajaan turut berbisnis dalam menyediakan sebagian kebutuhan para saudagar yang singgah di pelabuhan Bali Utara.

Suasana Pelabuhan Buleleng (Bali Utara) pada abad ke-19 | Sumber: KILTV Leiden
Perdagangan Perantara dan Pranata Ekonomi
Para pedagang dari Makasar, Bugis, Madura, Jawa, Madura, Arab, dan sebagian India serta pedagang Tionghoa di pelabuhan-pelabuhan Bali utara sebagai bagian dari perdagangan perantara. Menurut Liem Twan Djie, bahwa perdagangan perantara merupakan cabang perdagangan yang menjadi mata rantai antara perdagangan besar-besaran dan atau industri di satu pihak dan perdagangan kecil dan atau penduduk konsumen, masing-masing produsen di pihak lain.[1] Oleh karena itu, barang dagangan yang ditawarkan oleh pada pedagang perantara ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, baik dari yang bersifat mikro kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, kain (katun), hingga gambir maupun kebutuhan yang cukup besar seperti candu dan emas.
Posisi pedagang perantara dalam struktur perekonomian di Bali mengikuti pola yang digambarkan oleh Geertz (1980: 87), ada empat hal yang yang dapat digarisbawahi dan harus diperhatikan dalam perdagangan di Bali hingga abad ke-19, yaitu, (1) pasar berputar secara periodik; (2) pasar yang muncul akibat hubungan-hubungan pertukaran tradisional; (3) pasar terisolasi secara politik berupa perdagangan di pusat-pusat pelabuhan; dan (4) tempat perdagangan yang penting bagi pedagang asing adalah pelabuhan-pelabuhan yang ada di pinggir pantai, yang dikendalikan oleh kerajaan.
Oleh karena itu, pasar muncul sebagai akibat dari suatu kebiasaan dan bersifat spontanitas serta tidak menetap, dan pasar bukan suatu keharusan sehingga banyak pasar yang dikelola oleh pedagang asing terutama dari kalangan pedagang Tionghoa, baik mengelola pasar maupun transaksi perdagangan di pelabuhan. Beberapa tempat tertentu pedagang nusantara juga mendapatkan kepercayaan untuk mengelola daerah perekonomian. Para pucuk pimpinan yang mengelola teritori perdagangan di pelabuhan biasanya disebut syahbandar. Syahbandar sebagai institusi cukup signifikan sebagai managerial pelabuhan yang menertibkan perkapalan dan pelayaran, mengatur lalulintas perdagangan internasional, menjadi juru bicara kerajaan terhadap pihak asing.
Syahbandar juga mempunyai posisi yang strategis dalam mengurus pelabuhan, sekaligus diberi kewenangan untuk memonopoli komoditas. Jabatan syahbandar cukup otonom di bidang dagang dan mempunyai tanggung jawab langsung kepada raja (Utrecht, 1962: 119-120). Sehingga hanya mereka (biasanya orang asing) yang cakap dan kaya, berpenguruh di bidang ekonomi dan loyal kepada raja yang berpeluang ditunjuk sebagai syahbandar (Parimartha, 2014: 65-66). Kedudukan syahbandar di Buleleng pada umumnya dipegang oleh orang-orang Bugis, Arab, atau Tionghoa dan mereka ini sangat berpengaruh, baik bagi kerajaan maupun jaringan ekonomi yang dibangun dengan pihak luar.
Stratifikasi sosial di Bali utara tidak banyak mengalami pergeseran oleh perubahan politik akibat jatuhnya Kerajaan Buleleng ke pangkuan kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1849. Kebijakan Kolonial Belanda mengukuhkan pelabuhan Pabean, Sangsit, dan Temukus sebagai daerah pemukiman khusus orang-orang Timur Asing, seperti Tionghoa, India, dan Arab (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1883).
Seperti halnya orang asing lainnya, pihak kerajaan (penguasa) mengangkat seorang kepala kampung atau kapiten (kepitein) (Lohanda, 1995: 33, 50-54) untuk menertibkan komunitasnya. Walaupun kapiten bertugas mengatur komunitasnya, tetapi dalam peraturan pemerintah kolonial Belanda, penunjukkan seorang kapiten tidak serta merta merupakan wakil yang sah dari masyarakat asing. Institusi kapiten dijadikan alat politik oleh orang-orang Barat terutama Belanda yang diadopsi dari pranata syahbandar di Nusantara (Lohanda, 1995). Agaknya peran dan fungsi kapiten di Kerajaan Buleleng adalah akibat kontak dagang yang telah berlangsung sejak abad ke-17.
Bali Utara: Titik Temu Pedagang Nusantara
Menurut Schulte Nordholt (1981: 16-47) terdapat tingkat-tingkat perdagangan di Bali dan Lombok, yaitu (1) perdagangan lokal kepulauan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), dapat dikategorikan sebagai pedagang kecil, yang dilakukan oleh penduduk pribumi, pedagang Arab, dan Tionghoa; (2) perdagangan antarpulau yang dilakukan oleh pedagang tingkat menengah, dilakukan oleh pedagang Tionghoa, Arab, dan Bugis; (3) pedagang jarak jauh atau besar, terutama dilakukan oleh orang-orang Eropa dengan kapal-kapal besar.
Dalam perdagangan skala kecil dan menengah ini, dari dan ke Bali, Jawa, Madura, Lombok, hingga Sumbawa dan Makasar sebagian besar diperankan pedagang muslim kosmopolitan di Nusantara. Peranan pedagang muslim semakin penting ketika pelabuhan di Bali Utara dinyatakan sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1861, artinya tidak ada pajak impor maupun ekspor yang dikenakan. Dampaknya, pelabuhan Buleleng berkembang menjadi entrepôt daerah timur dalam jaringan perdagangan dari dan ke Singapura semakin ramai (Schulte Nordholt, 2006: 224).
Perdagangan Rempah
Bali pada awalnya bukan penghasil rempah yang dibutuhkan pasaran internasional, namun pedagang muslim memainkan peran dalam mengendalikan pertukaran hasil komoditi Bali dengan daerah lain. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 sumbangan komoditas terkait dengan hasil rempah sebatas pala dan cengkeh, namun dalam jumlah yang signifikan adalah kain kapas, akar mangkasla, bunga kosumbo, beras, sapi, ding-ding (daging kering), sapi, dan budak.
Pala dari Bali merupakan pengembangan dari pala spisies jenis pala panjang dan diperkirakan didatangkan dari Seram, Gilolo, dan kepulauan lain di Maluku. Bahkan dalam perdagangan lokal, hasil pala panjang dari Bali yang baik dan berkualitas yang dibawa oleh pedagang muslim ke Jawa dan sebagian penduduk Jawa menyebutnya dengan jenis “pala bali” (Annabel The Gallop dkk., 2020:245). Alhasil permintaan “pala bali” semakin tinggi, diperlukan pembudidayaan di sekitar perbukitan Buleleng dan Bangli sehingga melimpahnya hasil “pala bali” semakin hari harganya semakin murah meskipun tetap diminati di pasaran. Sementara itu, perdangangan cengkeh dari Bali tidak bisa menembus pasaran di pulau-pulau lain karena penanamannya tidak dibudidayakan. Kalaupun ada cengkeh yang dijual ke pasaran, itupun dalam jumlah yang sangat terbatas.
Perdagangan Budak
Tidak dapat menutup kenyataan, bahwa perdagangan yang melibatkan pedagang Nusantara melalui pelabuhan di Buleleng yang cukup marak, yakni perdagangan opium (candu) dan budak. Tingginya perdagangan budak dipicu oleh kebutuhan tenaga kerja yang sangat murah di Batavia baru selesai tahun 1660. Para budak secara besar-besaran didatangkan dari Jawa, Ambon, dan Bali ini tinggal tidak jauh dari para majikannya (Blusse 2004: 48-49).
Pada tahun 1790-an penduduk Batavia terdapat 10.000-an adalah budak di dalam kota dan 30.000-an budak yang berada di luar kota. Di antara budak-budak tersebut sebagian terdiri dari budak atau orang keturunan budak Bali. Begitu pula dengan kota-kota besar di Jawa, seperti Surabaya, dan Semarang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 juga dibanjiri budak dari Bali. Hal ini salah satunya dampak dari melimpahnya perdagangan rempah nusantara turut menumbuhkan bandar-bandar pelabuhan semakin berkembang menajdi kota-kota besar. Sisa-sisa perbudakan yang masih melekat di setiap kota besar adanya daerah pabelan, yang artinya pemukiman orang-orang Bali.[2]
Seturut dengan perkembangan tersebut perbudakan cukup efektif memasok tenaga kerja dengan biaya yang sangat rendah. Sementara itu, perdagangan budak juga dinikmati tidak hanya pedagang perantara yang akan menjual kembali ke kota-kota besar, tetapi juga dinikmati oleh pengusa lokal, baik kerabat raja maupun punggawa kerjaaan. Perdagangan yang melembaga dan meliputi otoritas raja ini semakin meningkat karena pihak raja diuntungkan dengan perdagangan budak, baik melalui pajak maupun melalui penjualan langsung. Menurut Menurut Korn ada beberapa sebab seseorang dapat dijadikan budak, antara lain (1) karena keturunan yang tidak mempunyai sanak saudara, (2) mempunyai hutang yang tidak sanggup membayarnya, (3) sebagai rampasan perang, dan (4) mendapat grasi dari hukuman mati oleh raja (Korn, 1932:173).
Raja Buleleng dapat meraup hasil dari pajak penjualan budak sebesar 3.000 sampai 4.000 gulden pertahun, dengan asumsi setiap budak pria dijual per kepala 20 dollar (ringgit), penghasilan raja mendapatkan 8000 gulden per tahun (Gde Agung, 1989:26). Tingginya permintaan budak Bali disebabkan kualitas fisiknya yang dinilai baik dan tabiatnya yang dianggap unggul di antara sesama budak belian. Orang Bugis dan orang Tionghoa yang sebagian besar menjadi perantara transaksi penjualan budak antara pihak kerajaan dan pembeli asing atau lainnya (Trisila, 2011). Pemesanan budak tidak hanya untuk kebutuhan di kota besar di Jawa, tetapi di Lombok pun impor budak dari Bali.[3] Tempat mangkalnya pedagang budak, antara lain di pelabuhan Pabean, Buleleng.[4] Sampai paruh pertama abad ke-19 perdagangan budak di Buleleng berada dibawah aturan main raja dan para punggawa kerajaan tau juga sebagian besar pembeli budak harus melalui perantaraan syabandar.
Perdagangan Ekspor-Impor
Pembukaan bandar dagang di Singapura oleh Inggris pada awal abad ke-19 berdampak pada arus perdagangan antarpulau dan kegiatan niaga khususnya komoditi ekspor-impor. Sejak tahun 1820-an para pedagang Bugis dan pedagang Tionghoa telah menempati posisi kunci sebagai pedagang perantara dengan merajut jalinan dagang regional bekerja sama dengan penguasa lokal -punggawa atau raja- yang mempunyai kekuasaan ekonomi (Kraan dalam Indonesia Circle No. 62 1993: 6. Cf. Geertz 2000: 167). Perdagangan itu menggeser perekonomian Bali, yang berkembang menjadi pengekspor dan pengimpor hasil bumi, ternak, dan barang-barang innatura tertentu. Total nilai transaksi perdagangan dengan Bali (termasuk Lombok) yang terpantau di bandar Singapura terus meningkat dari 140.342 dolar pada tahun 1832-1830 dan menjadi 572.512 dolar tahun 1843-1844 (Nordholt, 1981: 30; Kraan, 1993).
Bali sebagai daerah agraris sangat ditopang dengan hasil pertanian berupa beras sebagai komoditas unggulan yang mendominasi mata dagangan ekspor. Pada tahun 1825 Bali mencapai swasembada beras dan berhasil mengekpornya bersama hasil pertanian dan barang lainnya, seperti tembakau, kacang, kapas, kelapa, minyak kelapa, sapi ternak, kuda, dan babi. Pelabuhan Buleleng berperan sebagai gerbang perdagangan hasil-hasil pertaniannya dari daerah-daerah lain di Bali. Sapi merupakan salah satu ternak ekspor yang sangat potensial walaupun proses pengapalannya di pelabuhan sangat merepotkan.


Pengapalan ternak sapi dan bongkar barang impor melalui pelabuhan Buleleng pada ke-19 | Sumber: KILTV Leiden
Untuk barang-barang yang diimpor dari daerah lain masuk ke Bali, antara lain candu, gambir, [biji] besi, barang dari katun, dan sutra (Hanna, 1990: 72-73). Kebutuhan Candu cukup tinggi di Bali karena para raja dan punggawa hingga rakyat jelata banyak yang mengonsumsinya. Bahkan secara terbuka di beberapa daerah terdapat rumah candu dan barangnya dijual dengan harga murah. Dalam perdagangan candu yang dilakukan oleh pedagang muslim dari Bugis bersifat ilegal dan kecil-kecilan karena pedagang yang memegang lisensi sebagian besar di tangan pesaingnya, [5] yakni pedagang Tionghoa. Perdagangan kain, baik katun maupun sutra yang diimpor dari India atau dari pasar bebas di Singapura yang didominasi oleh pedagang Muslim. Hingga saat ini khusus untuk pedagang kain didominasi oleh pedagang Arab dan India muslim di kota-kota besar di Bali. Akan tetapi, pedagang Tionghoa juga mengambil peran dalam perdagangan kain di Bali, terutama menjual (mengekspor) kain khas tenun dari Bali ke Jawa (Batavia) hingga ke Sumatra.
Salah satu barang impor yang unik adalah porselen yang berupa mangkok atau piring dan guci. Porsolen didatangkan dari China, namun pedagang muslim juga memainkan peran untuk mendistribusikan porselan, baik atas pesanan raja untuk melengkapi interior atau sebagai hiasan dinding (eksterior) puri-puri di Bali.[6]
Kekalahan Kerajaan Buleleng pada tahun 1849 melalui Perang Jagaraga dan otoritas Bali utara berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda juga berdampak pada pola pranata ekonomi terutama peran pedagang Muslim dari kalangan pedagang Bugis-Makasar dan Jawa mulai mulai berkurang serta bergeser ke pedagang Tionghoa yang cukup berperan. Akan tetapi, privilese masih didapatkan oleh pedagang muslim lainnya dari kalangan pedagang Arab dan India yang masuk sebagai orang timur asing.
Penutup
Bali utara yang terletak berhadapan langsung dengan Laut Jawa merupakan jalur (utama) rempah Nusantara pada posisi yang strategis, tetapi kondisi Bali yang bukan penghasil rempah sehingga tidak memungkinkan menjadi “pemain kunci” dalam hiruk-pikuknya perdagangan rempah dunia. Bali cukup diuntungkan dengan mendapatkan “remah-remah” dari perdagangan rempah yang dioperatori oleh pedagang Nusantara dari Bugis, Makassar, Jawa, Madura, Arab, India, dan Tionghoa yang memainkan peran sebagai pedagang perantara yang turut andil dalam meningkatkan perkembangan perekonomian Bali, terutama di Bali Utara di bidang perdagangan rempah, budak, dan ekspor-impor pada abad ke-18 hingga abad ke-19.
Perdagangan rempah memang tidak dihasilkan secara signifikan dari Pulau Dewata, sehingga sumbangan komoditi rempah ini nilai nominal atau komersialnya sangat minim. Akan tetapi, Bali pernah menghasilkan pala panjang yang terbaik setidak-tidaknya menurut orang-orang Jawa sehingga pala panjang yang dihasilkan dari perbukitan di Bali dikenal luas dengan “pala bali.”
Meskipun agak pahit untuk disebutkan, bahwa pedagang Nusantara juga terlibat dalam perdagangan budak di Bali, tetapi kenyataan historis ini menjadi pemain aktif bersama pedagang Tionghoa selama permintaan budak terus diperlukan oleh majikan atau pengusaha dari daerah-daerah lain. Perdagangan budak di Bali secara struktural dikuasai oleh penguasa, yakni raja dan para punggawanya, namun secara operasional di lapangan dilakukan oleh pedagang Nusantara dan Tionghoa sebagai pengepul atau dealernya, bahkan melayani hingga pengiriman budak yang diangkut dengan kapal-kapal pinisi dan jung.
Segmantasi yang agak cair adalah perdagangan ekspor-impor yang memiliki mata dagangan yang bervariasi, seperti beras, tembakau, kacang, kapas, kelapa, minyak kelapa, sapi ternak, babi, kuda, candu, kain, dan porselen (keramik). Tidak semua mata dagangan ekspor-impor dioperatori oleh para pedagang Nusantara, namun sebagai pedagang perantara dapat memperjualbelikan, seperti beras, sapi, candu, dan kain. Perdagangan candu cukup menggiurkan karena permintaan candu di Bali cukup besar, tetapi pemerintah Belanda memberlakukan peraturan dan pembatasan, sehingga pedagang Bugis dan Madura yang berkecimpung dalam perdagangan ini bersifat ilegal dan dalam jumlah kecil. Andil para pedagang Nusantara yang andal dalam perdagangan kain terutama dari kalangan pedagang Arab dan India (muslim) yang masih “membekas” eksistensinya hingga saat ini. Perdagangan porselen atau keramik dan gerabah secara umum memang didominasi oleh pedagang Tionghoa.
Persaingan dagang antarpedagang Nusantara hampir di semua sektor cukup ketat di Bali Utara, namun sepanjang catatan sejarah tidak pernah terjadi pergesekan yang masif hingga memicu tindak kekerasan meskipun kebijakan zaman kerajaan hingga Bali Utara dikuasai Hindia Belanda lebih banyak menguntungkan para pedagang Tionghoa.
Daftar Pustaka
Agung. Ide Anak Agung Gde. 1989. Bali Pada Abad XIX. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Blusse, Leonard. 2004. Persekutuan Aneh: Pemukin Cina, Wanita, Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC. Yogyakarta: LKiS.
Gallob, Annabel Teh dkk., 2020. Nusantara Semasa Raffles: Catatan dan Laporan Perjalanan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Timor, Rotti, Sawu, Solor, Flores, dan Sumba. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Geertz, Clifford. 1980. Negara: The Theatre State in Nineteeth-Century Bali. New Jersey: Princeton University Press.
Geertz, Clifford. 2000. Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas. Yogyakarta: Bentang.
Hanna, Willard A. 1990. Bali Profile: People, Events, Circumstances 1001–1976. Maluku: Rumah Budaya Banda Naira.
Indische Gids No. 30. 1908 “De Opium-regie op Bali”
Korn,V.E. 1932. Het Adatrecht van Bali. ‘s-Gravenhage: G. Naeff.
Kraan, A. van der. 1993. “Bali: 1848”, dalam Indonesia Circle No. 62. London: Oxford University Press,.
Kraan, A. van der. 1983. “Bali: Slavery and Slave Trade”, dalam Anthony Reid (ed.), Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia. St. Lucia: University of Queensland Press.
Liem Twan Djie. 1995. Perdagangan Perantara Distribusi Orang-orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi. Jakarta: Gramedia.
Medhurst, W.H. 1837. “Short Account of the Island of Bali”, dalam J.H. Moor, Notices of the Indian Archipelago and Adjacent Countries. Singapore.
Mona Lohanda. 1995. The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942. Jakarta: Djambatan.
Nordholt, Henk Schulte. 1981. “The Mads Lange Connection a Dannish Trader on Bali in the Middle of the Nineenth Century: broker and Buffer”, dalam Indonesia 32.
Nordholt, Henk Schulte. 2006. The Spell of Power: Sejarah Politik 1650-1940. Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV Jakarta.
Parimartha, I Gde. 2014. Lombok Abad XIX. Denpasar: Pustaka Larasan.
Pageh, I Made. 2015. “Dari Tengkulak Ke Subandar: Perdagangan di Singaraja Kota Keresidenan Bali dan Lombok Tahun 1850-1940.” Dalam A.A.A. Dewi Girindrawardani dan Slamat Trisila, Membuka Jalan Keilmuan: Kusumanjali 80 Tahun Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U. Denpasar: Psutaka Larasan.
Raffles, Thomas Stamford. 1978. The History of Java. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Reid, Anthony. 2000. Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Global Perdagangan Asia Tenggara 1450-1680. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Trisila, Slamat. 2011. “Siasat Bisnis Orang-Orang Cina di Bali Sekitar Abad XIX,” dalam Nursam dkk. Sejarah Yang Memihak. Yogyakarta: Ombak.
Utrecht, E. 1962. Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok. Bandung: Sumur Bandung.
Vickers, Adrian. 1989. Bali a Paradise Created. California: Periplus Editions.
Vickers, Adrian. 2012. Bali Tempo Doeloe. Depok: Komunitas Bambu.
[1] Lihat Liem Twan Djie, Perdagangan Perantara Distribusi Orang-orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi (Jakarta: Gramedia, 1995), p. 3; Untuk memahami peningkatan perdagangan perantara yang diaminkan oleh pedagang Tionghoa di Buleleng (Bali Utara), lihat I Made Pageh, “Dari Tengkulak sampai Subandar: Perdagangan Komoditas Lokal Bali Utara Pada Masa Kolonial Belanda 1850-1942” (Tesis belum diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998), hlm. 74, 151-161.
[2] Terbentuk beberapa perkampungan di Batavia berbasis orang-orang Bali merupakan dampak dari banyaknya budak yang didatangkan dari Bali. Kualitas budak pria dari Bali rupanya juga cocok untuk dipromosikan sebagai prajurit guna menambah pasukan Kolonial Belanda. Lihat Adrian Vickers. Bali: A Paradise Created. (California: Periplus Editions. 1989), hlm 14-20.
[3] Permintaan budak terkait dengan pesatnya pertumbuhan Kota Ampenan sebagai pelabuan persinggahan jalur alternatif perdagangan Australia, Singapura, dan China. Lihat I Gde Parimartha. Lombok Abad XIX. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2014), hlm, 64.
[4] A. van der Kraan, “Bali: Slavery and Slave Trade”, dalam Anthony Reid (ed.), Slavery, Bondage and Dependency in Southeast Asia. (St. Lucia: University of Queensland Press, 1983), hlm. 328-329.
[5] Dalam catatan Medrust, candu diperoleh pedagang Bugis melalui pasar di Singapura. dalam Adrian Vickers. Bali Tempo Doeloe. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 207.
[6] Pasca-Puputan Badung, banyak ditemukan porselen yang berusia tua dari Negeri China di antara puing-puing bagunan Puri Pamecutan dan Puri Denpasar yang rusak berat, lihat H.H. van Kol, 1914: 409. Dari pengamatan di lapangan, sampai sekarang masih tampak porselen atau keramik dipertahankan yang menjadi hiasan di Puri Pamecutan [Badung], Puri Karangasem, dan Puri Singaraja (Buleleng).


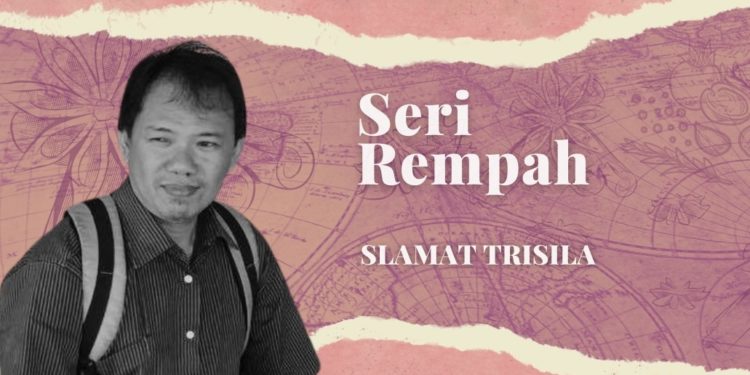


















![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











