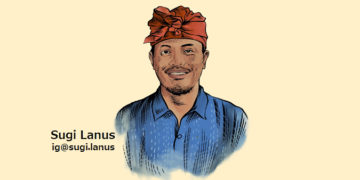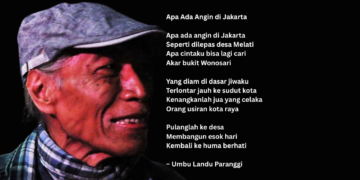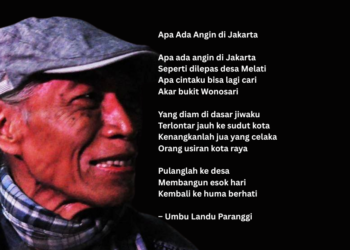SORE berselimut mendung tak menghalangi seluruh warga Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Banyuwangi untuk mengadakan selametan kampung. Ritual tahunan yang sudah berlangsung turun temurun itu telah menjadi ritus kolektif untuk memohon berkah kepada Tuhan YME dan leluhurnya. Menjelang matahari terbenam, setiap keluarga sibuk menggelar tikar dan menyiapkan hidangan khas Nasi Tumpeng dan Pecel Pitik di halaman rumahnya.
Selain itu, sebagian warga yang terlibat langsung pada ritual adat Tari Seblang juga mengadakan selamatan di panggung utama pertunjukan. Panggung itu terletak di tengah kampung, menutup jalan utama. Panggung pertunjukan beralaskan karpet hitam dan sebuah balai terbuka berhias janur dan bunga-bunga segar menghadap ke timur sebagai elemen sakral untuk menempatkan berbagai macam sesaji. Balai ini disebut sebagai Sanggar Pamujen berfungsi seperti altar meletakkan berbagai sesaji dan hasil bumi.
Usai sholat maghrib berjama’ah, acara selamat pun dimulai serentak oleh seluruh warga. Lampu-lampu dipadamkan, digantikan oleh ajug-ajug, lampu minyak yang diletakkan pada sebatang bambu. Do’a secara Islam dipimpin oleh ulama setempat yang berpusat di panggung pertunjukan. Usai selamatan, para santri dari anak-anak hingga remaja dipimpin oleh tokoh agama melakukan pawai obor keliling kampung dengan mengumandangkan adzan di beberapa situs-situs penting desa.
Minggu (23/06/24) lalu menjadi malam sakral yang dipilih oleh pelaku adat Bakungan untuk menyelenggarakan ritual adat Seblang. Selain ritual bersih desa dengan acara inti selamatan dan ritual Tari Seblang, beberapa hari sebelumnya panitia yang diinisiasi oleh Karangtaruna setempat menyelenggarakan berbagai pentas seni dan bazar untuk memeriahkan ritual tahunan ini.
Setelah sholat Isya’, warga mulai berdatangan memenuhi panggung pertunjukan tari Seblang. Ritual ini juga dihadiri oleh pejabat setempat untuk membukanya secara seremonial. Serangkaian acara sempat terhenti oleh hujan yang sudah tak bisa dikendalikan. Walau demikian, tak seberapa lama hujan pun berhenti.
Iring-iringan penari seblang datang dari arah timur, membelah kerumunan penonton yang cukup padat. Seorang penari wanita paruh baya bernama Isni, 52 tahun dalam keadan tak sadarkan diri memegang dua bilah keris di kedua tangannya. Memasuki kalangan pertunjukan, penari Seblang itu didamping oleh Lurah Bakungan, Dukun dan Pengudang serta diiringi oleh dua orang pemuda membawa obor api pada barisan terdepannya. Gending Giro khas Banyuwangian dari Gemelan Gedhe menyambut rombongan Seblang dengan bertalu-talu menyemarakkan malam yang sakral.
Ritus Tarian Masyarakat Pedesaaan

Suasana Panggung Pertunjukan Seblang Bakungan | Foto: Akbar Wiyana (2024)
Menilisik tari Seblang adalah usaha penulis menelusuri jejak praktik koreografi yang mangakar dan membumi pada masyarakat ujung timur Jawa, Banyuwangi. Catatan ini setidaknya menjadi pijakan awal untuk mencari bentuk akar seni pertunjukan tari yang berkembang di masyarakat tradisi Using sebelum menarik lebih jauh kepada praktik kesenian di masa moderen dan kontemporer. Paul Wolbers dalam Maintaining Using Identity Through Musical Performance: Seblang and Gandrung of Banyuwangi memperkirakan Seblang merupakan tradisi yang paling tua di Banyuwangi. Lebih jauh, Wolbers menyebut tradisi ini memiliki hubungan paralel dengan tradisi Nini Thowong yang berkembang di masyarakat Jawa dan tradisi Sanghyang di Bali. Tradisi-tradisi itu sama-sama menggunakan pendekatan spiritual dan kepercayaan akan kekuatan alam semesta di luar kedirian manusia. Begitu juga dengan gendhing-gendhing yang digunakan juga memiliki pola dan kemiripan bahasa satu sama lain yaitu berarakar pada bahasa Jawa Kuna.
Tari Seblang menjadi representasi seni tari yang cukup arkaik dimana praktik ritus tari ini masih dijalankan oleh masyarakat pendukungnya hingga hari ini. Tidak ada catatan pasti kapan tradisi tari ini pertama kali diadakan. Seperti sejarah lisan pada umumnya, masyarakat setempat percaya munculnya tradisi seblang bersamaan dengan babat alas berdirinya kampung Bakungan. Untuk mendirikan kampung, para tetua saat itu harus menebang pohon beringin yang cukup besar. Beringin itu dipercaya menjadi tempat bersemayam paraDanyang. Melalui pendekatan spiritual, Danyang yang mendiami pohon beringin itu dipindah ke tempat lain dengan syarat masyarakat harus mengadakan ritual Tari Seblang. Jika tidak, maka penduduk desa akan mengalami bencana. Sehingga, ritual Tari Seblang menjadi ritus tolak bala untuk keselamatan kampung sekaligus menjadi penanda berdirinya kampung Bakungan.
Asumsi sejarah yang berkembang, kehadiran tradisi Seblang di Bakungan sezaman dengan perkembangan pembangunan Kota Banyuwangi atau sekitar abad 18 sebagai ibukota kabupaten semenjak kolonialime menguasainya. Pasca pemindahan ibu kota dari Ulu Pangpang ke Toyo Arum atau kini dikenal Banyuwangi.
Tari telah menjadi bagian yang sangat penting dalam nafas tradisi masyarakat di Nusantara. Tak terkecuali di Banyuwangi, seni tari tumbuh dari aktivitas tradisi yang bersifat sakral. Dalam bingkai pengetahuan tradisi yang sakral itulah tersimpan pengetahuan relasi manusia dengan kekuatan kosmologi di sekitarnya. Baik yang bersifat materi yang direpresentasikan relasinya dengan sumber daya alam di sekitarnya maupun imateri yang bersifat magis spiritual dalam hubungannya dengan kekuatan di luar kediriannya telah menjadi pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Maka menyaksikan ritual Tari Seblang Bakungan, saya merasa diajak kembali membaca tanda alam dan arsip keseherian masyarakat Banyuwangi yang hidup diantara budaya agraris dan maritim sebagai penopang kehidupannya yang dibalut dengan laku spiritual yang tumbuh dari spirit komunalitas kerakyatan. Lebih dari itu, Seblang juga mengekspresikan situasi serpihan sejarah kolonialisme dan realitas keberagaman identitas hibrid masyarakat Banyuwangi.
Estetika Keseharian pada Ritus yang Dipanggungkan

Penari Seblang menggendong boneka bayi, didampingi oleh Pengudang diiring gending Uga-uga | Foto: Akbar Wiyana (2024)
Seblang di Bakungan berbeda dengan Seblang di Olehsari. Di Bakungan, penari seblang adalah seorang wanita tua yang sudah menopause. Ritual dilakasnakan pada bulan Dzulhijjah tepatnya selepas perayaan hari raya Idul Adha. Pementasannya diadakan pada malam hari yang berlangsung hanya semalam, dimulai sekitar pukul delapan hingga sebelas malam.
Pementasan ritual tari seblang terdiri dari 17 repertoar tarian yang diiringi gending atau lagu. Seblang Lukinto, Tajen, Padha Nonton, Adol Kembang, Nglemar-nglemir, Uga-uga, Ratu Sabrang, Liya-liyu, Donsrok, Kembang Gadung, Sukma Ilang, Emping-emping, Surung Dayung, Mancing-Mancing, Pari O’ing, Erang-erang. Ketujuh-belas repertoar itu dibawakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Dalam keadaan trance, penari seblang larut dalam gending-gending yang dibawakan dua sinden perempuan dengan diiringi gamelan.
Bahasa koreografi Seblang sebenarnya sangat sederhana, bahkan terkesan menari sangat bebas mengikuti alunan gamelan. Namun, ia memiliki dasar gerakan sebagaimana tarian seblang di Olehsari yaitu gerakan sapon. Umumnya gerakan sapon muncul pada saat iringan gamelan memasuki ritme tempo yang rendah. Gerakan sapon memainkan sampur atau selendang ke kanan dan kekiri dengan tubuh membungkuk ke depan. Gerakan ini mengekspresikan aktivitas membersihkan, menyapu dan menyingkirkan berbagai halangan yang ada di depan mata. Gerakan ini juga ditemui pada tari Saghyang Dedari. Pada gending pertama Seblang Lukinto, gerakan sapon ini dominan dilakukan.
Dari ketujubelas repertoar, saya menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa bahasa koreografi yang dipanggungkan dalam bingkai ritus tari Bakungan ini mencerminkan ekspresi kerakyatan sangat kental. Narasi-narasi yang dihadirkan tidak jauh dari keseharian masyarakat pedesaan Using yang lekat dengan budaya agraris. Begitu juga budaya pesisir juga tak luput menjadi bagian dari ekspresi ritus ini.
Dalam pementasan, ekspresi gerak koreografi pada ritus Seblang sangat tergantung dengan syair yang dibawakan oleh sinden. Dari tujuh belas deretan lagu yang ada, dari judulnya sudah bisa mendeskripsikan pesan dan gagasan repertoar yang disampaikan. Tak hanya itu, alat peraga berupa objek keseharian yang dekat dengan kehidupan agraris dan maritim seperti bajak, jala dan pancing dihadirkan untuk memperkuat gagasan adegan yang disampaikan. Tanpa metafora dan stilisasi adegan serta koreografi yang rumit, ritus tarian ini tampil begitu apa adanya.
Pada lagu Ratu Sebrang misalnya, penari Seblang menuju ke arah penonton yang duduk mengelilingi panggung pertunjukan dengan membawa selendang. Penari Seblang akan menncari dua penonton anak-anak. Selendang itu kemudian dikalungkan kepada penoton menuju ke tengah panggung untuk berperan sebagai sapi dengan bajaknya. Kedua anak yang berberpan sebagai sapi tersebut merangkak berjalan selayaknya sapi yang sedang membajak sawah. Adegan ini memotret aktivitas sepasang suami istri petani yang beraktivitas mengolah lahan sawah, menanam padi, hingga memanennya dengan ani-ani.
Bagian lagu Mancing-mancing juga mengekspresikan adengan aktivitas mencari ikan di pesisir yang menggambarkan kehidupan nelayan. Sama seperti adegan sebelumnya, partisipasi beberapa penonton dibutuhkan untuk melengkapi adegan ini. Maka penari Seblang menunjuk beberapa anak di sekitar panggung untuk berperan menjadi ikan-ikan yang siap ditangkap. Adegan ini juga menjadi salah satu yang menarik perhatian penonton karena selalu menampilkan gelak tawa dari ekspresi humor penari seblang dan pengudang-nya.
Selain adegan yang mengekspresikan budaya agraris dan maritim itu, ritus tari Seblang ini juga tak luput memotret keragaman identitas yang saling berinteraksi di sekitarnya. Adegan Tajen atau sabung ayam ditampilkan pada bagian awal pertunjukan setelah lagu Seblang Lukinto. Repertoar ini menampilkan adegan sabung ayam antara masyarakat Banyuwangi dan masyarakat Bali yang diperankan oleh pemuda setempat. Masing-masing pemilik ayam memakai pakain identitas budaya masing-masing dengan membawa seekor ayam jago yang kemudian diadu di kalangan. Diiring gamelan yang rancak menambah keseruan sabung ayam yang telah menjadi potret kehidupan masyarakat Banyuwangi dan Bali kala itu.
Tak kalah menarik ketika penari Seblang membawakan adegan Donsrok. Menurut cerita yang berkembang, adegan ini menceritakan sosok pejabat Belanda di Banyuwangi kala itu. Tanpa diiringi syair lagu, gamelan dibunyikan dengan tempo mars yang mirip drumband. Penari Seblang memperagakan bahasa tubuh yang menceriminkan kepongahan seorang Belanda. Dada dibusungkan dan tangan berada dipinggang. Sesekali ia memelintir kumisnya. Adegan penari Seblang ini telah memotret situasi kolonialisme saat itu.
Beragam tema lain yang tampil pada repertoar Seblang banyak memotret pengalama hidup sehari-hari serta objek-objek alam sekitar. Seperti, kehidupan seorang ibu yang sedang menimang anaknya maka diiringi dengan lagu Uga-uga. Permainan Manjer Kiling dengan adegan adegan anak kecil bermain Kiling (Baling-baling tradisional) maka diiringi lagu Emping-emping. Sedangkan lagu Adol Kembang mengiringi adegan sang penari menjual bunga kepada penoton.
Jika Seblang Bakungan dilihat sebagai fenomena seni, ritus ini sejalan dengan kecenderungan paradigma seni yang dicetuskan oleh beberpa filsuf abad ke-20 di dunia Barat. Seperti John Dewey, Heidegger, Gadamer, Scharfstein, Berleant dan Katya Mandoki.
John Dewey melihat keterkaitan era antara seni dan pengalaman sehari-hari. Baginya seni berakar pada pengalaman-pengalaman yang intens dan koheren. Karya seni membantu memformulasikan dan mengartikulasikan pengalaman manusia, menghajar kita bagaimana sebaiknya melihat dan merasa karena pengalaman estetik itu bersifat paradigmatik. Heideger melihat seni sebagai siasat untuk memantapkan dan mengubah perspesi sehari-hari, membukakan kemungkinan-kemungkinan baru yntuk menafsir kenyataan dan dengan itu setiap kali menciptakan kembali dunia manusia yang khas dan baru.
Begitu juga Gadamer melihat seni sebagai pengalaman keterleburan intens antara subjek (masyarakat) dengan dunia diluarnya, dan pengalaman semacam itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari hari. Schrafstein, melihat seni dari sisi fungsional, bahwa seni memungkinkan manusia menyatu (fusion) dengan realitas lebih besar di luar dirinya, dengan manusia lain dan masyarakatnya, dan akhirnya dengan realiras transendental.
Sedangkan Berleant mempromosikan estetika yang bersifat partisipatoris dan dengan begitu mendukung bahwa seni adalah bagian dari pengalaman sehari-hari yang bersifat kontekstual-kultural. Sejalan dengan itu, Katya Mandoki melihat bahwa dalam kerangka bio estetika yang lebih luas, estetika pada dasarnya adalah soal penajaman sensibilitas dalam kiprah pencerapan sehari-hari yang merupakan kebutuhan natural hidup. Secara lebih spesifik, konteks luas ini ia sebut sebagai “the prosaic”, yakni medan percaturan praktik sosio-kultural sehari-hari dimana gaya, retorika dan dramaturgi digunakan untuk memikat, menangkap serta mengelola minat dan hasrat manusia.
Seblang Bakungan sebagai Representasi Budaya di Ruang Antara

Penari Seblang saat menarikan adegan menjual bunga kepada penonton diiring lagu Adol Kembang. Bunga-bunga segar itu dipercaya memiliki berkah mendatangkan kebaikan | Foto: Akbar Wiyana (2024)
Berbicara tentang kesenian Banyuwangi memang tak bisa dilepaskan dengan spirit kerakayatan. Nafas kebudayaannya dibentuk dari residu historis yang memposisikan kawasan tapal kuda Jawa ini sebagai ruang geografi yang selalu berada pada posisi subordinat dari politik kuasa pusat, baca keraton. Sejak era Majapahit hingga Mataram Islam, wilayah yang berada jauh dari pusat kuasa ini memungkinkan tumbuhnya budaya egaliter.
Begitu juga hubungannya dengan Bali. Blambangan menjadi benteng terakhir kekuatan Hindu di Jawa untuk membendung pengaruh Islam. Bali memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk wajah kebudayaan Banyuwangi. Sri Margana dalam Perebutan Hegemoni Blambangan, menyebut etnis Using yang konon dikenal sebagai masyarakat asli Blambangan merupakan konfigurasi etnis baru, peranakan Bali yang tidak berkasta (out of caste), terbentuk pada masa periode kolonisasi Bali atas Blambangan lebih dari seratus tahun.
Posisi in-between atau di-antara dua arus kebudayaan besar Jawa dan Bali inilah yang menciptakan hubungan relasi kuasa yang timpang atas kebudayaan pinggiran yang tereksklusi dari masing-masing pusat. Maka jika dibaca dengan teori Hibridatas Homy K. Bhaba, maka posisi kebudayaan Using yang hibrid ini merupakan taktik dan strategi kebudayaan yang senantiasa menegasikan segala macam kategorisasi biner yang pada akhirnya produk budaya hibrid akan ditempatkan dalam apa yang disebut “ruang ketiga” pada setiap kategori biner. Sehingga, Using/Osing mampu merepresentasikan dirinya sabagai identitas tersendiri melalui ekspresi bahasa, kesenian rakyat dan ritual adatnya.
Namun, sebagai budaya pinggiran yang in-between ini sepanjang sejarahnya kerap kali menjadi korban ketimpangan relasi kuasa seperti akses pengetahuan, ekonomi, politik dan kebudayaan. Ketika Using/Osing diteguhkan sebagai representasi identitas kultural, puncaknya terjadi pada tahun 70an seiring dengan kebijakan politik kebudayaan Orde Baru untuk membendung pengaruh westernisasi dan kampanye anti-komunis. Maka wacana revitaliasasi kebudayaan daerah mengemuka menjadikan Using/Osing tampil dan dikenal di ruang publik. Ekspresi kebudayaan Using menjadi identitas kultural Banyuwangi yang dilegitimasi oleh negara.
“Eksotiasasi” kebudayaan Using pun menjadi magnet baru untuk mendukung pembangunan daerah misalnya pengembangan pariwisata. Berbagai ekspresi kebudayaan Using menjadi komoditas yang stategis untuk menjadi objek turisme. Keadaan ini seperti mengulang kembali cara pandang kolonial melihat kebudayaan masyarakat. Yaitu dengan membangun narasi kepada masyarakat tentang seni yang indah-indah serta kehidupan desa yang damai dan tentram semata. Fenomena itu bisa dilihat dari karya-karya seni pertunjukan yang tampil di ajang-ajang seremonial dan festival yang mendukung agenda-agenda pemerintah. Pada konteks Seblang, ritus ini kerap hadir menjadi bagian dari Banyuwangi Festival dengan menggunakan tajuk promosi “The Mystic Dance of Seblang Bakungan”. Narasi praktik mistisme diproduksi berulang-ulang untuk menarik minat kunjungan wisatawan.
Kondisi ini turut mempengaruhi perkembangan wacana dan praktik kesenian di Banyuwangi khususnya pada disiplin seni tari dan pertunjukannya. Tradisi Seblang kaya akan pengetahuan masyarakat Using yang dinamis seakan tersamarkan oleh wacana seni budaya yang meromantiasasi magisme belaka. Padahal membicarakan adat masyarakat tradisi sangat membutuhkan kacamata yang holistik dengan memperhatikan antara sistem kepercayaan, relasinya dengan alam sekitar bahkan dinamika situasi sosial, ekonomi dan politik yang turut membentuk kebudayaannya.
Melihat kecenderungan dinamika wacana seni yang berkembang di tingkat lokal, saya melihat terjadi keterputusan pengetahuan yang berkembang di masyarakat Using. Jalin kelindan Ritus Seblang Bakungan antara pengetahuan yang bersifat spiritual imaterial dan material-keseharian tak begitu banyak dibicarakan. Padahal, wacana itu perlu digali dan dihadirkan untuk melanjutkan estafet pengetahuan tradisi kepada generasi berikutnya. Saya menduga, dominasi wacana yang kebudayaan yang berkembang di daerah seperti di Banyuwangi kerap kali diproduksi tunggal oleh otoritas dan elit kebudayaan setempat. Sehingga masyarakat tak memiliki alternatif pengetahuan. Kondisi ini telah mengakibatkan mandek-nya skena kesenian dan kebudayaan yang berkembang alih-alih kritis dan peka akan situasi kekinian.
Ritus tari Seblang Bakungan, selain melibatkan roh-roh leluhur yang hadir di tengah masyarakat melalui medium tubuh perempuan penari. Ritus ini mengajararkan kita akan kepekaan para leluhur dalam membaca alam, situasi kekinian, keseharian dan bahkan kritik pada kepongahan sosok Belanda pada masa kolonialisme yang menindas masyarakat Banyuwangi kala itu melalui reperetoar Donsrok. Seblang Bakungan menjadi ritus yang bersifat spiritual atas kekuatan alam yang diekspresikan melalui napak tilas pada sumber-sumber mata air sebagai bentuk penghormatan kepada sumber daya alam dan leluhurnya.
Jauh sebelum para pemikir seni kontemporer Barat mewacanakan estetika sehari-hari sebagai salah satu aliran seni yang hari ini cukup populer. Ritus Seblang Bakungan bersama masyarakat pendukungnya telah terlebih dahulu menjalani praktik seni pertunjukkan yang mampu mengikat masyarakatnya melalui dramaturgi pertunjukan ritus yang sangat lengkap.
Esai ini ditulis dibawah program Arts Equator Fellowship 2024.
Sumber Bacaan :
- Bambang Sugiharto, Seni dan Dunia Manusia dalam buku Untuk Apa Seni, Bandung, 2020
- Paul Wolbers, Maintaining Using Identity through Musical Performance: Seblang and Gandrung of Banyuwangi East Java (Indonesia), University of Illinois, 1992
- Wiwin Indiarti, Simpang Jalan Kebudayaan: Identitas, Hibriditas dan Komoditas Budaya di Banyuwangi, Makalah dalam Talkshow Kebudayaan dengan tema “Peran Seni Budaya dalam Pendidikan” yang di selenggarakan oleh Panitia Dies Maulidia UKM Teater Ping gir Kali – Institut Agama Islam Ibrahimy, Genteng – Banyuwangi, 31 Maret 2018.
BACA artikel lain dari ARIF WIBOWO