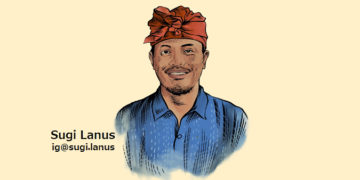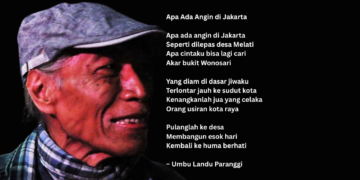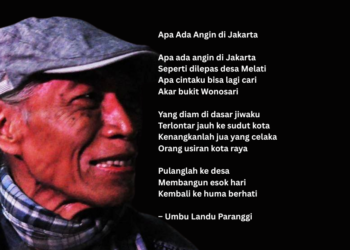PURI Agung Kaleran Tabanan yang biasanya sepi itu mendadak ramai. Menjelang matahari menyingsing, sejumlah orang mulai berkumpul dan memadati halaman puri dengan rumput yang hijau nan lapang. Pengunjung disambut dengan instalasi seni berupa panel-panel zig-zag berbalut kanvas putih. Sekilas menggambarkan figur posisi berdiri, berlutut hingga jongkok membentuk sekuen bergradasi. Instalasi itu menjadi penyambut sekaligus mengarahkan pengunjung untuk munuju ke panggung utama berlatar Pemedal Agung.
Di sisi kanan panggung pada sebuah bale, menjadi ruang pamer arsip-arsip visual Bali 1928. Sedangkan di sisi kiri, bidang dinding bale yang sepertinya bangunan gudang beratap pelana itu direspon dengan sentuhan visual menarik. Jajaran kipas-kipas dengan latar belakang frame cermin yang menghasilkan efek pantulan baik dari kipas itu sendiri maupun objek sekitarnya. Kedua instalasi seni itu merupakan karya Gurat Institute. Tak ketinggalan, di Bale Banjar sisi Selatan Puri juga terdapat aktifivas workshop Tari Kebyar Duduk. Matahari kian meredup, pencahayaan yang ditata oleh tim artistik mulai nampak. Musik latar Balinese Ceremonial Music garapan composer Collin Mcphee itu sayup-sayup menambah suasana venue festival yang mampu membawa imaji jembatan masa lalu dan masa kini.
Saya sebagai penonton pada gelaran “Merayakan Marya” pada 26-28 April 2024 ini melihatnya alih-alih sekedar festival, melainkan rangkaian repertoar pertunjukan yang jalin menjalin sebuah bentangan ruang produksi pengetahuan. Baik itu tentang Marya maupun dramaturgi sebuah kuratorial seni pertunjukan yang patut dibincangkan. Dimana pada pertiwa itu telah menjadi ruang alternatif mempertemu-hubungan berbagai subjek baik seniman, penampil maupun penonton untuk berdialog dan bertukar gagasan.
Jika The Famous Squatting Dance: Jung-jung te Jung hadir dalam karya tunggal yang beberapa kali telah dipanggungkan, maka berangkat dari karya itulah “Merayakan Marya” hadir dalam bentuk dramaturgi festival. Kurang lebih itulah sepenggal narasi yang disampaikan oleh Mulawali Institute dalam sebuah liputan press rilis yang diterbitkan tatkala.co. Dimana sprit Marya dihadirkan kembali dalam berbagai bentuk program seperti tari dan seni rupa kontemporer, pameran arsip Bali 1928, workshop tari hingga napak tilas. Festival ini bisa menjadi pemantik untuk memperluas cakrawala artistik maupun wacana ragam praktik kesenian di Bali.
I Ketut Marya di Antara Silang Zaman
Seperti pada beberapa ulasan The Famous Squatting Dance yang telah saya tulis sebelumnya. Keberadaan sosok I Ketut Marya (1897-1968) hidup semasa ketika Bali mengalami perubahan lansekap sosial politik yang cukup dinamis. Pasca meletusnya Perang Puputan (1906) dan Puputan Klungkung (1908), Pulau Bali telah berada dibawah kekusaan kolonialisme Belanda. Sebagai wilayah jajahan dengan geografi pulau yang kecil dengan kebudayaan Hindu yang kuat pun kontras dengan wilayah jajahan lainnya di Nusantara. Maka Pemerintah Kolonial mulai mengeksploitasi pulau ini dengan mengembangkan industri pariwisata. Visi ini sejalan dengan politik Bali Seering (1938), sebuah kebijakan politik kebudayaan untuk Bali untuk memperkuat citra Bali sebagai Pulau Surga dengan keindahan alam tropis dan kebudayaan yang otentik. Kebijakan ini juga sebagai upaya Pemerintah Kolonial membendung pengaruh gejolak politik pergerakan yang terjadi di Jawa.
Di masa Bali yang dinamis itu, salah satu penanda zaman yang cukup menonjol adalah kemunculan Gong Kebyar di Buleleng. Kesenian musik gamalen ini menjadi tonggak revolusi seni musik, tari dan seni pertunjukan Bali. Sehingga, membicarakan tari Bali di abad 20, tak bisa dilepaskan dengan kehadiran Gong Kebyar. Peneliti, seniman dan pelancong Barat pun berdatangan, menikmati keindahan alam dan budaya Bali yang otentik. Walter Spies, Colin McPhee, Margaret Mead dan Gregory Bateson adalah sederet nama yang banyak mendokumentasikan kesenian Bali pada kisaran awal abad 20. Pada saat itulah Bali mengalami Renaisans Budaya.

Komang Tri Ray Dewantara (Mang Tri), penampil The (Famous) Squatting Dance : Jung-jung te Jung | Foto: Amrita Dharma
Dalam tulisan Edward Herbst, Bali 1928, vol. IV Seni Pertunjukan Upacara, menyebut kerakater gamelan Gong Kebyar itu melalui kutipan berikut; “Beberapa seniman sepuh dari Bungkulan menyebutkan bahwa musik penuh semangat, marching band, pascaperang Belanda telah mempengaruhi selera dan gaya kesenian kebyar pada masa permulaannya”.
Sementara itu, Colin McPhee secara khusus menulis catatan tentang Gong Kebyar yang berkembang di Buleleng itu dalam Music in the Form and Instrumental, Organization in Balinese Orchestral Music :
“Regen Buleleng, Anak Agung Gde Gusti Djelantik, yang pada tahun 1937 bercerita pada saya, menuturkan bahwa penanggalan dalam catatan hariannya menunjukkan gamelan kebyar pertama kali diperdengarkan kepada khalayak umum pada Desember 1915, yaitu pada saat beberapa sekaa gamelan terbaik di Bali Utara mengikuti perlombaan gamelan di Jagaraga”.

Pengunjung menziarahi pameran seni rupa karya Gurat Institute dalam sebuah performance monolog puisi | Foto: Amrita Dharma
Marya hadir dan mulai menarik perhatian para peneliti barat juga tak lepas dari persinggunganya Gong Kebyar. Jika sebelumnya ia seorang seniman tari Gandrung yang menghibur masyarakat dari desa ke desa. Melalui persinggungannya dengan Gamelan Gong Kebyar, Marya meresponnya dengan ragam koreografi kontemporer Bali pada saat itu yaitu jongkok dan nyeregseg yang begitu dinamis. Dari situlah Ia melahirkan tari Igel Jongkok yang kini dikenal sebagai Kebyar Duduk. Etnolog Miguel Covarubias mengenalkan Mario (julukan di kalangan peneliti dan seniman Barat) kepada khalayak dunia hingga sosoknya dikenal sebagai koreografer tari yang mahsyur dari Bali.
Narasi itulah yang menjadikan Marya sebagai sosok penting dalam perkembangan dan periodisasi tari di Bali. Masa hidupnya, Marya berada pada zaman transisi yang penuh gejolak sosial politik dan saling-silang pertukaran budaya dari zaman kolonialisme hingga kemerdekaan. Latar belakangan zaman inilah yang menyimpan kekayaan “arsip” pada tubuh Marya.
Pada masa hidupnya Marya berkarya dengan penuh dedikasi yang tinggi sebagai seorang seniman tari sekaligus masyarakat biasa tanpa tendensi politis atas realitas Bali yang terjajah kala itu. Dari sederet karya-karyanya setelah persinggungannya dengan Gong Kebyar, bahasa koreografi yang nampak adalah semata estetika tarian Bali yang sangat romantik nan dinamis. Kosa koreografi-nya masih tetap merepresentasikan bahasa tubuh koreografi tradisi Bali yang sangat khas. Marya dan karya-karyanya berada pada posisi ambiguitas di satu sisi ia menjadi seniman tari yang telah mendobrak kemapanan tradisi. Di sisi lain, dalam suasana realitas politik Bali kala itu ia hadir memenuhi hasrat kolonialisme.
Kecakapan Mulawali Institute mengolah Marya sebagai material arsip pengetahuan dalam sebuah gelaran festival patut diapresiasi. Di tengah saling silang wacana yang berkelindan, alih-alih terjebak pada cara pandang kolonilistik memaknai wacana estetika timur dan lokalitas yang romantik. Spirit dekolonisasi pengetahuan atas arsip-arsip peninggalan orientalis itu nampak begitu kuat. Begitu juga koreografi jongkok warisan Marya tak semata-mata dibaca ulang untuk meromantisasi kebesaran Sang Maestro.
Estetika jongkok dibaca ulang lebih jernih melalui perspektif poskolonial. Sebagai masyarakat terjajah, koreografi jongkok bahkan telah menciptakan pengalaman menubuh pada gestur sikap sehari-hari. Fenomena ini terjadi pada masyarakat di negara-negara bekas jajahan di kawasan global selatan. Tak hanya terlihat pada gestur tubuh koreografi sehari-hari, pengalaman itu juga terlihat dari sifat inferior yang masih sulit dihapus. Gagasan reflektif ini begitu kuat hadir pada karya The (Famous) Squatting Dance : Jung-jung te Jung sebagai basis pengembangan Festival Membaca Marya.
Estetika Jongkok dalam bentuk Koreografi Kontemporer
Tak berhenti meromantisasi sosok dan karya Marya sebagai maestro legendaristari Bali yang mampu mengubah wajah tarian Bali pada masa abad 20 yang saat ini kita kenal. Wayan Sumahardika sebagai direktur artistik Mulawali Institute, melalui karya tunggal teater-tari The (Famouse) Squatting Dance : Jung-jung te Jung mencoba menelisik dan memaknai ulang gagasan estetika jongkok yang dikembangkan oleh Marya. Bersama dua karya seniman tari lain yang mengusung bahasa koreografinya Marya, adalah Ninus dan Gusbang. Festival yang berlangsung tiga malam ini menjadi ruang panggung presentasi tiga karya yang tampil secara berturut-turut. Melalui ketiga karya itu, kemapanan estetika tari Bali yang lahir dari Marya dimaknai ulang menjadi lebih kontekstual dan konstruktif dalam membaca ulang patahan sejarah Bali pada abad 20. Karya repertoar ini layak menjadi pintu masuk untuk menjelajahi Bali dan seni pertunjukan kontemporernya.
Melalui “Bee Dance”, Ninus mengambil insipirasi dari Tari Oleg Temulilingan yang diciptakan Marya pada tahun 1952 atas pesanan John Coast. Gagasan koreografi yang diisung Ninus itu adalah “transmigrasi” pengetahuan melalui bahasa koreografi yang menembus batas budaya dan geografi yang berusaha mendioalogkan timur dan barat dalam hal ini Bali dan Eropa, serta keragaman biografi tubuh para penarinya. Karya ini sangat reflektif ketika wacana identitas dan ke-otentikan kerap kali menghegemoni masyarakat untuk menguatkan kepentingan ekonomi pariwisata budaya.

Sejak Padi Mengakar karya Gung Bang Sada. Foto: Amrita Dharma
Sedangkan Gusbang menampilkan gagasan koreografi “Sejak Padi Mengakar” yang menggunakan material koreografi laku Jongkok pada Kebyar Duduk. Koreografinya lahir dari kegelisahan atas perubahan spasial di lingkungan desanya dari kawasan agraris menuju kawasan industri pariwisata yang masif. Hilangnya sawah dan kebun menjadi fasilitas akomodasi pariwisata perlahan tak hanya mengubah setting spasial desanya namun juga kondisi sosial yang juga berubah dari masyarakat agraris menuju industri. Laku duduk atau jongkok menjadi bahasa koreografi yang menjembatani budaya agraris. Laku duduk dan jongkok diinterpresi mencerminkan relasi dan kedekatan antara manusia dan bumi.
Ketiga karya repertoar tari di atas tampil di bawah tema kuratorial “Merayakan Marya”. Ketiganya lahir menjembatani estafet spirit Marya di masa lalu. Jika Marya semata mengembangkan gagasan estetika koreografi yang lahir dari pengetahuan tradisi serta respon terhadap gamelan Gong Kebyar yang dinamis sekaligus romantik itu. Maka, ketiga karya yang tampil ini berusaha melampaui Marya. Para seniman tari ini tak hanya berkutat pada tataran estetika dan stilisasi gerak semata. Namun juga secara kritis menghadirkan gagasan konstruktif dan ekspresi kekinian yang patut disampaikan kepada khalayak atas situasi Bali kontemporer hari ini.
Menyitir pernyataan Sal Murgiyanto, seniman dan kritikus tari senior Indonesia. “Kontemporer”, selain mengacu pada kondisi kekinian juga diekspresikan tidak melulu pada bentuk dan bahasa koreografi semata. Namun lebih dari itu bagaimana sebuah karya dapat menyingkap sisi gelap zaman serta keberpihakannya pada nilai-nilai kemanusiaan.
Melalui ketiga karya itu, setidaknya Bali yang mememiliki tradisi dan pengetahuan tari yang kuat itu tidak terjebak pada kemapanan yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Namun lebih dari itu, karya seniman muda Bali tersebut merupakan ungkapan gagasan kritis atas kondisi Bali hari ini dalam bentuk repertoar koreografi yang cukup tajam.
Estetika Festival sebagai “Pertunjukan Teater”

Penonton merespons salah satu instalasi seni rupa karya Gurat Institute | Foto : Hizkia Adi Wicaksono
Saya teringat dalam sebuah obrolan santai bersama seorang sahabat pada suatu perjalanan sepulang dari Pura Agung Besakih medio 2023 lalu. Sahabat saya ini mantan jurnalis yang bergelut pada aktifisme kebudayaan dan isu perempuan di Jogja. Obrolan itu membicarakan perihal bagaimana idealnya karya tari atau disiplin seni pertunjukan dipresentasikan kepada publik dalam sebuah kuratorial seperti halnya pameran seni rupa? Mengingat karakater seni tari atau seni pertunjukan bersifat sementara (emphemeral). Berbeda dengan seni rupa yang berwujud kebendaan baik itu visual dua atau tiga dimensi.
Sebagai penulis yang baru seumur jagung menceburkan diri pada praktik wacana seni pertunjukan, saya melihat festival “Merayakan Marya” ini sebagai prototype festival yang cukup kreatif mengemas presentasi beberapa karya tari di bawah payung kuratorial. Melalui beragam program seperti presentasi karya ketiga seniman dalam sebuah pertunjukan, pameran arsip dan seni rupa, workshop, ceramah dan diskusi publik hingga napak tilas nampak dirancang melalui pendekatan berperspektif penonton dalam menikmati sajian program acara.
Acara disusun berdasarkan urutan yang begitu tertata dan saling berkaitan antar program. Pada waktu jeda, transisi satu program ke program berikutnya selain pemandu acara memiliki peran untuk mengarahkan, denting alarm yang menggema juga cukup efektif untuk meningatkan dan mengarahkan penonton. Sehingga penonton yang hadir pun di setiap malamnya secara psikologis akan didorong untuk menikmati sajian program secara runtut.
Selama tiga malam, presentasi ketiga karya repertoar tampil secara berurutan setiap malamnya dari The (Famous) Squatting Dance, Bee Dance dan Sejak Padi Mengakar. Pada tiap tampilan repertoar, penonton diajak secara ulang alik menikmati karya ketiga seniman tari kontemporer sekaligus karya Marya sebagai presedennya. Seperti Bee Dance pada karya Ninus. Pada penampilan malam itu dikemas melalui sequence (urutan) pembabakan yang cukup eksploratif. Bee Dance menggunakan metode lintas media dari film tari dari layar ke panggung. Kemudian Ninus hadir sebagai penari di tengah panggung sebagai representasi tubuh sang koreografer sekaligus penampil. Secara halus transisi babak akhir repertoar tampil menyambung berupa penampilan tari Oleg Tamulilingan lengkap dengan gamelan Gong Kebyar-nya.

Profesor I Made Bandem, akademisi tari ISI Denpasar melakukan koreografi Kebyar Duduk saat memberikan ceramah publik | Foto: Amrita Dharma
Hal ini juga dilakukan pada malam ketiga, ketika karya Gusbang, Sejak Padi Mengakar tampil di tengah panggung. Namun sayangnya, transisi antara karya baru dengan preseden yang dihadirkan berupa Kebyar Terompong tidak dilakukan. Sehingga jeda pergantian antara repertoar baru dan presedennya itu tidak terlihat seperti malam sebelumnya. Jeda pergantian waktu itu menyebabkan rangkaian repertoar pertunjukan malam itu terasa terputus. Mungkin jika repertoar karya Gusbang itu ditampilkan secara menyambung dengan Kebyar Terompong akan nampak lebih dramatis.
Catatan yang menarik dari festival ini juga ada pada bagian ceramah dan diskusi publik dari para akademisi dan seniman tari di Bali. Sesi ceramah dan diskusi dalam sebuah festival umumnya tampil secara terpisah dengan pertunjukan. Namun, pada festival ini sang dramaturg secara jeli menempatkan waktu ceramah dan diskusi publik ini terintegrasi dengan pertunjukan utama. Alih-alih menjadi ceramah dan diskusi yang membosankan, penonton malah diajak terhanyut menikmati praktik estetika para seniman sekaligus menghayati wacana yang disampailan oleh para tokoh seniman dan akademisi tari seperti I Made Bandem dan I Wayan Dibia.
Pola setting tempat duduk audience dan panggung juga tak luput sangat mempengaruhi fokus audience menikmati dan menyerap gagasan yang dihadirkan. Walaupun di ruang terbuka, strategi untuk menciptakan fokus diskusi yaitu dengan menata kursi-kursi audience secara grid di malam kedua dan setengah melingkar di malam ketiga. Venue diskusi sengaja diposisikan menyatu dengan panggung untuk mengintegrasikan ruang antara forum diskusi dengan pertunjukan itu sendiri. Kesadaran ruang dan kejelian tim artistik menciptakan perspesi penonton pada sebuah gelaran untuk membangun festival yang lebih hidup seperti ini menjadi catatan yang sangat menarik.
Upaya sang dramaturg membangun interaksi antara pertunjukan, karya seni, dan diskusi dengan audience yang hadir nampak menciptakan festival yang hidup dan intim. Pengunjung dan audience terlihat begitu aktif dilibatkan. Alih-alih menjadi penonton yang pasif, mereka pun hadir juga sebagai bagian dari pertunjukan festival itu sendiri.

Penonton diantara instalasoi seni “infinity” karya Gurat Institute | Foto: Amrita Dharma
Seperti Bertolt Brecht (1898-1956) tokoh teater postmodernis dunia yang sangat berpengaruh. Dalam hal teknik pemanggungan, ia menawarkan gagasan untuk melepaskan asumsi dinding pemisah antara penonton dan penampil. Baginya, layar sekalipun sudah tak lagi berguna. Penonton harus diberi kesempatan untuk melihat secara langsung set dekor pada saat memasuki teater. Teater tetaplah teater, bukan sepenggal kehidupan yang ditampilkan ke atas panggung.
Pada konteks tradisi Bali dan di Nusantara pada umumnya, teknik pemanggungan yang digagas oleh Bertolt Brecht itu sebenarnya sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat kita sejak dulu. Seperti pada seni pertunjukan yang berkembang pada tradisi Bali klasik tak mengenal batas ruang yang begitu tegas antara penampil dan penonton. Sehingga pertunjukan terlihat begitu sangat intim dan cair. Pada ritual-ritual upacara di Pura misalnya, tari dan seni drama tampil di antara ruang-ruang halaman Pura dan hiruk pikuk upacara. Aktivitas semacam itu telah mengakar kuat menjadi “pertistiwa pertunjukan” dalam ritus upacara masyarakat Bali.
Kembali pada obrolan saya dengan seorang sahabat, apakah ini bentuk peristiwa “pameran” pada disiplin seni tari dan pertunjukan yang ideal? Ideal atau tidak itu sangat tergantung dengan konteks yang melatarbelakanginya. Pada konteks Bali, festival ini telah memberi ruang alternatif untuk membangun dialog dan diskursus tentang wacana tari yang dapat diakses oleh seniman, penikmat seni maupun masyarakat. Bali sebagai entitas ruang dengan industri pariwisata budaya-nya yang dibangun sejak masa kolonial telah menciptakan persepsi kebudayaan yang “ajeg” dan gemerlap demi melanggengkan kepentingan industri pariwisata budaya. Maka, menciptakan alternatif gagasan seni tari dan pertunjukan yang menyingkap sisi gelap zaman menjadi sangat perlu dihadirkan bukan?
Esai ini ditulis dibawah program Arts Equator Fellowship 2024.