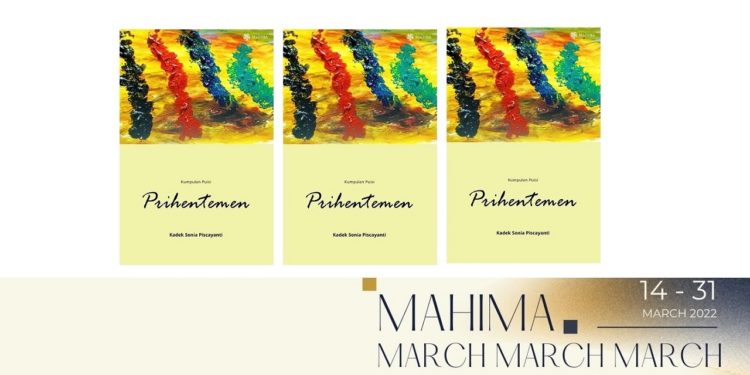Akhirnya, manusia datang pada simpulannya yang tak pernah lepas bernama ingatan. Ya, semasih ingatan ada, semasih ada yang diingat, susah melepaskannya. Manusia, ingatan, rasa, kenangan, semuanya kait mengait tanpa kemudian bisa diputus. Setidaknya, saat manusia merasakan desir yang sama, di sana manusia terdiam sejenak, untuk benar-benar menyadari rasa ngilu menjalar panas dingin di sekujur tubuh. Apakah mengenang itu selamanya menyakitkan?
Perpisahan apa pun bentuknya memang selalu melahirkan duka lara. Perpisahan yang paling dirasakan memisahkan adalah kematian (mati raga dan jiwa). Mereka yang mati, seolah-olah pergi begitu saja tanpa basa-basi guna sedikit saja memastikan yang ditinggalkan baik-baik saja. Mati yang mati, begitulah disebutkan pada Kekawin Sumanasantaka: kematian adalah caraku untuk tahu seberapa dalam kau mencintaiku.
Dunia sastra kawi itu memang memandang kematian adalah sebuah keromantisan, tak heran memang karya-karya yang lahir memang memiliki tujuan: manunggal. Satu. Sederhananya: mati.
Membaca Sumanasantaka, seketika bayangan kematian yang penuh derita itu sirna. Kematian digambarkan seperti hujan bunga-bunga dari langit, mereka yang mati maupun yang masih hidup sama-sama merasakan turunnya hujan itu dalam suka cita yang berbeda. Kematian juga digambarkan matinya manusia dengan begitu saja (tiba-tiba), ya bisa dikatakan bahwa hidup tidak lebih dari satu hembusan napas.
Lalu, pujian-pujian terhadap penguasa waktu (Kala) menjadi melodi dari puisi cinta para penyair pemuja kematian itu. Begini kurang lebih: Kala, kelak bila saatnya tiba, aku ingin mati dengan indah, aku mati begitu saja, saat bunga-bunga sumanasa (cempaka) itu berguguran lalu jatuh tepat di dadaku. Kala, aku akan menemuimu dalam kesempurnaan pujaku saat mataku terkatup, dadaku berhenti naik turun, dan senyumku manis mengembang. (salah satu bagian dari Kekawin Sumasantaka, bagian tokoh utama Putri Indumati menginginkan kematiannya).
Entah mengapa kemudian, ketika membaca karya sastra kawi saya selalu diajak jalan-jalan mengenal lebih dekat kematian. Teks-teks lontar itu mengajarkan pada saya, bahwa kematian itu nyata adanya. Lalu, bagaimana cara mengantar kematian orang terkasih kita dengan indah: puisilah mantranya.
Prihentemen, karya Kadek Sonia Piscayanti kembali mengajak saya menjenguk ingatan saya tentang apa itu kematian, apa itu kehilangan, dan bagaimana rasanya kehilangan seorang bapak. Lelaki yang tak lain adalah cinta pertama setiap anak perempuan. Menyebut kata: Bapak, seperti yang saya sudah katakan ada desir ngilu yang membuat sekujur tubuh panas dingin, adalah ribuan ingatan melesat serupa kilatan cahaya, berlompatan ke sana-sini.
Kepergian bapak bagi anak perempuannya adalah hari patah hati paling berat. Lelaki yang selalu hangat, penuh cinta, kasih yang melimpah ruah tetiba hanya terdiam tanpa mengucapkan apa pun. Tak ada lagi, genggaman hangat tangannya saat kita merasa dunia ini tak adil. Tak ada lagi, senyum penuh optimisme yang membangkitkan rasa percaya diri untuk tetap melangkah.
Atau tak ada lagi hal-hal konyol yang sering kita lewati bersama: menertawakan hal-hal sepele atau menjadikan hal-hal yang dianggap sepele bernilai luar biasa. Mengenang itu membuat kita gila, kadang tertawa sendiri, kadang berlinang air mata tanpa henti.
Prihentemen memuat sembilan belas puisi yang semuanya menguras rasa dalam membacanya. Rasa kehilangan itu nyata bila kita merasa memilikinya. Puisi-puisi ini seperti biografi Bapak dalam ingatan anak perempuannya. Seakan-akan tidak ingin cepat berlalu dan lupa, puisi-puisi ini menjadi luapan segala rasa yang mengamuk dalam dada seorang anak perempuan yang patah hati. Kematian yang indah dan begitu saja, tanpa pesan, hanya sendiri menempuh jalan sunyi.
[PRIHENTEMEN
Prihentemen dharma dumaranang sarat
“sunia memanggil manggil dalam gigil: lepaslah lepaslah dengan adil ]
Petikan puisi di atas bila dibaca berulang-ulang terasa getar serupa mantra, hangat yang mememuhi rongga dada seakan-akan api yang membakar seluruh raga Bapak. Setitik air mata menjadi semacam air suci yang meruwat segala kemalaan Bapak semasa hidup. Mata yang nanar adalah seberkas cahaya yang menerangi jalannya menuju penyatuannya dengan sunya.
Tubuh adalah tungku pemujaan, tubuh dan jiwa anak perempuanmu sedang melakukan upacara karang mengarang untuk mengantar kepergianmu yang indah itu, Bapak.
Seseorang yang belajar hakikat melepas tidak akan berhenti untuk senantiasa mengikhlaskan yang terjadi. Menerima sesuai dengan kadar ikhlas dalam dirinya dan berusaha mengatasi apa pun dengan memaksimalkan dirinya. Berkali-kali jatuh sedih, berkali-kali pula bangkit memerintahkan diri untuk tetap berjalan meski lorong kesunyian selalu terbuka. Hyang Sunyi penguasa kesunyian, seperti mengutuk manusia menjadi makhluk yang paling sunyi.
[SUNIA
Aku lahir dari kesunyian yang kau ciptakan
Semadi yang abadi
Pada tiap sel-sel yang kau puja dalam pori-pori
Pada api dan air yang menjadi energi
Pada rongga udara yang menerka cahaya
Aku ada pada semua getar debar sunia
Kau ada pada setiap tapak detak retak
Ruang ruang yang ning
Nun
Ngang
Ang Ung Mang…]
Hakikat manusia berjalan menuju rumah yang paling sunyi. Manusia mencari-cari rumah sunyi itu. Di mana? Katanya, dalam Kekawin Dharma Niskala letaknya dalam hati. Orang-orang sering menyebutnya puspa-hredaya, isinya hati, mekar kuncupnya hati, gelap terangnya hati, riuh sunyinya hati. Semuanya di hati.
Seperti puisi Sunyi, yang lahir dari kesunyian akan kembali dalam kesunyian. Mereka pemuja kesunyian, mendamba mati yang begitu saja, sebab waktu kematian selalu menjadi rahasia. Rindu untuk pulang ke rumah, adalah alasan menjenguk ingatan, seberapa dalam kenangan itu melekat. Bila belum sama sekali mengalami mohon agar tidak berpura-pura merasakan, sebab air mata selalu mengalir bahkan ketika mengenang kekonyolan sekali pun. Seberapa pun membangun benteng kesadaran, tetap saja kematian itu tidak bisa diterima sebagai sesuatu keadaan yang indah.
Pikiran manusia sering merespon perasaan yang kemudian membiarkannya larut berlama-lama. Sadar bahwa diri sedang tak sadar, melarutkan perasaan itu menjadi semacam aktivitas untuk menyegarkan kembali berbagai peristiwa. Mengulang yang dialami dalam ingatan rasa. Respon-respon bermunculan, hantaman, hentakan, semuanya diulang berkali-kali oleh ingatan rasa. Penguasa rasa tak pernah berhenti bermain-main dengan perasaan. Sayangnya, ingatan itu selalu menang menyeret manusia.
Saya ingin selalu menjenguk Bapak dalam kesembilan belas puisi ini, karena saya merasa memilikinya. Mengenangnya meski dikatakan manusia terjebak dalam ingatan rasa, saya tidak peduli. Siapa yang peduli pada perasaan seorang anak perempuan yang patah hati? Hanya mereka [para anak perempuan] yang mengalami perpisahan abadi dengan Bapaknya yang [tahu, paham] bagaimana kenangan itu sangat mahal.
Sejenak, biarkan upacara kata dari Kadek Sonia Piscayanti itu juga mengantarkan para anak perempuan yang patah hati untuk merasakan kehadiran Bapak mereka di setiap kata yang ditulis dalam Prihentemen.
Bila reinkarnasi nanti, aku hanya ingin tetap menjadi anak perempuanmu, Bapak. Kumohon. [T]
- Artikel ini disampaikan dalam sesi Book Launch Buku Puisi Prihentemen pada acara Mahima March March March di Rumah Belajar Komunitas Mahima, Rabu 23 Maret 2022