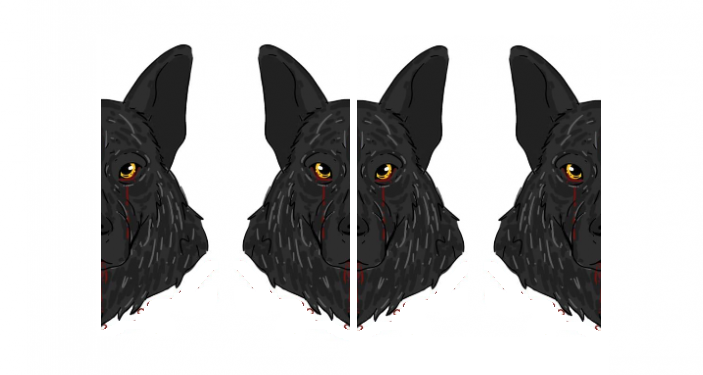“Mereka mungkin serupa Singa Nemea, Burung Simurgh, atau hewan-hewan mengerikan di Mitologi Nordik bahkan mungkin lebih buruk dari itu, hanya Gin yang tahu bagaimana Nanda kini tidak bisa bicara.”
Aku kembali meneguk teh hangat di meja. Di luar hujan seperti mempertebal ingatanku pada bocah itu. Udara dingin mulai melumati setiap yang bisa merasakan suhu di ruangan ini. Mail yang duduk di sampingku mulai mengusap-usap bahu dengan telapak tangannya. Secara cepat dan hanya sekilas. Itu hanya gerakan alternatif untuk menghangatkan bagian tubuhnya yang terasa kedinginan secara tiba-tiba. Tak lama kemudian suara pemantik menciptakan api terdengar. Mail kembali menyulut sebatang rokok. Sementara aku merasa seperti sedang tenggelam pada kubangan lendir hitam pekat dan lengket. Aku memang tidak menyukai saat-saat di mana matahari surup di sebelah barat.
“Sandeolo!” Mail lalu menghisap lagi sebatang rokok yang terselip di sela jari telunjuk dan jari tengahnya.
Aku menatapnya sejenak dan hampir lupa bagaimana orang-orang desaku memberikan istilah pada sore atau senja di mana orang-orang masa kini sangat mendambakannya sebagai sebuah jeda yang patut dirayakan di luar rumah, di pinggir pantai, di kafe atau warung kopi yang saat ini semakin berjejalan di sudut-sudut kota. Sementara itu aku teringat bagaimana setiap anak kecil atau wajaranya orang-orang harus sudah berada di rumah masing-masing. Jika sudah menginjak sore, Setiap orang tua pasti akan mencari dan mengajak pulang anaknya yang sedang asyik bermain di luar sambil mengatakan, sandeolo ayo pulang. Lalu para orang tua menggandeng tangan anak-anaknya.
“Kau pasti sudah dengar sendiri dari Gin soal Nanda yang tak bisa bicara lagi.”
Aku mengangguk. Itu adalah sore dengan langit berwarna merah keungu-unguan. Nanda dan Gin memaksa untuk melanggar larangan para orang tua. Jangan pernah masuk ke barongan saat sore. Tapi semua anak kecil tahu tempat paling nyaman dan aman untuk bersembunyi adalah di dalam barongan. Dan anak-anak kecil juga tahu barongan adalah sarang Wewe Kopek, demit perempuan yang dipercaya orang-orang desa memiliki payudara menggantung hingga menyentuh tanah yang suka sekali menyembunyikan anak-anak di sela-sela payudara dan ketiaknya.
Nanda dan Gin sore itu memutuskan untuk masuk ke dalam barongan. Hanya bocah-bocah cengeng, goblok, dan penakut saja yang mempercayai kata-kata orang tua yang kebanyakan tidak masuk akal dan bohong dan kita dipaksa untuk memercayainya. Begitu gumam Gin pada Nanda. Sementara Nanda adalah bocah perempuan yang tidak seperti bocah perempuan kebanyakan. Ia mencintai kebanalan dan perkara-perkara menyimpang dengan kehendak orang pada umumnya, tak peduli benar atau salah, baik atau buruk. Ia selalu berada pada pilihan yang paling sedikit dipilih orang. Soal paras, jangan ditanya lagi ia memang gadis tomboi, namun tingkah laku lelakinya tak bisa melunturkan keayuan alami wajahnya. Di saat-saat itu dadanya juga sudah mulai tumbuh, ia benar-benar serupa mawar yang hendak merekah, dan harum aromanya sedikit-sedikit telah terhirup oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk Gin.
Sebelum tragedi itu, Gin seperti insan yang ingin memulai kehidupan dari nol. Tapi itu mustahil, meski bengal Gin juga termasuk muslim seperti aku dan teman-teman desa lainnya. Jadi konsep reinkarnasi tentu tidak diimaninya. Ia merasa sangat berdosa, dan dosa di mata Gin serupa setumpuk penyesalan yang membebani kedua pundaknya. Sebelum ia tidak terlihat lagi untuk beberapa waktu yang tidak kami sadari, ia menemuiku saat sore menjelang magrib di sebuah gubuk yang berada di tengah-tengah ladang jagung keluargaku. Ia mendadak menghadangku yang hendak beranjak pulang. Bagaimanapun hanya anak tidak beradab yang tidak pulang ke rumah sewaktu sore menjelang.
“Tapi kau harus mendengar ini semua, jika kau benar-benar mencintai Nanda!” Gin seperti sedang mengacungkan lading ke depan leherku. Dari mana bocah yang paling aku benci di desa ini tahu perasaanku pada Nanda.
Ia memaksa untuk kembali duduk di dipan gubuk yang terbuat dari bambu itu.
“Aku tahu semuanya, aku tahu kau membenciku dan aku tahu kau terlalu mencintainya. Tapi yakinlah aku tidak melakukan apa-apa pada perempuan tomboi itu.”
Aku hanya diam saja waktu itu, memang siapa juga yang tahu kalo ia berkata jujur atau sedang berbohong. Apa yang berada di benak seseorang mustahil diketahui orang lain, kebenaran dan kepalsuannya jika tak ada bukti nyata.
“Aku akan menceritakan padamu semuanya, jadi simak baik-baik!” perintahnya. Aku pikir itu hanya semacam pembelaan agar dosa-dosa dipundaknya sedikit meringan. Tapi sedikit banyak aku sudah tahu apa yang mereka lakukan waktu itu, aku mengira-ngira semuanya. Dan entah kenapa sore itu aku ingin mendengarkan seluruh yang keluar dari mulut bocah itu.
*
Saat Kamni yang menjadi penjaga mulai menyandarkan dahinya di batang pohon mangga dan menutup mata sambil menghitung. Gin segera menggandeng tangan Nanda. Gin menatap Nanda sambil tersenyum, dalam senyumnya seolah ada maksud yang tersembunyi. Sementara wajah Nanda tampak biasa saja, tak ada tanda-tanda kecemasan sedikitpun. Ia memang perempuan yang semacam itu.
“Aku tahu tempat sembunyi paling aman dan bocah-bocah cengeng itu tak akan tahu,” ucap Gin sambil berlari melewati anak-anak lainnya yang berlarian ke sana kemari, kebingungan mencari tempat sembunyi paling aman.
Sementara Gin dan Nanda berbeda ia berlari ke arah timur melewati rumah-rumah warga, hingga ia sampai di hadapan barongan, tampak duri-duri pohon bambu menjalar ke sana kemari seolah melindungi diri mereka sekaligus mencegah tak ada yang boleh masuk ke dalamnya. Nanda sempat bertanya apakah ada jalan masuk ke dalam. Sementara Gin hanya tersenyum, seolah berkata ‘tentu saja’. Aroma tidak sedap sesekali tercium. Angin yang berhembus seolah membawa aroma-aroma yang entah dari mana. Saat itu aku mengamati mereka dari balik tumpukan karung berisi jerami kering. Dan ketika pandanganku teralihkan oleh beberapa lalat yang mengerubungi borok di lututku mereka berdua sudah tidak ada, seperti terhisap entah ke mana. Tidak lama kemudian sayup-sayup azan magrib terdengar dari kejauhan. Dan waktu itu aku segera berlari pulang, sambil mengingat wejangan para orang tua, ‘setiap anak harus di rumah menjelang magrib’ sambil berlari aku memikirkan dengan keras, ‘ke mana mereka berdua pergi?’.
Jawaban itu baru datang sekitar enam tahun kemudian. Ketika kami lulus SMA, dari mulut Gin yang entah bisa dipercaya atau tidak. Sebab semua bocah seisi desa tahu bahwa ia memang tukang bual. Tapi waktu itu aku heran dengan diriku sendiri yang dengan tanpa ada keterpaksaan mendengarkan seluruh cerita Gin hingga habis.
Begini ceritanya, menurut versi Gin yang akan kuceritakan seingatku.
Saat itu ia berhasil memasuki barongan melalui sebuah celah yang terbentuk dari lekukan-lekukan alami pohon bambu, dan hanya bisa dimasuki dengan merangkak. Gin dan Nanda merangkak bergantian. Dan saat mereka berdiri sambil mengibas-ngibaskan baju dan telapak tangan yang kotor, mereka melihat sebuah pemandangan yang berbeda. Gin hanya bergeming tidak percaya denga apa yang ia lihat, tidak seperti biasanya begitu pikirnya.
Sebelumnya, di dalam barongan yang berada di timur desa ia hanya mendapati tempat yang teduh. Dengan tanah yang dipenuhi daun-daun bambu kering, jika siang hari kau akan mendapati burung murai batu, cendet, juga bajing berseliweran di antara pohon-pohon bambu. Di dalamnya memang agak gelap, dan di sela-sela pohon bambu tumbuh beberapa tanaman liar sejenis umbi-umbian. Orang dulu mengatakan barongan tidak lebih adalah pagar desa, untuk menghalau balak, angin kencang, atau serangan kawanan hewan liar yang datang dari hutan. Tapi sejauh aku tinggal di desa, tak pernah ada serangan hewan liar atau semacamnya, yang ada hanya larangan dari orang tua agar anak-anak tak memasuki barongan.
*
“Tapi apa kau percaya cerita ayah Kamni yang mengatakan adanya pasar setan atau Wewe Kopek, lelembut perempuan dengan kedua payudara nglewer menyentuh tanah.”
“Goblok, itu hanya akal-akalan orang tua agar anak-anak kecil tak masuk ke barongan.” Mail mematikan putung rokoknya di asbak kayu yang berada di meja, dan kembali mengambil lagi dari bungkus rokoknya.
“Jika itu akal-akalan kenapa dulu kau tak berani masuk juga.”
“Bukan tidak berani aku hanya tidak tertarik.”
“Kau hanya tidak mau mengakui bahwa kau pernah takut,” aku kembali memandangi halaman rumah dari balik kaca jendela. Hujan masih belum reda. Hujan putih memang memiliki durasi waktu yang lebih lama, berjam-jam bahkan biasanya tembus pagi. Air sungai di sebelah selatan jalan raya tampak sudah mulai meluap. Orang-orang yang berada di tenda-tenda makan kaki lima tampak kesusahan atas hujan yang tidak terlalu deras namun enggan untuk berhenti. Air mulai menenggelamkan kaki-kaki kursi dan meja makan mereka. “Bukankah ketika Nanda kehilangan suara hujan juga turun seperti ini, apa kau ingat Il?”
“Aku bukan penderita Amnesia, Fud!” Mail mengangkat kedua kakinya ke atas kursi, lalu kembali menghisap sebatang rokok yang menyala di sela jari tangan kirinya. “Bagaimana aku lupa peristiwa besar di Tegal Singit, itu serupa G30SPKI di Indonesia, atau Holocaust di Eropa. hanya saja punya Tegal Singit ini lebih tidak masuk akal dan tak pernah tercatat dalam buku sejarah manapun.”
*
Usai magrib, menurut orang-orang desa masih dalam rentang waktu sandeolo. Langit mendadak putih dan hujan segera turun mengguyur Tegal Singit. Sore itu aku duduk di beranda mencemaskan mereka berdua, ah sejujurnya hanya Nanda yang aku cemaskan. Sama sekali tidak peduli pada Gin, bahkan jika ada kesempatan aku ingin memasukkannya ke lubang buaya, biar lenyap ia dari semesta. Aku hanya bisa mengira-ngira apa yang terjadi dengan mereka sebelum Gin menceritakan semuanya padaku sore itu.
Ia melihat sebuah perayaan besar di pusat kota, lebih meriah dari karnaval HUT RI yang dirayakan setiap bulan Agustus di kecamatan-kecamatan, berkali-kali lipat katanya. Sesaat bocah itu—maksudku Gin—hanya terpaku, kakinya terasa berat, saat itu ia merasa ada yang aneh. Tapi Nanda tampak sumringah, ia seperti kupu-kupu yang baru keluar dari kepompongnya dan tentu saja Ia ingin segera terbang dengan sayao barunya.
“Kenapa kau tidak cerita dari dulu jika ada tempat yang semenyenangkan ini? Ini seratus kali lebih seru dari Pasar Malam di Kecamatan,” katanya sambil berlari tanpa menghadap ke arah bocah itu. “Ayo, tunggu apalagi!”
Nanda meraih tangan bocah itu, dan berlari di sekitar wahana bermain dan tenda-tenda kecil atau stan jualan. Stan-stan itu menjual apapun: makanan, mainan, juga pakaian. Tapi mereka berdua tidak bawa uang. Mereka berdua hanya berlari, tapi diam-diam bocah itu memperhatikan wajah orang-orang yang berada di sana, hampir dari semua yang tidak memakai topeng atau tidak tertutup rambut, memilik wajah yang tampak pucat mirip mayat katanya. Nanda sepertinya tidak pernah memperhatikan orang-orang yang berwajah pucat, atau ia sudah tahu tapi tidak terlalu peduli, begitu cerita Gin padaku.
“Lubang tadi seperti pintu ke mana saja milik Doraemon, aku ingin memukulmu Gin karena merahasiakannya.” Begitu ujar Nanda pada bocah itu, sambil melotot, sedikit jengkel dan tampak girang.
Hingga sampailah mereka di sebuah tenda besar serupa Dom atau gedung olahraga di kabupaten kota. Setelah membaca pernyataan di dekat pintu: Masuk Gratis. Nanda tentu saja mengajak bocah itu masuk. Tapi Gin hanya menggeleng, ia mengaku padaku bahwa ia benar-benar takut berada di tempat itu. Baru kali itu ia merasa takut. Nanda hanya tertawa sebentar, sambil mengejeknya dengan pernyataan yang tampak sepele. Tapi bocah itu merasa seperti sedang dihantam palu besar. Kau tidak asyik, begitu ujar Nanda sambil tertawa mengejek. Kemudian Nanda meninggalkannya sendirian. Ia memilih memasuki Dom sendiri, tanpa bocah itu.
Sehingga bocah itu mengaku tampak menyedihkan, mata orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya terasa seperti sedang menertawakannya dan secara tidak langsung mengatakan, bocah menyedihkan, pengecut, kampungan, cengeng. Tapi entah kenapa bocah itu tak bisa ke mana-mana, kakinya terasa berat. Tubuhnya tidak seperti biasanya seolah paku besar menancap dari kepala hingga jantung bumi. Hingga tidak lama kemudian ia merasakan ada sebuah tangan yang mendorongnya tapi ia tidak bisa menoleh ke belakang. Ia terhuyung-huyung lantas membuka pintu Dom itu. Di dalamnya ia menemukan Nanda berada di tengah-tengah Dom diselimuti kegelapan yang entah mengapa terasa pekat dan kental, ia duduk di lantai sendirian sambil memeluk lutut, sorot cahaya dari atas mengguyurnya. Bocah itu bertanya banyak pada Nanda, tapi tak satupun pertanyaan dijawab. Ia juga menggoyang-goyang bahu Nanda. Tapi Nanda tidak beranjak atau sedikitpun melawan. Saat itulah ia merasa Nanda telah berubah, ada sesuatu yang telah dicuri darinya. Tapi oleh siapa?
Hingga beberapa saat kemudian, Dom mendadak lenyap. Suara rebana, kentongan dan perkakas memasak yang dipukul dengan pemukul seadanya lamat-lamat terdengar mendekat. Kerumunan warga dusun dengan obor dan suara berisik perkusi menggantikan semuanya. Suasana hiruk pikuk kota yang tadi Bocah itu lihat mendadak lenyap entah ke mana. Itulah saat warga desa bersukaria menemukan Nanda dengan Bocah itu. Sebelum mereka tahu Nanda telah berubah dan bocah itu atau Gin yang dituduh orang-orang dusun menjadi penyebabnya. Setelah menceritakan semuanya Gin tidak pernah terlihat lagi di dusun. Mungkin saja ia tidak tahan dengan perlakuan orang-orang padanya. Aku juga tidak mengerti mana cerita yang bisa dipercaya mana yang tidak. Itu hanya cerita dari Gin yang aku ceritakan ulang seingatku.
*
“Jika seperti itu hanya Nanda yang tahu, apa yang terjadi.”
“Berarti tidak mungkin ada Burung Simurgh, Singa Nemea atau hewan pemakan suara, seperti yang sering kau ungkit-ungkit itu dari novel bersampul biru berilustrasi Datsun Bluebird tahun 1979 warna kuning.” Kataku sambil mendengus dan meliriknya dengan sedikit kebencian yang menggumpal di dada.
“Tapi apa yang tidak mungkin di dunia nyata, jika perkara-perkara tidak masuk akal sering terjadi.” Mail mendadak bangkit dari duduknya, dan berjalan masuk ke raung tengah. “Aku ingin ke toilet.”
Sepertinya aku juga sama, kandung kemihku sudah terasa penuh sejak tadi. [T]
—Januari 2021
_____