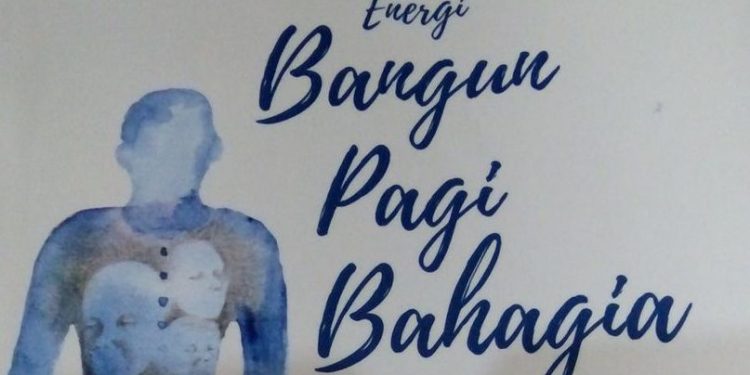#Judul buku: Energi Bangun Pagi Bahagia #Penulis: Andy Sri Wahyudi #Penerbit: Garudhawaca Yogyakarta #Tahun Terbit: Juni 2016
Adalah sebuah berkah ketika seseorang memiliki karunia dapat menikmati dan menghayati kata-kata. Terlebih jika memiliki pengalaman bersentuhan dengan puisi, baik sebagai penikmat maupun penciptanya.
Andy Sri Wahyudi adalah satu dari sedikit orang yang ‘beruntung’ mendapat karunia untuk meresapi dan tumbuh bersama puisi. Ia memaknai ‘keberuntungan’ ini dengan penuh syukur, dan sungguh-sungguh menyapa, bercakap dengan kata-kata saat mereka mengetuk pintunya.
Mungkin awalnya kata hanya ingin singgah, tapi Andy membuat mereka betah bermalam-malam, bahkan hingga dini hari. Barangkali ini juga yang membuat penulis jadi penuh energi dan bangun pagi dengan bahagia. Kita tidak pernah tahu, rahasia percakapan malam seorang penyair dengan anak-anak imajinasinya.
Sebagaimana sajak-sajak yang ditulis Andy dalam buku kumpulan puisi terkininya, Energi Bangun Pagi Bahagia, kita pun hanya dapat menerka-nerka pergulatan apa yang dialami sang penyair ketika menuliskannya. Apa sesungguhnya dipikirkan dan dirasakan penulis ketika itu? Hanya puisi dan tuannya yang tahu.
Membaca judul buku, boleh jadi pembaca berharap akan menemukan sebuah sajak yang memiliki judul serupa. Tapi ternyata tidak. Penamaan itu justru lahir dari gabungan dua sajak. Pertama, puisi pembuka ditulis tahun 2014 berjudul Energi, dan kedua,-hampir jadi puisi penutup-, ditulis tahun 2015, yakni Bangun Pagi yang Bahagia.
Keseluruhannya, buku ini merangkum 57 sajak yang ditulis dalam kurun waktu 2012 hingga 2016. Karya yang ditulis selama tahun 2015 mendominasi isi buku, dan puisi yang ditulis tahun 2012, paling sedikit dimunculkan. Saya kurang tahu pertimbangan penulis dalam pemilihan sajak-sajak yang dimuat.
Teater dan Kata
Namun, justru sajak yang ditulis pada tahun 2012 yang mengelitik saya untuk menjadikannya bacaan pertama-bukan puisi pembuka-. Hanya ada dua puisi bertahun 2012, yakni Dingin di Jari Tanganku dan Tempat Duduk yang Terus Berjalan. Dalam dua karya itu, tampak sekali sisi Andy yang telah bertahun-tahun bergelut dengan dunia teater.
Coba kita tengok dua puisi ini:
Dingin di Jari Tanganku
jari-jari tangaku lupa padaku
ia bergerak-gerak sendiri ketika malam hari
aku takut, takut sekali, jari-jariku marah padaku,
karena aku tak tahu jumlah lekukan garis-garis jariku
di manakah jam dinding?
apakah ini diam?
tapi aku mendengar hidup yang berdetak-detak
esok pagi jari-jariku akan memuat bunyi yang yang bersinar-sinar
Jogja, 2012
Tempat Duduk yang Terus Berjalan
di luar jendela ada bulan, separuh dan samar.
ia menatapku tapi aku tak berani menatapnya.
karena di bulan ada raksasa sedang melamun
mungkin mengenang cinta pertamanya.
raksasa itu telanjang bulat dan berwarna kabut.
apakah kamu takut dengan kenangan?
bertemanlah dengan raksasa di bulan,
ia akan mengajarimu mengenal kenangan
tak ada lagi rumah, tak ada lagi arah, tak ada lagi lelah
semua akan bergerak menjadi kenangan.
juga aku dan kamu.
mesin perjalanan terus bersuara.
Jakarta Jogja 2012
Terlepas dari sisi kepadatan isi puisi dan keketatan pemilihan diksi, dua puisi tersebut memiliki daya visual yang cukup kuat. Kita dapat membayangkan jika kata-kata di dalamnya diteaterkan. Andy seakan tak pernah membiarkan dirinya untuk berhenti bertanya, membiarkan imajinasinya bebas mengelana, mencari jawab akan kegelisahan-kegelisahannya. Begitu pula ia terus membuka ruang dialog dengan diri sendiri.
Tidak dapat dipungkiri, teater tampaknya cukup kuat mempengaruhi penulisan puisi-puisi Andy, sehingga lebih banyak dituliskan dalam gaya bertutur yang cair. Hanya saja cara seperti ini memang memungkinkan membuat penulis tergelincir sehingga kata-kata jadi terlalu cair dan kehilangan daya renungnya. Namun Andy masih mampu mempertahankan kesubliman kata-katanya dan tetap menyisakan teka-teki untuk pembaca.
Bentuk percakapan-percakapan dalam pertunjukan teater, dapat dilihat pula dalam puisi Andy berjudul Kangen, ditulis di Bali tahun 2013 hingga 2014.
ibuk, kini aku bisa membuat pagi dan matahari kecil, dari dinding-dinging kebahagiaan dan tanah warisan nenek moyang. apakah ibuk suka buah tomat dan papaya? di dalamnya ada vitamin yang melunturkan kesedihan dan membuatku rajin mengukir cita-cita. buk, hari ini aku ingin bertemu dengan sejarah remaja. bertemu dengan hidung lucu kekasihku dan kecerdasan berpikirnya. ibuk, aku melihat pantai berwarna nila, ingin rasanya menyelam di dalamnya. aku ingin membuat dunia dari keringat dan perasaanku. dunia untuk saudara dan teman-temanku, juga untuk semua yang kucintaiku dan yang memusuhiku. aku ini bara api, buk, tapi aku juga udara pagi. ibuk, jangan melupakan pelukan bunga sore, yang kutanam di pot plastik bekas sabun colek. jangan ya, buk.
Bisa kita baca pula kepolosan penulis, sebuah rindu yang mungkin sudah tak tertahan. Barangkali sebagai bentuk kemurnian daya ungkapnya, penulis membiarkan kata ibu ditulis sebagaimana bahasa lisan, yakni ibuk. Padahal dalam bahasa tulis, tidak pernah kita jumpai penulisan ibuk. Namun Andy membiarkan kata itu ditulis apa adanya. Terlihat kesederhanaan dan kedekatan penulis dengan alam, bagaimana dia mengungkapkannya pada kalimat terakhir sajak itu. Hal serupa dapat dirasakan juga dalam sajak Di Bawah Fajar Menyingsing: Ir Soekarno. Andy bahkan membuatnya seperti seseorang tengah mendongeng.
Pada banyak sajak-sajaknya, Andy memang kerap meminjam alam sebagai metafor-metafornya, semisal laut, bunga, gunung, bukit, langit, udara, air, matahari, padi, angin, ombak, bintang, cahaya bulan, tanah. Alam Bali pun ternyata menggoda Andy untuk menuangkannya dalam puisi.
Ada beberapa sajak yang ditulisnya di Bali, sebagian besar di daerah Budakeling. Upaya Andy untuk memahami Bali, tersurat pada “Cita-cita untuk Ibu Suasti”. Meskipun tidak sepenuhnya memahami tradisi dan kultur Pulau Dewasa, ia berusaha menuliskannya apa adanya. Misalnya pada puisi itu, dia menuliskan, beras doa menempel di antara kedua alisnya. Jelas yang dia maksudkan adalah bije.
Gugatan
Sebagian besar puisi Andy dalam buku ini mencerminkan kedamaian, persabahatan, keharuan, dan kepekaannya memperhatikan hal-hal kecil di alam. Namun bukan bearti ia enggan untuk ambil bagian pada isu-isu besar, semisal terkait peristiwa 1928, 1945, 1965, dan 1998. Ekspresi ini muncul pada karya-karyanya bertahun 2015. Bisa dibaca puisinya Aku Menggugat Kepada Lupa. Puisi terpanjang dalam buku ini. Keberanian Andy terkesan juga muncul pada sajak Merenung di Kamar Bangsat: Pang.
Tapi saya rasa sangat penting untuk diingat pula, puisi bukanlah tempat sampah yang bisa sekenanya diluapkan dengan umpatan-umpatan kotor. Kadang kita perlu untuk tahan dan sabar, tidak terpancing untuk reaktif, terlebih jika hendak merespon persoalan-persoalan sosial. Saya percaya, siapapun yang memahami kedalaman puisi, akan bertimbang untuk ini.
Upaya Andy selama ini patut kita apresiasi, selain produktif berteater, ia tetap bersetia tumbuh bersama puisi. Kebahagiaan sederhana yang kerap luput dari perhatian kebanyakan orang. Andy dan kita beruntung masih memiliki kesadaran untuk setidaknya berusaha mengundang puisi, singgah dan mengentuk pintu ‘rumah’ kita, lalu bersama menyeruput satu dua cangkir kopi semalaman. (T)