Sidang Pembaca yang budiman, coba tanya anak-anak kita hari ini. Mereka lebih kenal siapa, Norman Erikson Pasaribu atau Iben MA? Lebih ngerti isi novel Bumi Manusia atau alur drama Korea Love Scout? Lebih nyaman baca buku 30 halaman atau scroll TikTok tiga jam tanpa jeda?
Kira-kira apa jawabannya? Ya, sudahlah. Mari kita bersama diam sejenak dan menenggelamkan diri dalam renungan eksistensial bahwa kita sedang hidup di zaman di mana membaca dianggap kegiatan aneh. Bahkan kadang, membaca lebih dianggap sebagai hukuman daripada hiburan.
Padahal membaca itu suatu fondasi. Bukan cuma fondasi ilmu, tapi fondasi cara berpikir, cara hidup, bahkan cara kita menghadapi dunia yang makin kompleks ini. Tapi apa mau dikata, minat baca di negeri kita ini sedang dalam sakaratul maut. Dan parahnya, kita pura-pura tidak tahu. Bahkan cenderung tak mau tahu, dan berharap semua akan baik-baik saja. Kita membiarkan generasi muda tumbuh di tengah dunia yang hiperaktif, cepat, ramai, penuh notifikasi, tanpa dibekali keterampilan membaca yang kuat. Itu bukan sekadar kekurangan. Saya pikir itu adalah bom waktu.
Diam-Diam Merawat Budaya Anti-Baca
Para Pembaca yang budiman, mari kita buka data. Indonesia pernah menempati peringkat 60 dari 61 negara soal minat baca, itu menurut World’s Most Literate Nations. Bahkan dalam survei PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022, skor literasi anak-anak kita tetap stabil, di posisi bawah.
Banyak faktor yang bisa dituding, misal; budaya lisan yang dominan, pendidikan yang fokus pada hafalan, akses bacaan yang terbatas, hingga teknologi digital yang lebih menyenangkan daripada halaman-halaman buku. Tapi mari kita jujur saja, kita sendiri sebagai masyarakat, orang tua, guru, pembuat kebijakan, memang gagal membangun ekosistem membaca yang relevan dan menarik.
Faktor lain bisa jadi karena sejak kecil anak-anak kita lebih dididik untuk patuh daripada penasaran. Mereka lebih dibiasakan menghafal definisi daripada merenungi isi. Lebih sering disuruh belajar demi nilai ujian daripada belajar demi mengerti. Belum lagi buku-buku pelajaran kita yang, tebal, penyajian yang kaku, dan sering kali lebih bikin ngantuk daripada bikin paham.
Kita sering menyuruh anak membaca buku tebal yang membosankan, padahal mereka hidup di dunia visual, interaktif, dan serba cepat. Kita menilai buku dari “beratnya”, bukan dari kemampuannya membuat anak penasaran. Kita lupa bahwa kecintaan membaca bukan muncul dari kewajiban, tapi dari rasa ingin tahu yang dibangkitkan secara perlahan.
Celakanya, yang disalahkan adalah anak-anak kita. Dibilang malas, bodoh, tak punya semangat. Padahal sepertinya ini soal rancangan sistem pendidikannya. Sistem yang tak pernah memberi ruang untuk belajar dengan dasar rasa ingin tahu. Sudah jelas kan, siapa yang sejak awal mematikan gairah membaca itu sendiri?
Dunia Melesat, Kita Masih Ngelag
Sementara itu, dunia di luar sana sudah lari jungkir balik. AI menulis puisi, robot bisa mencuci baju, bahkan anak 12 tahun di luar negeri sudah bikin startup. Dunia kini berubah bukan per minggu, tapi bahkan per jam. Dan semua perubahan itu berawal dari satu hal, membaca dan kemampuan memahami informasi.
Tapi anak-anak dan generasi muda kita apa kabar? Kebanyakan dari mereka membuka internet bukan untuk belajar, tapi buat scroll gosip. Mereka bisa tahu semua fakta soal artis Korea, tapi gak mengerti kenapa harga cabai di saat-saat tertentu bisa naik. Mereka tahu semua lirik lagu terbaru, tapi gagal paham isi Pancasila sila ketiga. Kita mencetak generasi yang update soal tren, tapi blank soal makna yang lebih hakiki. Yang cepat baca caption, tapi susah mencerna esai. Yang bisa main HP 10 jam, tapi baca buku 10 menit sudah teriak bosan. Dan kita membiarkan itu terjadi, sambil nyeruput kopi di pagi hari.
Membaca Bukan Sekadar Aktivitas, Tapi Proses Menjadi Manusia
Filsuf-filsuf dunia sudah memberikan peringatan ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Plutarch berkata, “Pendidikan adalah menyalakan api, bukan mengisi bejana.” Kant mengajarkan pentingnya berpikir sendiri, “Sapere aude” atau “Beranilah menggunakan akalmu sendiri!”, dan itu cuma bisa dilakukan kalau otak dilatih untuk mencerna bacaan.
Paulo Freire lebih ekstrem lagi, dia mengatkan bahwa membaca itu senjata pembebasan dari penindasan. Literasi adalah alat pembebasan. Suatu bangsa, seperti bangsa kita ini, yang tak serta merta serius membangun budaya baca, pastinya sedang menyiapkan generasi yang tidak mampu membebaskan dirinya dari kebodohan, manipulasi, atau ketidakadilan.
Jika kita terus menoleransi rendahnya minat baca, maka bersiaplah menghadapi masa depan dengan generasi yang mudah terpapar hoaks, tapi malas memverifikasi. Anak-anak yang gagap menghadapi kompleksitas dunia kerja digital. Masyarakat yang pasif dan gampang diarahkan oleh narasi politik dangkal, dan itu sudah terjadi. Bangsa yang makin tertinggal dalam kompetisi global karena tak mampu mengolah dan menciptakan pengetahuan baru.
Kita akan menghasilkan lulusan sekolah yang sekadar hafal, bukan paham. Yang mudah lupa karena tak pernah membaca untuk mengerti, hanya membaca untuk nilai dan lulus. Sekali kita kehilangan kemampuan membaca dengan mendalam, kita kehilangan kemampuan berpikir merdeka. Para pembaca yang budiman pasti ingat dengan ungkapan dalm bahasa Latin “Cogito ergo sum”yang berasal dari filsuf Prancis René Descartes. Aku berpikir, maka aku ada. Jika generasi penerus kita tidak mampu “berpikir”, maka kita bersiap bangsa ini untuk tidak mampu ”ada”. Itulah bom waktu kita.
Tidak Klasik, Jangan Kaku
Meningkatkan minat baca tidak bisa hanya dengan membangun perpustakaan atau menyuruh anak membaca buku pelajaran. Harus ada perubahan pendekatan yang relevan dengan zaman, dan tetap setia pada tujuan budaya baca, yaitu membangun manusia yang berpikir. Solusi mengatasi krisis baca ini tidak bisa lagi pakai pendekatan Orde Baru atau bahkan Orde Lebih Baru: “ayo membaca!” atau “membaca itu penting!” Lah, para pembaca tahu anak-anak sekarang bukan robot. Mereka perlu alasan yang masuk akal. Mereka perlu konteks yang relevan.
Jangan remehkan komik atau webtoon karena dari situ anak-anak bisa diajak pelan-pelan ke literasi yang lebih berat. Meski perlu strategi khusus karena beresiko, bisa kita gunakan media sosial, bukan malah dilarang. Konten edukatif di TikTok atau YouTube bisa jadi pintu masuk, cuma memang harus selektif.
Kita juga harus membangun kebiasaan bertanya, bukan sekadar menjawab soal. Anak yang suka bertanya pasti akan cari jawaban, dan itu bisa jadi lewat membaca. Pemerintah bisa melibatkan influencer. Ajak seleb membaca buku dan cerita di IG Story-nya. Dengan demikian, dalam konteks modern ini membaca akan punya gengsi. Bisa juga dengan membuat membaca sebagai kegiatan seru. Agak susah ini, dan butuh effort memang. Misal, diskusi buku sambil ngemil, review bacaan lewat meme, atau apa pun yang bisa membuat kegiatan membaca jadi lebih hidup.
Dosa Kolektif Kita
Krisis baca ini bukan soal anak malas atau gerusan zaman yang makin canggih. Ini soal kita sendiri, yang tak pernah sungguh-sungguh mencintai membaca, lalu menurunkan ketidakcintaan itu ke generasi berikutnya. Kedengarannya seperti dosa turun-temurun ini. Dan kalau ini dibiarkan terus, kita sedang menyiapkan generasi yang kehilangan kekuatan dasarnya yaitu akalsehat.
Generasi yang bisa membaca tapi tak paham, bisa sekolah tapi tidak mengerti dunia, bisa bicara panjang tapi kosong makna. Generasi yang riuh di permukaan tapi kosong di dalam. Generasi yang akan tumbuh menjadi massa yang gampang diarahkan, dijadikan komoditas politik, atau bahkan tumbal pembangunan.
Mungkin memang anak-anak dan genersi muda kita tak suka membaca. Tapi lebih parah dari itu, mungkin kita semua sedang melupakan mengapa membaca itu penting. Jikaitu benar, maka itu bukan sekadar kelalaian. Maaf kata, itu sudah masuk kategori dosa kolektif kita. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI
Tag









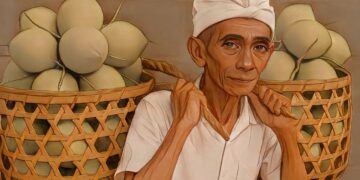













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










