SEORANG wartawan dari media internasional menghubungi saya beberapa hari lalu untuk meminta pendapat soal perkembangan arsitektur di Bali belakangan ini yang, menurut pendapatnya, semakin menjauhi nilai-nilai tradisi.
Sementara, awal tahun 2024 lalu, seorang kawan arsitek dari Swedia mengajukan satu pertanyaan mudah tetapi sangat rumit untuk bisa dijawab dengan gamblang, “What is Bali Architecture?”
Pertanyaan kedua, dari kawan dari belahan dunia dingin, itu sudah lama berputar di kepala, sementara pernyataan dari wartawan media internasional tersebut membuat saya melihat-lihat sosial media instragram. Ya, media sudah lama menjadi alat imperialism budaya di mana budaya-budaya dari negara tertentu masuk dan merangsek masuk mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dari akar tradisi di tempat lain.
Dari postingan di sosial media saya mendapati banyak hal yang terjadi dalam arsitektur di Bali selama beberapa tahun terakhir. Saya sendiri meyakini apa yang kita saksikan itu bukan sekedar bentuk atau wujud arsitektural di permukaan saja, tetapi ada kekuatan besar yang menggerakan lahirnya wujud-wujud tersebut.
Dominasi fungsi komersial pada lingkungan fisik terbangun hari ini
Menilik dari fungsi-fungsi yang saat ini tumbuh dan berkembang dalam arsitektur adalah yang mewadahi aktivitas komersial dalam berbagai skala. Kedai kopi sampai mall-mall raksasa yang juga dipenuhi dengan kedai makanan dan minuman serta produk-produk barang konsumsi lain seperti baju yang cepat berganti mode, arena bermain anak-anak artifisial, tempat nongkong anak-anak muda, dan seterusnya.
Fungsi-fungsi komersial ini merupakan anak kandung dari sistem ekonomi neoliberal yang memiliki tugas untuk memacu konsumsi yang menggerakkan roda perekonomian. Tanpa adanya konsumsi dan kompetisi, sistem ekonomi liberal tidak akan bisa tumbuh. Akibatnya, kompetisi untuk terus meningkatkan daya saiang dan persaingan harus diciptakan. Setiap pelaku usaha harus diberi peluang untuk membuka usahanya, bisa perlu, dengan banyak relaksasi peraturan.
Keterbukaan peluang untuk membuka usaha ini mengarah pada kebebasan di mana pemerintah, alih-laih membatasi, menarik diri dari pasar. Membiarkan pasar untuk menciptakan sistemnya sendiri dianggap lebih efisien dan efektif dalam menunjang keberhasilan.
Tanpa banyak kita sadari, perlahan ruang terbuka kita tergantikan perannya oleh kehadiran toko-toko dan kedai yang berkumpul di satu tempat yang kita kenal sebagai mall. Setiap hari, terutama di akhir pekan, ribuan orang datang berduyun-duyun bahkan sampai memacetkan jalan di depannya.

Karya arsitektur komersial di tahun 1970an masih memiliki elemen-elemen yang membuatnya menjadi bagian dari komunitas setempat | Foto: Maha Putra
Meski terkesan sebagai ruang publik, mall sebetulnya melakukan seleksi atas siapa yang boleh dan tidak boleh masuk melalui pemberlakukan tiket, minimal tiket parkir. Dominasi fasilitas komersial yang ada di dalam mall juga secara halus memberi syarat lain bahwa yang boleh masuk hanyalah mereka dari golongan ekonomi tertentu. Akibatnya, terjadi ruang-ruang publik yang sebetulnya adalah ruang privat. Ruang-ruang yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu dengan syarat tertentu.
Tidak hanya di dalam mall, ruang-ruang kota kita sekarang sebetulnya boleh dibilang adalah sebuah pasar yang sangat besar. Sebuah tempat di mana usaha-usaha perdagangan barang dan jasa mendominasi setiap jengkalnya. Sehingga, setiap titik lokasi bisa menjadi alat yang bertugas untuk melipatgandakan modal. Akibatnya, tidak ada lagi ruang-ruang komunal karena sudah berganti ruang komersial. Privatisasi ruang publik, istilah ekstremnya.
Peranan arsitektur dalam memacu konsumsi
Dalam kondisi di mana setiap petak lahan harus berfungsi melipatgandakan modal, maka arsitektur memiliki tugas ekstra. Ia tidak lagi berfungsi hanya sebagai penyedia ruang-ruang fungsional. Arsitektur memiliki tugas lain yaitu untuk membangun brand tidak hanya untuk usaha-usaha tadi tetapi juga branding untuk kota. Dari sinilah komodifikasi wujud-wujud arsitektur dimulai dimana tugas utamanya adalah untuk menciptakan citra atau image tertentu sehingga melahirkan gaya-gaya arsitektur unik ikonik.
Gaya-gaya arsitektur ikonik, bentuk-bentuk yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya dan dapat dibagikan dengan mudah di media sosial, digunakan untuk menarik pengunjung yang akan dengan sukarela mengeluarkan uangnya sebagai syarat masuk ke fasilitas yang dirancang oleh arsitek tersebut.
Sebuah kedai kopi dengan bentuk tidak lazim bisa membuat orang antre untuk bisa duduk di dalamnya. Sebuah restaurant dengan tema Eropa atau kedai mie bergaya Korea atau Jepang kini jamak kita jumpai.
Di saat kompetisi pasar berlangsung dengan minim intervensi pemerintah, setiap ruang usaha dipaksa untuk mampu bertahan. Maka, setiap pemilik usaha dan arsiteknya dipaksa untuk terus melakukan inovasi. Mengulangi bentuk yang sudah ada bukanlah pilihan yang baik dalam hal ini. Bentuk-bentuk wajib untuk terus diciptakan, disegarkan, dibuat berbeda dengan bentuk yang sudah ada, sehingga trend-trend dalam bidang arsitektur berganti dengan cepat. Di satu saat, orang menggemari sarang burung dan tanda jantung di tepian tebing, lalu berganti menjadi ayunan raksasa, kini beralih menjadi ruang atau kedai ikonik dengan berbagai tema.
Kecepatan trend ini menuntut setiap ruang bisa diubahsuai dengan cepat sehingga melahirkan gaya arsitektur dan ruang yang adaptif. Misalnya, kafe atau restoran bisa dirancang agar dapat digunakan untuk kegiatan komunitas pada jam-jam tertentu, sehingga ruang tersebut tidak hanya terbatas bagi satu trend fungsi saja. Ini bisa menciptakan komunitas-komunitas baru yang lebih cair melampaui komunitas tradisional yang rigid.
Peranan media sebagai sumber inspirasi dan referensi karya arsitektur
Untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang selalu baru tersebut, sekali lagi media memainkan peranan pentingnya. Website seperti pinterest, archdaily, dezeen dan lainnya menyediakan berbagai macam referensi yang bisa menjadi sumber inspirasi. Yang lainnya bisa juga melakukan komodifikasi dari wujud-wujud tradisional yang tidak berhubungan dengan arsitektur sebagai sumber inspirasinya. Misalnya bangunan seperti tumpeng, arsitektur yang berbentuk seperti lidah api, dan seterusnya. Apapun sumber inspirasi dan wujud yang dihasilkan, tujuan utamanya adalah meningkatkan konsumsi.

Desain sebuah kedai kopi menyatu dengan pusat kecantikan dan toko donat. Tampilannya mengedepankan kebebasan ekspresi ikonis | Foto: Maha Putra
Desain-desain ikonik yang muncul saat ini ditujukan untuk menarik perhatian di media sosial. Ini akan menjadi pengaruh bagi kerumunan untuk tergiring berkunjung ke tempat-tempat yang sedang ramai di media sosial dan menghasilkan fenomena ‘viral‘.
Untuk menjadi viral, suatu sifat seperti virus yang bisa menjangkiti orang dengan cepat, karya-karya arsitektur menjadikan aspek visual sebagai hal yang utama bahkan mengalahkan kualitas produk yang dijajakan di dalamnya. Kemampuan membuat ruang-ruang yang bersifat ‚comodified experience, tempat dimana arsitektur dan desain interiornya bisa dijadikan sebagai latar untuk membangun citra diri di sosial media.
Arsitektur dan tata ruang kita di abad komersialisasi
Keberhasilan melipatgandakan modal membuat nilai property suatu wilayah meningkat. Ini membuatnya menjadi menarik untuk investasi. Pemilik modal dari berbagai belahan dunia hadir dan mencoba peruntungannya. Mereka adu strategi pemasaran dan bersaing menghadirkan wujud arsitektur terkini. Urusan perijinan menjadi pelik karena pemerintah memilih untuk menarik diri dari pasar. Besar kemungkinan, hal ini membuka peluang bermainnya aparat di tingkat lokal untuk mengambil keuntungan.
Mereka bisa menetapkan aturannya sendiri yang tidak tertulis dalam aturan formal negara. Kita mungkin masih ingat ada bendesa yang ditangkap karena dituduh memeras investor, ada pemimpin desa yang didemo oleh warganya karena mengijinkan pembangunan fasilitas komersial di wilayahnya. Konflik-konflik horizontal bisa saja terjadi dalam kondisi pasar seperti ini.
Konflik ini belakangan muncul dalam wujud masalah agraria, salah satunya, pagar laut. Konon di Serangan ada investor yang memagari wilayah perairan dengan dalih yang cukup sulit diterima akal yaitu mencegah tindak kriminal penimbunan bahan bakar. Ini seolah menunjukkan jika negara tidak mampu menangani wilayahnya sehingga harus dibantu oleh investor.
Kuatnya peranan investor yang seolah melebihi peran negara bisa memicu fenomena gentrifikasi. Ini adalah gejala tersingkirkannya masyarakat lokal dari wilayah yang sudah dihuninya secara turun temurun karena wilayah tersebut memiliki keunggulan di mata investor yang memiliki kekuatan modal dan politik yang tidak mampu mereka tandingi. Gentrifikasi ini membuat bagian-bagian tertentu dari kota menjadi sangat ekslusif, hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki daya beli tinggi. Ruang-ruang kota menjadi sangat formal dan anorganik. Masyarakat tidak lagi memiliki tempat-tempat informal yang berkembang secara organik.
Antara komunalitas dan individualitas
Jika kita kembali ke pertanyaan pertama tentang arsitektur Bali yang mulai kehilangan tempatnya, maka analisis di atas sedikit memberi titik terang. Karena Bali saat ini sudah menjadi pasar yang sangat besar dimana investor dalam berbagai skala berupaya untuk mendapatkan keuntungan finansial, maka kita bisa menduga bahwa suara merekalah yang lebih dominan dalam menentukan wujud ruang-ruang terbangun kita hari ini.
Suara masyarakat lokal terdengar tetapi samar-samar. Dominasi suara dan peranan investor ini, yang didorong untuk terus bertahan dan berkembang, mendorong lahirnya karya-karya arsitektur ikonik untuk dirinya sendiri. Menjadi ikon di tengah lingkungan membuat daya jual karya tersebut ‘meningkat’ di tengah masyarakat yang haus akan validasi diri. Karya-karya arsitektur semacam ini adalah yang mengedepankan nilai individualistik.
Selanjutnya, kita menuju ke pertanyaan kedua tentang apa itu arsitektur Bali yang ditanyakan kawan dari negara Eropa. Dengan cara membuat jarak atau mengkontraskan dengan karya-karya ikonik kita bisa mendapat jawabannya. Arsitektur Bali adalah yang memiliki sifat komunalitas. Ini berlawanan dengan sifat individualistik. Sifat komunalitas ini dimulai dari kepemilikan lahan komunal, milik desa adat, yang menciptakan banyak ruang-ruang sosial. Dalam wujud fisik arsitekturnya, dominasi nilai komunalitas juga nampak jelas. Setiap karya mengandung ’common parts‘ atau bagian yang sama serupa.
Ukuran bangunan tradisional biasanya sebangun antara satu rumah dengan rumah lain. Wujud arsitekturalnya: bentuk atap, dinding, bahkan ornament-ornamennya, memiliki wujud-wujud keserupaan antara satu bangunan dengan yang lain. Keserupaan juga pada material yang digunakan. Dalam beberapa kasus, rumah-rumah tradisional dikerjakan secara gotong royong. Nilai-nilai komunalitas ini membentuk apa yang disebut sebagai sense of place atau rasa ruang bersama. Hal ini membentuk identitas dimana masyarakat merasakan lingkungannya merupakan perluasan dari karakter dirinya baik secara personal ataupun secara berkelompok.

Hibriditas antara elemen ikonis dan komunal dari sisi wujud dan material arsitektur | Foto: Maha Putra
Jika sekarang kita sering mendengar bahwa identitas arsitektur Bali mulai memudar, kita bisa melacaknya dari semakin berkurangnya nilai-nilai kebersamaan. Suara-suara investor individualistik yang memekakkan telinga mungkin lebih dominan terdengar disbanding suara publik yang sayup-sayup.
Pemerintah sebenarnya sempat berupaya untuk menghadirkan kembali nilai komunalitas ini dengan mengeluarkan peraturan yang, misalnya, mensyaratkan penggunaan ornament yang sama bagi semua jenis bangunan, penggunaan material lokal yang sama, ataupun pengaturan agar bentuk-bentuk atap tampak serupa. Akan tetapi, hal tersebut sepertinya tidak sejalan dengan nilai individualistik dan kebebasan ekspresi yang dianut oleh cara kerja ekonomi pasar neoliberalistik dan arsitek yang menyukai ekspresi tanpa batas. Meski demikian, beberapa arsitek memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa. Mereka ini mampu menghadirkan individualism sekaligus nilai-nilai komunalism dalam karyanya. Jumlah mereka memang tidak banyak, saat ini.
Semakin dominannya cara kerja pasar bebas ini bisa jadi akan semakin menenggelamkan identitas lokal. Atau, bisa jadi kita sedang menuju ke arah keseimbangan baru? Keseimbangan yang diakibatkan oleh masyarakat yang semakin heterogen karena Bali sekarang dihuni oleh masyarakat yang sangat multikultur bahkan multibangsa. [T]
Penulis: Gede Maha Putra
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel tentangARSITEKTURatau artikel lain dari penulisGEDE MAHA PUTRA







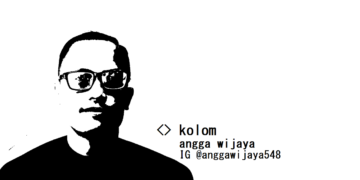













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











