NGURAH PARSUA merupakan salah seorang sastrawan produktif kelahiran Bondalem, Buleleng, 22 Desember 1946. Ia menulis hampir semua genre sastra: puisi, cerpen, novel dan esai. Ia mampu menjaga stamina hingga tua, sehingga bukan saja banyak karya yang dihasilkannya, juga rentang waktu penciptaan yang panjang.

Ngurah Parsua
Bagi Parsua, sastra sangat mengasyikkan. Meminjam ungkapan Subagio Sastrowardoyo, Parsua mengibaratkan bahwa sastra khususnya puisi, dapat menunda seseorang untuk bunuh diri. Lebih dari menunda bunuh diri “simbolik”, sastra memberi pelajaran, pertimbangan dan membuat kita ikhlas menjalani hidup. “Saya mengagumi Rabindranath Tagore,” tulisnya lebih lanjut (2014: vi).
Tagore kita tahu pernah berkunjung ke Bali. Nobelis India itu mengunjungi pusat-pusat ritual dan kebudayaan Bali, mulai Ubud, Puri Gianyar, Istana Tampaksiring, Gunung Kawi, Puri Karangasem, hingga desa Munduk yang terletak di tengah Pulau Dewata. Spirit Shantiniketan Tagore sebagai tempat yang damai dan pusat belajar, membuat Parsua terobsesi meneroka “kedamaian susastra”; sumber ilham yang tak habis ditimba.
Parsua memublikasikan karyanya sejak tahun 70-an di Bali Post, Karya Bhakti, Nusa Tenggara, Warta Bali, Merdeka, Berita Buana, Berita Yudha, Suara Karya, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Simponi, Eksprimen, Srikandi, Suara Pembangunan, Mutu, Arena, Bukit Barisan, Horison, Basis, Minggu Pagi, Prioritas, El Horas, Liberty, Selekta, Varia, Dewan Budaya dan Dewan Sastra (Malaysia).
Puisinya berjudul “Khabar” diterjemahkan oleh Kemala, penyair dan peneliti sastra asal Malaysia, dimuat Majalah Asia Week sebagai puisi pilihan (1983). Puisinya “Kepada Bali” diterjemahkan Vern Cork dalam The Morning After (2000). Sebuah cerpennya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, dalam buku Bali Behind te Seen: Recent Fiction from Bali (Australia). Puisinya “Perjalanan Terakhir” dibacakan di Universitas Kebangsaan Malaysia oleh penyair Dr. Noor SM (1983).
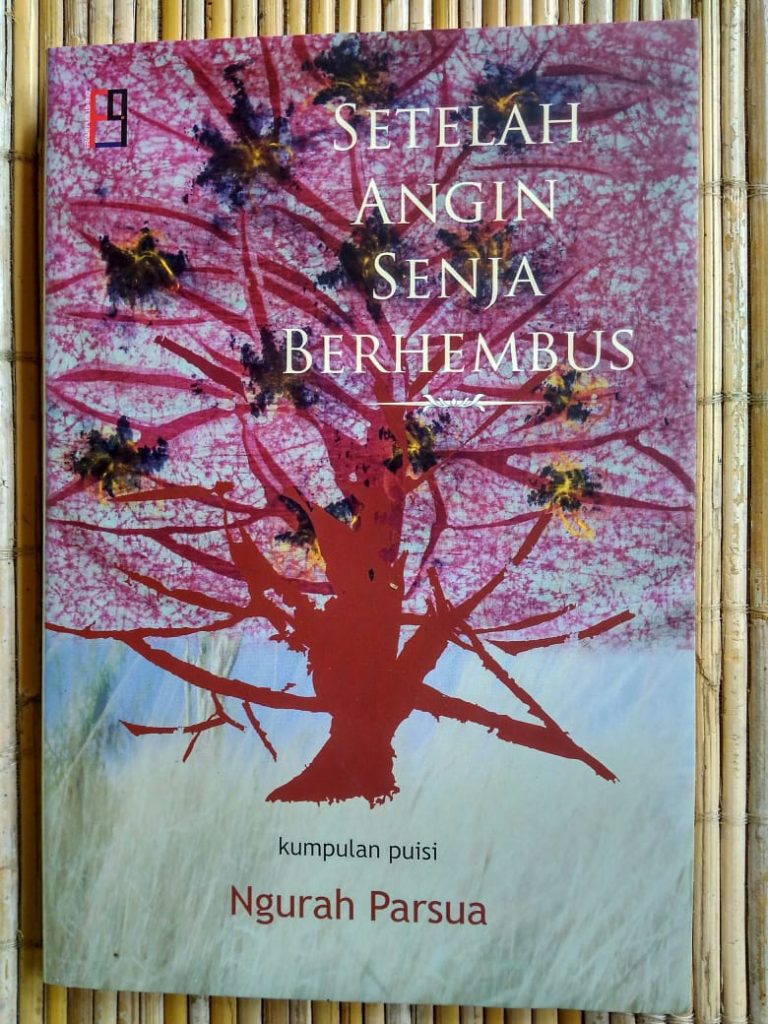
Ngurah Parsua aktif di Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesiba) yang pernah memberi atmosfir sendiri dalam kehidupan seni modern Bali. Ia juga rajin mengikuti sayembara sastra, memenangkannya atau masuk nominasi. Buku-bukunya terbit sejak tahun 70-an, dan berlanjut hingga sekarang.
Buku puisinya tercatat: Matahari (1970), Setelah Angin Senja Berembus (1973), Sajak-Sajak Dukana (1982), Pemburu (1987), Sajak-Sajak Langit (1994), Duka Air Mata Bangsa (1999), Air Mengalir (2008), Manusia Perkasa (2007), 99 Puisiku (2008), Bunga Sunyi (2009), Potret Pohon Air Mata (2012), Nyanyian Cemara Langit (2014) dan Setelah Angin Senja Berhembuas (2015, kemasan baru dengan tambahan 4 kumpulan lainnya).
Buku cerpennya adalah Sekeras Baja (1984), Anak-anak (1987), Rumah Penghabisan (1995), Perempuan di Pelabuhan Sunyi (1995), Senja di Taman Kota (2003), Angin Malam (2008), Pohon Langit (2012) dan Cinta Mawar Shakuntala (2017). Ada pun novelnya: Permulaan Duka (1995), Petapa Bunga (2009) dan Sembilu dalam Taman (2014). Sedangkan buku eseinya adalah Catatan Kebudayaan dari Bali (1983), Hakekat Manusia dan Kehidupan (1999) dan Karya Sastra dan Prosesnya (2012).
Selain itu, karyanya terhimpun dalam antologi bersama seperti Antologi Sepuluh Penyair Indonesia-Malaysia (1983), Antologi Penyair ASEAN (1983), Tonggak (susunan Linus Suryadi Ag, 1987) dan Bahana di Margarana (2005).
Ngurah Parsua menerima Penghargaan Listibiya Provinsi Bali (1974), Italart-BKKNI (1983), Penghargaan Mpu Tantular Balai Bahasa Denpasar (2010), Penghargaan Pemerintah Kota Denpasar (2011), Widya Pataka Perpustakaan Provinsi Bali (2012) dan Anugerah Bali Jani Nugraha (2021).
Karya Mutakhir: Sekilas Tinjauan
Ngurah Parsua terus berkarya ditandai terbitnya buku-buku mutakhirnya. Saya sempat menyunting sejumlah buku Parsua, terutama diterbitkan Framepublishing rentang waktu 2014-2019. Buku-buku tersebut adalah Nyanyian Cemara Langit (kumpulan puisi, 2014), Sembilu dalam Taman (novel, 2014), Setelah Angin Senja Berhembus (puisi, 2015), Cinta Mawar Shakuntala (cerpen, 2017), Kita dan Pendidikan Sastra (kumpulan esai, 2016) serta Rindu dan Cinta Sang Pemuja (puisi, 2019).
Saya menemukan pelbagai hal menarik dari karya mutakhir pengarang berlatar sarjana pertanian dan pernah menjadi kepala sekolah ini. Dalam buku Cinta Mawar Shakuntala, saya melihat Parsua konsisten dengan cerpen-cerpen reflektif. Ia ceritakan pergulatan tokoh-tokohnya dalam nilai kehidupan yang berubah. Meski beresiko terbentur atau kalah, tokohnya pantang menyerah. Tapi jika pun sang tokoh meraih kemenangan atas tatanan nilai yang diperjuangkan, kemenangan itu bukanlah berbentuk materi apalagi kemenangan besar, melainkan kemenangan spritual dalam capaian-capaian kecil. Dan itu merepresentasikan nilai universal kemanusiaan.
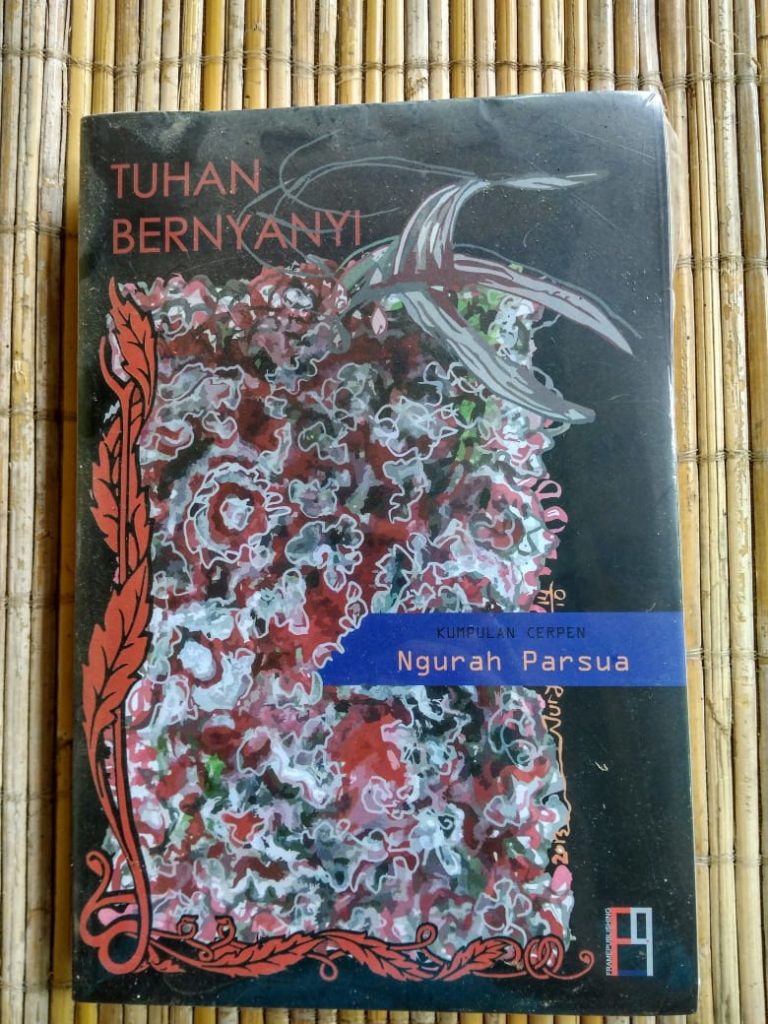
Nilai-nilai hidup disampaikan Parsua lewat narasi keindahan. Kalah dan menang, jaya atau bangkrut, hidup atau mati, merupakan takdir kehidupan. Namun bagaimana kalah dan menang dicapai, kejayaan ditegakkan dan kebangkrutan dihayati, hidup diisi dan kematian dipasrahkan, itulah yang penting benar. Tak heran, narasi Parsua selalu merengkuh alam sebagai latar, flora dan fauna sebagai umpama, gejolak laut dan langit Tanah Air yang menaungi batin tokoh-tokohnya.
Cerpennya tentang seekor burung yang mencari Tuhan dalam cerpen “Tuhan dan Keindahan”, misalnya, sangat reflektif dan filosofis:
Si burung cantik sempat tertawa kecil. ’’Jangan terlalu sentimental,’’ katanya sambil merajuk. ‘’Meskipun aku dilahirkan sebagai burung betina, aku tak pernah sedih dan menyesali nasib atasnya,’’ katanya sambil kembali merajuk. ‘’Lihatlah, penderitaan hidup si miskin, orang bernasib malang, seorang pengemis, menderita di umur tua, selalu dirundung sakit. Orang malang selalu ditimpa sial. Atau bentuk penderitaan jenis lainnya, memang bertebaran di dunia. Tidak sepertimu, penderitaan tak membuatnya menyesal. Apalagi memprotes Tuhan! Semua kelahiran di dunia, ada sebab dan akibatnya.’’
Keindahan bahasa cerpen Parsua terasa wajar, tak ada dramatisasi dalam apa yang sempat dikenal dalam isu sastra mutakhir sebagai “tamasya bahasa”. Meliuk-liuk indah, tapi abai akan isi. Pada Parsua, keindahan bukan saja lantaran ia juga seorang penyair, namun karena cerpen sarat renungan lazim memercikkan keindahan kalimat dan bahasa dengan sendirinya. Tak perlu lagi dibuat-buat. Parsua bahkan fasih mengartikulasikan materi kehidupan purbani, roh-roh halus, dunia tak kasat mata, pohon hayat kabajikan dan sejenisnya secara wajar dan apa adanya (bukan seadanya).

Itulah sebabnya cerpennya kadang mengambil judul-judul konseptual seperti “Pohon Sunyi” yang ia “rumuskan” sebagai: “sebuah bayang misterius. Letaknya di wilayah bayang khayal pikiran manusia. Sulit menemukan denahnya dengan pasti. Kadang mampu tertangkap utuh. Bayangnya seperti berada di pohon sunyi. Ruang misteri tempat berdialog dengan sunyi. Tempat manusia mencari jati diri.”
Persfektif Novel
Novel Parsua, Sembilu dalam Taman (2014), merupakan trilogi novela: “Hidup di Dunia”, “Sembilu dalam Taman”, “Abu dan Debu”. Ketiganya disatukan dengan judul utama yang diambil dari satu bagian yang pernah terbit secara solo tahun 1986. Novel ini berkisah tentang perjalanan hidup I Gusti Made Lodra, pemuda bangsawan Bali, dalam memburu cinta sejati. Cintanya dengan Artini, yang ia amsal sebagai gadis masa depannya, kandas di tangan orang tuanya sendiri. Menariknya, kegagalan itu bukan lantaran campur tangan keluarga besar Lodra yang notabene dari lingkungan Puri Mengwi, namun penolakan dari ibu Artini yang merupakan keluarga biasa.
Ini tentu persfektif unik. Lazimnya, cerita dengan latar bangsawan, dalam soal pilihan hidup si anak, campur tangan pihak si darah birulah yang selalu dominan. Tapi ini tidak. Keluarga Artini, dari kalangan rakyat biasa, justru tegas menolak. Penolakan keras itu pun datang dari sang ibu, sosok perempuan yang dalam banyak kisah suaranya kerap tenggelam dalam dunia patriarkal. Dan penolakan itu pun bukan karena kecemasan psikologis tentang ketidaksetaraan, melainkan karena ketidaksenangan sang ibu melihat sikap Lodra yang seenaknya dan tak bertanggung jawab.
Melalui cara ini, pengarang membangun persfektif baru dalam relasi sosial masyarakat Bali. Memang, ia tidak berpretensi membongkar hal-ihwal yang lebih besar, misalnya membenturkan persoalan adat dan kebebasan. Membongkar hegemoni kasta dan semacamnya. Namun cukup mengulik soal-soal kecil, lewat struktur cerita yang boleh dikata konvensional, Parsua memberi arti berbeda.
Percintaan Lodra dengan perempuan kedua, Sylvei, kemudian memunculkan hal-hal simpatik dan situasi demokratis. Sylvei merupakan perempuan Prancis. Meskipun upacara perkawinan mereka dalam tata-cara puri, itu bukan simbol keterkungkungan adat. Itu pilihan Sylvei sendiri. Maka pasangan pengantin itu bebas berdiskusi, berdebat bahkan bertengkar, termasuk soal adat dan agama. Latar puri bukan sesuatu yang masif, namun terbuka untuk dikritik termasuk oleh “orang asing”.
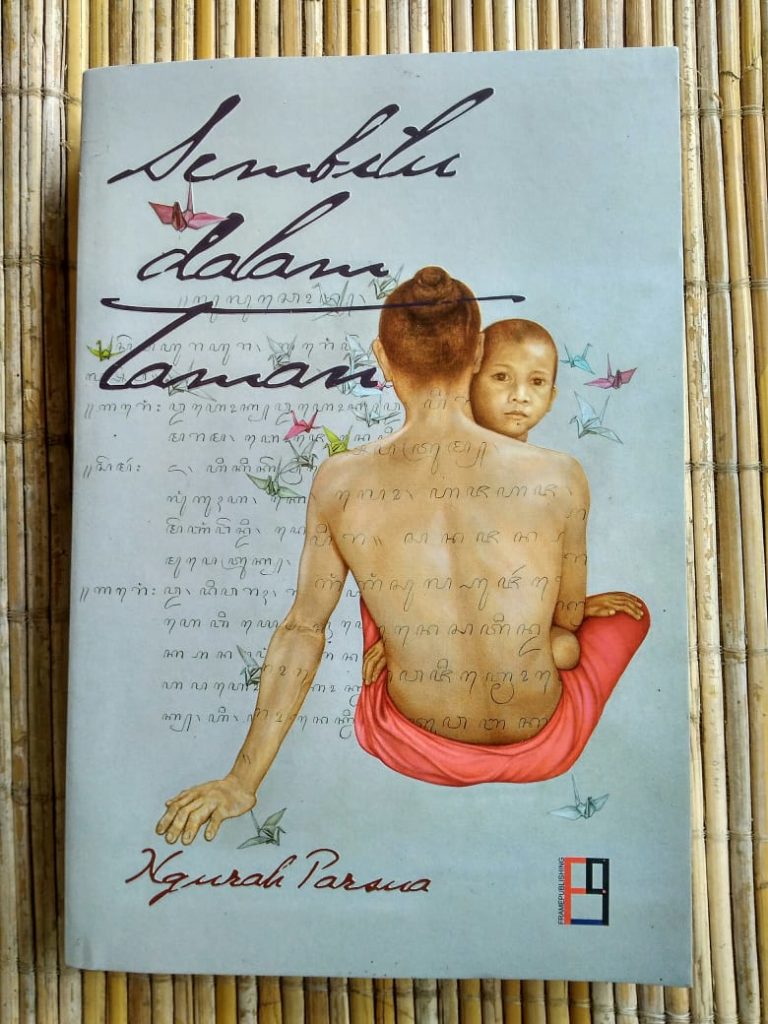
Kerap kali dalam perdebatan-perdebatan itu Lodra tersudut oleh pertanyaan atau pernyataan Sylvei yang tajam, lalu ada jawaban yang ditemukan bersama. Di sini terlihat adanya demokratisasi puri dan demokratisasi sikap orang puri. Ini bertolak-belakang dengan kisah-kisah yang lazim tentang kekokohan tembok para bangsawan Bali sebagaimana ditemukan dalam karya-karya Oka Rusmini, misalnya.
Upaya Parsua mencairkan relasi sosial orang Bali lewat interaksi yang padan dan hubungan wajar, membuat novel ini seolah terbebas dari pretensi “ideologis”. Namun, jika didalami, selain memuat persfektif “sungsang” tentang hubungan puri dengan masyarakat kebanyakan, novel ini bernilai ideologis dalam arti sebenarnya. Berlatar Bali tahun 70-an hingga menguatnya sentralisme Orde Baru, Parsua membentang panorama antropologis dan paradoks turistik yang meluas pada ranah sosial-politik lokal (Bali).
Kejernihan Puisi
Sementara itu, sebagai penyair yang malang-melintang dalam pengalaman penciptaan, bentuk bagi Parsua bukan hal esensial yang perlu dikejar atau diperjuangkan. Inilah yang teramati dari antologi puisi Rindu dan Cinta Sang Pemuja. Dalam kesederhaan bentuk, makin terasa keinginan untuk menyuguhkan hal-hal maknawi secara suntuk. Analogi paling sering dirujuk sehubungan dengan ini tidak lain filosofi Candi Borobudur: semakin ke puncak semakin tampak kepolosan—arupadhatu—melewati tingkatan-tingkatan yang ramai motif, relief, ukiran, tatahan—kamadathu, rupadathu.
Dalam khazanah puisi tradisional Nusantara, kesederhaan malahan bagian upaya untuk menyampaikan makna supaya bisa ditilik oleh masyarakat luas. “Gurindam 12” karya Raja Ali Haji misalnya, merujuk situasi sekitar bagi antaran isi yang bernilai moral dan spritual. “Barangsiapa tidak sembahyang/ ibarat rumah tidak bertiang,” itu salah satu contoh, dekat dan mengena. Syair Ronggowarsito dan Ida Pedanda Made Sidemen, juga demikian. Renungan dan terawang batin mereka sampaikan dengan jernih tapi dalam.

Dalam puisi modern Indonesia, kita menemukan kesederhanaan semacam itu misalnya pada puisi Rendra, Subagio Sastrowardoyo, D. Zawawi Imron maupun Sitor Situmorang. Ngurah Parsua pada hakikatnya adalah penyair yang ingin mencapai tingkatan tersebut. Puisinya terbentuk dari ungkapan, ujaran atau renungan yang tenang, tidak menggebu, namun setiap bagian menyimpan renungan. Coba simak puisi berikut:
Tulus; lapis paling hening
Dasar terdalam
Pengenang terpercaya
Bukan sekedar menangkap
Bayang-bayang tuhan
Tempat bertemunya rindu dan mengerti
Duka dan gembira; pimpin dan jagalah
Raksasa mana mengerti kalbu?
Telah dikunci kasih sayang itu
Dipagari bunga melati
Kalbu; ruang kemanusiaan abadi.
(“Kalbu”, hal. 22)
Gagasan Esai
Sementara itu, seolah padan dengan puisinya yang sederhana, esai-esai Parsua dalam buku Kita dan Pendidikan Sastra (2016), juga ditulis bersahaja. Cara menyampaikan gagasannya tidak ruwet, mudah dicerna. Berisi persoalan di seputar wacana sastra dan isu kebudayaan secara umum, jalan ke luar yang ditawarkan terasa dekat dengan pembaca.
Sebagai sastrawan, Parsua menyajikan sejumlah esai yang berhubungan langsung dengan proses kreatif penciptaan, baik proses kreatifnya sendiri, maupun proses kreatif sastrawan lain. Melalui perspektif “proses kreatif” ini, pembaca mengetahui lebih dekat “ruang dalam” seorang sastrawan. Bahwa sastrawan tak hanya bergulat dengan konvensi jagad estetik, juga mempertaruhkan persoalan etik: tanggung jawab moral, nilai rohani/spritualitas, sampai pada soal-soal sosial.

Sebaliknya, sebagai sastrawan yang aktif di pusaran isu-isu kebudayaan, Ngurah Parsua juga mengangkat “persoalan lapangan” ke dalam esainya. Salah satu yang menarik minatnya adalah dunia pengajaran atau pendidikan sastra yang masih dianggap “jauh panggang dari api”. Banyak pihak melihat penyebab lemahnya apresiasi sastra di sekolah karena faktor guru yang kurang menguasai bahan-ajar. Sebagian menganggap kurang akomodatifnya kurikulum atas pelajaran sastra dibanding mata pelajaran eksakta.
Parsua melihatnya secara komprehensif. Mulai dari pengertian dan posisi sastra di tengah masyarakat; apa hubungan sastra dengan “perut kenyang” dan bagaimana posisi sastra dalam masyarakat Bali? Lantas, dari pemaknaan ini lahirlah tinjauan-tinjauan kritis yang kadang di luar dugaan kita, termasuk soal pendidikan sastra di sekolah yang menurutnya berkorelasi dengan dunia pendidikan kita secara keseluruhan: melek aksara, tapi tuna acuan nilai.
Demikianlah kiranya perkenalan kita dengan sosok Ngurah Parsua dan sekelumit karya-karyanya, sosok yang berulang tahun bertepatan dengan Hari Ibu, 22 Desember. Selamat ulang tahun, Pak Parsua, sehat dan bahagia! [T]










![Mengenang Joko Pinurbo [2-Tamat]: Sore Hari Bersama Sang Penyair](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin2-1-360x180.jpg)
![Mengenang Joko Pinurbo [1]: Menemukan Sajak di Sebuah Rumah, di Ujung Sebuah Gang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/05/wicaksono-adi.-foto-jokpin-360x180.jpeg)

















