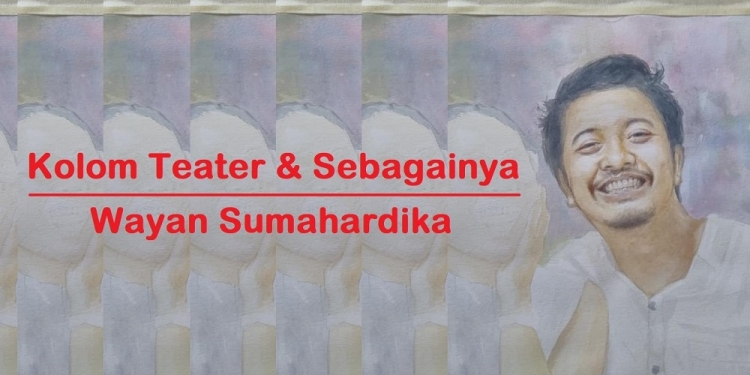Katakanlah buah hati orang tua adalah anak-anaknya, maka naskah teater adalah buah karya penulis teater itu sendiri. Melihat orang tua yang menjaga dan merawat anaknya penuh kasih, sampai memantau buah hatinya saat berinteraksi dengan lingkungan di luar rumah, sebenarnya mirip dengan perasaan seorang penulis naskah teater merelakan buah karyanya untuk dimainkan khalayak publik. Jika buah hati adalah anak biologis, buah karya adalah anak rohani. Keduanya punya persamaan yang utama, yakni sama-sama berperan sebagai anak.
Penulis naskah dalam hal ini mungkin salah satu yang paling beruntung karena diberi kesempatan ganda menjadi orang tua, yakni orang tua biologis sekaligus orang tua rohani. Layaknya orang tua yang punya penyikapan dan perlakuan beragam terhadap anak biologisnya, beragam pula penyikapan dan perlakuan penulis naskah kepada anak rohaninya. Ada penulis naskah yang pasrah, diapakan saja anaknya, ya boleh-boleh saja. Adapula penulis yang begitu protektif terhadap naskah, semisal adegan dalam naskah tak boleh dipotong, setiap kata adalah darah, hati-hati pada makna dan pemenggalan, perhatikan struktur dramatik teks dan berjibun tata tertib lain yang mesti ditaati. Saking protektif dan menggebunya, kadang omongan penulis jenis ini justru jauh lebih banyak dibanding dengan naskahnya sendiri yang ternyata cuma seiprit.
Perihal kuantitas, ada penulis yang terus melahirkan anak, brojol hampir setiap hari. Di sisi lain, ada juga yang seperti program KB, cukup punya satu sampai dua anak seumur hidup. Bahkan tak sedikit yang mandul, uniknya tetap menganggap diri sebagai orang tua. Ya.. Minimal orang tua bagi anak segala bangsalah.. Yang paling miris mungkin adalah orang tua yang tak jelas siapa dan dimana anaknya, tapi suka sekali menggurui para calon orang tua tentang cara-cara membuat anak yang baik dan benar. Dari sekian ragam orang tua ini, termasuk orang tua manakah saya kemudian?
Pertanyaan ini kontan saja muncul ketika menyaksikan kawan-kawan Teater Kampus Seribu Jendela Undiksha memainkan naskah saya dalam acara Parade Teater Canasta November lalu. “Dongeng-dongeng yang Tersesat di Sekitar kita”, merupakan anak rohani yang pertama kali saya tawarkan untuk dipentaskan oleh orang lain. Waktu itu, kawan-kawan Teater Kampus Seribu Jendela, sempat menanyakan naskah apa yang sekiranya cocok mencerminkan ‘Mitos’ sebagai tema dalam parade. Kontan saja saya jawab, ‘bagaimana kalau pakai naskahku saja?’
Naskah yang saya tulis pada tahun 2016 ini memang sudah sejak lama teronggok dalam laptop. Tak pernah sekalipun ada niat mementaskannya. Saya merasa naskah ini belum jadi seutuhnya, ingin sekali memperbaiki, tapi apa yang mesti diubah? Ada semacam kemumetan, harus diapakan lagi agar naskah bisa rampung. Paling tidak, rampung menurut penilaian saya sendiri. Berulang kali dibaca, berulang kali hasilnya sama. Meminta orang lain buat membaca sudah tak mungkin. Lagipula, siapa yang mau membaca naskah teater yang tebalnya minta ampun dan membosankan bukan main?
Namun sebagai orang tua, betapa berdosanya saya jika terus membiarkan anak terkungkung dalam laptop. Sebab fitrah naskah teater sejatinya memang untuk dipanggungkan. Persoalannya, saya pribadi masih belum percaya diri untuk mementaskannya sendiri. Mau menawari naskah pada kawan untuk dimainkan, takut dikira pamer. Kalau menunggu diminta orang, sudah jelas pasti tak ada. Apa untungnya mementaskan naskah saya yang notabene masih amatiran ini? Lebih baik mementaskan naskah sendiri. Jelek bagusnya, toh juga karya sendiri. Atau memainkan naskah dari dramawan yang sudah mumpuni. Itu jauh lebih menjanjikan. Paling tidak naskah-naskah karya dramawan ini sudah teruji secara struktur, gagasan, dan bentuk cerita. Sudah matang sebagai naskah, sudah layak untuk dipentaskan.
Maka setelah menimbang dan berpikir untung rugi, jadilah saya memberanikan diri menawari kawan-kawan untuk mementaskan naskah saya. Adalah Dian Ayu Lestari sebagai sutradara, seorang mahasiswi Prodi Manajemen Undiksha semester III. Pada deretan aktor ada Desia, Lala, Yuni Febri, Listya, Irhas, Kurnia, Yoga, Oga, Haruto, dan Indra. Sementara artistik dan musik ditata oleh Wahyu, Dede, dan Jagad. Dalam proses yang hampir dua bulan itu, mereka sempat menanyakan bagaimana harus membedah naskah ini? Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada naskah?
Saya jawab, “terserah kalian bagaimana membedah dan mementaskannya. Naskah boleh diobrak-abrik, dipreteli, diapakan saja, bebas! Yang penting pentasnya bagus!”
Mereka cuma membalas, “Hehehehe.. Kami usahakan, Kak.”
Tak sabar rasanya ingin melihat seperti apa naskah saya diwujudkan. Perspektif seperti apa yang ditawarkan? Adakah yang akan berubah? Saya jadi berdebar-debar dibuatnya. Setelahnya, setiap ada waktu saya sempatkan diri untuk bertanya, “bagaimana perkembangan pentasnya? Uda bagus pentasnya?” Dan selama itu pula hanya dijawab dengan “hehehehe…”
“Pah! Betapa tak meyakinkannya mereka”, pikir saya.
Sebagai penulis naskah, tak bisa dipungkiri, kita punya harapan besar terhadap pentas. Ada rasa geregetan apabila pentas nantinya tak sesuai dengan imajinasi dan keinginan estetik kita sebagai penulis. Di puncak penasaran dan geretan saya pada naskah inilah, siang hari sebelum pentas, cepat-cepat saya ke Canasta agar dapat melihat mereka gladi. Di tengah semangat yang menggebu untuk menyaksikan mereka, sialnya latihan justru cuma bolak-balik pada satu adegan saja. Itupun hanya adegan bernyanyi yang diulang-ulang karena sang vokalis sumbang menyanyikannya. Waduh, saya jadi berpikir, jangan-jangan mereka salah menginterpretasi naskah saya?
Ingin sekali rasanya meminta mereka mengulang adegan dari awal sampai akhir agar saya sendiri dapat menyaksikan hasilnya. Ingin sekali rasanya menambahkan properti pentas di atas panggung yang bagi saya belum cukup maksimal dieksplorasi, ingin sekali rasanya mengoreksi akting para pemainnya, ingin sekali rasanya menyampaikan keinginan estetik yang saya harapkan dalam naskah, menceritakan latar belakang di balik naskah itu dibuat, dan realisasinya di atas panggung. Keinginan-keinginan ini kemudian lagi-lagi dibenturkan pada pertanyaan, “kalau mesti menuruti keinginanmu, kenapa bukan kamu saja yang menyutradarai pentas? Kenapa bukan kamu saja yang jadi aktor? Kenapa bukan kamu saja yang mengisi semua lini dalam pertunjukan?”
Sebab setiap orang punya caranya sendiri mengeksekusi dan mengeksplorasi suatu naskah. Saat naskah dilepaskan ke ruang publik, saat itulah penulis dikatakan mati. Perannya sebagai penulis seketika berganti menjadi pembaca. Ia tak ada bedanya dengan pembaca lain yang menikmati karyanya. Pun demikian dengan interpretasi penulis sendiri terhadap karyanya, sama saja kedudukannya dengan interpretasi para pembaca lainnya. Ia sudah tak punya kontrol yang cukup buat memantau ke mana arah karyanya terbawa, apalagi mengikat interpretasi orang-orang dalam membaca karyanya. Kualitasnya persis dengan keikhlasan dan kepercayaan orang tua melepas anaknya ke jalanan. Bertemu dengan berbagai macam orang yang mempunyai latar belakang, kelas, sosial, kultur bahkan sejarah berpikir yang berbeda.
Demikian pula pertemuan naskah saya dengan kawan-kawan Teater Kampus Seribu Jendela. Saya tak lagi punya hak dan kewajiban mengatur naskah. Saya adalah penonton, yang fungsi, kedudukan, dan nilainya sama seperti penonton yang dudk di sebelah saya. Di halaman Canasta, pada permainan panggung khusuk dan sederhana, kawan-kawan yang semula saya sangsingkan ternyata cukup berhasil memikat penonton. Beberapa penonton memuji bagaimana mereka memanggungkan naskah. Berbekal evaluasi terhadap naskah di sana-sini, saya jadi bersemangat. Keinginan menulis dan menyempurnakan naskah kian menggebu-gebu. Di akhir diskusi, salah satu audiens bertanya, siapa yang membuat naskah ini? Kawan-kawanpun menjawab bahwa itu adalah naskah karya saya, sayangnya di poster pentas mereka lupa mencantumkan. Perasaan ini saudara-saudara, tahukah bagaimana rasanya? Rasanya sama seperti seorang ayah yang anaknya berhasil jadi juara kelas. Lalu orang-orang menoleh kepada saya. “Ooo.. jadi itu anakmu ya, Sum?” [T]
Denpasar, 2020