MANUSIA di era digital terhubung secara global melalui berbagai platform media. Media digital tidak hanya mampu mempertemukan para pengguna dari ruang dan waktu berbeda untuk berbagi informasi, namun juga telah membentuk kulturnya sendiri.
Demikian diungkapkan Prof.Dr.Mite Setiansah, SIP, M.Si dalam orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar Bidang Media dan Komunikasi, Universitas Jenderal Soedirman, 4 Februari 2025. Selanjutnya dijelaskan, berbagai platform percakapan di media sosial seperti X dan Thread selalu riuh dengan perbincangan tentang berbagai hal, mulai dari yang remeh-temeh hingga diskusi-diskusi politik berat.
Netizen yang selalu ingin tahu dan takut ketinggalan informasi kemudian melahirkan generasi FOMO (Fear of Missing Out), yang selalu tidak tenang kalau tidak membuka media sosialnya. Bahkan di saat sedang bersama orang lain (phubbing) atau dalam sebuah acara penting.
Komunikasi yang termediasi di era digital telah membentuk karakter dan pola-pola interaksi yang khas, yang membedakan dari komunikasi tatap muka yang dikenal sebelumnya. Anonimitas, invisibilitas, introjeksi solipsistic, asinkronitas merupakan karakter-karakter digital user yang memberikan kebebasan untuk menjadi siapa saja.
Ketiadaan tanda-tanda nonverbal dari lawan bicara kemudian sering diisi oleh pihak lain melalui interpretasi dan asumsi pribadi yang kemudian menjadi awal dari lahirnya post truth. Fenomena sosial di mana fakta objektif sering diabaikan dan digantikan oleh keyakinan emosional atau preferensi pribadi.
Literasi Digital
Hadirnya beragam bentuk ilusi komunikasi era digital, menurut Prof.Mite Setainsah yang saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fisip ini telah berimbas pada maraknya beragam bentuk disinformasi maupun misinformasi di masyarakat. Kondisi ini menuntut penguasaan literasi digital oleh kelompok masyarakat yang semakin menguat.
Terdapat banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang literasi digital. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kata kunci yang hampir selalu muncul dalam setiap definisi, yaitu access, manage, understand, integrate, communicate, evaluate, dan create (Law et al., 2018). Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.1) sebagai kerangka kerja yang diusulkan oleh Uni Eropa memberikan 5 area kompetensi literasi digital, yaitu: (a) Literasi informasi dan data, (b) Komunikasi dan kolaborasi, (c) Pembuatan konten digital, (d) Keamanan, dan (e) Pemecahan masalah (Tinmaz et al., 2022).
Hasil dari analisis literatur sistematis terhadap 43 artikel tentang literasi digital menyimpulkan setidaknya ada 12 frase yang memperlihatkan kompetensi literasi digital, yaitu: Problem solving, Safety, Information processing, Content creation, Communication, Digital rights, Digital emotional intelligence, Digital teamwork, Big data utilization, Artificial Intelligence utilization, Virtual leadership, dan Self-disruption (Tinmaz et all., 2022).
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia telah meluncurkan program Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN) yang ditujukan kepada berbagai kelompok masyarakat. Melalui GLDN telah dikampanyekan empat pilar literasi digital nasional, yaitu cakap digital (digital skills), aman digital (digital security), etika digital (digital ethic), dan digital culture atau budaya digital (Kurnia et al., 2021; Setiansah et al., 2024).
Upaya peningkatan literasi digital masyarakat juga dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, di antaranya adalah Japelidi (Jaringan Pegiat Literasi Digital), dan Tular Nalar – MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). Japelidi merumuskan 10 kompetensi literasi digital yang mencakup akses, seleksi, paham, analisis, verifikasi, evaluasi, distribusi, dan produksi (Amihardja et al., 2022).
Pegiat Japelidi bekerjasama dengan Tular Nalar-MAFINDO juga aktif menyelenggarakan berbagai sosialisasi dan pelatihan literasi digital untuk para pemilih pemula yang diberi nama program Sekolah Kebangsaan (SK) dan untuk para lansia melalui program Akademi Digital Lansia (Setiansah et al., 2023). Muara dari semua kegiatan tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya ilusi komunikasi di ruang digital.
MITE Helical Model
Semua permasalahan yang melekat pada dinamika interaksi dan komunikasi manusia yang dipaparkan Prof. Mite Setiansah adalah gambaran dari model helikal tentang proses komunikasi yang tidak pernah sungguh-sungguh menemukan akhirnya.
Pemahaman akan hal itu hendaknya bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua dan mempertanyakan ulang, apakah selama ini kita sungguh-sungguh telah melakukan komunikasi yang bermakna? Atau itu hanya ilusi belaka?.
Secara keseluruhan, penerapan Model Helikal dalam komunikasi dapat membantu individu dan kelompok untuk memahami kompleksitas komunikasi dan meningkatkan efektivitas interaksi mereka; terutama dalam konteks yang beragam dan dinamis (Larson, 2020). Oleh karena itu, Mite Setiansah menawarkan MITE Helical Model of Communication yang merupakan hasil adopsi dan adaptasi terhadap Model Komunikasi Helikal dari Frank Dance.
MITE Helical Model of Communication memberikan porsi perhatian yang besar pada aspek Message, Interaction, Transaction, dan Evaluation.
Message adalah bagian penting yang menjadi alasan terjadinya aktivitas komunikasi. Pengecekan terhadap kebenaran pesan (cek fakta) menjadi sebuah proses penting dalam tahapan komunikasi.
Interaction memperlihatkan bahwa komunikasi efektif harus terjadi dua arah, diwarnai dengan saling memberikan feedback secara timbal balik. Transaction mempersyaratkan adanya adaptasi dan negosiasi dari pihak-pihak terlibat agar diperoleh kesepahaman.
Evaluation menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan betul-betul komunikasi yang bermakna, sehingga evaluasi dan perbaikan perlu selalu dilakukan untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk ilusi komunikasi.
Lebih lanjut Guru Besar Komunikasi yang juga menjadi Asesor BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) ini menuturkan, secara praktis penerapan MITE Helical Model of Communication maupun peningkatan literasi digital memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan melibatkan peran serta pemerintah secara struktural.
Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang. Secara kultural, upaya mengurangi ilusi komunikasi dapat dilakukan dengan mendorong keterlibatan berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan sharing knowledge tentang literasi digital dan komunikasi inklusif dan empatik (Novsak Brce & Kogovsek, 2020). Komunikasi yang dijalankan dengan menghargai dan menghormati berbagai perbedaan yang dapat mengakibatkan terjadinya ilusi komunikasi dan menghambat terciptanya komunikasi efektif.
Sebagaimana dinyatakan dalam model komunikasi helikal, bahwa fenomena komunikasi yang terjadi hari ini tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu dan juga harapan yang dituju di masa depan. Orasi ilmiah dalam pengukuhan Guru Besar Mite Setiansah ini juga tidak lepas dari perjalanan yang telah dilalui sebelumnya.
Selamat untuk Prof.Dr.Mite Setiansah, SIP, M.Si. [T]
Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU








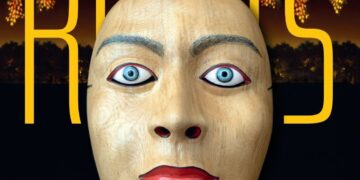













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










