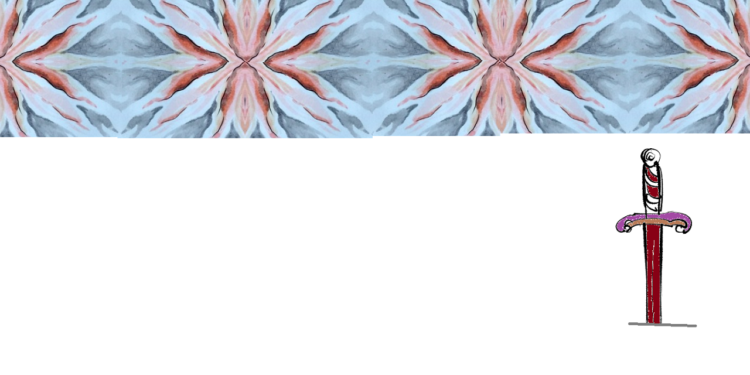MATA pedang itu menyala-nyala, berpendar, berkilatan di bola mataku. Bilahnya lurus, sepanjang jangkauan pikiranku, juga kecil, dan halus, serahasia persembunyianku.
Jujur saja, aku sempat merasa jumawa, tetapi setiap rekah rasa jumawa yang tersedak keluar dari tindak, kata, pikir dan rasaku, ujungnya pasti kecewa dan derita.
Jadi, enam indria serta pikiran sebagai raja indria yang kuat sangat kuat dan nyaris tak terbatas itu seolah-olah mencipta bahagia berujung derita. Anehnya setiap derita yang kutrima, ujungnya juga bahagia. Jadi aku selalu dalam suka dan duka, suka duka itu adalah aku.
Namaku Budi, sunyi sepi, sendiri, dan tak berarti. Ya awalnya kurasa, kupikir dan kunilai Budi hanya sebuah nama sederhana, yang ditempelkan begitu saja, entah ayah bunda, kakek nenek, eyang-eyang dan orang-orang yang bersentuhan dengan masa kanakku.
Bagiku saat itu, nama Budi tidaklah cocok dan pas dengan diriku, dengan segala kemampuanku. Berkali-kali aku ganti nama, Parama Suksma, Suksma Raga, Cakra Buana, Surya Buana, Surya Braga, Surya Praja, Surya Suksma juga Jagatnata, Nata Buana dan beberapa nama yang menggambarkan kehebatanku sebagai laki-laki. Ahhh ya, laki-laki, hanya itu penandaku sebagai manusia, selebihnya aku juga bisa jadi binatang, atau tumbuhan, semua mahluk yang berjiwa.
Aku juga suka nama Ning, Hening, Ayu, Hati, Sunyi, Nurani dan lain-lain, refleksi dari rasa terdalamku,, tapi tentu tak cocok dengan kelelakianku. Jadi ya Budi, memang budilah yang paling cocok dan pas, untuk kemisteriusan sunyiku yang lelaki.
Aku bangga dengan kelelakianku, karena itulah yang sejati-jatinya yang aku punya, selain hidup itu sendiri. Hidup, rasanya itupun aku tak punya karena telah kurasakan dua kali kematian. Jadi apa bedanya hidup ataupun mati berkali-kali.
Orang tua, keluarga, saudara, teman aku tak punya, hanya kenalan yang datang dan pergi silih berganti. Banyak yang mencariku, yang ingin menjadi pengusaha maupun penguasa, dari bupati, gubernur sampai presiden. Mereka kadang menjadi murid, anak-anak, atau bahkan peliharaanku.
Hampir semua orang terkenal dan hebat itu sempat berurusan denganku. Kubantu sampaikan doa-doanya pada Tuhanku. Anehnya semua yang kuminta pada Tuhan dikabulkan, tapi aku tak boleh muncul ke permukaan apalagi meminta imbalan.
Ada saja yang kesurupan, menerima wahyu, mendapat pesan agar mencariku, melaluiku agar pesannya terkabulkan. Hebat kan?
Pedang, mata pedang itu berkilat-kilat. Memenuhi keinginanku dengan cepat.
Ia melesat, terlihat atau, tak terlihat
“Pedang apakah itu? Pedang siapakah itu ” Selalu kutanya dalam zikirku. Tak kutemukan jawaban. Makin kutanya, pedang itu makin nyata. Mengantarkan asa, kadang masuk ke dalam raga.
“Mungkin pedang itu milikku, apakah aku ksatria akhir jaman, penunggang kuda putih itu? ” tanya dan harapan di dadaku membuncah. Ada rasa bangga sekaligus luka, ada sedikit bahagia berhimpitan dengan derita, yang menimpa hidupku, berlapis-lapis dalam fana.
Aku tahu masa laluku adalah raja besar, penguasa dunia, bahkan semesta. Kecerdasanku menciptakan tata cara berkuasa. Diplomasi, strategi dan birokrasi. Kecerdasan paripurna adalah api dingin yang menyublin.
“Bertahta, berkuasa atas manusia bagiku biasa. Kini tapaku untuk surga. Bukan menguasai, tapi mencintai. Tekadku kini hanya untuk darma, tidak ingin apa-apa, tidak juga mau jadi siapa-siapa”
Namaku Budi, sebuah nama lelaki, nama bagi rasa hati yang murni, suci dan sejati.
Dalam kesunyian ini yang kuingat hanya takdirku sebagai lelaki, kesejatian api. Yang kulihat hanya mata pedang yang berkilat-kilat. Mengelana, meniadakan rasa dan asa, menjalankan darma, memendar cahaya.
Pada kematian ini, aku tak ingin sembunyi. Tak perlu kau tangisi, kau ratapi. Takdir telah mengutusku kembali, menjadi saudara sehati bagi ksatria sejati yang dinanti.
Mata pedang menjadi mataku, kemuarnian api kelelakianku yang suci dan sejati.
Mata pedang itu berkilat-kilat. Asaku menggeliat, menyerang, menerjang. Berperang.