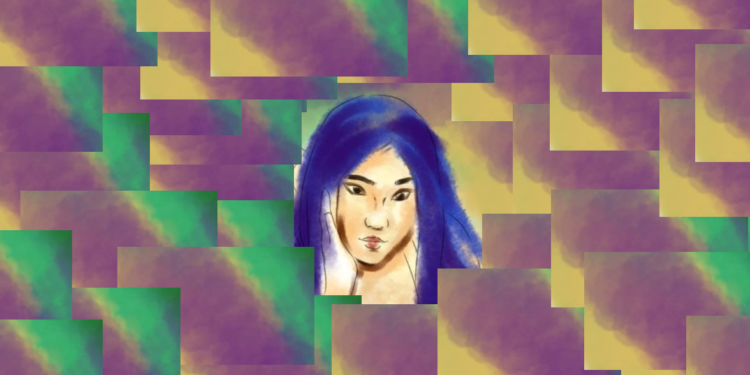KETIKA MARIA berkata padaku bahwa hubungan kami hanyalah sebatas teman, aku tidak berpikir tentang ilusi. Dia berkata begitu dengan tiba-tiba, amat lancar, saat kami makan malam dan seharusnya merayakan ulang tahun kebersamaan kami yang pertama sejak awal kenal.
Aku baru saja berdiri, mengangkat gelas, dan menyatakan hendak bersulang, saat dia memotong, “Turunkan gelas dan tutup mulutmu—aku punya hal penting yang mau kutakan kepadamu.”
Suaranya sekonyong-konyong jadi terdengar dingin sehingga aku merasa kupingku membeku. Aku duduk, menaruh gelas, dan menatap Maria. Tak bisa kuterka apa yang bakal dikatakannya. Seulas senyum masih saja bermain di bibirku. Maria menggeser letak botol anggur, bubuk garam, asbak, vas bunga—pokoknya segala yang terletak di antara kami—lalu berkata, “Kurasa sebaiknya kamu berhenti cengengesan.”
Suaranya begitu dingin sehingga aku tahu aku tak punya pilihan lain. Dengan jemariku kuusap bibirku yang membeku dan terus menatapnya. “Ini tak akan lama,” ucapnya lalu melanjutkan berbicara selama lebih dari dua puluh menit.
Dia mengatakan hal-hal yang biasa diucapkan orang dalam situasi semacam itu: bahwa kami pernah bahagia bersama, sungguh luar biasa kami pernah punya kesempatan untuk lebih saling mengenal, ada saat-saat yang akan dia kenang selamanya, betapa memalukan kami sampai harus meyakini itu hanya ilusi, tapi hidup ini punya aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi.
“Pendeknya,” dia bilang, “Hubungan kita adalah teman dan kini aku harus pergi.” Dia kembali memindahkan asbak sehingga berada di antara kami, mematikan rokoknya di asbak, dan beranjak pergi.
Pelayan menghampiri meja setelahnya dan bertanya kepadaku apakah aku mau memesan sesuatu untuk hidangan penutup. “Kenapa tidak,” ujarku dan memesan kopi. Pelayan itu mengangguk, mengosongkan asbak lalu menaruhnya di dekatku. Tak ada orang lain sama sekali di seberang meja. Saat itulah, tepatnya, gagasan tentang ilusi melintas dibenakku.
Itu semua bermula kala aku berpikir dalam lamunanku bahwa dia menyukaiku. Sebenarnya, lamunan itu dimulai oleh tanda-tanda. Tandanya cukup jelas dan menyakiniku bahwa Maria suka padaku. Aku juga tidak tahu, apakah dia benar-benar mencintaiku atau tidak. Sebab, cinta dan suka adalah dua bahasa yang berbeda. Tapi aku yakin, seyakin pemuda di desaku, saat orang suka terhadap pasangan, mula-mula mereka akan melakukan seperti apa yang pasangan lakukan: pakaiannya sama, kesukaannya sama, dan hampir dunia mereka sama.
Demikianlah ilusiku bagaimana aku bisa tertarik pada Maria dan terus memantau hubungan kami berdua. Setiap kata, kalimat, bahasa, rasa, titik, koma, gambar, video, audio—kusimpan dengan rapi ke galeriku dan kusimpan di dalam kotak penyimpanan gawai.
Aku membingkai dan menata semua itu layaknya perpustakaan, atau bahkan seperti labirin. Ya, meski tak punya tempat yang dapat mengawetkan itu semua, setidaknya labirinku bisa menampung kisahku—atau kisah kami—dalam berbagai peristiwa. Di sebuah gawai, aku simpan kisah itu ke tempat yang orang lain, jika melihatnya bakal bersusah payah mencarinya. Kukunci dengan gembok besar karena orang lain tak boleh mengetahuinya. Dalam berbagai fail, catatan dan rekam data tak lupa kurinci dengan amat tentang semua itu: selain deskripsi tentang percapakan kami, kucatat juga di mana dan bagaimana hingga percakapan itu menjadi bagian museum kami, serta di mana tepatnya letak kalimat-kalimat tersebut di hpku.
Hal terakhir itu sungguh amat penting karena baru pertama kalinya—yang berarti seumurku hidup belum melakukan hal tergila itu—hpku telah menjadi gudang beragam kantong, kotak, fail, lemari penyimpanan data, dan rak, atau—seperti yang sering kuatakan pada Maria—“labirin buku yang bisa dibaca tanpa jadi kenangan belaka.”
Kini aku berdiri di dalam labirin itu—dan rupanya Maria tidak pernah menemukan jalan masuk ke situ—dan menatap heran saat ternyata semua kalimat-kalimat itu kini telah kehilangan bahasanya. Segala yang hingga kemarin merupakan pengingat dan rekaman percakapan kami, kini telah menjadi sekadar beban kenangan, limbah tak berguna, sampah. Dan jika sebelumnya hatiku akan terenyuh setiap kali teringat pada, katakanlah, sebait kata yang digunakan olehku sendiri untuk dekat padamu, kini yang ada hanyalah kata omong kosong yang meruap dari sebuah kantong yang dipenuhi ilusi-ilusi bekas. Kusadari, cinta ternyata tak hanya buta, tapi tuli, menumpulkan penciuman, serta menghambat indra perasa dan peraba.
Rumahku kecil dan jauh dari tempat Maria. Saat aku membuangi apa yang hingga belum lama ini menjadi koleksi museum cintaku, otot-ototku terasa ngilu akibat kerja keras. Kukutuk cinta dan Maria dan takdir yang telah mempertemukan kami. Diriku sendiri, secara alamiah, tak kusebut di dalamnya. Sebab setahuku, ini bukanlah salahku atau Maria. Memang benar, seiring bertambah kedekatan kita dalam bercanda ria, aku lebih berkembang menjadi seorang sahabat ketimbang seorang kekasih. Tapi aku melakukan semua itu justru demi cinta, bukan yang lain. Seandainya Maria bersedia menerimaku, segalanya pasti akan jauh berbeda. Tapi kini semua sudah terlambat.
Aku takjub sendiri pada betapa cepatnya saat cinta lenyap bersamaan dengan hati yang berbalik seperti kaos kaki, meski aku yakin ini bukanlah salahku. Ilusi itu berguna, terutama jika bisa berubah jadi mimpi. Namun, cinta yang tak berbalas sungguh tak ada gunanya. Itu hanyalah dedak yang bisa membelenggu hati. Tak lebih. Ilusi masih jauh lebih baik. [T]
— KLIK untuk BACA cerpen-cerpen lainnya