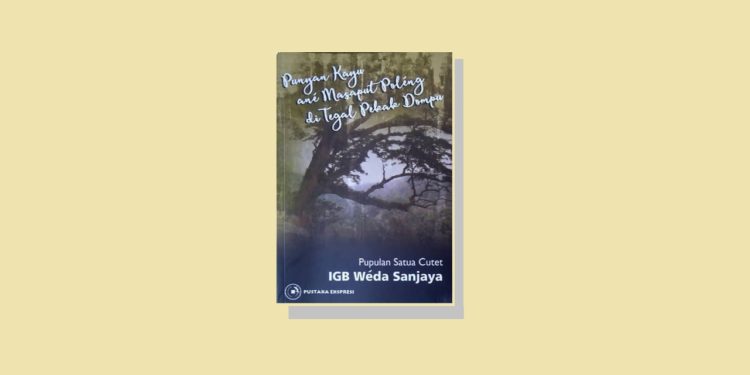Oleh Wayan Esa Bhaskara
Sebuah sayembara selalu berhasil jadi motivasi pengarang untuk menulis. Begitu pula keberadaan Gerip Murip sebagai salah satu sayembara bagi pengarang sastra Bali modern. Dari sayembara ini, yang dimulai sejak 2017, bermunculan karya-karya berkualitas. Entah mengapa, sayembara, lomba, atau penghargaan sastra dalam konteks sastra Bali modern selalu memunculkan karya-karya bagus.
Bukan berarti karya yang diterbitkan secara mandiri tidak atau kurang berkualitas. Namun, keberadaan sayembara, lomba, atau penghargaan sastra telah melewati meja kurator yang tidak ada dalam penerbitan karya secara mandiri. Pada sisi lain, peran editor dalam penerbitan karya mandiri menurut saya kurang maksimal.
Pada sayembara Gerip Murip oleh Penerbit Pustaka Ekspresi tahun 2021, melahirkan muka baru dengan kumpulan cerpen bernas Punyan Kayu ane Mesaput Poleng di Tegal Pekak Dompu karya I Gusti Bagus Weda Sanjaya. Kumpulan cerpen ini cukup menarik perhatian saya. Mengambil judul panjang bukan satu-satunya daya tarik. Daya tarik berikutnya dari segi kisah-kisah pada 12 cerpen bergerak dengan napas-napas baru.
Melihat sudut pandang lain, keberadaan sayembara dan sejenisnya menjadi bumerang sebab inisiatif seseorang menulis hanya ketika ada sayembara atau lomba. Selain keberadaan sayembara, jika ditilik inisiatif menulis menurut Orwell dalam esainya Mengapa Saya Menulis (1946), ada empat motif seorang penulis menulis atau menerbitkan karyanya.
Pertama, sekadar sebagai egoisme, yaitu keinginan untuk tampak lebih pintar, populer, dikenang setelah dirinya meninggal, ataupun menempatkan diri pada kedewasaan semu. Dalam konteks ini, seseorang menulis bertujuan sekadar ingin membalas terhadap penghinaan-penghinaan atas kehidupan masa kecilnya.
Kedua, antusiasme estetis, yaitu keterpesonaan pada kata-kata. Persepsi atas keindahan dan hasrat ingin berbagi pengalaman yang dianggapnya cukup bernilai. Ketiga adalah impuls historis, yaitu mencari fakta-fakta sejati dan menyimpannya untuk keperluan pelacakan asal-usul. Keempat adalah menulis sebagai tujuan politis. Politis dalam makna yang sangat luas.
Mencermati semua cerpen yang termuat dalam kumpulan ini, tampak tujuan keempatlah yang mendekati. Tujuan keempat ini sebetulnya dipertegas oleh Suparno dan Yunus (2009), yang mengungkapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai seorang penulis adalah menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, menjadikan pembaca beropini, menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, dan membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika.
Pada cerpen pertama, Ujan Ai di Desa Kawiswara sudah melecut kepala pembaca dengan metafora kuning dan merah. Jika pembaca adalah warga Tabanan, yang juga kota kelahiran IGB Weda, pasti merasa sangat dekat dan terwakilkan oleh kisah tersebut. Atau bisa jadi, pembaca yang lahir pada era sebelum reformasi pun sangat menyukai kisah dalam cerpen ini. Melalui cerpen ini, terlihat representasi ideologi sosial sekaligus ideologi penulisnya yang dihadirkan sebagai bentuk kritik terhadap tatanan sosial.
Cerpen berikutnya, Putu Leser Uli Cenik Tuara Bisa Nyledet bagi saya adalah contoh anekdot yang sering kita temukan di sekitar. Kembali, IGB Weda menempatkan cerpennya sebagai media kritik terhadap budaya korup. Formula yang digunakan dalam cerpen ini cukup jarang dieksekusi oleh penulis lain. Keberadaan kritik dalam cerpen-cerpen berbahasa Bali selama ini hanya selintas lalu atau tersirat dan tidak dibangun sejak awal cerita.
Tokoh Putu Leser adalah cermin orang jujur. Dalam cerpen, ia dikisahkan dikelilingi oleh orang-orang yang bertolak belakang dengan dirinya. Inilah musabab goyahnya pendirian Putu Leser. Dicerminkan oleh pikiran tokoh, Ningeh pabesen uli panglingsir tiange ajaka dadua, nyingakin angka telungatus yuta di buku rekening desane, nadak nyledet keneh tiange…. Uli sukat ento tiang bisa nyledet (12).
Sepanjang pembacaan saya terhadap cerpen berbahasa Bali, formula yang paling digemari penulis melalui tema sosio-kultural di Bali. Persinggungan antara mempertahankan tradisi dan menjalani modernisasi yang identik dengan segala kemudahan menjadi adonan yang paling gampang ditemukan. Biasanya pengarang menyampaikan kritik sosial, pesan moral, serta kegelisahannya pada praktik sosio-kultural Bali melalui tokoh-tokohnya. Beberapa penulis yang membuat tema ini tidak jenuh ialah I Made Sugianto dan Putu Supartika. Dua pengarang yang menurut saya sangat lihai merajut alur dengan variatif dan tentu saja ciri khas ending yang ciamik dari kedua penulis.
Kali ini saya menemukan kesan sama pada cerpen Punyan Kayu ane Mesaput Poleng di Tegal Pekak Dompu yang juga dipilih sebagai judul kumpulan ini. Isu alih fungsi lahan dipadukan dengan lokalitas tentang saput poleng adalah pilihan cerdas. Betapa pengarang paham bahwa masyarakat terlalu khusuk pada simbol-simbol, di sisi lain ada sebagian dari kita yang begitu takut kepada simbol. Begitulah saput poleng ditempatkan dalam cerpen ini.
Cerpen Memen Tiang Demen Mamitra tidak saja menarik karena mengangkat isu perselingkuhan. Dalam cerpen ini, penulis mengajak pembaca memaknai bahwa kesetaraan akan bisa terjadi jika kedua belah pihak memiliki upaya yang sama. Dalam konteks selingkuh, laki-laki atau perempuan bisa sama-sama menjadi pelaku. Sebaliknya, laki-laki atau perempuan bisa juga menjadi korban.
Kritik pada cerpen ini disampaikan dengan bahasa yang lugas tanpa kesan untuk canggung melakukan oto-kritik pada masyarakat. Mengingat masyarakat kita masih kukuh pada pijakan bahwa dalam perselingkuhan sebab musababnya adalah dari pihak istri. Cerpen Memen Tiang Demen Mamitra ini memiliki daya ledak yang baik dan cukup berhasil mengaduk psikologis pembaca.
Persoalan terkait relasi laki-laki dan perempuan menjadi pilihan paling digemari oleh penulis cerpen berbahasa Bali. Kelemahan yang sering ditemui adalah terkait tema yang berkutat pada kisah cinta pacaran. Lalu apakah cerpen IGB Weda ini menyalahi norma masyarakat yang menempatkan bahwa pelaku perselingkuhan adalah perempuan? Jawabannya tentu keberadaan realitas dalam cerpen tersebut. Mengingat dalam karya sastra tedapat produksi dan reproduksi makna.
Latar agraris menjadi menu menarik pula untuk dinikmati dalam beberapa cerpen. Selain cerpen Ujan Ai di Desa Kawiswara, ada cerpen Made Yasa Padidi Dadi Petani di Desa. Kisah-kisah tentang desa tani atau desa agraris memang bukan hal baru dalam cerpen-cerpen berbahasa Bali. Kembali ditulis dan pentingnya kisah-kisah ini, terlepas dari nyata atau imajiner, tetap menarik untuk dibaca pada zaman modern seperti saat ini.
Cerpen-cerpen seperti ini sangat mungkin mengajak pembaca ke masa lalu. Bayangkan saja ketika cerpen ini kembali dibaca pada puluhan tahun mendatang, oleh generasi berikutnya, bisa jadi kosa kata seperti numbeg, ngurit, malasah, dan nandur menjadi arkais. Sama seperti para tokoh-tokohnya yang seakan-akan hadir dari masa lalu.
Getir memang, sebab profesi petani tidak lebih diminati daripada dokter atau pegawai negeri. Aklesit nu ada masi di bucun keneh tiange, geginane dadi petani, memacul bilang wai ento tuah geginan ane tuara nganutin jaman. Tusing pesan ngangobin yen sambatang (hlm. 29). Kutipan dari pemikiran tokoh yang menggugah pemikiran dan menyentuh perasaan. Karena sastra adalah produk sosial, cerpen adalah salah satu bentuk teks sastra, maka inilah cermin masyarakat kita hari ini.
Cerpen yang suasananya agak berbeda ada pada cerpen Perang Leak. Cerpen ini mengisahkan kegemaran seseorang yang menonton perang leak. Cerpen dengan tema leak tentu sudah banyak ada. Tawaran baru yang diberikan ialah pada pemilihan sudut pandang penceritaan kisah remeh temeh, namun merupakan realitas sebagian masyarakat kita yang biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu seperti misalnya saat malam Nyepi. Cerpen dengan tema semacam ini akan sangat mudah diterima karena menggambarkan praksis masyarakat. Cerpen ini tidak memberikan suasana magis layaknya cerpen-cerpen lain dengan tema serupa. Ini disebabkan oleh ending cerpen yang diramu dengan humor. Formula ending yang sama dipakai lagi pada cerpen Juru Peleng. Cerpen dengan suasana magis malah saya dapatkan pada cerpen Kerauhan. Suasana magis tergambar dari narasi penggambaran latar pada awal-awal cerpen.
Asep dupa sane ngalub nusdus irung, tetabuhan saking sekaa gong sane ngalanturang ayah, lan kekidungan sane kalanturang ring coronge, ngawi cihna pujawaline sedeng kamargiang. Minab para dewata sami sampun sayaga jaga rauh saha macacingak ring kahyangan sane nedeng kapujawali (hlm. 62).
Suasana magis berikutnya saya temukan pada cerpen Soca Ulunangen. Pada kutipan berikut, Saking putih genahe jimbar, marawat raris pawakan I Dadong, mabusana sarwa putih. Malih sayan resik kantenang titiang, lan sayan miik adek titiang, sakewanten tan prasida titiang ngawedalang baos nang asiki (hlm. 70).
Mozaik cerita dengan beragam topik dipayungi oleh tema sosio-kultural Bali. Yang kemudian menjadi kekuatan adalah cara pengisahan pada cerpen-cerpen tersebut. Ada penebalan pada otokritik, formulasi pada ending, dan tentu mencoba pengisahan absurd dengan keberadaan tokoh yang bukan manusia.
Dalam tulisan ini, saya tidak mengatakan kumpulan cerpen Punyan Kayu ane Mesaput Poleng di Tegal Pekak Dompu karya I Gusti Bagus Weda Sanjaya adalah karya tanpa cela. Setidaknya, tempat yang telah diperoleh sebagai jayanti pada wimbakara Gerip Maurip bisa jadi indikator. Satu hal yang saya garisbawahi adalah cerpen-cerpen dalam kumpulan ini berpotensi memantik diskusi. Ini menarik, sebab sebagian penulis cerpen berbahasa Bali sudah cukup puas ketika karyanya hanya dibaca dan cukup sukses sampai pada frasa menghibur pembaca.
Memang bukan tugas penulis untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu salah juga ketika penulis dibebankan pada kewajiban semacam itu. Sebab ketika sudah di tangan pembaca, sebuah karya akan bebas diinterpretasikan. Tapi bagi saya, sudah saatnya sastra Bali mulai menapak pada membangun critical thingking pembaca. Peran ini hendaknya ditumbuhkan di ruang-ruang kelas. Sebagai seorang guru cum penulis, I Gusti Bagus Weda Sanjaya tidak membebankan tujuan khusus pada karya-karyanya. Namun, dalam perjalanannya karya-karyanya sendiri yang membentuk dan menemukan arah pembacaan.[T]
_____

_____