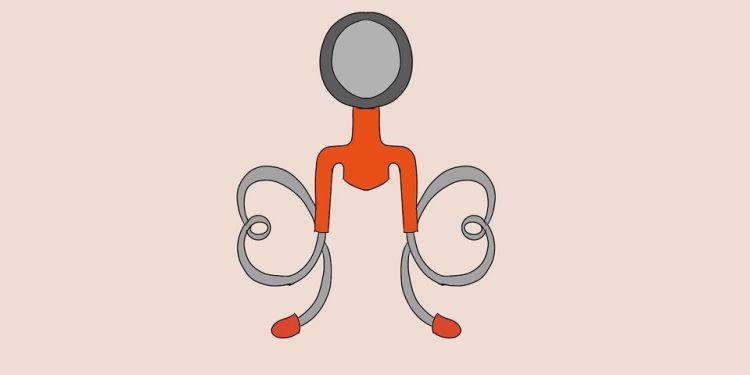“Maafkan keadaan rumahku ini. Tak sebagus tempat tinggalmu.” Made temanku sewaktu SMP memulai perbincangan denganku. Ia tidak seberuntung diriku. Hidupnya amat sederhana, tapi tak pernah mengeluh. Selalu saja kulihat kedamaian dalam hatinya. Ia pelihara beragam unggas di rumahnya. Itik dan beberapa entog berkeliaran di rumahnya. Rumahnya memang bertembok bata, belum sempat diplester sudah didahului oleh lumut yang melukisnya. Beragam lukisan lumut kulihat dari realis sampai yang abstrak.
Aku duduk di balai sakapat. Tempat yang biasa digunakan jika ada yang mengunjungi rumahnya. Dari tempat itu, bisa terlihat keindahan yang tersembunyi di semesta ini. “Sedari dulu kerjamu seperti ini?” tanyaku.
Ia tak segera menjawab. Ia lebarkan pipinya. “Nasib baik tidak berpihak padaku. Setelah tamat SMP, aku tak bisa melanjutkan karena faktor biaya. Aku jalani hidupku seperti ini. Aku sudah berusaha mencari jalan kehidupan, tapi inilah hidup yang terkadang amat susah ditafsirkan.”
Ia teman sebangkuku waktu dulu. Otaknya cukup bagus. Aku paling sering bertanya dengannya. Ia paling jago matematika di kelasku. Jika guru tidak masuk, dialah yang mengajari teman-temanku. Ia anak kesayangan guru matematika kami. Kalau tak ada yang bisa menjawab tugas dari guruku, ialah yang ditunjuk paling akhir. Tapi itulah hidup. Kepintaran yang dimilikinya harus pupus karena keadaan keluarganya. Ia jalani hidup sesederhana ini. Ia sodorkan ketela yang baru saja habis dikukusnya. Kuambil satu. Kunikmati. Kurasakan kenikmatan dalam setiap tarikan ketela ke kerongkonganku. “Kenapa kurasakan kenikmatan di sini?” bisikku. “Padahal, hidupnya amat sederhana.”
Ia tak banyak tanya padaku. Seperti kebiasaannya sewaktu SMP dulu. ia jarang bicara. Mungkin sadar akan keberadaan dirinya yang serba kurang.”Gimana kalau rumahmu kuperbaiki?”
Ia tersenyum tipis. “Tak usah. Biarkan saja. Aku merasakan kenyamanan. Aku tak mau merepotkan siapapun. Biarlah hidup ini kujalani seperti ini. Dulu juga ada yang mau merehab rumahku, tapi aku tak memberikannya.”
“Kenapa?” tanyaku ingin tahu.
Ia menarik napasnya. “Rumah ini meskipun begitu di dalamnya ada cinta. Istriku yang membangunnya. Aku tak berani mengganti tiang-tiangnya. Jika kuganti, kuyakin istriku tak akan bisa terima. Itu ada delapan tiang kayu. Kedelapannya istriku yang mengerjakannya. Aku bersyukur punya istri seperti dia walau sebentar. Kematian tak bisa dilawan. Ia meninggal saat melahirkan anakku. Anakku juga bersamanya. Aku tak mau menghilangkan rasa cintanya hanya karena sebuah rumah sebagai tempat berteduh. Cinta itulah tempat berteduhku. Cinta itulah rumahku. Cinta meneduhkan hatiku.”
Aku semakin simpati dengan sikapnya. Tak kusangka temanku sederhana seperti ini menyimpan cintanya yang tulus kepada istrinya. Mungkin jika sepertiku sudah beralih pikiran. Bisa-bisa menikah lagi. Aku menjadi orang bodoh terhadap kehidupan. Orang yang kukira menderita ternyata ada aliran cinta di dalamnya.
“Sering-seringlah kemari!” pintanya. “Aku juga kangen sama teman-teman yang lainnya. Aku yakin teman-temanku sudah menjadi orang sukses.”
Aku mengangguk. Kukatakan bahwa teman-temannya ada yang menjadi hakim. Ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi jaksa bahkan ada yang menjadi dokter. Kusampaikan juga temannya yang sering minta jawaban padanya. Sumi. Gadis yang baru remaja itu.
Ia tersenyum. “Sumi memang cantik. Tapi…”
“Tapiiiiiiiiiiiiii kamu jatuh cinta. Hahhahahahaha.”
Ia tertawa lebar. Aku juga tertawa. Kukatakan ia sudah menjadi dokter spesialis. “Jika kau berobat padanya, pasti tak akan dikasi bayar.”
“Hahahahaha! Tidak, aku tak mau sakit. Jangan sampaikan kehidupanku seperti ini. Ia memang gadis baik dan pintar juga. Cuma aku lebih mampu dalam bidang matematika saja. Yang lainnya Sumi memang jago.”
“Kau selalu merendah. Gimana kalau Sumi ke sini? Apa kau akan menolak?”
“Ndak sih. Tapi khan malu aku ini. Rumahku seperti ini.”
“Kuyakin Sumi tak akan terpengaruh sama rumahmu. Aku tahu Sumi itu masih menyimpan sesuatu padamu.”
Sore itu, aku pulang. Aku tak berhasil membujuk temanku ini. Pantang baginya untuk meminta bantuan pada orang lain. Meskipun seperti itu, tapi cinta selalu ia rawat sepanjang hidupnya. Diam-diam kufoto dirinya dan rumahnya. Kukirimi Sumi. Ia balik bertanya. “Siapa ini? Gagah sekali.”
“Kau ternyata jatuh hati juga padanya?”
“Ah, nggak cuma memuji saja.”
“Siapa tahu dari pujian bisa tergoda.”
Ia temanku sebangku waktu SMP dulu.” Ia cepat mengingatnya.
“Putraaaaaaaaaaaaaaa! Ke mana saja kau selama ini? Aku kangen padamu.”
“Nah, apa yang kuduga sebelumnya ternyata benar. Cinta monyetmu kambuh lagi. Hahahahaha!”
“Pokoknya ajak aku ke sana. Tidak boleh tidak. Aku harus bertemu Putra. Ia teman karibku dulu. Tak boleh lupa sama teman apapun keadaannya.”
“Bagus! Bu Dokter. Tapi, aku pasti akan disalahkan sama Putra. Ia katakan tak boleh disampaikan sama Sumi. Memangnya kalian pernah ada janji?”
“Ndak sih. Tapi mungkin pernah ada yang pernah kuucapkan. Tapi apa ya?” Pokoknya besok, aku harus bertemu Putra. Tidak boleh tidak. Apapun alasanmu. Kau harus mengantarku ke rumahnya.”
Besok pagi, kebetulan Sabtu, Sumi tak membuka praktik. Kami ke rumah Putra kembali. Kami susuri jalan menuju rumahnya. Pohon-pohon di pinggir jalan menuju rumahnya masih berdiri tegak. Kesejukan mengalari perjalanan kami. Suara burung menyertai kami. “Damai sekali desa ini.”
“Benar Sumi. Beda dengan kehidupan kita. Rumah kita dikitari tembok beton. Halaman beton. Di sini kita bisa menghirup bau tanah. Bau tumbuhan yang masih memancarkan cintanya pada kehidupan. Di sini, tak ada pohon plastik. Tak ada bunga plastik serba alami.”
Kami menuju rumah Putra. Ia baru saja selesai menyiangi rumput di halamannya. “Kamu ini mimpi atau gimana?” tanyanya.
“Katanya boleh sering-sering ke sini?”
“Ya boleh. Tapi khan baru kemarin. Aku jadi curiga? Pasti ada yang kau cari ke sini?”
“Ndak. Aku hanya mengantarkan Bu Dokter.”
“Oh Bu Dokter. Maaf Bu, rumah ini tidak sehat. Di sini duduk Bu Dokter. Nanti Ibu kotor duduk di sana.”
Air mata Sumi meleleh. Ia tak menduga Putra yang pernah ia janjikan dulu seperti ini. “Jangan mendekat Bu Dokter. Tubuhku kotor dan bau juga.”
Sumi terus mendekati Putra ia memeluknya erat sekali dan air matanya terus menetes. “Aku masih mencintaimu Putra. Aku Sumi. Maaf, aku meninggalkanmu.” [T]
Catatan:
- Sakapat: rumah bertiang empat