Setelah hampir sebulan penuh pada Februari lalu Bali marak menggelar aneka macam kegiatan dalam rangka Perayaan Bulan Bahasa Bali, tibalah kita pada bulan Maret. Bulan usai perayaan. Bulan yang barangkali akan kita lewati dengan biasa-biasa saja. Seperti melewati ulang tahun, esoknya kita jalani dengan rutinitas biasanya. Seperti perayaan pada hari ibu yang kita siapkan sungguh-sungguh, atau upacara kemerdekaan RI yang kita jalani penuh seluruh lalunsetelahnya, kembali kita lewati hari dengan perasaan yang pula bisa-biasa saja. Maka apalagikah yang harus diluarbiasakan di bulan Maret ini, apabila hal-hal di luar kebiasaan kita, semacam Perayaan Bulan Bahasa Bali misalnya, telah purna, usai kita lakukan?
Mungkin karena hakikat perayaan, pesta, festival dan sebangsanya, biasa digelar hanya untuk kepentingan euphoria dalam rangka. Hal-hal yang sebenarnya biasa dilakukan sehari-hari menjadi tampak luar biasa. Yang biasa menggunakan bahasa Bali, menjadi luar biasa memakainya saat perayaan. Yang biasa bekerja pada bidang keaksaraan Bali jadi merasa berdaya guna. Kebiasaan yang diluarbiasakan ini, hadir juga dalam seni teater, contohnya pada proses membangun pemeranan. Sederet watak manusia yang biasa hadir dalam realitas sehari-hari, diobservasi, disadari, lalu direspon oleh para aktor sebagai sesuatu yang luar biasa untuk kemudian dihayati dalam latihan menuju pentas. Sampai titik ini, penyelenggaraan perayaan dan penyelenggarakan teater memiliki kualitas yang sama.Yakni sama-sama membuat hal-hal yang biasa jadi luar biasa. Mewujudkan realitas sehari-hari biasanya, jadi luar biasa di atas panggung pertunjukan dan panggung perayaan.
Menjadi berbeda ketika permainan peran watak manusia yang luar biasa ini mampu hadir sebagai ruang refleksi dalam kehidupan biasa sehari-hari para penontonnya. Dalam teater, ada daya gugah yang terbangun untuk membandingkan watak manusia di atas pentas dengan watak diri sendiri. Ada pertanyaan yang berkecamuk atas situasi yang diperlihatkan dalam panggung pertunjukan dengan situasi nyata sehari-hari. Refleksi menjadi penting kehadirannya karena mampu membuka ruang renung penonton akan realitas hidup yang tengah mereka hadapi. Lalu bagaimana dengan penyelenggaraan Perayaan Bulan Bahasa Bali? Sudahkah segala kegiatan, segala kerja yang dilakukan mampu berperan menjadi ruang refleksi atas realitas yang tengah dihadapi masyarakat dalam konteks bahasa Bali? Sebagai bahasa lokal yang tiap tahun kian berjarak dipakai oleh penggunanya. Hal-hal apa saja yang sudah tercapai? Hal-hal apa yang mesti diperbaiki?
Beberapa pertunjukan teater yang telah digelar sepanjang Februari di Ksirarnawa, Art Centre lalu, boleh jadi merupakan bahan refleksi penting untuk mengidentifikasi kemungkinan potensi, masalah, kelebihan dan kelemahanatas kerja Perayaan Bulan Bahasa Bali tahun ini. Pada pentas kelompok teater SMA misalnya, kita cukup dikejutkan dengan usaha kawan-kawan pelajar menghadirkan teater di luar kebiasaan mereka dengan menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa utama pertunjukan. Beberapa kelompok yang tampil diantaranya adalah Teater Angin SMA N 1 Denpasar yang membawakan naskah Ketemu ring Tampak Siring, Teater Topenk SMA N 2 Denpasar yang membawakan naskah Togog, Teater Tiga SMA N 3 Denpasar dengan naskah Kilang, dan Teater Antariksa SMA N 7 Denpasar memainkan naskah Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang.
Dilihat dari lakon yang dimainkan, bagi para pembaca Sastra Bali Modern tentu sudah tak asing lagi kedengaran. Sebab lakon-lakon ini adalah hasil adaptasi dari karya sastra para penulis Sastra Bali Modern. Naskah Ketemu ring Tampak Siring adalah cerpen karya Made Sanggra, Togog adalah cerpen karya Nyoman Manda, Kilang adalah adaptasi novel Malancaran ka Sasak karya Gde Srawana dan Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang adalah novel karya Djelantik Santha. Pada pentas yang terselenggara, penonton dapat menyaksikan beragam hasil adapatasi yang dipentaskan, mulai dari teater dengan bentuk realis, surealis dan operet.
Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang menyertai, pentas kawan-kawan teater SMA ini menjadi hal yang luar biasa untuk diapresiasi, karena mampu merespon Sastra Bali Modern menjadi pertunjukan teater berbahasa Bali. Cara kerja adaptasi semacam ini, selain mampu meningkatkan minat baca anak-anak terhadap karya Sastra Bali Modern, juga memungkinkan terjadinya praktik belajar bahasa Bali secara langsung. Bahasa Bali tak hanya dihayati sebagai bagian mata pelajaran yang hadir dalam pembelajaran di kelas, yang cenderung kaku dan membosankan, melainkan menjelma menjadi kebutuhan menggunakan bahasa Bali sebagai media komunikasi antarpemainnya. Pun demikian dengan para penonton yang mau tidak mau mesti terbiasa atau sedikit tidaknya belajar bahasa Bali jika ingin mengerti tentang cerita pentas yang disajikan.
Sayangnya, format pentas yang begitu apik ini tak disertai dengan kerja diskusi karya sastra lebih lanjut. Pentas hanya usai sebagai pentas. Padahal jika ingin dikembangkan, acara bisa dilengkapi dengan diskusi sastra. Mengkaji karya sastra yang telah dimainkan oleh kawan-kawan teater, sembari menghubungkannya dalam konteks pertunjukan. Apalagi beberapa pengembangan naskah dari kelompok teater SMA ini mengalami penyesuaian di sana-sini atas cerita karya sastra yang dimainkan. Hal ini bisa jadi bahan pemantik diskusi. Dalam diskusi ini pula, terbuka pontensi lahirnya kritikus-kritikus Sastra Bali Modern untuk diperkenalkan dan dipersilakan hadir sebagai narasumber di hadapan publik.
Keluarbiasaan pentas dari kawan-kawan teater SMA juga tak diimbangi dengan pentas kawan-kawan teater kampus yang justru hanya pentas sekadarnya alias biasa-biasa saja. Kampus yang seharusnya memiliki penalaran dan pemahaman lebih kritis dan matang daripada kelompok teater SMA, malah terjebak pada bentuk-bentuk pentas improvisasi semacam bondres, arja, sendratari, dan lain sebagainya. Pilihan bentuk semacam ini sah-sah saja jika ingin digunakan apabila diimbangi dengan adanya upaya merespon karya sastra. Alih-alih mengadaptasi karya sastra, kebanyakan dari teater kampus ini justru memainkan cerita-cerita semacam Jaratkaru, Swarga Rohana Parwa, dan Atma Prasangsa.
Yang tak kalah lucu, saat menautkan cerita-cerita yang dimainkan oleh kawan-kawan teater kampus pada halaman google. Muncul berita Bali Post (http://www.balipost.com/news/2019/07/11/80576/Atma-Kertih-Penyucian-Jiwa-Paripurna,…html) yang mengatakan bahwa cerita Jaratkaru, Swarga Rohana Parwa, dan Atma Prasangsa adalah contoh-contoh cerita yang berpotensi untuk digarap dalam acara PKB tahun ini yang notabene mengusung tema Atma Kertih. Apakah pentas memang dimaksudkan untuk acara PKB mendatang? Atau hanya kebetulan belaka? Saya pribadi berharap bahwa semoga saja hanya kebetulan. Alangkah tak eloknya, menjadikan Perayaan Bulan Bahasa Bali hanya sebagai batu loncatan untuk pentas di PKB. Sudah sama-sama acara disbud provinsi, membawakan pentas bondres, sendratari, dan sebangsanya dengan judul cerita yang sama pula. Betapa biasa. Betapa tak punya visi meluarbiasakan pentas.
Kemandulan kreativitas ini adalah salah satu indikator penting yang semestinya dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut. Mengingat acara Perayaan Bulan Bahasa Bali baru menginjak tahun kedua penyelenggaraan. Begitu jomplangnya jika mau dibandingkan dengan Festival Bahasa Sunda se-Jawa Barat yang diselenggarakan setiap tahun sejak 1990 oleh kawan-kawan Teater Sunda Kiwari. Festival yang diniatkan dalam rangka memelihara rasa memiliki masyarakat terhadap Bahasa Sunda ini mampu bertahan setiap tahun lantaran konsep dan format kerja yang terus menerus berusaha untuk dievaluasi, diperbakai dan dikembangkan lebih lanjut.
Salah satu caranya, yakni menyajikan naskah yang berbeda setiap tahunnya. Penyajian naskah bisa berangkat dari hasil adaptasi karya sastra Sunda, karya sastra Indonesia bahkan karya sastra dunia yang diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Strategi semacam ini secara tidak langsung mampu membuka ruang ulang alik kerja penerjemahan antarbahasa ke dalam bahasa lokal yang dalam konteks ini jarang dilakukan oleh kebanyakan pegiat bahasa Bali. Lebih jauh, pentas juga memproduksi naskah-naskah teater yang dibuat khusus berbahasa Sunda. Ditambah dengan menggunakan pendekatan modern dalam pertunjukannya, walhasil pentas dalam festival menyajikan bentuk dan konteks yang lebih cair dengan masyarakat dan zamannya. Luar daripada itu, Festival Bahasa Sunda juga membuka kemungkinan bagi kelompok teater Jawa Barat yang di daerahnya tak memakai bahasa Sunda untuk mementaskan pertunjukan dengan ragam bahasa asalnya masing-masing, bahasa Indramayu, misalnya. Yang meski sama-sama dari Jawa Barat, namun punya varian bahasa yang berbeda.
Hal ini jadi penting jika dikaitkan dengan tulisan Eriadi (jro Penyarikan Duuran Batur) dalam http://www.tatkala.co/2020/02/01/bahasa-bali-berkibar-oke-bee-dapatkah-bertahan-catatan-bulan-bahasa-bali/ yang mempersoalkan tentang terhimpitnya kosakata bahasa Bali Aga karena lebih berkembangnya anggah-ungguhing bahasa Bali dalam masyarakat. Bagaimanakah pihak panitia dan tim kreatif merespon fenomena ini? Sementara jika diperhatikan seksama, teater-teater yang pentas dalam Perayaan Bulan Bahasa hampir semua berasal dari wilayah Denpasar. Jika pun ada pentas yang memakai dialek Buleleng, Negara, dan sebagainya, kebanyakan hanya disikapi sebagai bahan banyolan semata. Alih-alih membuka peluang jelajah bahasa, strategi semacam ini justru jadi bumerang tersendiri meneguhkan varian bahasa satu, mengesampingkan varian bahasa lainnya.
Kehadiran teater dalam Perayaan Bulan Bahasa Bali semestinya bukan hanya disikapi sebagai pengisi acara saja. Melainkan diniatkan sebagai gerakan membangun politik bahasa agar segala varian bahasa Bali, dari bahasa Bali Aga sampai Majapahitan, dari bahasa gunung sampai pesisir, dari bahasa asli sampai pendatang, dari segala lini di Bali, mampu tampil percaya diri di hadapan publik. Visi dan gagasan pertunjukannya jelas, yaitu mengeksplorasi bahasa Bali dengan segala macam varian yang hadir dalam realitas sehari-hari masyarakatnya.
Alhasil, pentas teater bahasa Bali tak hanya diwarnai dengan ragam bahasa sor singgih, kidung atau kekawin yang sudah biasa dihadirkan di pura-pura. Apalagi menghubungkannya dengan cerita Prabu Aji Saka, hanya gara-gara ceritanya berkaitan dengan aksara Bali. Kalau gagasan dan interpretasinya sebatas itu, baca komik anak dancow saja sebenarnya sudah cukup. Tak perlulah susah-susah menampilkan teater, apalagi menyajikan slide aksara hanacaraka sebagai artistik pertunjukan. Sajian yang mengingatkan kita pada rupa aksara Bali yang ditulis di papan kelas. Di bulan Maret ini, usai Perayaan Bulan Bahasa Bali, anak-anak SD di kelas-kelas mungkin tengah kembali pada rutinitas belajar bahasa Bali biasanya. Mengantuk menyaksikan guru bahasa Balinya menerangkan aksara Bali. Ala kadarnya, dengan pola biasa, dengan semangat yang biasa-biasa saja. [T]
Denpasar, 2020


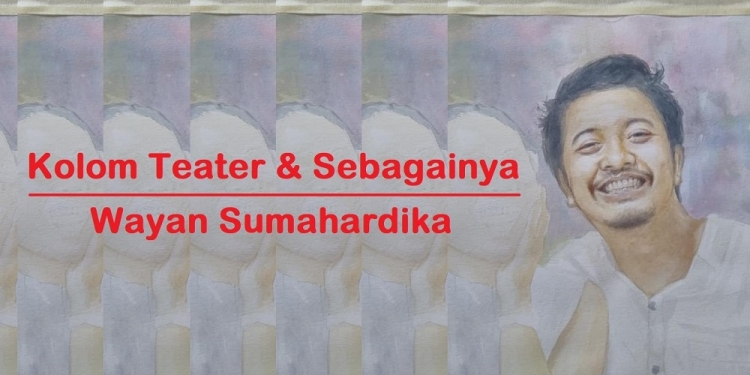









![Laporan Pentas “The Seen and Unseen” dari Australia [4] – Pentas Terakhir Sebelum Pulang](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2020/03/amri.-australia4.-berpose-sebelum-pulang-75x75.jpeg)
















