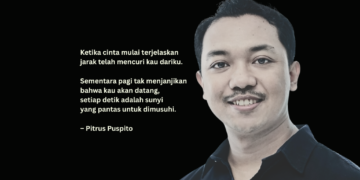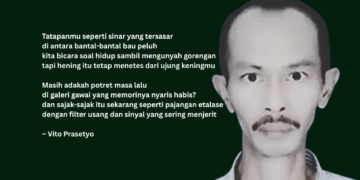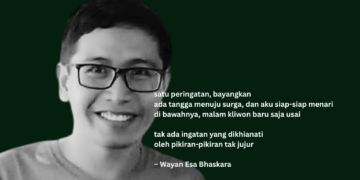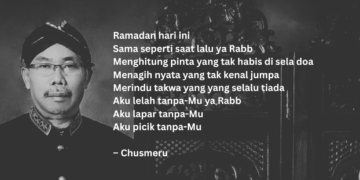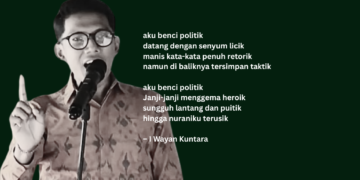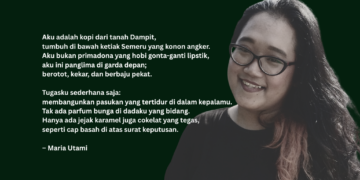KEDAI EMBARA
Bayangkan setelah tutup mata, warna tiada,
hitam putih, ketikan dan kertas,
merah, bungkus renyah lidah,
biru, tangkup alir air,
kuning, mi instan dan penjaranya,
dan hijau, sayur-sayur kabur.
Jadi tunawarna sesudah buka mata.
Bayangkan setelah buka mata, warna berbeda,
kopi sulit dikenali,
lampu jalan berwujud bayang,
permata tak lebih dari kerikil,
dan bibir milik kekasih kehilangan goda.
Jadi tunarasa sesudah tutup mata.
Bayangkan setelah kedip mata, warna seperti sediakala,
wajah sendiri tak dilupa,
ragu langkah di penyeberangan kota hilang,
awan selalu pantulkan suasana,
panas cabik cahaya,
dan matahari putih terbit di sela pohon cemara.
Jadi tunakarsa sesudah tatap mata.
Bayangkan setelah tatap mata, warna tetap sama,
air dan arak tak jauh beda,
gula rasa laut,
roti gosong coklat,
aspal sepupu dekat tanah basah,
dan semangka semanis darah.
Jadi tunamakna sesudah kedip mata.
Singaraja, 12 Maret 2019
MATRA I
Mencintai seperti membeli nasi.
Bisa makan di tempat atau dibungkus.
Ada sayur atau lauk perkara pemesan.
Harganya tetap sama.
Dalam porsi itu ada kesegalaan yang dimakan bersamaan.
Selalu kuhabiskan.
Kadang, rasa benci timbul ketika ada sisa karena tidak suka.
Pedagang tidak mau mengganti.
“Itu bukan urusan kami! Kau yang bersalah! Kauminta yang kausisakan”
“Ya, seperti cinta, harus ada yang tersisa!” Sahut seseorang di sebelah.
Setelah selesai makan,
mata pedagang senja.
kesedihannya juga senilai dengan apa yang tersisa: Cinta.
Sebab selalu ada kasih dalam setiap suap.
Seperti halnya rasa,
cinta tidak akan membuatku rakus.
hanya saja,
dalam satu hari,
aku tidak puas hanya dengan sebungkus cinta.
Singaraja, 12-13 Juli 2017
MATRA II
Anggaplah kau adalah pohon.
Apakah yang dirasakan Akar, Batang, Ranting, Buah, dan Daun?
Kesalkah Akar?
Ia, tumpu bagi saudara-saudara asing.
Merintih-merintis dalam gelap.
Sementara yang lain berjoget, terlebih Ranting.
“Adakah di antara kalian melihat rupa Akar?”
Tanya Buah pada suatu reinkarnasi.
“Sepanjang hidup, tak pernah kudengar sapanya. Meski bertetangga”
Bisik Batang.
Yang lain semakin pongah.
Dalam perih, ia menggali permata air.
Tak peduli.
Kesalkah Batang?
Ia hanya berdiri.
Tak bisa ia usap peluh seperti Daun
atau meniru Akar yang rebahan-mendengkur.
Ia juga dilarang bernyanyi.
“Jika kau berbunyi dan berjoget, tidak hanya kau, kita bisa mati!”
Kata Buah selalu mementingkan diri sendiri.
“Tegakah kau merusak cinta Akar dan permata air yang bersih ini?”
Lanjut Daun yang masih sibuk menyembah langit.
Masih berdiri. Sunyi.
Kesalkah Ranting?
Ia tak lelah mendekap kerakusan Buah atau ketulusan daun.
Sikap kaku Batang berlagak tua membuat takut.
“Jika Buah dan Daun Hilang, maka habislah kita,” pikirnya
tanpa peduli diri.
Tetap saja. Ia.
Menyuapi Buah.
Meremas jari Daun.
Menyalami batang.
Kesalkah Buah?
Ia rajin menabung. Menyiapkan kehidupan.
Namun semua iri dan tidak percaya.
“Ia punya pesiguh! Ia mencuri segala milikku!” celetuk ranting ringkih.
Dengan bingung Akar berteriak berkali-kali. Tak satu pun menjawab.
“Di manakah permata airku?”
Batang tetap bisu, meski tahu.
Namun, tiap ocehan itu tetap memaniskan ia.
Kesalkah Daun?
Bangun. Langsung berdoa dengan rapal cepat.
“Yang maha kuasa, terimalah satu setengah miligram asap air kasih
yang diramu dalam pinggan permata. Oh, Langit yang agung.
Berkati kami keselamatan pelaut, keberuntungan pedagang,
Dan kemuliaan petani. Hindarkan dari segala penyakit.
Musnahkan musuh-musuh kami dalam kobaran radiasi.
Taburlah abu pembakaran dalam wujud berkah hadiah kepada daratan dan lautan datar.
Oh, Langit yang murni.”
Selalu terulang.
Semua tertawa. Mengira gila.
Kekurangan obat atau semacamnya.
Ia mati. Semua termangu.
Lalu, mantra matra itu menggema panjang. Alam rindang.
Jadi, masih kesalkah kau kepadaku?
Ataukah hanya aku?
Singaraja, 13-17 Juli 2017
NANTI, KAU INGIN NAMA ANAK KITA SIAPA?
: An.
Misalkan kita menikah,
kau ingin nama anak kita siapa?
kataku dengan nakal.
Jangan memilih nama dedaunan,
karena sedikit orang yang akan mengerti.
Jangan juga memakai nama seorang pengembara,
agar rahasia malam kita tetap menjadi rahasia.
Begitu juga dengan nama huruf yunani,
jangan, karena terlalu menyulitkan.
Tapi lebih baik gunakan nama awan,
karena ia suka memperlihatkan diri dengan apa adanya.
Seperti awan, aku apa adanya,
menunggu nama apa pun yang kau suka.
Singaraja, 28 April 2012
ZAWSZE II
Tak ada kata pengantar pada anak itu.
Suara adalah kesunyian.
Kata-kata ia jadikan gerak sedang petunjuk menjadi warna.
Ia memahami. Kecuali sunyi.
Seperti telah kukatakan, sunyi baginya adalah kegaduhan
bahkan nyanyian perawan dianggap angin yang tak terjemahkan.
Dirinya adalah setiap seruan.
Bahkan keinginan.
Ia datang,
menanyaiku dengan jiwa.
Mencari seseorang, mungkin ibu atau saudari.
Ia memiliki petunjuk.
Nama dalam warna.
Aku bantu ia dalam pencariannya.
Ia pergi.
Bahkan ketika pulang pun tiada antar.
Singaraja 6/3/2017
KOPISEPI
Kau meminum cinta yang kurus. Tapi tidak sampai kering.
Dengan harap segala yang tertinggal kembali diisi.
Seolah memurnikan.
Ampas kopi menepi, menyendiri. Bersemadi.
Pikiranmu terlalu lurus!
Cinta yang kau bilang murni itu ada bukan dengan menadah.
Tetapi Mengolah.
Ampas beruap. Meruang.
Menjadi bulir.
Jiwa yang basah.
Rancu antara darah atau air mata.
Kau menelan cinta yang pilu. Sampai tersendak.
Dengan bibir yang setipis ujung belimbing itu tidak akan cukup.
Ya. Ampas,
awal segala rasa cinta yang kau sebut murni itu
sedalam tubuhku,
hingga tidak akan habis untuk kau hamburkan
di halamanmu sendirian.
Singaraja, 9 Januari 2017