Berpuluh-puluh tahun setelah Bali berhasil mengembangkan PKB (Pesta Kesenian Bali) sebagai ruang akomodatif dalam merancang festival kebudayaan, dengan ratusan produk kesenian di dalamnya, mulai dari pertunjukan, lomba, workshop, sarasehan, pameran, dan lebih penting daripada itu, memelihara minat ratusan bahkan ribuan penonton untuk datang singgah setiap tahunnya, tak dapat kita hitung lagi banyaknya jenis festival yang tergelar, baik dalam lingkup banjar, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi di Bali. Setiap tahunnya, festival-festival ini, dengan berbagai macam nama dan bentuknya, seolah ingin berusaha mendefinisikan dirinya sebagai acara, yang seolah-olah punya andil tersendiri dalam pengembangan dan pemeliharan kebudayaan Bali. Menariknya, festival-festival yang tergelar ini, hampir semuanya berkiblat pada satu tonggak, yakni Pesta Kesenian Bali.
Maka, apa-apa yang festival, apa-apa yang kesenian, pastilah dihubung-hubungkan dengan PKB. Pun demikian dengan festival terbaru yang digelar di Bali tahun ini, Festival Bali Jani 2019. Sebuah Festival yang katanya dirancang dalam rangka menyeimbangkan capaian-capaian PKB, yang notabene lebih banyak memberi ruang pada seni tradisi, kini disandingkan dengan FBJ (Festival Bali Jani) yang diharapkan menjadi wadah pada bentuk-bentuk kesenian modern. Gagasan demikian tentu membuat banyak kawan yang modern menyambut baik acara ini.
Bahkan jika boleh diandaikan, masyarakat seni modern ini jadi seperti sebuah desa paceklik kekeringan yang baru saja disemprot air PAM oleh petugas PDAM. Semuanya jadi bergelimang air. Mulai dari masyarakat yang memang kekurangan air, yang membutuhkan air, bahkan yang biasa berenang di air sekalipun. Semua kepingin ikut mandi air. Mandi air seni. Bukan air seni kencing ya, melainkan air seni modern.
Maka, apa-apa yang mandi air seni ini, pastilah dianggap modern. Apa-apa yang modern, pastilah berharap pentas di panggung FBJ. Lucunya, banyak juga dari apa-apa yang merasa seni modern ini, berharap FBJ jadi seperti PKB. Lha? Ini apa-apan sebenarnya ne?
Samar-samar, pikiran semacam ini sudah terasa sedari awal terselenggaranya FBJ. Hal ini berlanjut sampai workshop Tata Kelola Festival yang diadakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 3 Desember lalu. Workshop yang semestinya lebih banyak bicara perihal strategi tata kelola festival, justru mengerucut pada soal bagaimana membenahi FBJ ke depannya. Hampir sebagian peserta yang berbicara, mengharapkan capaian FBJ agar sama dengan capaian PKB yakni, banyaknya penonton yang datang menghadiri festival. Artinya, jika banyak yang menonton, festival jadi bagus. Namun jika sedikit yang menonton, festival dinilai kurang berhasil.
Salah satu pembicara diskusi, komponis Wayan Gde Yudane dalam makalahnya padahal sudah menampik, “bahwa meskipun indikator kuantitatif, seperti jumlah kehadiran, diperlukan, ini tidak boleh menjadi fokus utama dalam menilai keberhasilan Festival. Seharusnya juga ada sekeranjang indikator kualitatif dan jangka panjang dari dampak festival terhadap dukungan produksi karya berkualitas dan pengembangan artistik, seperti ulasan nasional maupun internasional, liputan media dan bagaimana festival mengembangkan jangkauannya dalam jangka panjang.”
Ditambahkan oleh dramawan Putu Satriya Kusuma, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi, berpendapat bahwa festival agar bisa lebih cair dalam mengelola pertunjukan, baik dari segi ruang dan penataan artistik. Dalam perkembangannya misalnya, bukan tidak mungkin ada pentas yang menggunakan ruang kamar mandi di Art Centre Denpasar sebagai panggung pentas, yang penontonnya dipersilakan menonton pentas di balik celah ventelasi kamar mandi. Jika demikian adanya, dapatkah ratusan penonton sebagaimana yang dicita-citakan untuk menyamai PKB, menyaksikan pentas semacam ini?
Kita yang senantiasa menasbihkan diri bahwa seni modern adalah kesenian di ruang sunyi, sekalinya ada penonton berjubel menonton pentas sendiri, malah seringkali lupa pada apa yang kita bicarakan sebelumnya. Kita jadi larut membanggakan jubelan jumlah penonton tersebut. Yang tak pernah kita tahu darimana sebenarnya asal penonton ini. Bagaimana cara mereka hadir menonton pentas kita. Apakah mereka benar-benar hadir untuk kita? Atau hanya memenuhi tugas dinas semata? Bahagiakah mereka melihat pertunjukan kita? Atau malah sebaliknya, ternyata pertunjukan kita malah mengganggu kesibukan mereka. Apa sebenarnya yang mau dibanggakan dengan capaian penonton seperti ini?
Bicara kuantitas penonton, percakapan juga kerapkali nyerempet pada esksitensi Teater Kini Berseri, salah satu teater muda di Bali yang merupakan teater yang paling banyak masa penontonnya. Sayangnya, jarang orang membicarakan bagaimana proses kreatif mereka selama bertahun-tahun menggarap pentas drama realis, pantomime, hingga sampai memutuskan operet sebagai pilihan bentuk pertunjukan. Bagaimana pada tahun-tahun awal produksinya, memperkenalkan operet ke ruang-ruang publik di berbagai daerah Bali dengan mobil seadanya, bahkan naik motor ramai-ramai hingga ke lombok. Bagaimana strategi mereka dalam mengelola iklim penontonnya dengan secara konsisten menggelar pertunjukan selama 11 tahun, entah ada dana dari pemerintah, atau tidak.
Lain lagi dengan teater Putu Satriya, yang beberapa kali menyoal penonton. Sesungguhnya tanpa disadari telah melakukan pembinaan penonton sejak lama. Buktinya, setiap kali ia bawa garapan teaternya di Buleleng dan Denpasar hari ini, tak pernah sekalipun pentas Putu sepi. Selain ada saja puluhan penonton yang nyasar kerapkali duduk sampai usai pertunjukan, selalu pula dapat kita lihat puluhan wajah-wajah yang sama, hadir menyaksikan setiap pentas yang digelar. Beberapa dari mereka tak hanya jadi penonton saja, melainkan dengan sukarela menulis ulasan pertunjukan, mendokumentasikan pentas, membantu mengerjakan setting, bahkan turut serta ambil bagian jadi pemain dadakan.
Saya pribadi berpendapat, ini merupakan keberhasilan Putu yang tak akan pernah bisa disamai oleh kelompok teater manapun di Bali. Membawa dimensi teater bukan hanya sebatas pertunjukan semata, antara ruang menonton dan ditonton. Lebih dari itu, teater Putu adalah teater upacara, dimana penonton dibawa menembus batas kedudukan dan fungsinya sebagai penonton untuk turut serta menggarap pentas bersama kelompok teater itu sendiri. Dalam konteks ini, justru tak penting lagi mana yang sesungguhnya penonton, mana sesungguhnya yang ditonton.
Yang tak kalah menarik adalah pembicaraan dengan Yudane sebelum pentas pada FBJ bulan lalu. “Sing penting luwung ajak sing festivalne, ane penting to mongken jarak setipan karya kaune.” Semestinya, kehadiran festival ini dimanfaatkan untuk membuat karya yang bagus. Lalu karyamu ini kau manfaatkan untuk dipentaskan di festival-festival yang jauh lebih bagus mutu kualitasnya. To mara je setipan adane. Bukan berkarya dalam rangka FBJ saja. Lalu duduk diam menunggu FBJ tahun depan. Yang jika tak dipilih jadi protes, marah-marah, menggerutu tak jelas.
Jika benar kawan-kawan modern ini serius untuk mengelola festival, barangkali konsep ini pula yang sekiranya bisa menjadi potensi untuk dikembangkan. Indikator keberhasilannya, justru terletak pada seberapa jauh karya-karya yang hadir pada Festival Bali Jani mampu bergerak setelahnya. Mencari penonton yang lain di luar Bali, berinteraksi dengan arena kultural di luar festival, atau minimal gagasan yang hadir mampu memberikan inspirasi buat kerja-kerja kesenian selanjutnya. Jadi tak perlu lagi festival yang bersusah payah mempromosikan produk kelompok pesertanya, melainkan produk kelompok peserta inilah yang menjadi sebab festival ditunggu-tunggu kehadirannya.
Perihal ditunggu-tunggu, PKB yang senantiasa dijadikan pembanding keberhasilan festival juga sesungguhnya tak lagi punya daya tawar buat ditunggu-tunggu kok. Jika boleh jujur, monotonnya acara, minimnya gagasan, tak adanya lagi pembacaan terhadap konteks hari ini oleh tim kreatifnya adalah beberapa indikator yang membuat kuantitas penonton setiap tahunnya kian menurun. Masalah kualitas karya yang dihasilkan pun tak jauh-jauh amat dengan tahun sebelumnya. Diantara masyarakat yang berjubel datang ke PKB, sedikit yang datang benar-benar menyaksikan pentas. Lebih banyak ya untuk lihat-lihat barang antik atau beli baju diskonan di pameran. Penonton yang seperti inikah yang diharapkan untuk datang ke FBJ?
Sebab PKB sudah terlalu percaya diri dengan capaian-capaian masa lalunya, sebagaimana mereka yang masih tetap percaya PKB adalah tonggak festival Bali. Jika pikiran ini masih terpancang di kepala setiap orang, apalagi di kepala seniman modern FBJ, maka boleh jadi, bertahun-tahun setelah FBJ digelar, nasibnya akan sama seperti PKB. Bahkan mungkin lebih buruk. Apa-apa yang ada di FBJ sesungguhnya tak ada apa-apanya. Bahkan jika FBJ tak ada sekalipun, ya tak apa-apa juga. Karena sudah biasa sesungguhnya seni modern kita di Bali bergerak tanpa ada dukungan apa-apa. [T]
Denpasar, 2019


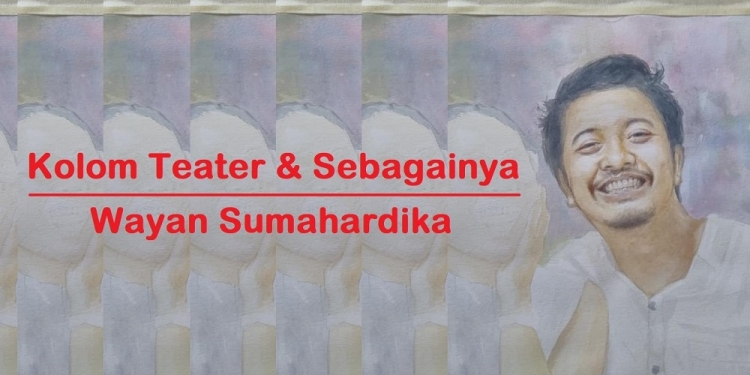









![Once Upon A Time in Nepal [2] – Are you okay Sonia?](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2019/12/sonia.-nepal2-75x75.jpg)
















