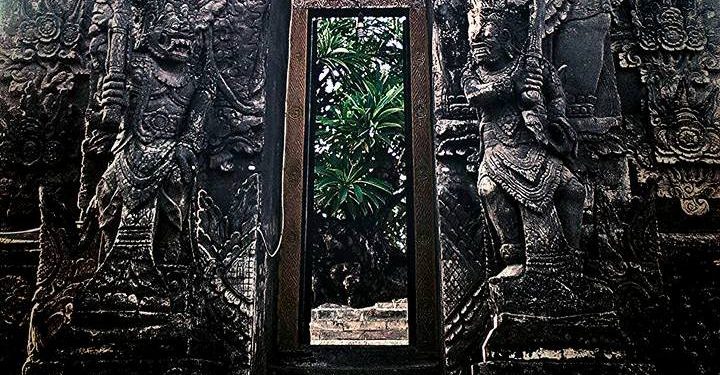MEMBACA buku sejarah adalah membaca penafsiran-penafsiran. Membaca buku sejarah adalah membaca kejadian masa lampau yang hanya mungkin ditilik kembali dengan membangun serpihan-serpihan peninggalan, catatan-catatan yang sarat subjektivitas, dan hikayat-hikayat yang acap lebih mirip dongeng.
Karena itu, buku sejarah tak mungkin mampu menghadirkan keutuhan. Ada begitu banyak bias yang mungkin muncul. Ada banyak peristiwa —kecil-besar— yang sangat mungkin hilang dari catatan dan ingatan.
Menceritakan kejadian masa lampau adalah menyusun mozaik tanpa nomor urut. Setiap orang bisa menciptakan bentuk yang berbeda dari bahan yang sama. Bahkan asal-usul seorang Ken Arok pun bisa melahirkan ribuan cerita.
Benarkah ia hanya seorang yang bukan siapa-siapa, lalu muncul begitu saja menumbangkan Tunggul Ametung? Jangan-jangan Ken Arok memang telah dipersiapkan secara matang oleh kelompok tertentu. Jangan-jangan Ken Arok berhasil karena ia memang “dibantu” oleh Ken Dedes dari dalam. Jangan-jangan …
Semuanya terkesan masuk akal. Semuanya terkesan debatable.
Hampir tak mungkin kita menemukan penulis sejarah yang benar-benar “jujur”. Akan selalu saja ada data yang disingkirkan karena dianggap tidak sesuai dengan alur yang “semestinya”. Hampir tak mungkin menemukan penulis sejarah yang mampu melepaskan diri dari subjektivitas, sebab penafsiran atas fakta dalam sejarah bukanlah seperti mencari angka 6 dari perkalian 2 dan 3.
Angle alias sudut pandang sangat menentukan dalam penafsiran itu. Dan, ya, angle itu sangat ditentukan oleh minat seseorang, visi seseorang, bahkan mungkin juga ditentukan oleh latar belakang politik seseorang.
Sangatlah naif memutlakkan kebenaran sejarah. Karena itu sejarah harus senantiasa dicerna dengan kecerdasan tinggi dan kesiapan mengakui bahwa kita sedang berhadapan dengan cerita yang “mungkin benar”.
Ingatlah perdebatan tentang G 30 S yang hingga kini pun tak kunjung usai. Padahal banyak saksi mata yang masih hidup. Ingatlah “kegerahan” pakar sejarah Sartono Kartodirdjo terhadap kecenderungan penulisan sejarah yang serba menonjolkan hero-hero, jagoan-jagoan.
Padahal, katanya, ada jutaan petani yang sangat mungkin berperan sangat besar dalam menentukan pergerakan sejarah. Padahal, katanya, ada jutaan kaum ibu yang sangat berperan menentukan sejarah kebudayaan manusia. Ingatlah kebiasaan para diktator yang sangat senang “menghapus” kejadian-kejadian yang tak disukai dari runtun cerita sejarah. Ingatlah hobi para penulis kerajaan yang hanya pintar memuji raja dan tak pernah menengok pada gelombang perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat kecil.
Raja dan para hero memang bisa membangun sejarah berdasarkan kehendaknya. Tetapi ibu rumah tangga, petani, buruh, dan nelayan pun membangun sejarahnya sendiri. Tetapi jejak perubahan yang mereka buat memang sulit dilacak karena mereka tak punya tukang catat dan perubahan yang mereka ciptakan pun cenderung gradual.
Menulis sejarah adalah meruntun jutaan kemungkinan kausalitas dalam sebuah peristiwa. Tak ada satu keahlian pun yang bisa memastikan bahwa catatan di saku seorang sejarawan saling berkaitan. Sekali salah mengaitkan peristiwa, sekali salah menyusuri jejak kausalitas dalam peristiwa, maka sejarah yang ditulis pun menjadi “mungkin tidak benar”.
Pada dasarnya sejarah adalah bangunan yang terbuat dari kemungkinan-kemungkinan. (T)