PADA awal bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 7 atau 8—sepekan setelah Idulfitri, sebagian umat Islam di Jawa akan melangsungkan hari raya yang kedua. Tapi hari raya ini tidak termasuk syariat Islam, hanya tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman Sunan Kalijaga—sebagaimana kepercayaan orang-orang yang rutin menggelarnya. Orang Jawa menyebutnya “Kupatan” atau Lebaran Ketupat.
Sebagaimana sebutannya, umat Islam di Jawa, seperti di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, misalnya, akan membuat banyak ketupat pada hari tersebut. Tak hanya ketupat, tapi juga alu-alu (banyak orang mengenalnya dengan sebutan lepet)—kuliner khas yang terbuat dari beras ketan dan santan (terkadang dengan toping kacang tunggak merah) yang dibentuk memanjang seperti alu, alat penumbuk dalam proses menutu padi, dan dibungkus dengan daun lontar atau daun pisang muda.
“Tradisi ini sudah turun-temurun,” ujar Tari sambil menganyam daun lontar muda menjadi ketupat. Lelaki paruh baya itu awalnya membuat pola gulungan daun lontar—yang panjang—di tangan kanan dan kiri. Lalu ia menggabungkan kedua pola tersebut menjadi rancang-bangun yang tampak rumit bagi yang tak bisa. Tari mulai menganyam ujung-ujung lontar itu dengan terampil. Ia menyusupkan ujung tersebut ke sana ke mari, menjadi ketupat yang sempurna, presisi dan terlihat manis.

Alu-alu (Lepet) setelah dimasak | Foto: tatkala.co/Jaswanto
Benar. Umat Muslim di Desa Gaji, seperti keterangan Tari, dari dulu hingga sekarang, nyaris selalu menggunakan daun lontar muda sebagai wadah ketupat, alih-alih menggunakan janur—daun kelapa yang masih muda—seperti umumnya di daerah lain. “Karena di sini banyak pohon lontar,” Tari menerangkan. Di Tuban, pohon lontar tumbuh dengan subur di pinggir-pinggir tegalan sampai di lereng-lereng bukit kapur. Sedangkan kelapa, khususnya di daerah bukit pedalaman, tak banyak tumbuh.
Pada lebaran ketupat, banyak warga Gaji yang membuat ketupat sendiri, walaupun tak sedikit pula yang memilih membelinya dari penjual. Di desa ini, satu ketupat tanpa isi dijual 1.500 rupiah. Orang-orang biasa membeli minimal sepuluh ketupat. Pada momen seperti ini, Rajit dan istrinya bisa mengantongi ratusan hingga jutaan rupiah. Bertahun-tahun yang lalu Rajit dan Tarsini—suami-istri—memang dikenal sebagai penjual lontar dan ketupat yang cakap. Namanya tersiar seantero Desa Gaji dan sekitarnya. Bukan saja bahan lontarnya yang bagus, tapi juga bentuk ketupatnya yang rapi dan presisi—tidak terlalu besar maupun kecil. “Bahan baku [daun lontra] punya sendiri. Di pinggir ladang saya banyak pohon lontar,” terang Rajit.

Ketupat setelah dimasak | Foto: tatkala.co/Jaswanto
Ketupat-ketupat yang sudah jadi akan diisi beras dan dimasak. Menjelang sore hari, ketupat dan alu-alu yang sudah masak, lengkap dengan lauk-pauk seperti serundeng (abon kelapa), ayam goreng, sambal kacang, telur dadar, tempe goreng, dll, sebagian akan diantarkan ke sanak-keluarga dan tetangga terdekat. Sebagian lagi dibawa ke musala atau masjid untuk kemudian dinikmati bersama-sama setelah didoakan. Jamaah satu akan memakan ketupat yang dibawa jamaah lainnya. Saling tukar-menukar. Di musala, tak ada jamaah yang memakan ketupat bawaan sendiri.
Makna Kupatan
Hari Raya Ketupat (Kupatan) bisa dikatakan sebagai bentuk perayaan (kemenangan) atas hawa nafsu selama Ramadan—ditambah dengan puasa sunah enam hari setelah Idulfitri pada bulan Syawal. Banyak yang meyakini bahwa tradisi Kupatan ini berangkat dari upaya-upaya Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa—yang juga berdasar pada kebudayaan Jawa. Sebagaimana hal-hal lain dalam budaya Jawa yang penuh dengan simbolisasi dan makna filosofis, ketupat juga dianggap demikian.
Masyarakat Jawa percaya Sunan Kalijaga (Raden Said) sebagai sosok pertama yang memperkenalkan ketupat. Budayawan Zastrouw Al-Ngatawi mengatakan, tradisi Kupatan muncul pada era Wali Songo dengan memanfaatkan tradisi slametan (kenduri) yang sudah berkembang di kalangan masyarakat Jawa sebelum Islam. Tradisi ini kemudian dijadikan sarana untuk mengenalkan ajaran Islam mengenai cara bersyukur kepada Allah, bersedekah, dan bersilaturahmi di hari lebaran.

Ketupat pasar sebelum dimasak | Foto: tatkala.co/Jaswanto
Menurut H.J. de Graaf, ketupat merupakan simbol perayaan hari raya Islam pada masa pemerintahan Demak yang dipimpin Raden Patah awal abad ke-15. Graaf menduga bahwa kulit ketupat yang terbuat dari janur berfungsi untuk menunjukkan identitas budaya pesisiran yang ditumbuhi banyak pohon kelapa—walaupun banyak yang berpendapatan bahwa kata “janur” merupakan kependekan dari “jatining nur” (fitrah—suci). Warna kuning pada janur dimaknai de Graff sebagai upaya masyarakat pesisir Jawa untuk membedakan warna hijau dari Timur Tengah dan merah dari Asia Timur.
Lebih jauh, dalam beberapa sumber di internet, Kupatan merupakan akulturasi dari tradisi pemujaan Dewi Sri—dewi pertanian dan kesuburan, dewi pelindung kelahiran dan kehidupan, dewi kekayaan dan kemakmuran. Ia adalah Dewi tertinggi dan terpenting dalam teologi-mitologi masyarakat agraris. Ia dimuliakan sejak masa kerajaan kuno seperti Majapahit dan kerajaan lain di Sunda dan Bali.
Ada pula sumber lain yang berpendapat bahwa tradisi Kupatan di tanah Jawa sudah ada sejak zaman Hindu dan Budha yang diaplikasikan dalam bentuk sesajen. Islam melalui Wali Songo kemudian memodifikasinya—untuk tidak mengatakan merekonstruksikannya. Hal tersebut bertujuan agar arwah manusia yang meninggal dunia dalam masa bayi bisa tenang. Di dalam tradisi Jawa kuno, Kupatan sama dengan hari raya kecil atau hari raya untuk ritual arwah-arwah anak kecil.

Ketupat bawang sebelum dimasak | Foto: tatkala.co/Jaswanto
Menurut Clifford Geertz, Kupatan adalah tradisi slametan kecil yang dilaksanakan pada hari ketujuh bulan Syawal. Kata Geertz, dulu, hanya mereka yang memiliki anak kecil dan telah meninggal saja yang dianjurkan untuk mengadakan slametan ini. Menurutnya, tradisi ini umumnya banyak dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Abangan.
Geertz tidak salah. Di beberapa daerah di Jawa Timur, misalnya, hanya orang tua yang kehilangan anak saja yang melaksanakan Kupatan. Entah karena keguguran atau meninggal sewaktu masih bayi. Kalau tidak punya riwayat keguguran atau anak yang meninggal sewaktu bayi, tidak ada keharusan untuk Kupatan.
Menurut penuturan orang-orang dulu, Kupatan adalah momen spesial yang didedikasikan untuk anak-anak yang sudah meninggal. Semacam penghiburan dan wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya yang sudah meninggal supaya arwah anak-anak kecil ini bahagia dan tidak bersedih di alam sana. Sebab, mereka tidak bisa merasakan meriahnya Idulfitri sebagaimana teman-teman sebayanya yang masih hidup. Orang tua yang tidak menggelar Kupatan pada bulan Syawal dianggap sudah melupakan atau kurang memperhatikan anaknya yang telah meninggal.

Ketupat pasar dan bawang sebelum dimasak | Foto: tatkala.co/Jaswanto
Dalam bahasa Jawa, hari raya biasa disebut “bhada” atau “riyaya”. Kata bhada diambil dari bahasa Arab “ba’da” yang artinya sudah. Sedangkan riyaya berasal dari bahasa Indonesia yaitu “ria” yang berarti riang atau gembira. Adapun kupat (ketupat) dalam bahasa Jawa berasal dari kata “papat” atau “laku papat”—sesuai dengan bentuk ketupat yang punya empat sisi senagai simbol harapan di momen Idulfitri. Empat perilaku tersebut, yakni lebar (pintu maaf terbuka lebar), lebur (melebur dosa), labur (kembali menjadi pribadi yang suci bersih), dan luber (pengharapan agar rezekinya melimpah). Hal ini sejalan dengan semangat Idulfitri itu sendiri.
Selanjutnya, dalam bahasa Jawa, kupat juga diyakini kependekan dari “ngaku lepat” yang artinya mengakui kesalahan. Oleh karena itu, ketika hari raya ketupat, orang-orang Islam di Jawa—yang merayakannya—saling memberi dan berbagi ketupat sebagai simbol atas pengakuan dosa-kesalahan dan mengakui kekurangan diri masing-masing di hadapan Allah, keluarga, dan juga kepada sesama. [T]
Repoter/Penulis: Jaswanto
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:









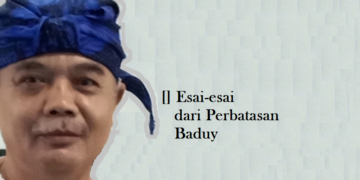













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










