DALAM dunia pendidikan, kemampuan berbicara bukan hanya tentang menyampaikan kata-kata, melainkan juga menyangkut kepercayaan diri, daya pikir kritis, dan keterampilan sosial. Siswa yang piawai berbicara cenderung tampil percaya diri di depan kelas, berani bertanya, serta mampu mempresentasikan gagasannya dengan jelas dan meyakinkan. Seperti yang diungkapkan oleh Tarigan (2008), kepercayaan diri ini tidak lahir secara instan, tetapi terbentuk melalui latihan konsisten dan lingkungan belajar yang mendukung.
Keterampilan berbicara juga melatih siswa berpikir secara logis dan kritis. Dalam diskusi atau presentasi contohnya, mau tidak mau para siswa dituntut untuk menyusun gagasan secara runtut, mengevaluasi informasi, dan merespons pendapat orang lain dengan argumen yang kuat. Kemampuan tersebut, menurut Lunsford dan Ruszkiewicz (2009), melibatkan proses berpikir yang mendalam dan reflektif. Lebih jauh lagi, jika kita berbicara dalam konteks sosial, sebagaimana dikemukakan Brown (2001), keterampilan berbicara rupanya menjadi sarana penting dalam menjalin relasi, menyampaikan empati, dan menavigasi dinamika komunikasi antarbudaya.
Berbekal ketiga pandangan utama tersebut –yakni kepercayaan diri, daya pikir kirtis, dan keterampilan sosial, saya mengajar materi pidato di SMA Asisi Jakarta dengan pendekatan yang tidak biasa. Pada tahun 2022, saya memperkenalkan kepada siswa kelas XI tiga gaya berpidato yang berbeda—formal, semi-formal, dan non-formal—melalui tiga tokoh yang sangat kontras: Kim Nam Joon dari BTS, Najwa Shihab, dan Sujiwo Tejo. Saya menayangkan video pidato ketiga toloh tersebut di kelas.
Mengapa saya perlu contoh? Mengapa saya merasa perlu memberi role model dengan menayangkan pidato ketiga tokoh di atas terlebih dahulu sebelum meminta para siswa siswa untuk berbicara di depan kelas dan membawakan pidatonya? Sebab saya rasa, mengajarkan pidato kepada siswa SMA tidak sesederhana meminta mereka maju ke depan kelas lalu berbicara. Sebab saya guru yang banyak mau, saya ingin para siswa saya tahu benar apa tujuan mereka berbicara, apa tujuan mereka berkomunikasi. Saya tidak ingin apa yang mereka sampaikan hanya angin lalu, tak berbobot, dan sia-sia. Saya ingin mereka benar-benar mengalami dan memahami kekuatan sebuah kata-kata (baca: pidato), baik dari sisi isi maupun gaya penyampaian.
Pilihan saya untuk memutar pidato Kim Nam Joon (RM BTS) di PBB —yang penuh percaya diri, terstruktur, dan mengangkat isu identitas serta mimpi– bukan hanya karena kekuatan pesannya, tetapi karena di tahun tersebut BTS tengah menjadi idola bagi mayoritas siswa saya.
Berikutnya, saya memilih menayangkan pidato Najwa Shihab yang berjudul Indonesia Butuh Anak Muda adalah karena gaya semi-formal Najwa yang tegas dan bernas saya nilai sangat tepat untuk memperkenalkan pentingnya berpikir kritis dan tanggung jawab sosial bagi remaja seusia para siswa saya.
Dan terakhir, saya putarkan potongan pidato Sujiwo Tejo di TEDx yang membahas tentang persamaan matematika dan bahasa agar para siswa saya tahu ada jenis pidato yang tidak resmi (non-formal) namun kuat dan mengena. Penyampaian Sujiwo Tejo yang blak-blakan, ngalor-ngidul, dan sesekali menyisipkan kata-kata seperti “jancok membuat situasi jadi di ruang kelas sesekali dipenuhi tawa para siswa.
Sujiwo Tejo Lebih Dipilih
Saat mempersiapkan materi tersebut, saya sempat mengira bahwa tokoh atau jenis pidato yang paling disukai oleh para siswa saya tentu Kim Nam Joon atau Najwa Shihab. Ya, di awal saya merasa gaya Sujiwo Tejo akan sulit dipahami siswa karena terlalu bebas dan tidk sistematis. Saya piker, cukuplah dengan Kim Nam Joon untuk menyampaikan tujuan yang ingin saya capai melalui pembelajaran pidato.
Tapi ternyata saya keliru.
Yang mengejutkan adalah hasil diskusi dan survei setelahnya. Dari keempat kelas yang saya ajar, mayoritas siswa justru paling menyukai gaya Sujiwo Tejo. Mereka mengatakan, “nggak ngebosenin, Pak,” atau “kayak ngobrol tapi dalem.” Bahkan ada yang mengutip ulang ucapannya saat diskusi santai. Mereka merasa gaya ini lebih “hidup” dan “nggak ngajar dari atas.”
Hal yang sama pun terjadi saat saya kembali mengajar di SMA Asisi Jakarta pada tahun 2024. Kali ini, saya mengajar kelas XII dengan materi yang serupa—yakni pidato—namun dalam kerangka kurikulum yang berbeda (dulu dengan Kurikulum 2013, sekarang saya menggunakan Kurikulum Merdeka). Ya, meski telah berselang dua tahun, gaya pidato Sujiwo Tejo rupanya masih menjadi favorit para siswa saya.
Saya merenung dan bertanya: Mengapa –meski telah berselang dua tahun dan telah mengalami pergantian kurikulum– gaya pidato Sujiwo Tejo yang cenderung tidak sistematis, penuh improvisasi, bahkan terkesan ngawur, justru begitu disukai?
Saat itulah saya teringat pada pemikiran Carl Rogers, seorang psikolog humanis, yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif tidak selalu tentang struktur atau logika yang kaku, tetapi tentang keaslian, empati, dan kehadiran penuh (Rogers, 1980). Dan itulah yang, menurut saya, dirasakan siswa dari gaya Sujiwo Tejo: ada kejujuran, ada kedekatan emosional, ada “jiwa” di balik setiap kata yang ia ucapkan.
Terlebih lagi, karena Kurikulum Merdeka yang ditetapkan di SMA Asisi saat ini memang lebih luas bagi siswa untuk berkespresi secara otentik dan membangun makna secara personal. Kurikulum ini tak lagi mengharuskan siswa meniru struktur formal semata, tetapi mendorong mereka untuk menemukan suara mereka sendiri.
Maka dari itu, bagi saya, Sujiwo Tejo bukan sekadar pilihan gaya pidato alternatif, melainkan representasi dari pendekatan pedagogi yang lebih manusiawi, reflektif dan inklusif—yang cocok untuk generasi hari ini, dan mungkin juga untuk generasi setelahnya.
Ironi di Balik Panggung Kelas
Namun, meski Sujiwo menonjol dan paling disukai sebagai contoh, ironi justru muncul saat siswa diminta membuat dan membawakan pidato mereka sendiri. Hampir seluruh siswa (baik siswa Kurikulum 2013 maupun siswa Kurikulum Merdeka) memilih meniru pola Najwa Shihab yang tersusun rapi, punya alur, dan “aman untuk dinilai.” Saya pun bertanya dalam hati: jika mereka lebih menyukai gaya Sujiwo Tejo, mengapa yang mereka tiru justru gaya Najwa Shihab?
Untuk memahami fenomena ini, saya mencoba mendekatinya lewat dua kerangka teori: retorika klasik Aristoteles dan teori modal budaya dari Pierre Bourdieu.
Dalam retorika klasik, Aristoteles menyebut bahwa kekuatan pidato bertumpu pada tiga unsur utama: ethos (kredibilitas pembicara), pathos (kemampuan membangkitkan emosi), dan logos (logika dan struktur argumen). Menariknya, Sujiwo Tejo—meskipun dikenal sebagai dalang nyentrik, penulis eksentrik, dan tokoh budaya yang sering bicara “seenaknya”—justru memiliki ethos yang kuat di masyarakat; termasuk pula di mata para siswa saya. Ia dipercaya bukan karena gelarnya, melainkan karena kejujurannya. Mereka merasakan kehadiran seorang manusia yang otentik, yang bicara dari hati dan bukan dari podium kekuasaan. Inilah ethos yang tidak dibangun dari otoritas, tetapi dari keberanian menjadi diri sendiri. Authenticity speaks louder than prestige.
Di sisi lain, Najwa Shihab, sebagai jurnalis kritis dan aktivis literasi, jelas memiliki ethos yang tinggi. Ia hadir dengan reputasi yang sudah mapan, dengan bahasa yang lugas namun tetap anggun. Bagi para siswa saya, Najwa dikenal sebagai serigaIa yang ditakuti oleh para politikus dan pejabat public.
Dari segi pathos, Sujiwo Tejo kembali unggul: ia mampu membuat siswa tertawa, berpikir, bahkan terhenyak. Ada tawa yang mengendap menjadi renungan. Sementara itu, Najwa memang membangkitkan emosi, tetapi dalam bentuk yang lebih tenang, reflektif, dan terkadang berjarak. Namun, segalanya berubah ketika siswa harus berbicara untuk “dinilai”. Di sini akhirnya logos mengambil alih. Dalam hal logos—struktur, urutan argumen, dan koherensi— para siswa saya merasa lebih aman mengikuti jejak Najwa. Pidato yang tersusun rapi, dengan pembukaan yang jelas, isi yang runtut, dan penutup yang mengikat, terasa lebih “masuk akal” dan lebih mudah diikuti, terutama di dalam kerangka ujian.
Modal Budaya: Menyesuaikan Diri di Ladang Sosial
Pertanyaan mengapa siswa menyukai gaya Sujiwo namun meniru Najwa juga saya temukan lewat teori Modal Budaya, Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, gaya, pengetahuan, dan kebiasaan yang dianggap “bernilai” akan berbeda tergantung ladang sosial tempat seseorang berada. Dan di dalam dunia pendidikan, lebih spesifik lagi di dalam ruang kelas, rupanya apa yang dinilai tinggi bukanlah sekadar keberanian atau kejujuran, tetapi keteraturan.
Di ruang kelas, gaya Najwa Shihab mewakili modal budaya yang sah secara institusional—tertata, sopan, bisa diukur. Sedangkan gaya Sujiwo, meski disukai, tak punya tempat di ruang penilaian formal. Kata-katanya yang “liar” atau strukturnya yang tidak sistematis dianggap melanggar norma akademik. Maka, ketika harus dinilai, siswa kembali ke bentuk yang diakui: struktur, alur, dan ketegasan. Mereka menyukai Sujiwo, tapi memilih Najwa karena menyadari sistem yang menilai mereka lebih menghargai keteraturan daripada spontanitas.
Di titik inilah pemikiran Pierre Bourdieu dalam The Forms of Capital menjadi sangat relevan. Bourdieu menyatakan bahwa sistem pendidikan modern cenderung mengafirmasi bentuk-bentuk modal budaya yang telah dibakukan. Hal-hal seperti kemampuan menyusun teks akademik, berbicara runut serta logis, atau menggunakan bahasa formal akan lebih dihargai lebih tinggi daripada spontanitas, improvisasi, atau keberanian menyampaikan hal-hal yang tak lazim.
Maka wajar bila kebanyakan para siswa, saat berpidato ada kecenderungan bukan untuk menyampaikan gagasan tetapi untuk dinilai. Unuk mempreoleh nilai. Mereka pun cenderung memilih jalur yang lebih aman. Mereka tahu bahwa keunikan gaya Sujiwo –meskipun menginspirasi, tidak akan mendapat skor tinggi di rubrik penilaian guru. Maka, meski pun hati mereka memilhak pada keberanian Sujiwo Tejo, namun pilihan teknis mereka tetap jatuh pada ketelitian Najwa Shihab. Di sinilah letak ironi tersebut: keberanian mungkin disukai, tetapi keteraturanlah yang dihadiahi.
Menjembatani Dua Dunia: Gaya dan Rasa Milik
Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa mengajar pidato bukan sekadar mengajarkan teknik berbicara, tetapi juga membantu siswa merasa memiliki suara mereka sendiri. Mereka mungkin menyukai gaya Sujiwo, namun belum tentu merasa cukup percaya diri untuk menirunya. Saya sadar bahwa sistem pendidikan dan penilaian formal masih beroperasi dalam keangka struktur dan standar tertentu. Rubrik penilaian pidato yang digunakan, betapapun saya mencoba melonggarkannya, tetap akan memuat aspek-aspek seperti struktur yang logis, keteraturan bahasa, dan kesesuaian isi.
Inilah dilema pedagogis yang saya hadapi: bagaimana mendorong keberanian berekspresi tanpa membuat siswa merasa “berisiko” karena keluar dari pakem? Bagaimana menceptakan ruang kelas yang tidak hanya menilai keterampilan formal, tetapi juga mengapresiasi keberanian untuk menjadi diri sendiri? Maka tugas saya –atau mungkin kita semua sebagai guru– adalah menciptakan ruang aman bagi mereka –para siswa– untuk mencoba, bermain, dan mengekspresikan diri tanpa takut salah.
Pengalaman ini membuat saya terus bertanya ulang: bagaimana menciptakan ruang kelas yang lebih membebaskan? Saya berharap para siswa saya bukan hanya bisa membuat pidato yang “baik,” tapi juga mampu berbicara dengan jujur, dengan gaya mereka sendiri. Saya terus mengulang pertanyaan: Bagaimanakah mendesain pembelajaran pidato yang tidak hanya mengajarkan teknik, tapi juga membangkitkan keberanian dan kejujuran? Dan yang terpenting, bagaimana mengapresiasi keberagaman gaya dalam berbicara, tanpa terjebak dalam satu standar tunggal yang mengabaikan jiwa di balik kata?
Sujiwo Tejo mengajarkan saya bahwa kadang, kekuatan pidato tidak terletak pada keteraturannya, tapi pada keberaniannya untuk mengganggu keteraturan itu sendiri. Dan mungkin, itulah pelajaran paling penting yang bisa saya bawa ke ruang kelas. Sebab pidato yang mengena tidak selalu yang paling rapi atau runut, tetapi yang paling jujur dan berani.
Jakarta, 12 April 2024.
Referensi
- Bourdieu, Pierre. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). Greenwood.
- Brown, H. Douglas. (2001).Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New York: Longman.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan Pembelajaran dan Asesmen: Sekolah Menengah Atas. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/
- Keraf, Gorys. (1980).Komposisi. Ende: Nusa Indah.
- Lunsford, Andrea A., & Ruszkiewicz, John J. (2009).Everything’s an Argument. Bedford/St. Martin’s.
- Rogers, C. R. (1980). A way of being. Houghton Mifflin.
- Tarigan, Henry Guntur. (2008). Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa.
Penulis: Stebby Julionatan
Editor: Adnyana Ole







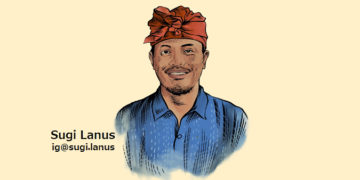













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











