“Ketika puputan selesai, penelitian dilakukan pada [jenazah] orang-orang yang gugur. Maka di antara korban terdapat putra raja yang berusia dua belas tahun, adalah satu-satu[nya] (putra mahkota pewaris tahta). Ia tergeletak di tengah-tengah (serakan mayat) dan sejumlah banyak wanita-wanita. Apakah ia ingin memperlihatkan bahwa adat Bali yang suci dan luhur lebih tinggi dari kehidupan?”
Itulah petikan catatan Soerabalasch Handelsblad sebagai himpunan informasi pascaperang Puputan Klungkung yang ditulis oleh Belanda. Mengalahkan Kerajaan Badung melalui perang berdarah pada tanggal 20 September 1906, ternyata belum sepenuhnya membuat hasrat menjajah dan menjarah pemerintah Kolonial Belanda puas. Sebab, satu kerajaan lagi yang dihormati sebagai sasuhunan raja-raja lain di Bali yakni Klungkung tak mau tunduk. Meski berbagai perjanjian dagang telah diatur dan adat masatya telah dilarang di daerah ini, Raja Klungkung tampaknya bukan tipe yang kompromis untuk dikendalikan oleh Belanda.
Lantas kalau Kerajaan Klungkung tak mau tunduk, cara apa yang dapat dilakukan untuk membuat sang raja bertekuk lutut?
Di siniah persoalannya. Apabila kita mencermati Kidung Bwāna Winaṣa karya rakawi Ida Padanda Ngurah dari Gria Gde Belayu, alasan bertempur dengan Kerajaan Klungkung ini terkesan kurang diperhitungkan dengan matang oleh pihak Belanda. Apabila dibandingkan dengan penyerangan terhadap Kerajaan Badung, pemerintah Kolonial Belanda tampak memainkan strategi yang lebih rapi. Pertama-tama, mereka mengirim kapal dagang Sri Komala untuk berlabuh di Sanur, lalu menuduh masyarakat setempat merampok isinya. Dari peristiwa ini Belanda menuntut Raja Denpasar untuk membayar ganti rugi sebesar 3600-ringgit sebagai sanksi atas pelanggaran hukum tawan karang.
Tentu Raja Denpasar sesungguhnya sangat mampu membayar tuntutan itu. Akan tetapi, persoalannya tidak terletak pada jumlah materi, melainkan martabat dan harga diri seorang ksatria. Akibat menolak sanksi sepihak tanpa melalui proses peradilan ini, Kerajaan Badung akhirnya diserang Belanda dan berakhir dalam tragi yang dikenang dalam kening masyarakat sebagai puputan.
Peristiwa Puputan Badung yang merenggut ribuan korban jiwa ternyata tak menyebabkan nyala dari nyali Kerajaan Klunglung meredup. Mungkin dalam bayangan Belanda, Raja Klungkung akan gentar melihat betapa sebelumnya lautan darah dan gunung mayat memenuhi alun-alun Kerajaan Denpasar. Usaha teror untuk menyerang psikologis rakyat Klunglung sebelum menyerang fisik mereka secara langsung melalui perang gerilya tampak sia-sia.
Dengan alasan yang sangat sepele, yaitu terbakarnya Gudang Candu (opium) berikut mantrinya yang diduga diprovokasi dan dimotori masyarakat Klungkung, serdadu Belanda datang tanpa kata-kata, tetapi senjata! Mereka merangssek masuk ke dalam istana Klungkung melalui Pelabuhan Kusamba. Meriam, bedil, dan granat yang sebelumnya telah memakan ribuan nyawa di Badung digunakan lagi untuk meremukkan lebih banyak tulang-belulang manusia.

Foto Ida I Dewa Agung Jambe, Raja Klungkung dan Putranya I Dewa Agung Gede Agung yang Gugur dalam Puputan Klungkung | Foto diambil dari Tempo.co
Meski demikian, Raja Klungkung yang saat itu dipimpin oleh Ida I Dewa Agung Jambe menyambut kedatangan Belanda dengan cara yang ksatria. Bahkan, putra mahkota yang masih sangat belia karena baru berumur 12 tahun turun langsung ke medan laga. Para ksatria yang lainnya juga mengangkat berbagai senjata pusaka. Keris, tombak, dan meriam kanon bernama I Bangke Bahi yang sebelumnya telah ditiupi mantra juga telah dipersiapkan. Maka di depan istana yang sehari-hari ditujukan untuk pentas berbagai kesenian itu, senjata Bali vs Barat bertubrukan mengadu tuahnya.

Perhiasan Kalung Ida I Dewa Agung Gede Agung, Putra Mahkota yang Gugur dalam Puputan Klungkung Sempat Dijarah Belanda Kini Dikembalikan ke Museum Nasional | Foto: Museum Nasional Republik Indonesia
Di antara riuh perang Puputan Klungkung yang bergejolak dari medio hingga berpuncak pada 28 April 1908 itu, Ida Padanda Ngurah-rakawi Kidung Bwāna Winaṣa mencatat pijar keberanian para perempuan yang ternyata tidak tinggal diam menghadapi perang. Mereka yang kerap distigmakan hanya menghuni ruang seperti sumur, dapur, dan tempat tidur ternyata tak bergeming untuk turun ke medan tempur.
Tentu ini bukan kali pertama terjadi di bumi Klungkung. Ida I Dewa Agung Istri Kanya sebagai raja perempuan yang pernah bertahta di Smarapura itu juga pernah melawan Belanda dalam pertempuran di Kusamba sebelumnya. Spiritnya seolah memberi teladan untuk menggerakkan batin dan badan para puan sehingga tak ragu menyerang. Terlebih, Jendral Michelle yang terkenal kejam berhasil ditaklukkannya dalam kecamuk di tepi laut Kusamba.
Maka dengan sangat mengharukan, Kidung Bwāna Winaṣa yang juga berjudul Bali Sanghara ini mencatat peran perempuan yang gugur sebagai kusuma bangsa.
Sagrehan para wadu sigra lumampah, prasama telas wisianti, keneng brahmasara, dewagung ndah tan kabranan, sigra tikel dening mimis, sama wus pejah, para istri ndah tan kari. (Kidung Bwanā Winaṣā, Pupuh Durma, bait 19)
Terjemahan.
Para wanita serempak menyerang, [tetapi] semuanya habis terbunuh, terkena tembakan peluru, saat itu Dewa Agung [Jambe] tidak terluka, [namun] dengan cepat terkena tembakan beruntun, sehingga akhirnya bersama-sama gugur, para perempuan tidak satu pun yang masih hidup.
Dari petikan Kidung Bwana Winasa di atas, kita bisa melihat bara semangat para perempuan untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan Klungkung atas intervensi Kolonial Belanda. Turunnya para perempuan di Perang Puputan Klunglung ini tidak saja menepis isu gender yang tidak membumi di Bali (gender equality). Tetapi melampaui semua itu, perempuan yang turun ke medan perang dapat dibaca sebagai puncak perlawanan habis-habisan Bali vs. Belanda. Sebab sesungguhnya kaum perempuan, anak-anak, dan seseorang yang tak memegang senjata pantang diserang dalam etika perang ‘dharma yuddha‘.
Apabila mereka sampai turun dalam Perang Puputan Klungkung, artinya ada tanah-air kelahiran yang harus dibela dengan tumpah darah. Mereka tak perlu memohon anugerah Yaksa seperti Srikandi untuk mengubah jenis kelamin sehingga dapat berperang melawan Bhisma ketika perang Bharata Yuddha terjadi. Dalam ayunan langkah mereka yang menapak aroma anyir sisa darah dan serakan mayat, Durga Mahisa Sura Mardini tidak hanya hadir dalam cerita, tetapi dalam kehidupan yang nyata.
Meski akhirnya kemenangan ada di pihak Belanda, para perempuan Klungkung yang turun ke medan tempur itu telah menghaturkan persembahannya yang paling utama. Luka dan lebam raga yang menghijau adalah rekah daun sebagai alas sesaji (patraṃ). Darah yang mereka pertaruhkan adalah salaksa tirta dari mata air dan sungai terpilih Negeri Bharata Warsa (toyaṃ). Hembus nafas mereka adalah aroma dupa yang dinyalakan dari homa keberanian (dupaṃ). Tubuh mereka yang berbusana serba putih adalah mekar bunga yang tak pernah layu (puṣpaṃ).
Itulah persembahan perempuan Bali di tengah kecamuk perang Puputan Klungkung. Mereka yang saban hari terampil membuat sesaji kepada para dewata, tak disangka di penghujung perang juga berani menyerahkan jiwa dan nyawa. Kepada para puan yang tak tercatat sebagai pahlawan, tetapi menghaturkan satu-satunya miliknya, yaitu ‘nafas’, penulis menundukkan kepala. [T]
Paris, 27 April 2025
Penulis: Putu Eka Guna Yasa
Editor: Adnyana Ole
- BACA artikel lain dari penulisPUTU EKA GUNA YASA









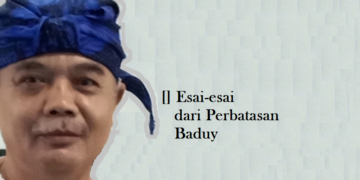













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)










