WAKTU sebagai suatu yang berjalan lurus adalah sebuah pandangan yang kiranya perlu untuk digugat terus. Cara melihat waktu serupa ini tentu berguna untuk membagi-baginya – memberinya label detik, menit, dan jam. Sederhananya untuk bisa mengendalikan.
Keinginan untuk mengendalikan, yang khas cara melihat setiap hal dalam logika modern, perlu dibaca ulang. Menempatkan kembali diri kita, manusia, bukan sebagai pusat dari segalanya menurut saya bijak untuk dilakukan. Bagaimana jadinya jika waktu tidak berjalan lurus? Bagaimana jika waktu itu terlipat dan yang kita anggap sebagai yang sekarang maupun yang dulu ada dalam satu tempat? Barangkali kita jadi terheran-heran, barangkali juga, kita bisa menyingkap hal-hal baru yang tidak kita sadari sebelumnya.
Pada sebuah pameran yang diadakan pada tahun 1981, bertajuk Westkunst, Zeitegnossische Kunst seit 1939 (Seni Barat, Seni Kontemporer sejak 1939), ditampilkan karya-karya seni Barat yang dianggap paling mewakili zamannya. Tiap periode dibagi-bagi dan dibuatkan ruang sendiri. Pengunjung museum pun datang dan seakan diajak menyusuri sejarah seni yang berprogres, yang maju, yang terus berkembang secara formal.[1] Pendekatan kuratorial yang menampilkan seni sebagai suatu progres historis formal merupakan bentuk sikap mereka yang melihat bahwa seni Avant Garde setelah perang dunia kedua kehilangan semangat beserta daya pembebasannya, seni Avant Garde kemudian menjadi “seni museum“.[2] Sungguhpun sekadar seni museum orang-orang Westkunst tetap percaya ada yang abadi pada kualitas intrinsik sang karya maupun seniman.

Salah satu karya dalam pameran “Resonansi Waktu” di Museum Sonobudoyo Yogyakarta
Melangkah jauh, pada tanggal 25 April 2025, digelar sebuah pameran yang berbeda sekali pendekatannya dengan Westkunst, bertajuk Resonansi Waktu di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Menampilkan 48 karya dari 31 seniman pameran ini dikuratori oleh Dianna Raa‘difah. Utamanya, pameran ini berupaya untuk menampilkan karya-karya seniman muda dan tua. Pameran ini, meski dengan panel-panel yang serupa lorong seperti pada Westkunst, akan tetapi tidak berupaya menampilkan karya dalam sebuah liniearitas dan progres. Alih-alih pameran dirancang sebagai sebuah ruang terlipat dimana seniman muda dan tua menubuh dengan narasi pameran. Sang kurator tampaknya percaya pada yang formal dalam sebuah karya terdapat pula kandungan yang historis, dengan kesan dan rasanya sendiri yang sangat terkait dengan seniman beserta lingkunganya.
Karya-karya lintas generasi dari seniman semacam Widayat dan Nasirun hingga Flea Aura dan Andika Namaste marak meriah dalam pameran ini.
Pada salah sebuah instalasi karya Widayat, berjudul Topeng Primitif (1999) tampak sebuah dua potong kayu yang digambari dengan tinta membentuk semacam topeng tribal yang kasar dan asing tetapi matang. Dunia pada karya Widayat merupakan sebuah dunia yang luwes dan arkais. Simbol-simbolnya signifikan dan ramai. Kadang juga terasa mistis. Gaya dekoratif tribal serupa dapat ditemukan pula pada karya Widayat lain yang diapamerkan disini berjudul Sedang Mancing Kebelet Kencing. Karya ini bermedium kanvas dengan hasil cukilan kayu, menampilkan figur seorang seperti berdiri kencing dengan latar dekorasi ikan dan air.

Pengunjung menikmati pameran “Resonansi Waktu” di Museum Sonobudoyo Yogyakarta
Dunia lain tampak pada sebuah karya lain yang teramat menarik hati dari seorang seniman muda. Sebuah lukisan oleh Flea Aura yang berjudul When Time are Spirals, Nothing is Linear Anymore: Spiraling Through What Was Never Ends (2025) yang didominasi warna merah dan figure tengkorak serta mahluk seperti buaya. Lukisan ini mengesankan objek-objek yang terbakar dengan api sebagai sebuah simbol emosi dan kekerasan waktu. Waktu maka menjadi sebagai suatu yang mampu membakar dengan ingatan dan harapan sekarang maupun masa lalu.
Pameran ini membawa pengunjungnya untuk berjalan terus dalam dialog dan komunikasi lintas generasi ini. Ruang ke ruang meriah dengan dialog karya-karya yang menempatinya.
Di ruang yang paling tengah – dan yang paling besar, dalam alur pameran terdapat sebuah intalasi kain yang begitu megahnya. Sebuah bendera digantung dari Kolektif Jalan Gelap yang berjudul Limbicium Seiklus (2024) berukuran 3 x 3 meter. Karya ini secara cermat membawa ilmu pengetahuan neurologi mengenai kebahagiaan dan menjelaskan proses otak dalam penciptaan rasa bahagia dan tautan trauma dan kebahagian dibentuk dengan grafik-grafik khas mereka. Mereka tidak takut kelihatan memesinkan kerja emosional manusia dengan menghadirkan ilmu neurologi melainkan melalui karya mereka, kerja emosi manusia malahan terlihat begitu dalamnya. Tidak dapat dipungkiri, ilmu neurologi adalah sebagian dari beberapa cabang ilmu yang berkembangnya amat pesat di masa sekarang. Bagi saya, maka, respon mereka terhadap ilmu pengetahuan bukan saja menunjukkan kedalaman sang seniman, melainkan juga merupakan sebuah tanda; seniman sebagi produk zaman yang mana.
Mengutip dari teks kuratorial, sang kurator berupaya membangun semacam jembatan yang ia harapkan bekerja secara harmonis. Oleh sebab itu, ruang karya-karya berada tidak diusahakan untuk terlihat kontras antar generasinya.
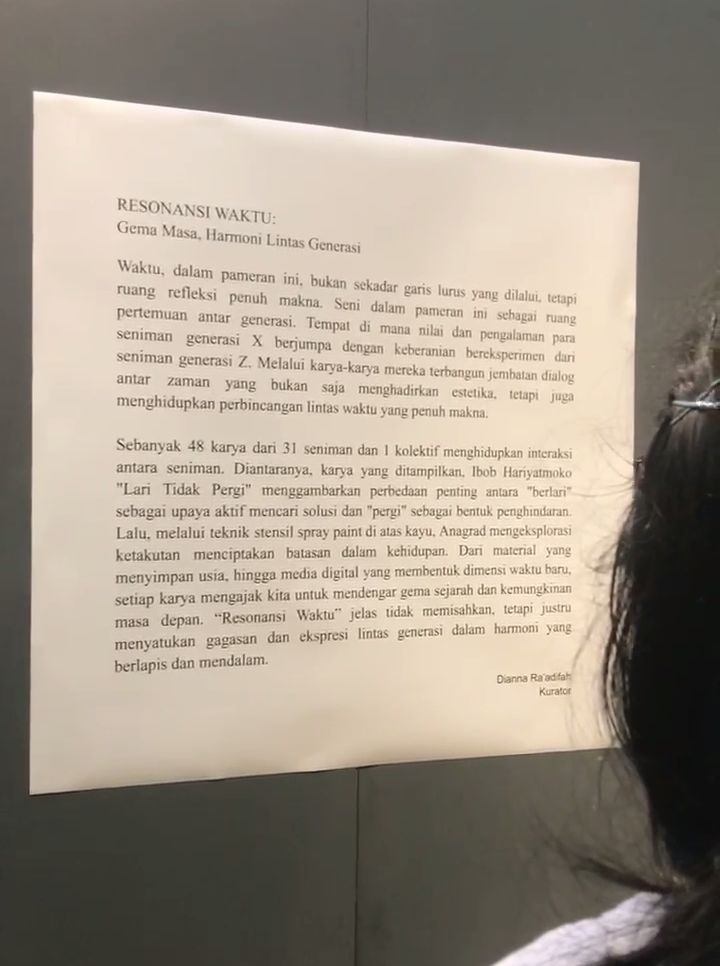
Pengunjung membaca teks pameran “Resonansi Waktu” di Museum Sonobudoyo Yogyakarta
Saya memuji upaya kurator yang saya rasa telah mengonsepsi waktu sebagai suatu yang luwes dan cair, konsep waktu yang amat kiwari.
Sebab seperti yang saya lihat disini, karya-karya berkomunikasi bukan untuk saling setuju dan saling memberi pengetahuan satu sama lain. Karya-karya dalam ruang yang tidak beraturan kronologisnya, yang terlipat keterkaitan waktunya, justru menunjukkan sebuah khaos yang meletup-letupkan sebuah penawaran baru. Pameran ini bagi saya telah berhasil dalam menggerakkan hati dan membuat tersenyum senang dalam menciptakan dialog berisik antar seniman. Sahut-sahutan yang dari awal hingga akhirnya membangun antusiasme kepada siapa saja yang melaluinya, dengan begitu dialog ini harmonis dengan caranya sendiri. [T]
[1] Poinsot, J. M. (1996). Large exhibitions: a sketch of a typology. In Thinking about exhibitions.
[2]Calvocoressi, R. (1981). Cologne: Westkunst. The Burlington Magazine, 123(943), 634–638. http://www.jstor.org/stable/880388
Penulis: Sectio Agung
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:





























