BEBERAPA hari lalu, saya menemukan mahasiswa menyanyikan lagu-lagu tahun 90-an yang kata mereka lebih enak didengar, daripada lagu-lagu sekarang. Bahkan anak saya yang duduk di kelas 8 alias kelas 2 SMP juga memutar lagu -lagu dari Queen, Frank Sinatra, dan malah hafal juga liriknya. Setelah itu playlistnya beralih ke rapnya 50 Cent, dan ke Dimash Kudaibergen yang beraliran crossover klasik.
Saya jadi merenung, generasi Z dan gen Alpha masih saja menyanyikan lagu legedaris yang lahir dari era saya belum lahir. Terbersit pemikiran apa jadinya manusia, kalau hidupnya cuma makan nasi, lauk, dan sayur, dengan variasi rasa dan plating ala sekarang yang canggih, tapi tidak pernah “makan lagu”? Pertanyaan yang mungkin aneh, tetapi mungkin jika dicari jawabannya dapat membuat kita memiliki cara pandang baru soal musik.
Lagu dan Resonansi Jiwa
Musik, dalam sejarah umat manusia bukan sekadar bunyi-bunyian pengisi waktu senggang. Justru bisa jadi musik adalah salah satu teknologi paling purba yang diciptakan manusia untuk satu tujuan utama dan sederhana yaitu bertahan hidup secara mental. Dan mengapa sampai ada lagu-lagu legendaris yang bertahan hingga saat ini? Sepertinya mereka adalah salah satu bukti paling keras bahwa manusia tidak cuma butuh makan nasi dengan gizi seimbang tapi juga butuh “makan lagu”.
Jika dikira-kira, mungkin begini cara kerjanya: tubuh butuh gizi, jiwa butuh resonansi. Resonansi itu menurut buku IPA Fisika didefinisikan sebagai peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar. Nah, syaratnya frekuensi kedua benda ini harus sama.
Lagu-lagu legendaris, dari masa ke masa, bertahan memang karena melodinya enak atau liriknya puitis. Tapi pasti bukan semata-mata karena itu. Lagu-lagu itu bertahan, karena membawa frekuensi rasa tertentu yang dibutuhkan orang-orang di zamannya, dan seringkali berlanjut serta tetap relevan di zaman setelahnya.
Lagu bukan cuma datang, lewat, dinikmati, dan pergi. Lagu itu merasuk ke dalam diri, menjadi bagian dari narasi hidup manusia, bagian dari identitas dan gerak jiwa, suatu rasa yang setiap saat bisa dikunjungi kembali dan menimbulkan kenyamanan tertentu. Maka janganlah kita heran kalau dalam masyarakat, kita bisa menemukan lagu-lagu yang jadi staple food mental kita. Sebut saja lagu-lagu Didi Kempot untuk patah hati massal, atau Deny Caknan yang bertutur tentang kesederhanaan dan cinta, lagu-lagu Rhoma Irama untuk keresahan sosial, lagu-lagu kepunyaannya Hindia untuk generasi galau urban modern, dan seterusnya.
Ini semacam logika survival: manusia butuh soundtrack untuk bertahan. Jiwa butuh makanan, dan lagu adalah salah satu sumber pangannya. Ada orang yang bertahan di kerasnya hidup kota karena ditemani lagu Iwan Fals. Ada yang melewati patah hati pertamanya dengan Adele. Ada yang menjaga harapan hidupnya di lorong sempit hidup miskin sambil memutar Don’t Stop Believin’. Ini bukan kebetulan. Ini kerja kultural.
Jadi memang setiap zaman selalu menciptakan lagu-lagu bertahan hidup-nya sendiri. Kadang berupa lagu perjuangan politik. Kadang berupa lagu patah hati. Kadang berupa lagu-lagu pemberontakan. Kadang berupa lagu anak muda yang tidak mau menyerah kalah di tengah dunia yang makin absurd. Bisa kita bayangkan sejarah panjang manusia tanpa lagu-lagu itu. Mungkin revolusi-revolusi besar dunia akan terasa lebih sunyi tanpa mars. Mungkin patah hati akan terasa lebih mengenaskan. Mungkin kesedihan akan terasa lebih sepi dan menyakitkan. Dan mungkin juga, jangan-jangan, manusia sudah lama menyerah pada hidup kalau tidak pernah menemukan lagu-lagu itu. Dan populasi planet ini jadi tidak sebanyak sekarang.
Setiap Zaman Menciptakan Lagunya Sendiri
Lagu-lagu legendaris itu, kalau boleh kita sepakati, bekerja lebih dalam daripada sekadar “soundtrack” kehidupan. Mereka lahir karena ada kegelisahan. Ada luka sosial. Ada keresahan yang mendesak untuk disuarakan. Dan hebatnya, manusia tanpa perlu kursus teori musik, secara alami tahu saja lagu mana yang “bergizi” buat jiwanya di momen tertentu. Ini sejalan dengan gagasan Tia DeNora (2000) dalam bukunya Music in Everyday Life. DeNora bilang bahwa musik itu bukan cuma latar belakang hidup manusia, tapi agen aktif yang membentuk pengalaman, emosi, bahkan identitas kita sehari-hari. Lebih dalam lagi, musik itu alat kerja kehidupan.
Mereka adalah obat perasaan. Mereka adalah tempat persembunyian emosional. Mereka adalah bahan bakar jiwa untuk bisa bertahan sehari lagi, seminggu lagi, setahun lagi, dan entah berapa waktu lagi di dunia ini, yang kadang terasa terlalu keras untuk ditelan mentah-mentah. Itulah sebabnya banyak lagu legendaris justru lahir dari penderitaan sosial. Musik blues lahir dari derita orang kulit hitam di Amerika. Lagu-lagu perjuangan Indonesia lahir dari rakyat yang muak dijajah. Lagu-lagu punk lahir dari kemarahan anak-anak muda kelas pekerja. Bahkan musik dangdut pun, dalam sejarah awalnya, adalah suara minor dari pinggiran kota.
Nah, apakah kita masih merawat tradisi “makan lagu” ini? Atau jangan-jangan generasi kita hari ini malah mulai kehilangan kemampuan dasar ini, suatu kemampuan menikmati musik sebagai nutrisi jiwa. Mengingat dan melihat kenyataan bahwa semua musik kita hari ini terlalu dieksploitasi jadi komoditas, jadi iklan, jadi noise, bahkan jadi sekadar pemantik algoritma agar bisa viral di TikTok. Ini mungkin soal yang patut kita renungkan bersama. Karena manusia modern memang semakin kaya teknologi, semakin canggih gadget, tetapi anehnya juga semakin rapuh mental.
Jangan-jangan karena di tengah semua kemajuan itu, kita lupa caranya mendengarkan dengan benar. Bukan sekadar mendengar, lho ya, tapi mendengarkan. Benar-benar membuka ruang di dalam diri untuk rela beresonansi bersama getaran rasa yang dibawa musik. Menyediakan waktu. Menyediakan keheningan. Menyediakan telinga yang jujur dan hati yang mau disapa. Agak puitis, tapi hanya itu cara yang pas untuk mengungkapkan maksud ini.
Mungkin itulah sebabnya lagu-lagu legendaris tetap bertahan. Mereka adalah warisan kultural yang bukan cuma enak didengar, tapi juga menyediakan ruang aman untuk jiwa manusia istirahat sebentar dari kerasnya hidup. Lagu-lagu itu tidak mati karena fungsi dasarnya masih bekerja, yaitu menjaga manusia tetap waras. Dan pada akhirnya, manusia memang tidak bisa hidup dari roti saja. Atau nasi saja. Atau bahkan gaji saja. Karena di sela-sela semua itu, kita butuh makan lagu.
Musik, Memori, dan Penyembuhan
Oliver Sacks (2007) dalam Musicophilia: Tales of Music and the Brain bahkan menyebut musik sebagai jalan pintas menuju ingatan dan perasaan yang paling dalam. Para pembaca yang budiman pasti pernah merasakan, bagaimana lagu bisa membawa kita pulang ke masa lalu dalam hitungan detik lebih cepat dari foto, lebih kuat dari kata-kata. Sungguh luar biasa, bukan?
Makanya, dalam terapi penderita Alzheimer, musik sering dipakai untuk memancing memori yang terkunci. Lagu bisa membangunkan bagian diri yang sudah nyaris hilang. Psikologi modern sebenarnya sudah lama paham soal ini. Ada music therapy, ada sound healing, ada riset tentang pengaruh musik terhadap stres, kecemasan, bahkan daya tahan tubuh. Karena bisa jadi, sebagaimana tubuh kita butuh gizi seimbang, jiwa kita juga butuh playlist yang sehat. Bukan sekadar musik yang viral, bukan sekadar lagu yang ramai di TikTok saja, tapi lagu-lagu apapun, yang betul-betul bisa memberi ruang bagi jiwa kita untuk berteriak, mungkin mengumpat, mengeluh, merengek, bernapas dalam, merenung, atau bahkan sekadar diam dalam damai. Dalam damai maksud saya tentu bukan Rest in Peace.
Lebih jauh lagi, riset-riset psikologi modern juga menunjukkan bahwa musik memang punya efek terapeutik yang serius. Penelitian dari Thoma et al. (2013) misalnya, menemukan bahwa mendengarkan musik tertentu bisa menurunkan kadar hormon stres (kortisol) dalam tubuh. Ini bukan cuma soal feeling, tapi kerja biologis nyata.
Jadi, kalau ada orang bilang: “Aku tuh kalau galau, cuma bisa sembuh kalau dengerin lagu ini,” itu bukan lebay. Itu justru memiliki penjelasan yang sangat ilmiah. Tapi kita jarang memikirkan fungsi ini secara serius. Karena musik sering dianggap remeh sebagai sekadar hiburan, sekadar noise. Padahal mungkin justru sebaliknya, karena kesehatan mental kolektif sebuah masyarakat bisa dilihat dari bagaimana mereka memperlakukan musik.
Apakah kini makin banyak lagu-lagu dangkal? Apakah makin sedikit ruang di hati untuk mendengar musik secara dalam? Apakah makin banyak orang cemas, mudah marah, gampang meledak-ledak? Mungkin itu bukan cuma soal ekonomi atau politik hari kini yang makin tak tentu arah. Mungkin karena jiwa-jiwa itu sedang butuh nutrisi agar waras. Jadi jika ada lagu yang dibungkam, sepertinya memang ada yang tidak menginginkan kewarasan. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI







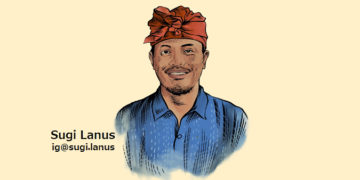













![Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam](https://tatkala.co/wp-content/uploads/2025/01/chusmeru.-cover-cerita-misteri-120x86.jpg)











