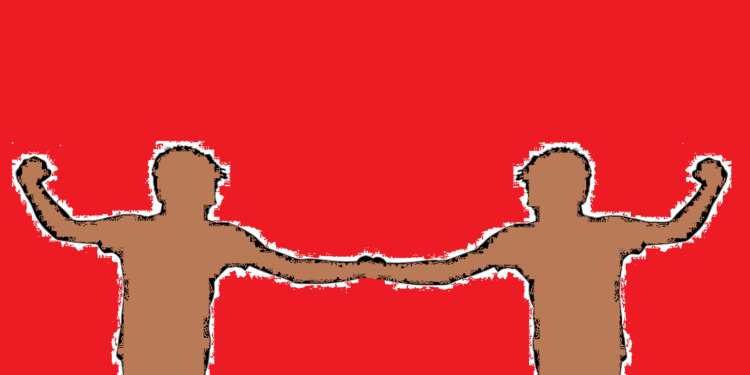BEREDAR kembali video viral mengenai pemukulan mahasiswa di salah satu toko 24 jam di Denpasar. Pemukulan ini dilakukan oleh sekelompok pemuda yang dalam video tampak datang dengan tingkah jagoan. Tanpa baju. Tanpa basa-basi, memukul pemuda yang sedang nongkrong di depan toko. Bahkan salah satu pelaku pemukulan tersebut nampak membawa sebuah senjata tajam. Ngeri. Menyaksikan video tersebut yang kebetulan lewat di linimasa media sosial saya, ada perasaan sangat miris di benak saya sebagai seorang pendidik.
Mereka, para pelaku pemukulan tersebut adalah sekelompok pemuda yang sepertinya masih belum jauh dari usia sekolah. Atau, jangan-jangan mereka semua masih berstatus pelajar? Bagaimana seorang yang terdidik bisa berperilaku seperti itu? Bagaimana mereka melewati masa-masa sekolahnya? Tidakkah mereka mendapat pendidikan karakter di bangku sekolah? Atau, inilah bukti bahwa pendidikan karakter yang digaungkan pemerintah kita gagal total? Atau kamilah, para pendidik yang telah gagal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat saya mencoba berpikir reflektif. Jangan-jangan mereka adalah korban dari kegagalan kami selaku pendidik? Mereka adalah korban. Mereka adalah produk pembentukan disiplin kami yang mengarah pada identitas gagal. Kamilah yang membentuk mereka menjadi orang-orang gagal.
Dalam pembentukan disiplin, Diane Gossen dalam bukunya Restitution-Restructuring School Discipline (1998) menyebutkan bahwa guru sujatinya memiliki lima posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini akan mengacu pada pembentukan identitas gagal pada murid.
Saat murid dihukum, dibentak, atau diancam oleh guru, murid akan menjadi pendendam atau berperilaku agresif. Sebaliknya, saat guru hadir dengan nada halus namun dengan tujuan membuat rasa bersalah, murid akan menjadi individu yang merasa dirinya gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang hal ini bisa lebih berbahaya dibanding murid yang dihukum, karena murid tertekan tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain.
Posisi kontrol teman dan pemantau dapat mengarah pada identitas berhasil, namun masih pada tataran kontrol positif oleh guru. Melalui kontrol seperti ini, murid akan menjadi pribadi yang disiplin namun tidak secara mandiri. Tidak memiliki disiplin diri. Ia akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin hanya untuk menjaga hubungan dengan guru, atau hanya jika diawasi. Disiplin semacam ini tidak akan bertahan lama dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Idealnya, guru dapat menciptakan identitas berhasil dengan penumbuhan kontrol diri pada murid, melalui posisi kontrol guru sebagai manajer. Dalam menjalankan posisi kontrol manajer ini, guru lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berusaha menguatkan watak atau karakter, sehingga murid akan mengevaluasi diri untuk menemukan cara menjadi diri yang lebih baik. Guru tidak hadir sebagai penghukum, tidak juga sebagai pemantau. Namun, saat murid melakukan kesalahan, guru akan berusaha membantu murid untuk menemukan solusi akan kesalahannya, dan menemukan pembelajaran dari kesalahan tersebut.
Hal ideal ini memang terdengar sangat sulit untuk dilakukan. Dalam menjalankan peran kontrol manajer ini, kita diperkenalkan dengan istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat.
Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan, bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang.
Secara lebih teknis, pelaksanaan restitusi oleh guru dilakukan melalui tiga tahapan yang disebut dengan segi tiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui tiga tahapan inilah murid diharapkan menemukan jawaban atas kesalahannya, tanpa membuat ia merasa menjadi individu yang gagal. Murid belajar bertanggung jawab, dan siap kembali pada kelompoknya tanpa mencederai harga dirinya.
Sepertinya konsep restitusi ini masih awam di telinga kita. Kami, para guru, para pendidik masih belum banyak memahami tentang restitusi ini. Bahkan, saat tau akan konsepnya, mungkin sebagian besar akan apatis, apakah hal ini bisa diterapkan di hadapan murid-murid kami? Selama ini para guru sudah sangat terbiasa dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Saat menemukan murid yang melanggar aturan, guru akan dengan semangat menghukum dengan dalih untuk membiasakan mereka menaati peraturan.
Mungkin semenjak kehadiran seorang senator yang suka menghukum para guru penghukum, guru mulai beranjak ke posisi kontrol pembuat rasa bersalah, atau mungkin sebagai teman. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah perkembangan positif. Namun belum cukup. Disiplin yang dibentuk dari kontrol ini masih belum mampu menghadirkan disiplin diri murid. Motivasi untuk berperilaku disiplin belum berasal dari motivasi internal.
Jika kita berbicara lebih jauh mengenai motivasi, secara umum ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang paling ideal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pembentukan disiplin di sekolah-sekolah belum banyak yang berhasil menyentuh motivasi yang ketiga tersebut. Murid cenderung dibentuk untuk disiplin agar dapat menghindari hukuman, atau mendapat pujian. Mereka tidak terbiasa menggali nilai-nilai kebajikan dari aturan-aturan yang harus mereka ikuti.
Maka, kamilah yang gagal menanamkan nilai-nilai kebajikan ini. Kami berkutat pada penegakan aturan. Layaknya seorang polisi di sekolah, kami berpatroli mencari murid yang melanggar aturan, mengejar mereka, dan menghukumnya. Mereka dihukum, tanpa mereka berhasil menemukan nilai kebajikan dari aturan tersebut. Mereka hanya tau mereka telah gagal mengikuti aturan, mereka layak dihukum. Kejadian serupa yang berulang menjadi hal yang biasa bagi mereka, tanpa ada pelajaran yang bermakna.
Saya membayangkan para pemuda yang melakukan aksi pemukulan tersebut saat berada di sekolah. Dengan seragam sekolah yang tak rapi, mereka nongkrong di kantin sekolah. Datanglah salah seorang guru yang ditugaskan menegakkan disiplin oleh kepala sekolah. Guru itu datang dengan wajah galak, kemudian menunjuk-nunjuk para murid itu, memelototi sambil membentak. Lalu mereka dihukum, dijejerkan di lapangan sekolah, dijemur, disaksikan teman-teman mereka. Mereka didisiplinkan. Dan jadilah diri mereka yang ada pada video itu.
Maka, kamilah yang gagal menanamkan disiplin pada mereka. Kamilah yang patut disalahkan. Kami gagal menanamkan budaya positif pada murid-murid kami. Kegagalan mereka adalah karena kegagalan kami. Mungkin kami yang perlu direstitusi. [T]