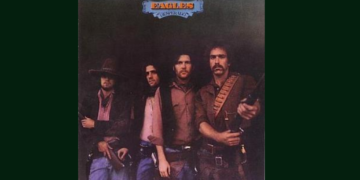Suasana kota Yogyakarta melekat dengan nuansa yang dinamis, diwarnai ragam festival kesenian yang tersebar di segala penjuru. Di tengah hingar bingar kota seni dan sibuknya perkuliahan, Indonesian World Jazz Meeting terselenggara di Artotel Suites Bianti, Yogyakarta. Hari Jumat 17 November 2023, saya berkesempatan hadir mengikuti konferensi.. Ketika itu kesadaran tentang kesuburan ekosistem musik jazz sedang mengudara bertepatan dengan 1 hari menuju perhelatan Ngayogjazz 2023.
Konferensi yang saya hadiri mempertemukan para pelaku industri musik jazz di Indonesia dengan para organizer festival maupun event dunia, termasuk media massa dari dalam dan luar negeri. Kehadiran saya setidaknya mewakili kalangan yang tidak bergumul banyak dengan dunia musik jazz. Pihak-pihak dari sejumlah subsektor ekonomi kreatif maupun lembaga pemerintahan lain pun belum tentu memiliki pemahaman yang mendalam soal bagaimana musik jazz seharusnya dikelola, maka dari itu konferensi ini menjadi ruang diskusi yang ditunggu-tunggu.
Pembicaraan tentang musik jazz dan festivalnya di tanah air tidak terlepas dari nama-nama seperti Irwansyah Harahap dan Djaduk Ferianto yang menginisiasi terma “World Jazz” begitu pun berkiprah untuk memulai festival jazz bercorak nusantara sebagaimana yang diungkap oleh Aji Wartono selaku board director dari Ngayogjazz. Baik almarhum irwansyah dan Djaduk memang sudah berpulang namun meninggalkan jejak dan warisan yang sangat berarti.
Kegiatan sarasehan terbagi menjadi sejumlah sesi dengan tema besar yang diangkat. Sesi pertama mengajak saya turut mempertanyakan “Apakah ada world music atau world jazz di Indonesia?” . Agus Setiawan Basuni selaku founder wartajazz yang ketika itu menjadi moderator bertutur tentang bagaimana seorang Joey Alexander menjadi nominasi penghargaan grammy sebanyak tiga kali. Peristiwa ini membangkitkan spirit soal pergerakan musik jazz di Indonesia yang sudah berlangsung di mana-mana. Ragam diskusi soal musik Jazz yang bergulir juga hendak mewacanakan lokalitas sebagai penguat identitas musik dalam konteks lanskap geografis.
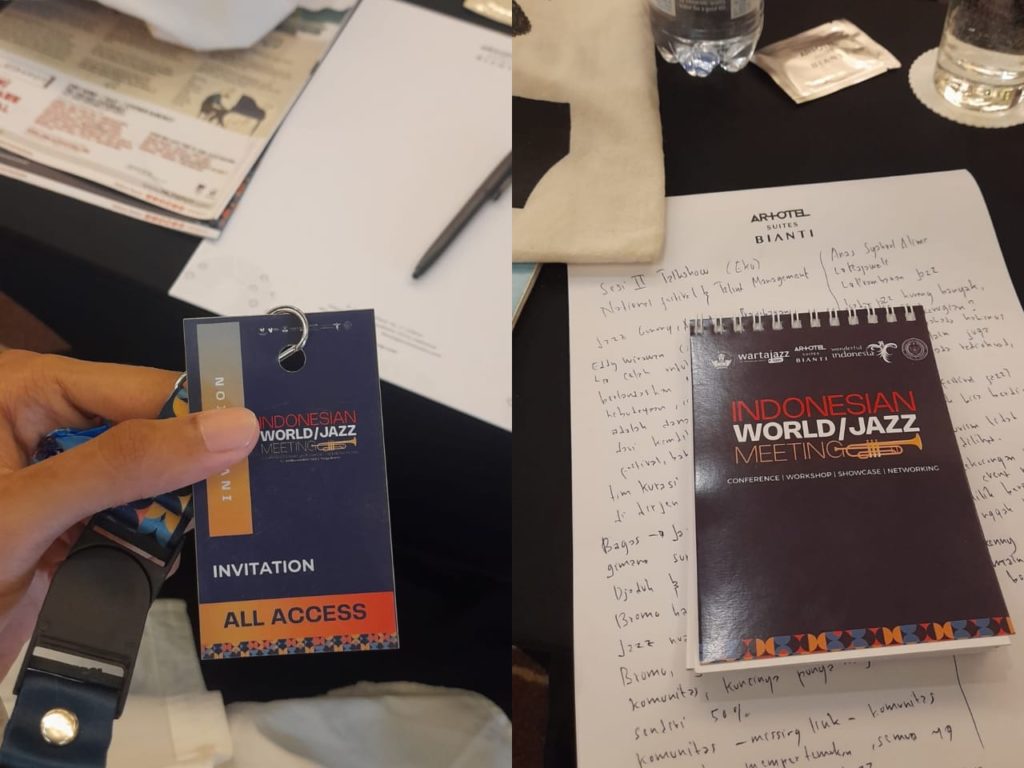
Keterangan Gambar: kesibukan mencatat percakapan di Indonesian World Jazz Meeting 2023
Ide dari Djaduk Ferianto mengenai Ngayogjazz pada tahun 2007 membuka ruang untuk kerja seni kolektif di Yogyakarta. Kolaborasi musik sangat terbuka dengan musik lintas genre yang pertunjukannya dilangsungkan di desa-desa. Saya mendapat cerita bahwa sebelum pandemi, Ngayogjazz bisa meraih jumlah sampai 40.000 total penonton. Setelah pandemi usai, jumlah penontonnya di angka 20.000 – 25.000 sebagaimana yang disampaikan Aji Wartono. “Tiket gratisnya unlimited, kita adakan workshop recording, ririungan, sharing, jam session, banyak hal” tutur sang board director.
Percakapan bertolak menuju Yuri Mahatma, seorang penggagas Ubud Village Festival yang memiliki misi untuk menghadirkan warna yang berbeda, karakter yang distingtif dan begitu terbuka untuk berkolaborasi di panggungnya. Saya juga menangkap bagaimana perhelatan festival musik jazz juga pada akhirnya bersifat pragmatis karena berupaya agar orang-orang yang tidak mengerti musik untuk bisa turut menikmatinya.
Sejurus dengan itu, Anas Syahrul Alimi sendiri tidak menyangkal bahwa di Prambanan Jazz yang ia kerjakan, musisi non jazz kerap hadir, dan itu murni terjadi di berbagai panggung festival jazz dunia. Sekilas kita membaca bahwa ada ketidaksesuaian genre dan idealisme, akan tetapi itu sudah lazim terjadi di mana-mana dan tidak mungkin dihapuskan.
Melalui percakapan yang berlangsung intens di antara semua narasumber, saya menyadari bahwa panggung musik jazz komersil juga berusaha menjual pesona alam dan ujung tombaknya tentu termasuk venue penyelenggaraannya. Vinko Mihajlovic yang turut hadir juga mengatakan bahwa di Montenegro sendiri, panggung “Petrovac Jazz Festival” ingin menawarkan suasana Mediterania demi memikat antusiasme penonton. Persoalan yang lebih penting lagi untuk digulirkan adalah bagaimana mereka bisa menjual musik sebagai subsektor ekonomi kreatif untuk menembus pasar internasional?
Hasil diskusi yang berjalan pada akhirnya tiba pada satu titik yang membuat saya menangkap bahwa diperlukan langkah yang lebih serius dalam mengelola subsektor ekonomi kreatif, terkhusus musik. International World Jazz Meeting 2023 yang mengundang sejumlah stakeholder yang bergerak di lingkup kementerian maupun wilayah ekonomi kreatif hendak mengupayakan konsep pembiayaan berupa “revolving fund” untuk memodali penyelenggaraan festival.
Setidaknya saya boleh menyarikan perkataan Ari Setyo dari Kemenparekraf bahwa modal yang telah membiayai harus diputar dan mendorong sustainability untuk perhelatan festival di tahun-tahun berikutnya. Artinya modal tidak pernah habis dan keberlangsungan festival tidak boleh mati begitu saja setelah sumber daya finansialnya tidak mencukupi.
International World Jazz Meeting 2023 menjadi jawaban atas “missing link”, ketakterhubungan antara musisi, pembuat event, dan stakeholder yang belum bergerak bersama menciptakan sinergi. Ketika sebelumnya penyelenggara festival banyak yang protes karena tidak dibiayai, maka pertemuan ini akan membuka ruang kerja sama dan koneksi yang semakin menguat. Terdapat celah untuk mensupport festival yang berlandaskan konstitusi berdasarkan undang-undang pemajuan kebudayaan.
Diskusi yang berlangsung mengetengahkan bagaimana dana abadi kebudayaan yakni Dana Indonesiana dari Kemdikbud dapat menjadi sumber yang menyokong maestro, memperkuat institusi, mendukung keberlangsungan festival, serta menjadi perwujudan peran serta negara dalam kontribusinya untuk ekosistem musik dan seni pertunjukan di tanah air.

Keterangan Gambar: sesi percakapan dengan sejumlah penggagas festival jazz di tanah air
Sarasehan berlanjut mengantarkan saya untuk menyelami Jazz Gunung yang diwakili oleh Bagas Indyatmono. Djaduk Ferianto dan Butet Kartaredjasa termasuk penggagas yang turut menuangkan andil, terutama berkaitan dengan wacana “Bromo bangkit kembali” pada tahun 2009. Djaduk Ferianto mengkurasi jazz dengan nuansa etnik untuk bisa menjadi penampil di perhelatan Jazz Gunung.
Festival Jazz Gunung berlangsung di Gunung Ijen, Bromo, Slamet, dan melibatkan komunitas, terutama musisi yang punya karya orisinil. Siapa sangka inisiatif untuk membangkitkan kehidupan di kawasan Bromo yang terdampak erupsi bisa bertransformasi menjadi festival Jazz yang tersohor?
Pertanyaan yang tebal muncul dari Frans Sartono, seorang wartawan musik senior yang kala itu juga diundang menjadi narasumber. Ia mengatakan “Harus menampilkan jazz yang seperti apa jazz Indonesia itu?”, sebuah pertanyaan yang relevan dengan judul konferensi yang saya hadiri. Bagi beliau, yang paling penting adalah bagaimana musik itu komunikatif ketika singgah di telinga, tidak peduli jazz atau bukan. Karena sekali lagi selalu ada unsur non jazz dalam sebuah festival jazz.
Tantangannya adalah bagaimana kita membawa yang lokal, mengusung musik etnik yang berpadu dengan idiom Jazz yang dilengkapi dengan “lingua franca” kita, atau bahasa pengantar termasuk pada lirik karya yang menjadi kunci terjalinnya resonansi antara penikmat dan musisi.

Keterangan Gambar: Frans Sartono (kiri) & Saya (kanan)
Kembali lagi pada persoalan krusial yang tak pernah rampung terselesaikan, seluruh penyelenggara festival berharap bahwa pemerintah dapat hadir memberi dukungan yang sebesar-besarnya. Mereka butuh perlindungan dan perizinan dari Kemenparekraf agar terwujud panggung festival yang hadir sebagai bentuk sinergi antara semua pihak yang terlibat, baik yang bergumul di ekosistem musik jazz, pelaku festival musik, dan komunitas yang belum tersorot stakeholder. [T]