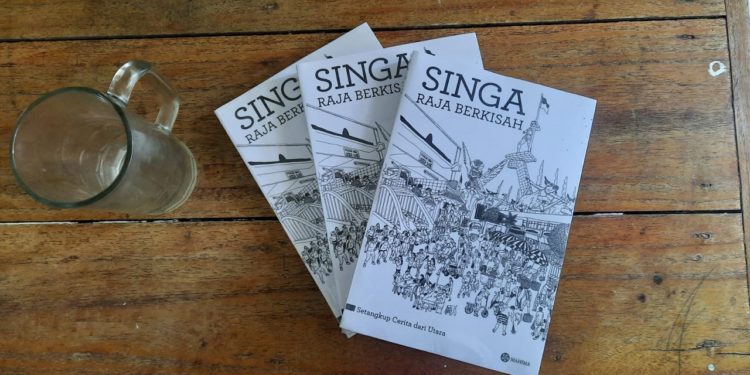Buku ini menghimpun 24 cerita pendek (cerpen) tentang Singaraja, kota di ujung utara Pulau Bali. Sebagian besar merupakan hasil lokakarya khusus yang digelar Lingkar Studi Sastra Denpasar sebagai bagian dari program “Membaca Kota Mengeja Kita” pada tahun 2022. Ditulis oleh para pengarang yang hampir semuanya lahir dan besar di Bali. Latar belakang pengalaman para pengarangnya di dunia sastra juga beragam. Ada yang sudah berpengalaman, bahkan karyanya sudah menembus arena sastra di tingkat nasional. Ada juga yang tampaknya masih terbilang pemula dalam menulis cerpen. Namun, dalam buku ini juga disertakan cerpen karya pengarang yang sudah mapan sekaligus menjadi mentor dalam program ini: Gde Aryantha Soethama dan Made Adnyana Ole.
Menghimpun cerpen dengan latar atau tema tentang suatu kota bukanlah hal yang baru dalam sastra Indonesia. Tahun 2003 pernah terbit antologi cerpen tentang Jakarta bertajuk Kota yang Bernama dan Tak Bernama[1]. Di Bali sendiri, pada tahun 2015, terbit kumpulan cerpen tentang Denpasar: Denpasar Kota Persimpangan Sanur Tetap Ramai[2]. Tak hanya cerpen, antologi puisi dengan latar atau tema khusus tentang suatu kota juga sesuatu yang jamak[3].
Kendati begitu, kehadiran buku kumpulan cerpen Singaraja ini tentu tetap penting dan karenanya patut diapresiasi. Melalui cerpen-cerpen dalam buku ini, pembaca tidak hanya dapat mengetahui potret wajah dan perkembangan Kota Singaraja pada suatu masa, tetapi juga tabiat kota melalui lukisan suasana batin warganya. Cerpen-cerpen dalam buku ini dapat diibaratkan sebuah “monumen kata-kata” yang senantiasa abadi. Monumen batu atau bangunan kota tua mungkin saja bisa hancur dimakan waktu, tapi “monumen kata-kata” dalam wujud karya sastra senantiasa ada hingga bisa “dikunjungi kembali” kapan saja, bahkan dari mana saja.
Latar Sebagai Kunci
Karena ditulis dalam rangka program tertentu, cerpen-cerpen dalam buku ini boleh dibilang sebagai karya dalam rangka atau karya pesanan. Namun, karya dalam rangka atau karya pesanan tidak selalu bermakna negatif. Pesanan dari penyelenggara mungkin terkesan membatasi, tetapi juga bisa menjadi tantangan kreatif bagi pengarang. Pengarang dalam berkarya kadang juga membutuhkan rangsangan untuk memantik lahirnya ide.
Namun, menghadirkan Singaraja dalam cerpen tidak selalu mudah. Pengarang tak hanya dituntut menghasilkan cerita yang menarik tetapi juga khas Singaraja. Cerpen Singaraja bukan semata cerpen dengan latar sebuah kota yang pernah menjadi ibukota Provinsi Bali, bahkan hingga Nusa Tenggara. Lebih dari itu, cerpen Singaraja mestilah unik yang tak didapatkan pembaca ketika membaca cerpen dengan latar berbeda.
Latar akhirnya memang menjadi kunci, unsur penting yang mesti mendapat perhatian pengarang atau sesuatu yang menonjol dalam cerpen-cerpen Singaraja. Latar yang khas biasanya disebut sebagai latar tipikal.[4] Latar jenis ini dibedakan dengan latar netral yang lebih bersifat umum. Jika latar netral bersifat universal karena bisa berlaku di mana saja, latar tipikal lebih mengesankan kelokalan. Karena itu, latar tipikal memiliki karakter lebih koherensif dan fungsional dengan unsur-unsur lain dalam cerita. Latar tipikal menjadi sesuatu yang tak tergantikan karena akan berpengaruh pada keutuhan cerita.
Itu sebabnya, latar tipikal menuntut deskripsi yang teliti dan detil sehingga mesti dilukiskan secara hati-hati. Tak hanya menyangkut deskripsi tempat yang tampak faktual, namun juga gambaran waktu dan lingkungan sosial budaya yang sesuai. Untuk menghadirkan latar tipikal, pengarang mesti mempertimbangkan bagaimana pembaca bisa menginterpretasikannya dengan suatu tempat, waktu dan sosial budaya tertentu di dunia nyata. “Matias Akankari” karya Gerson Poyk dapat dianggap sebagai contoh cerpen dengan gambaran latar tipikal yang kuat. Cerpen menghadirkan latar yang kontras, yakni hutan lebat di pedalaman Papua dan keramaian di Kota Jakarta. Selain mampu menggambarkan kedua tempat itu dengan cermat sehingga tampak faktual, pengarang juga berhasil melukiskan aspek waktu dan lingkungan sosial budaya yang mendukung karakterisasi tokoh dan konflik cerita.
Latar tipikal bisa juga tidak faktual karena tempat yang dimunculkan bersifat imajinatif. Namun, pembaca bisa menginterpretasikan latar sebagai suatu metafora atas suatu keadaan di suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Novel Incest karya I Wayan Artika menggunakan latar Desa Jelungkap yang imajinatif[5]. Namun, deskripsi tempat cerita itu tetap mampu merepresentasikan keadaan suatu desa tua di Bali dengan adat dan tradisi yang ketat. Jelungkap juga dapat dibaca sebagai metafora dari keadaan Bali mutakhir yang tidak pernah lepas dari tegangan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai modern.
Singaraja dalam Sastra Indonesia
Singaraja potensial menghadirkan latar tipikal karena memang kota ini memiliki kekhasan, terutama dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Bali. Citra menonjol tentang Singaraja tentu saja “Bali yang lain”. Pasalnya, di kabupaten yang memiliki wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Bali ini ditemukan sejumlah perbedaan mencolok dengan wajah Bali di bagian selatan dan timur. Mulai dari perbedaan pandangan tentang penanda arah kaja (utara) dan kelod (selatan) hingga karakter orang-orang Buleleng yang dicitrakan egaliter, multikultural, namun juga keras, bahkan kasar[6].
Sebagai latar cerita, Singaraja sudah mewarnai sastra Indonesia setidaknya mulai tahun 1930-an. Tahun 1932, terbit novel Kintamani karya Imam Soepardi, seorang pengarang sekaligus wartawan berlatar belakang etnis Jawa yang pernah berkunjung ke Bali. Dalam novel ini digambarkan keberadaan Pelabuhan Buleleng yang kala itu menjadi pintu masuk utama Bali.
Pukul 7 malam di Buleleng.
Di tepi Pelabuhan agak ramai, karena pukul 5 petang tadi ada berlabuh kapal muatan barang dari Surabaja. Banjak saudagar yang membawa barang dagangannja, sedang kembalinja kapal itu mengangkut sapi dari Pelabuhan itu jang hendak dibawanja ke Malaka.
Kuli-kuli bekerdja dengan radjinnja, sedang orang jang empunja milik, rebut mengatur barang dagangannja, djangan sampai ada yang ketinggalan.
Kian malam, keadaan itu kian sunji. Ditepi kantor pabean, jang tadinja banjak orang jang duduk dan mondar-mandir, sekarang djuga mulai sunji. Hanja ada seorang dua sadja jang lalu lintas disitu. [7]
Pada masa penjajahan Belanda, Singaraja memang menjadi pintu masuk utama Pulau Bali. Pelabuhan Buleleng merupakan gerbangnya. Pascakemerdekaan, terlebih setelah dipindahkannya ibukota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar, keberadaan Pelabuhan Buleleng pun meredup, bahkan praktis tak berfungsi lagi. Orang-orang yang ingin mengetahui geliat Pelabuhan Buleleng di masa lalu kini tidak hanya bisa menelusuri dari foto-foto atau rekaman video lama, namun juga dari deskripsi dan narasi dalam teks-teks karya sastra.
Kemunculan Singaraja sebagai latar dalam sastra Indonesia terutama lebih menonjol pada karya-karya Anak Agung Pandji Tisna, pengarang Indonesia asal Buleleng. Novelnya yang terkenal, Sukreni Gadis Bali (1935) dan I Made Widiadi (Kembali Kepada Tuhan) (1957) secara eksplisit menggunakan Singaraja sebagai landas tumpu cerita. Tradisi penulisan Singaraja sebagai latar cerita ini terus dilanjutkan oleh pengarang lain yang lahir atau tinggal di Singaraja, seperti Sunaryono Basuki Ks, Gede Dharna, Gde Winnyana hingga Kadek Sonia Piscayanti.
Singaraja tak hanya ditulis oleh sastrawan yang lahir dan tinggal di Bali, namun juga ditulis oleh sastrawan Indonesia dari luar Bali. Mereka antara lain Nur St. Iskandar yang menulis novel Djangir Bali, Bre Redana dalam cerpen “Lovina Junction”, serta Erwin Arnada dalam novel Rumah di Seribu Ombak (2011). Djangir Bali merupakan roman kisah cinta perempuan Bali dan lelaki bangsawan Madura dengan latar Singaraja. Sementara Rumah di Seribu Ombak berupa kisah persahabatan anak-anak Hindu dan Muslim di kawasan Desa Kalidukuh, Singaraja.
Dalam berbagai karya sastra Indonesia itu, Singaraja direpresentasikan dengan tiga citra utama, yakni dari dimensi historis, sosiologis, dan turistik. Secara historis, Singaraja kerap ditulis dalam jejak kejayaan masa silam sebagai kota pelabuhan penting pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 serta mitologi Singa Ambara Raja.
Pada dimensi sosiologis, Singaraja dicitrakan sebagai kota dengan karakteristik multietnis, multiagama, dan multikultural yang kuat. Novel-novel Pandji Tisna dan Sunaryono Basuki Ks konsisten menggambarkan wajah multikultural Singaraja. Selain itu, Singaraja juga direpresentasikan secara turistik sebagai destinasi wisata penting di bagian utara Bali dengan Pantai Lovina sebagai ikon.
Namun, ada kecenderungan Singaraja sebatas dihadirkan sebagai latar cerita. Karya-karya itu belum memperlihatkan gambaran problematika kota Singaraja yang khas dan ikonis sehingga dengan membaca karya sastra tentang Singaraja pembaca bisa mendapatkan pengalaman estetik bercita rasa Singaraja. Karena itu, Singaraja dalam sastra Indonesia masih menyisakan ruang kosong yang memberikan tantangan kreatif bagi para sastrawan.
Potret Ikonis Singaraja
Ruang kosong inilah yang tampaknya mencoba diisi oleh cerpen-cerpen Singaraja dalam buku ini. Terlebih lagi, sebelum menulis cerpen Singaraja, sebagian pengarang terlebih dulu mengikuti workshop penulisan yang diberikan cerpenis Gde Aryantha Soethama dan Made Adnyana Ole. Keduanya mengingatkan tentang pentingnya menggarap kisah-kisah yang khas dan bercita rasa Singaraja. Itu artinya, para pengarang ini berangkat dari kesadaran untuk menghadirkan cerita yang, seperti istilah Gde Aryantha Soethama, “unik dan otentik Singaraja”[8].
Cerpen-cerpen dalam buku ini memperlihatkan usaha keras para pengarangnya untuk menghadirkan potret ikonis Singaraja. Selain citra sebagai destinasi wisata bahari, khususnya kawasan Pantai Lovina dengan ciri khas atraksi lumba-lumba, muncul juga wajah ikonis lain Singaraja yang selama ini belum banyak digarap, seperti siobak sebagai makanan khas Singaraja, eks Pelabuhan Buleleng, warung patokan atau dagang kopi cantik (dakocan) di sepanjang jalur Pantai Utara Bali, kota pendidikan serta Gedong Kirtya sebagai gudang pustaka lontar Bali.
Walaupun begitu, masih ada sejumlah cerpen yang hanya meminjam latar Singaraja, sedangkan ceritanya tidak secara khusus menggambarkan problematika khas Singaraja, namun sesuatu yang lumrah terjadi di banyak tempat lain. Cerpen “Berputar-putar Sampah” karya Gading Ganesha, “Ditipu Bapak di Taman Kota” karya Geg Ary Suharsani serta “Kardus Lama di Kolong Tempat Tidur” tak lebih sebagai cerita urban yang bisa ditemukan di tempat lain.
Cerpen “Gigir Malam Bulan Oktober” karya Supartika juga tak terasa sebagai cerpen khas Singaraja karena tema tragedi 1965 jamak ditemukan di banyak tempat. Sungguh menarik jika cerita pembunuhan orang-orang PKI yang digarap merupakan cerita lokal Singaraja yang berbeda dengan kecenderungan cerita serupa di tempat lain. Namun, cerpen “Gigir Malam Bulan Oktober” memperlihatkan penggarapan alur dan konflik yang kuat sehingga tetap memikat. Dengan tempo yang cepat dan dialog yang padat, cerpen ini mengingatkan pada cerpen Supartika di Kompas tahun 2020, “Brewok” yang juga berkisah tentang jagal tahun 1965.
Ada juga kisah misteri di Kota Singaraja dalam “Krincing-krincing Tiga Dokar” karya Devy Gita serta kisah hubungan sesama jenis dengan latar dalam “Pecah Seribu, Dungu” karya Indah Fay. Keanekaragaman tema mengindikasikan keanekaragaman pemaknaan pengarang terhadap wajah dan tabiat Kota Singaraja.
Pantai Lovina tampaknya paling banyak dipilih sebagai latar dalam cerpen-cerpen di buku ini. Cerpen “Kati di Lubuk Laut Lovina” karya Lina PW berkisah tentang hilangnya seorang wisatawan saat snorkeling di laut Lovina, sedangkan cerpen “Wasiat Pengasuh Lumba-lumba” karya Putu Agus Phebi Rosadi bercerita tentang persahabatan intim manusia dan lumba-lumba. Dua cerpen tentang Lovina ini menghadirkan sisi-sisi humanis gemerlap turisme Lovina.
Secara umum, latar Singaraja dalam cerpen-cerpen di buku ini dibalut dalam kisah cinta. Ada kisah cinta remaja yang ringan-ringan, seperti “50.000 di Penimbangan” karya Ni Luh Putu Rastiti Era Agustini, ada juga kisah cinta mahasiswa dalam cerpen “Lamun-lamun Pantai Penimbangan” karya Gde Aries Pidrawan.
Cerpen “Lontar Cantik Made Cenik” karya Dian Suryantini dan “Asmara Margaret di Jalan Gajah Mada” karya Wayan Agus Wiratama juga cerita cinta tetapi mengandung elemen ikonis Singaraja yang menarik. Dalam “Lontar Cantik Made Cenik”, kisah cinta tokoh cerita berlatar Gedong Kirtya Singaraja, sedangkan dalam “Asmara Margaret di Jalan Gajah Mada”, pengarang tak hanya menyuguhkan romantika orang asing dan orang lokal tapi juga menyampaikan kritik mengenai makin lenyapnya situs bangunan tua di Kota Singaraja akibat perkembangan pembangunan.
Cerpen “Candu Baru” karya Manik Sukadana juga merupakan kisah cinta tokoh Kacrek dan Luh Asih berlatar Singaraja saat musim panen cengkeh. Kisah cinta keduanya kandas karena Luh Asih diceritakan bunuh diri karena beban persoalan di keluarganya. Namun, ada hal yang sedikit mengganggu dalam cerpen ini, yakni adegan Luh Asih memberitahu Kacrek mengenai keinginannya bunuh diri tetapi Kacrek tak melakukan apa-apa. Selain melemahkan aspek kejutan di akhir cerita, adegan itu juga terasa kurang masuk akal.
Masih berkaitan dengan elemen percintaan, cerpen-cerpen yang mengisahkan romantika para pedagang kopi cantik (dakocan) di sepanjang jalur Pantai Utara Singaraja menarik dicermati. Dakocan atau warung patokan memang menjadi salah satu ikon lain Buleleng. Bahkan, keberadaan dakocan ini juga diabadikan dalam lagu-lagu pop Bali yang sangat disukai orang Bali, terutam di kampung-kampung.
Cerpen “Pedagang Kopi Cantik Terbunuh di Sangsit” karya Gede Satria Aditya Wibawa dan “Warung Patokan Desa A” karya Komang Mudita berupaya menghadirkan ikon itu dengan mengukuhkan citra buram para perempuan yang terjun menjadi pedagang kopi atau penjaga warung patokan. Dalam cerpen “Warung Patokan Desa A”, menjadi dakocan atau penjaga warung patokan merupakan aib dan bagian dari masa lalu yang telah dilupakan.
Sejak itu gadis-gadis Desa A berbondong-bondong menjadi perantau. Adik-adik mereka kemudian disekolahkan, dibiayai sampai perguruan tinggi, hingga ada yang menjadi guru, bekerja di peternakan di Jepang, di kapal pesiar. Desa itu menjadi riuh dan ramai kalau hari raya. Di desa yang ditumbuhi lebat pohon durian dan rambutan itu, warung patokan cuma masa lalu.
Cerpen “Wayan Buduh” karya Eka Prasetya terbilang berhasil mengenalkan sudut-sudut Kota Singaraja. Pengarang tampak cerdik menggunakan karakter tokoh Wayan Buduh untuk mengajak pembaca menjelajahi tempat-tempat ikonis Singaraja.
Ikonis Singaraja tak hanya ditampilkan melalui latar tetapi juga gaya bahasa. Citra orang Singaraja dengan bahasa yang vulgar bahkan terkesan kasar mencoba disuguhkan Luh Ayu Dian Lestari dalam cerpen “Rok Mini Taman Limpit”. Dalam cerpen ini bertebaran kata-kata umpatan khas Singaraja, seperti cicing, nani, naskeleng. Penggunaan umpatan itu juga fungsional dengan karakter dan konflik cerita tentang dunia malam Kota Singaraja.
Karena ingin menghadirkan latar Singaraja, hampir semua cerpen dalam buku ini bergaya realis. Namun, ada satu cerpen bergaya absurd, yaitu “Kisah dari Negeri Tanpa Singa” karya Kadek Sonia Piscayanti. Cerpen ini menghadirkan aspek mitologi Singa Ambararaja yang menjadi lambang Kabupaten Buleleng. Cerpen ini tampaknya kelanjutan dari cerpen Sonia Piscayanti sebelumnya bertajuk “Kisah Ajaib dari Negeri Singa” yang dimuat dalam buku Karena Saya Ingin Berlari (2007) dan “Kisah (Masih) Ajaib dari Negeri Singa” yang termuat dalam cerpen “Perempuan Tanpa Nama”. Tak ada latar Singaraja atau Buleleng yang eksplisit dalam cerpen ini, tetapi pembaca dapat segera mengasosiasikan cerita ini sebagai lukisan absurd tentang Singaraja. Hilangnya patung Singa di tengah kota merupakan simbolisasi lenyapnya spirit Singaraja yang diikhtiarkan para pendirinya. Karena itu, cerpen “Kisah dari Negeri Tanpa Singa” dapat dibaca sebagai cara lain pengarang mengkritik perkembangan Singaraja, kota kelahiran yang sangat dicintainya.
Memang, secara struktur, cerpen-cerpen dalam buku ini memperlihatkan kesenjangan antara satu pengarang dan pengarang lain dalam hal kemampuan mengolah dan mengembangkan cerita. Beberapa cerpen mampu menggarap penokohan dan konflik dengan baik sehingga pembaca bisa mendapatkan elemen penting sebuah cerpen, yakni suspense dan surprise. Namun, ada juga cerpen yang penokohan dan plot ceritanya kurang tergarap sehingga cerita tak hanya sudah selesai saat pembaca membaca bagian awal cerita, namun juga menyisakan kejanggalan-kejanggalan. Tentu ini erat kaitannya dengan pengalaman para pengarangnya, tak hanya jam terbang dalam mengarang tapi juga persentuhan dengan karya-karya terbaik.
Sastra Boga
Kendati begitu, cerpen-cerpen Singaraja dalam buku ini juga menunjukkan hal-hal menarik. Cerpen tentang siobak menarik untuk diperhatikan karena selain menghadirkan wajah ikonis Singaraja sekaligus juga memberi warna gastronomi sastra atau sastra boga dalam buku ini.
Para peneliti sastra memaknai gastronomi sastra atau sastra boga sebagai pemaknaan makanan dari perspektif karya sastra[9]. Tak sebatas sebagai wujud material dan fisikal dalam cerita, makanan dalam gastronomi sastra juga berfungsi mengembangkan karakter tokoh dan alur cerita. Bahkan juga makanan sebagai representasi identitas tokoh cerita. Sederhananya, makanan menjadi penggerak cerita, bukan sekadar tempelan.
Dari 24 cerpen, dua di antaranya menggarap kuliner siobak sebagai tema cerita. Kedua cerpen itu, yakni “Ling Siobak Poleng” karya Bli Dodi alias I Wayan Dodi Putra Artawan dan “Perang Siobak”, cerpen karya mentor program ini, Gde Aryantha Soethama.
Dalam cerpen “Ling Siobak Poleng”, siobak dibalut dalam kisah cinta tokoh Komang Ling dan Ko Bagus. Ketika dihadapkan pada pilihan antara pergi merantau ke Denpasar bersama sang pujaan hati atau tetap tinggal bersama keluarga di Singaraja melanjutkan pekerjaan sang ayah sebagai penjual siobak, tokoh Komang Ling memilih bertahan di Singaraja. Keputusan yang juga didorong keinginan melanjutkan usaha warisan keluarganya, yakni warung siobak poleng. Sebuah pesan yang kuat dari pengarang tentang harapan masa depan yang lebih baik tidak mesti harus meninggalkan kampung kelahiran. Ini cerpen tentang kecintaan kepada keluarga dan Singaraja sebagai kota kelahiran. Namun, kurangnya penggarapan elemen konflik dan karakterisasi menjadikan cerpen ini terasa datar.
Pada cerpen “Perang Siobak”, siobak Singaraja hadir sebagai unsur yang luruh dalam keutuhan cerita. Siobak Singaraja bukan hanya sebagai pokok cerita, tetapi juga menggerakkan konflik cerita. Persaingan usaha menjadi tema mayor cerpen ini. Melalui karakterisasi tokoh-tokoh cerita, pengarang berhasil memantulkan potret tabiat orang-orang kota dengan batas yang demikian tipis antara kawan dan lawan, antara penolong dan penyolong. Cerpen yang sudah dimuat di Kompas, 30 Oktober 2022 dan dimuat kembali dalam buku Malam Pertama Calon Pendeta (2023) bolehlah dijadikan model cerpen Singaraja yang “unik dan otentik”.
Cerpen “Damun” karya Juli Sastrawan dan cerpen “Panak Nyonyah dari Kota Pabean” karya Putu Arya Nugraha juga mengandung anasir-anasir kuliner khas Singaraja. Selain siobak, dalam “Damun”, pengarang menghadirkan kuliner lain yang identik dengan identitas Kota Singaraja, yakni blayag dan sudang lepet. Begitu juga dalam “Panak Nyonyah dari Kota Pabean”, pembaca disuguhi sajian bakpao khas Singaraja. Sayangnya, pengarang tampaknya tak berminat mengeksplorasi aspek kuliner ini.
Masih ada satu cerpen kuliner lagi, yaitu “Simpang Tiga Perang Karapan” karya Wulan Dewi Saraswati. Cerpen ini berkisah tentang tokoh Cak Man, perantau dari Madura yang sukses berjualan kepiting saus mentega di Kota Singaraja. Memang, kepiting saus mentega bukanlah kuliner khas Singaraja, tetapi cerpen ini merepresentasikan wajah multikultural Singaraja dengan sikap warganya yang terbuka menerima pendatang, termasuk kuliner jenis baru yang dibawanya. Dimensi multikultural juga tercermin dalam cerpen “Panak Nyonyah dari Kota Paben” menyajikan kisah cinta beda etnis antara lelaki berlatar belakang etnis Bali dan etnis Tionghoa.
Siobak pun sejatinya representasi wajah muktikultural Singaraja. Makanan berbahan utama daging babi rebus yang diiris tipis-tipis dan dilumuri saus berwarna coklat itu tak lain sebagai perpaduan antara budaya kuliner Tionghoa dan selera orang Bali. Multikultural hadir dalam sajian di meja makan orang Singaraja.
Spirit Multikultural
Spirit multikultural memang terasa kuat gemanya dalam cerpen-cerpen Singaraja. Tak hanya dalam cerpen kuliner, juga pada cerpen-cerpen lain, seperti “Asmara Margaret di Jalan Gajah Mada” karya Wayan Agus Wiratama, “Lamun-lamun Pantai Penimbangan” karya Gde Aries Pidrawan, termasuk cerpen “Safir Tiba di Singaraja” karya Made Adnyana Ole.
Cerpen “Safir Tiba di Singaraja” menarik karena menggunakan latar Pelabuhan Sangsit, Buleleng. Memang, Buleleng memiliki sejarah sebagai pelabuhan utama Bali, terutama pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Namun, pascakemerdekaan, terutama setelah ibukota Provinsi Bali dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar, Pelabuhan Buleleng meredup hingga tak lagi difungsikan. Namun, Buleleng masih memiliki Pelabuhan Sangsit yang terletak sekitar 6 km di sebelah timur Pelabuhan Buleleng. Tak seperti Pelabuhan Buleleng, Pelabuhan Sangsit hanya digunakan untuk penyeberangan barang. Pelabuhan Sangsit ini berhadapan dengan Pelabuhan Sapeken, Kepulauan Madura.
Meski begitu, dalam cerpen Adnyana Ole, Pelabuhan Sangsit digambarkan kerap dipilih untuk menyeberangkan orang-orang dari sejumlah pulau kecil di sekitar Madura. Bagi orang-orang itu, Pelabuhan Sangsit merupakan pintu gerbang utama untuk ke Singaraja. Mereka menempuh pendidikan bahkan mengadu nasib di Singaraja. Itu terjadi sejak lama sehingga mereka kemudian menetap dan menjadi warga Kota Singaraja.
“Di Singaraja kita seperti hidup di rumah sendiri, hanya saja kotanya jauh lebih ramai dari kampung kita. Banyak orang luar Bali tinggal di kota itu. Ada dari Banyuwangi, Lombok, Jember, Probolinggo, Tuban, Lamongan, Bugis, Flores, Papua, bahkan ada orang dari Timor Timur. Apalagi orang dari dari Kepulauan Madura, itu banyak. Saking berbaurnya warga dari berbagai suku di kota itu, orang Singaraja jarang bertanya-tanya kita dari mana, bahkan mungkin mereka tidak tahu ada sekumpulan orang dari Kepulauan Kangaen menumpang hidup di kota itu,” cerita Ainur sembari tersenyum.
Cerpen “Safir Tiba di Singaraja” serta cerpen-cerpen lain menangkap identitas Singaraja sebagai kota multietnik dan multibudaya. Ini tak terlepas dari sejarah Singaraja yang menjadi tempat pertemuan berbagai manusia dan tentu saja persamuhan beragam budaya dan nilai-nilai. Warga Singaraja terbuka dengan kedatangan berbagai budaya berbeda dan nilai-nilai baru, bahkan merangsang lahirnya budaya baru dengan karakteristik hibrid.
Sikap terbuka terhadap budaya berbeda dan nilai-nilai baru itu yang kemudian membuat Singaraja kerap menjadi lokomotif dalam pembaruan kesenian Bali. Dalam seni gong kebyar dan drama gong misalnya, Singaraja hadir memberi warna berbeda sehingga memperkaya keragaman gaya kesenian tersebut di Bali. Bahkan, Singarajalah yang menjadi tempat lahirnya seni gong kebyar sebelum berkembang ke Bali Selatan dan wilayah lainnya di Bali.
Tentu kita berharap Singaraja juga bisa menawarkan warna baru dalam sastra. Terlebih lagi Singaraja memiliki jejak kepeloporan dalam sastra tradisional maupun modern. Tengok saja cerita Jayaprana-Layonsari yang melegenda itu. Cerita rakyat bertipologi cerita Rome-Juliet itu tak hanya berlatar Singaraja, melainkan juga tumbuh dan berkembang dari kota pesisir utara Bali itu.
Dari Singaraja pula sastra modern di Bali lahir dan berkembang hingga seperti sekarang? Tak hanya dalam sastra berbahasa Indonesia melalui karya-karya Pandji Tisna, melainkan juga dalam sastra berbahasa Bali melalui karya-karya Made Pasek yang juga sebagai orang Buleleng[10].
Karena itu, tak berlebihan jika muncul gagasan menjadikan Singaraja sebagai kota sastra. Kota ini punya potensi, tak hanya dibuktikan melalui jejak-jejak historisnya, melainkan juga harapan masa depan, seperti diisyaratkan oleh cerpen-cerpen Singaraja dalam buku ini. [T]
[1] Buku antologi ini menghimpun 30 cerpen berlatar atau bertema Jakarta. Buku ini diterbitkan sehubungan dengan acara Temu Sastra Jakarta yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 19—21 Desember 2003. Selain antologi cerpen, pada saat itu juga diterbitkan antologi puisi Bisikan Kata, Teriakan Kota.
[2] Buku ini menghimpun 25 cerpen berlatar atau bertema Denpasar sejak tahun 1950-an hingga tahun 2014. Sebelumnya juga diterbitkan antologi puisi tentang Kota Denpasar, yakni Dendang Denpasar Nyiur Sanur (2012) yang merupakan antologi puisi berbahasa Indonesia serta Denpasar lan Don Pasar (2013) yang berupa antologi puisi berbahasa Bali.
[3] Klungkung, kota kecil di timur Bali, juga pernah menerbitkan buku antologi puisi tentang Klungkung, yakni antologi puisi berbahasa Bali Pupute Tan Sida Puput (2001) serta Klungkung: Tanah Tua, Tanah Cinta (2016) dan Di Altar Catus Patta (2022) yang merupakan antologi puisi berbahasa Indonesia.
[4] Burhan Nurgiyantoro dalam buku Teori Pengkajian Fiksi (2013: 307).
[5] Awalnya, saat dimuat sebagai cerita bersambung di Bali Post, novel ini menggunakan latar faktual, yakni Desa Batungsel yang juga kampung kelahiran pengarangnya. Namun, karena sempat menimbulkan protes dari masyarakat desa itu hingga berdampak pada pengenaan sanksi adat kepada pengarangnya, saat diterbitkan di Yogyakarta sebagai novel, latarnya diganti menjadi Jelungkap, sebuah latar imajinatif.
[6] Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri saat memberikan paparan dalam seminar nasional Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 tahun Bali Era Baru 2025—2125, Jumat, 5 Mei 2023 menyebut karakter khas orang Buleleng, yakni keras dan cenderung kasar. Ini menunjukkan karakter keras dan cenderung kasar menjadi stereotip orang Buleleng. Bukan saja bagi orang Bali di luar Buleleng, tetapi juga di mata orang luar Bali.
[7] Imam Supardi dalam novel Kintamani (1949:82)
[8] Laporan mengenai workshop ini dapat dibaca di tatkala.co: https://tatkala.co/2022/09/26/apa-dan-bagaimana-kota-singaraja-dalam-cerpen-dari-workhsop-cerpen-membaca-kota-mengeja-kita/
[9] Wulansari, Rosalina Ayuning. 2018. “Gastronomi Sastra: Manifestasi Kekayaan Boga dan Budaya Nusantara”. Tersedia secara daring di tautan https://www.academia.edu/45182306/GASTRONOMI_SASTRA_MANIFESTASI_KEKAYAAN_BOGA_DAN_BUDAYA_NUSANTARA
[10] Penelitian guru besar sastra Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Udayana, Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt., menemukan karya-karya Made Pasek pada tahun 1910-an sebagai tonggak kelahiran sastra Bali modern. Baca buku Tonggak Baru Sastra Bali Modern (2012) serta Heterogenitas Sastra di Bali (2022).