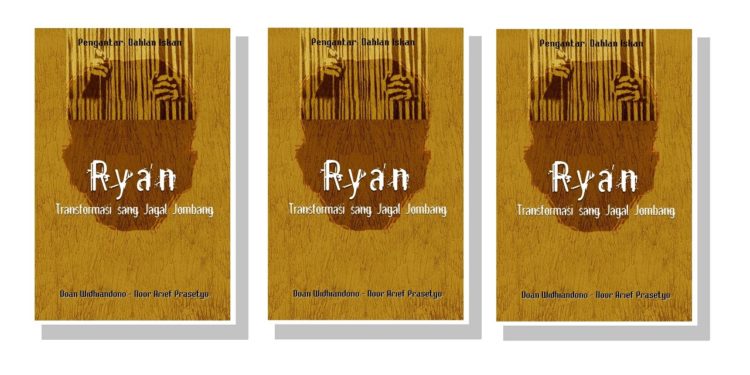Judul Buku : Ryan Transformasi sang Jagal Jombang
Jenis : Reportase
Penulis : Doan Widhiandono & Noor Arief Prasetyo
Penerbit : Padmedia
Cetakan : Pertama, 2022
Tebal : xvii + 278 halaman
ISBN : 978-623-5654-03-4
Peresensi : Stebby Julionatan
Saya teringat perkataan Cletus Kasady, tokoh villain dalam Venom: Let There Be Carnage (2021). Di film yang masuk dalam semesta Mavel Cinematic Universe (MCU) tersebut, sebelum Kasady membacakan sebuah puisi indah kepada Eddie Brock –sang superhero yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis investigasi, ia memulainya dengan kalimat: “People love serial killer, Eddie. And I will give you my story.”
Beratus-ratus kilometer jauhnya dari San Fransisco, di jagad non-fiksi, setahun sebelum film tersebut diluncurkan ke publik, Doan Widhiandono dan Noor Arief Prasetyo melakukan perjalanan ke Lapas Khusus Gunung Sindur – Bogor untuk menjumpai Very Idham Henyansyah. Kurang lebih 900 kilometer perjalanan yang harus ditempuh oleh kedua wartawan senior tersebut, dari Surabaya ke Jakarta dan dari Jakarta ke Bogor, untuk menjumpai terpidana mati yang dahulu di 2008 ramai disebut orang dengan sebutan “Ryan Jagal Jombang”.
Tapi saya tak ingin memanggil Ryan dengan sebutan “jagal”. Dia memang membunuh dan jumlah korbannya tidaklah sedikit, ada 11 orang, tapi biarlah hal tersebut sebagai masa lalunya. Saya tak ingin menghakiminya dengan meletakkan “jagal” sebagai kata yang memiliki hierearki nilai dan negatif. Jagal mungkin nanti akan saya gunakan tapi dalam pengertian yang lebih netral. Lagipula, seperti yang diceritakan oleh Doan dan Arief dalam buku ini, rentang 12 tahun di lembaga permasyarakatan telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan Ryan. Ia jadi rajin salat, puasanya tak pernah lepas -ia melakukan puasa kafarat selama dua tahun penuh, bahkan ketika ditemui oleh Doan dan Arief pada pertengahan Oktober 2020 lalu, Ryan baru saja dinyatakan lulus sebagai penghafal Al-Qur’an.
Diakui Doan dan Arief bahwa tulisan-tulisan mereka yang terkumpul dalam buku ini dipantik oleh rasa penasaran pada nasib Ryan saat ini, pasca 12 tahun menjalani penahanan, terlebih setelah menerima buku Misteri Kasus Rian: Pembunuhan Berantai terbitan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (2013) pada awal 2020. Wabah pandemi COVID-19 membuat keduanya harus sedikit menunda keberangkatan hingga Oktober 2020. Dari sanalah tulisan-tulisan dalam buku ini lahir, reportase pembunuhan berantai yang dilakukan Ryan, dimuat secara bersambung pada Oktober-Desember 2020 di harian Disway, lantas dibukukan dan terbit dengan judul Ryan Transformasi Sang Jagal Jombang (Februari 2022).
Buku Ryan Tranformasi Sang Jagal Jombang dicetak setebal 278 halaman, ini lebih tebal dari buku The Untold Story of Ryan karangan Ryan sendiri (128 halaman) yang saat ini keberadaannya telah ditarik dari pasaran. Dalam pengantarnya, Dahlan Iskan sempat berseloroh bahwa dengan terbitnya buku ini maka tak ada lagi misteri yang tersembunyi paska kepergian Ryan nanti. Tapi apakah benar demikian?
Transformasi Ryan
Homines arcani sunt et implicatae creaturae. Misteri dan kompleksitas manusia tidak akan pernah habis untuk digali; meski nantinya akan ada banyak peneliti dan jurnalis yang menulis soal Ryan. Pepatah tersebut secara implisit menjelaskan bahwa misterilah justru yang membuatnya (baca: Ryan) menjadi manusia; karena kompleksitasnya. Misteri pula yang membuat kita –sebagai manusia, memburu pengetahuan, membuat kita bergerak dan tak terperangkap pada kejenuhan rasionalitas.
Perubahan kebiasaan Ryan dari sosok pembunuh sadis sebagaimana yang diceritakan penulis ke sosok yang lebih spiritual bagi saya pribadi masih menjadi misteri. Hal apakah yang menggerakkannya? Benarkah sebuah penyesalan yang total? Hal yang (di satu sisi) dianggap sebagai buah “keberhasilan” dari proses “pendidikan” yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan dan tentunya juga menjadi hal yang “menyenangkan” untuk dibaca dan didengar oleh masyarakat awam.
Namun, (di sisi lain) kita juga tak dapat menyangkal bahwa beberapa temuan ilmiah telah membuktikan bahwa perubahan kadang hanya terjadi pada lapisan luar (perilaku) yang tidak melibatkan kesadaran. Misal, pada Psyco Cybernetics (1960) karangan Maxwell Maltz yang menyebut bahwa manusia “hanya” memerlukan 21 hari untuk mengubah kebiasaannya. Atau, Michael Foucault yang menjabarkannya dalam teori “pendisiplinan tubuh” (1975), yakni suatu upaya menguasai tubuh subjek agar menjadi individu baru yang diharapkan bahkan tanpa disadari oleh subjek tersebut.
Tulisan Doan dan Arief ini secara naratif gencar menyeret pembaca bahwa Ryan kini telah berubah menjadi lebih saleh. Hapalan Al-Qur’an, caranya berpakaian, kesantunan saat menjawab pertanyaan, keakrabannya dengan keponakan dan para napi lain, bahasa kasih dan kehangatan yang ditunjukkan Ryan pada ibunya, Siatun, serta surat permohonan grasinya kepada Presiden yang meminta waktu untuk menyelesaikan kafarat. Tapi apakah benar itu sebuah kesadaran ataukah sebuah hasil dari proses pendisiplinan?
Menikmati reportase yang lancar kedua jurnalis senior ini, saya sangat berharap ada turning poin, yakni proses kesadaran internal Ryan yang dapat ditangkap dan kemudian mereka tuliskan. Tapi tetap saja “transformasi” yang dimaksud keduanya hanyalah transformasi “kulit”; baju gamis panjang dan peci penutup kepala serta azan yang selalu menjadi pengingat Ryan untuk menghentikan kegiatannya (Bab 28. Ingin Pindah ke Sidoarjo, Mulai Bertransformasi). Meski tak salah melihat spiritualitas dari kacamata kuantitatif, tapi saya berharap melihatnya pula secara kualitatif.
Bias Heteronormatif
Misteri lain yang masih menggantung di benak saya adalah orientasi seksualitas Ryan yang dikatakan penulis telah melepaskan kehidupan gay-nya dan menjadi “normal”.
“Dia juga pernah ingin hdiup normal dan menikahi srang perempuan. Tetapi, kondisinya memang belum memungkinkan. Ryan bahkan menawarkan diri untuk memberikan konseling bagi mereka yang ingin keluar dari dunia LGBT.”
Juga pada:
“Ryan memang punya dasar agama yang cukup. Karena itu, saat begitu jauh tersesat, dia tetap bisa menemukan jalan kembali. Salah satu caranya adalah mendekatkan diri kepada Allah.”
Di sinilah saya merasa Doan dan Arief masih terjebak dalam kerangka heteronormatif. Tak hanya terjebak pada pemikiran bahwa menjadi heteroseksual itu yang “normal” dan berkedudukan lebih baik ketimbang “gay”, tapi juga terjebak pada pemikiran-pemikiran yang berikut saya pertanyakan: Apakah seorang gay tidak bisa menikah dengan perempuan? Apakah gay tidak bisa memanipulasi ereksi penisnya ereksi ketika diperhadapkan pada perempuan yang telanjang? Dan, apakah seorang gay tidak bisa membuahi sel telur? Lalu, apakah jawaban untuk “menjadi normal” adalah dengan dasar agama? Bagaimanakah Doan dan Arief dapat menjelaskan pijakannya itu pada kasus Herry Wirawan, kyai yang didakwa memerkosa 13 santriwati?
Judith Butler, filsuf yang subjek penelitiannya berfokus pada teoretisi gender, mengatakan bahwa gender itu performatif dan sifatnya adalah pengulangan. Di budaya kita saat ini, normanya setiap orang harus berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lelaki harus maskulin dan perempuan harus feminin. Itulah sebabnya mengapa bayi yang terlahir dengan alat kelamin ambigu, pada akhirnya harus dioperasi untuk “menormalkan” alat kelaminnya; membuat tubuh bayi menjadi lelaki atau perempuan.
Didikan di dalam lembaga pemasyarakatan telah mengkonstruksi dan menkonversi orientasi seksualitas Ryan, dan Ryan menerimanya. Ia dikonstruksi untuk menganggap bahwa orientasinya jahat, berdosa, melenceng, dan harus “dinormalkan”. Apalagi, jika kita mengingat statusnya sebagai seorang terpidana mati yang ingin dilepaskan dari jerat hukuman matinya, maka pertanyaan saya selanjutnya, apakah hal tersebut murni sebagai buah dari kesadaran ataukah efek dari pendisiplinan tubuh yang kita semua tidak tahu sampai kapan tubuh Ryan kuat merengkuh semua pendisiplinan itu. [T]
Probolinggo, 9 April 2022