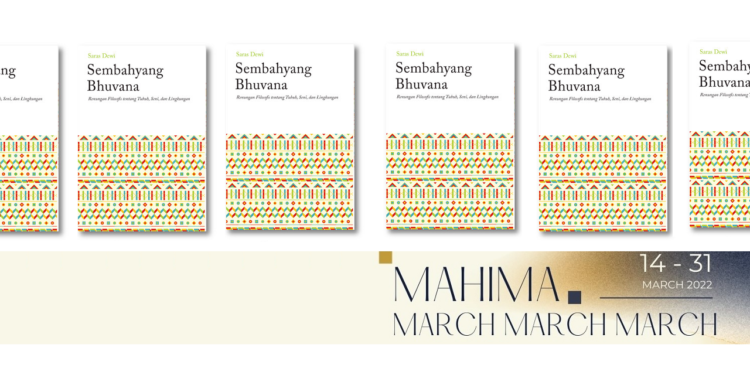Membaca Sembahyang Bhuvana karya Saras Dewi bagi saya adalah sebuah perjalanan panjang dari perjalanan tubuh, perjalanan pikiran, perjalanan spiritual, sekaligus pertanyaan yang belum hadir, memungkinkan segala hal yang terjadi; kemungkinan sekaligus segala ketakmungkinan.
Saya merindukan kelas filsafat bahasa yang bagi saya sangat saya gandrungi di kelas doctoral saya, dengan pengampu Prof. Januarius Mujiyanto. Kala itu saya mendapat pemahaman lebih dalam soal filsafat, dan kebetulan saya mendapat tugas membedah Wittgenstein.
Ketika saya membaca Sembahyang Bhuvana, kembali saya menemukan Wittgenstein disini. Bahwa filsafat memang mempertemukan semua kerinduan pada sebuah pertanyaan yang belum hendak selesai.
Tulisan saya soal Wittgenstein dapat disimak di Tatkala.co:
Bagi saya, dalam sebuah peristiwa membaca buku, ada banyak realitas dan imajinasi yang dihidupkan kembali. Menariknya, tidak satupun dari model pikiran itu yang dapat kita pahami dengan utuh sebagai sebuah makna yang tunggal, sebab dia hanya representasi gagasan dengan bahasa.
Sementara bahasa tidak akan pernah cukup digunakan untuk merepresentasikan gagasan, sama juga dengan pelukis yang tak pernah bisa menyuguhkan realita dengan gambar, semirip apapun objek dengan subjek yang digambar. Selalu ada hal-hal yang tak dapat dijelaskan oleh bahasa, oleh kata, oleh metafora. Dan disinilah barangkali, ini hanya barangkali, kita bisa menangguhkan kembali keyakinan kita pada apapun. Alih-alih yakin, kita harus terus mengupayakan penerjemahan makna yang baru terhadap apapun. Sebab, lagi lagi, tak ada yang bisa kita bahasakan dengan cukup.
Bagi saya Sembahyang Bhuvana adalah rangkuman dari rentetan pertanyaan, pernyataan, kegelisahan, dan suara Saras Dewi
dalam mencoba merepresentasikan gagasannya dalam tiga hal; tubuh, seni, dan lingkungan. Saya membatasi penjelasan saya pada perspektif Wittgenstein dalam konteks Tractatus-Logico Philosophicus, sebuah batas yang membingkai tulisan ini.
Tubuh sebagai Awal Tanya
Dalam tulisan pembukanya, Saras mengemukakan ide tentang bagaimana dia memulai pelajaran filsafat di jurusan Filsafat, ketika dia berusia 17 tahun. Ditanya buku filsafat apa yang dia baca, sejenak dia menimbang antara Bhagavad Gita atau Apologia nya Plato.
Ruang lingkup ilmu filsafat menjadi sebuah cabang pertanyaan pertama. Batang tubuh filsafat adalah awal tanya. Bagaimana membedakan atau mengkotakkan ilmu filsafat dari sistematika logosnya. Bhagavad Gita bertumpu pada kesadaran manusia sedangkan Apologia bertumpu pada sistematika logos yang kokoh.
Namun kemudian Saras menyadari bahwa tubuh adalah wahana yang digunakan untuk mengurai makna, memaknai realitas, atau mendudukkan realitas, yang tidak semata tercapai dengan struktur yang formal dan logis, namun juga dengan struktur yang sakral, struktur yang tak dapat terkatakan, seperti dalam konteks budaya Bali, dimana tubuh seringkali menjadi sebuah sarana untuk upacara sakral semacam Tari Sang Hyang. Ada struktur yang tak dapat terdefinisikan dengan jernih, karena keterbatasan kita memberi definisi, atau juga karena keterbatasan pengalaman dan imajinasi.
Campagna dalam tulisan Saras ini meminjam Chandogya Upanisad soal keterbatasan bahasa. Disinilah kemudian Saras juga mengupas rasa frustasi Wittgeinstein soal keterbatasan bahasa. Bahwa apapun yang belum dapat dikatakan dengan jernih, harus dibuang dalam kesunyian, atau tak dikatakan sama sekali.
BACA JUGA:
Bagi Wittgenstein dalam Tractatus Logico-Philosophicus, khususnya dalam tractatus nomor 1.1 The world is the totality of facts, not of things
Dunia ini kumpulan fakta, dan bukan kumpulan benda. Fakta itu sendiri bukan datang dan jatuh tiba-tiba, sendiri dan terpisah dari fakta lainnya. Hal ini dia nyatakan dengan tractatus 1.11. The world is determined by the facts, and by their being all the facts.
Tubuh, dalam perspektif Wittgenstein, adalah kumpulan fakta-fakta, bukan benda. Bukan object. Bukan sama sekali. Ia adalah kumpulan fakta, yang tidak berdiri sendiri.
Pada pengantarnya ia menjelaskan bahwa tractatus berusaha memberi batasan pada pikiran, atau pengejawantahan pikiran, dimana di dalam pembatasan pemikiran itu, kita harus menentukan batas apa yang terpikirkan dan yang tak terpikirkan. Jadi pembatasan bertumpu pada bahasa, dan apa yang tak dapat dibahasakan adalah nonsense.
Dan secara rendah hati dia mengatakan bahwa kekuatannya tak cukup untuk menyelesaikan semua problem pikiran dan bahasa, dan menyilakan filsuf lain melengkapinya. Dan bahkan diapun kelak menggugat pikirannya sendiri.
Kembali ke Sembahyang Bhuvana, Saras Dewi mencoba menguraikan persoalan tubuh dengan lebih kompleks, bahwa tubuh tidak sesederhana yang kita lihat, karena dia merangkum segenap fakta-fakta, sebab-sebab, akibat-akibat, trauma-trauma, dan banyak pertanyaan lainnya. Sehingga definisi tubuh tidak akan pernah mungkin menjadi definisi tunggal, jernih, dan terang-benderang, namun harus terus menerus dikupas, bahkan hingga muncul lapisan-lapisan baru yang mengejutkan dan tak dapat dijelaskan.
Tubuh memiliki suara yang dibawanya dan memiliki beban yang diwakilinya secara ideologi dan spiritual. Bahwa tubuh memiliki sebuah kekebasan yang bergerak ke ‘dalam’ dan ke ‘luar’, sebagai tubuh yang mewakili diri sendiri, dan sebagai tubuh yang mewakili sistem pikiran masyarakat. Seperti yang ditulis Merleau-Ponty soal tubuh dan keterjalinannya dengan lingkungan, dimana menurut Merleau-Ponty bahwa tubuh adalah sebuah keterjalinan antara manusia dengan alam, dimana manusia diwakili oleh tubuhnya berinteraksi dengan alam.
Seni sebagai Angan untuk Pembebasan
Seni adalah sebuah gagasan yang kita rindukan, karena sesungguhnya kita rindu pada kebebasan. Kita rindu pada kebebasan, barangkali sekali saja, sebelum semua berakhir sia-sia (?) atau berakhir tak sesuai harapan. Lalu kematian menjemput. Jadi apakah seni?
Dalam tulisannya “Seni dalam Lipatan Pandemi”, Saras mengatakan bahwa seni bisa menjadi sebuah cara mengekspresikan rasa, sebuah luapan perasaan yang terpendam selama pandemi, sebuah komunikasi antar batin yang membangkitkan empati dan sekaligus sebuah harapan, sebagai salah satu pegangan dalam mengatasi keputusasaan.
Seni adalah sebuah halaman yang lapang untuk mempertahankan kemanusiaan kita, bahwa masih ada harapan, masih ada hal-hal yang perlu dikerjakan. Setidaknya masih ada makna yang bisa dicapai atau dilengkapi.
Karya seni pada akhirnya adalah salah satu cara bagi manusia berbagi kegelisahan melalui simbol-simbol realita. Bahwa tujuan tidak pernah benar-benar kita raih, seperti rasa frustasi Wittgenstein pada realitas bahasa. Bahwa kita tak pernah benar-benar sampai. Ataukah apa mungkin kita benar-benar ingin sampai?
Saras menelusuri hal-hal yang lebih mendalam soal bagaimana seni mewakili hal-hal yang tak dapat kita terjemahkan dengan bahasa. Bahwa segala sesuatu adalah fenomena yang belum sepenuhnya dapat kita definisikan seperti bahasa yang belum dapat mengungkap dengan jernih sebuah fakta atau realita. Misalnya pada dunia Tari Sang Hyang dimana ada dua realitas tubuh; tubuh empiris dan tubuh non empiris. Di dalam dua realitas itu, selalu ada yang tak dapat dikatakan, sebuah fakta yang tak sesederhana bahasa, atau struktur logika.
Alam Sebagai yang Tak Terbatas Seluruhnya
Alam adalah sebuah realitas yang paling luas yang tak dapat didefinisikan dengan bahasa. Alam memiliki struktur sendiri, yang meskipun dikuliti dengan berbagai pendekatan saintifik, tetap menyisakan lubang besar dan hitam yang misteri. Apapun yang dilakukan oleh alam, hanya dapat dipahami oleh alam itu sendiri, dia bergerak dengan keinginannya sendiri, meskipun dapat dipicu atau diprovokasi oleh manusia.
Serangkaian fakta-fakta alam terlalu mustahil diterjemahkan dengan bahasa, sehingga dalam konteks laku budaya, alam memiliki pertautan dengan budaya. Dimana budaya memelihara alam, memuliakan alam adalah bahasa yang seharusnya digunakan untuk terus membuat alam ada, memelihara manusia dengan kebutuhannya.
Namun konteks ini berubah seiring dengan kemajuan jaman, bahwa alam diperalat untuk memahami manusia, bahkan dikerdilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga alampun membuat bahasa sendiri, yang sering disebut bencana.
BACA JUGA:
Saras Dewi dengan tawaran ekofeminisme mengatakan bahwa alam dan manusia harus berjalan beriringan, bukan berlawanan. Melalui kajian ritual Sang Hyang Dedari, Saras Dewi mengaktualisasikan teori Merleau-Ponty soal dualisme sisi alam yaitu sisi visible dan invisible. Sekala-niskala. Bhuana alit dan bhuana agung. Diri dan alam. Mikrokosmos dan makrokosmos. Seperti kata Wittgenstein dalam tractatus nomor 6.522. There are, indeed, things that cannot be put into words. They make themselves manifest. They are what is mystical.
Alam adalah pemilik segala pengetahuan yang maha. Kita hanya sebagian kecil yang menerka-nerka, mencoba-coba berusaha, memahami dengan keterbatasan. Akhirnya kita tiba pada tractatus nomor 7. What we cannot speak about we must pass over in silence. Dan segala hal yang belum dapat disampaikan dengan jelas, jernih, dan betul-betul pasti, harus kita lempar dalam kesunyian. [T]
Referensi
- Dewi, S. (2022). Sembahyang Bhuvana: Renungan Filosofis tentang Tubuh, Seni dan Lingkungan. Pojok Cerpen dan Tanda Baca.
- Lycan, W.G. (2000). Philosophy of Language. Routledge Contemporary Introductions to Philosophy.
- Wittgenstein, L. (1974). Tractatus Logico Philosophicus. Routledge Classic.
Catatan:
- Tulisan ini akan disampaikan dalam acara panel diskusi Philosophy in Language and Thought, Mahima March March March, 19 Maret 2022