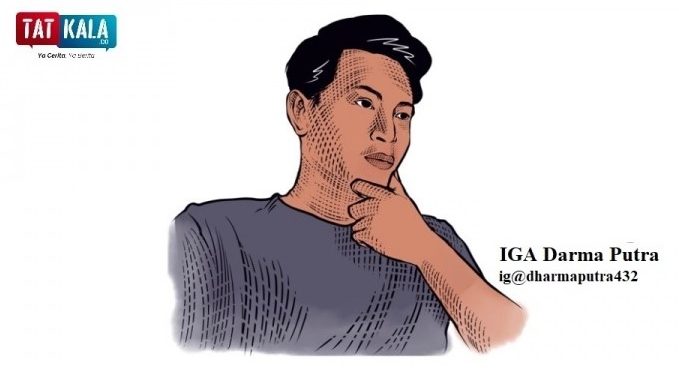Dasar tulisan sederhana ini adalah sebuah buku berjudul Meretas Jalan Meretaskan Peran yang diterbitkan oleh LKPP [Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan] Peradah Indonesia pada tahun 2004. Lebih tepatnya, yang saya baca adalah Kata Pengantar Editor-nya. Buku ini bukan milik saya, tapi milik Bli Arya Suharja yang namanya tertulis di sampul buku sebagai editor. Asal buku ini perlu saya jelaskan, agar pembaca tahu kalau sebuah buku tidak kehilangan maknanya meski hanya pinjaman.
Lebih-lebih karena buku ini adalah bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh editor dalam pengantarnya. Karena begitu, sudah kewajiban, buku pinjaman ini harus saya baca dan kembalikan pada saatnya nanti agar saya tidak kena kutuk karena mencuri ‘karunia Tuhan’. Pernyataan editor yang tidak kalah penting lagi untuk dicatat adalah bahwa buku ini merupakan salah satu wujud dharma bhakti bagi kemajuan masyarakat dan negara. Kedua kata itu, dimuat dalam satu teks lontar berjudul Wratti Sasana. Dharma salah satu terjemahannya adalah kewajiban, sedangkan bhakti saya terjemahkan sebagai pengabdian. Atau dengan kata lain: Sewana.
Hidup adalah pengabdian. Itulah core yang ingin saya sampaikan melalui tulisan ini. Mengapa itu? Tentu karena saya melihat hal ini dalam keseharian. Pertanyaan saya awalnya adalah ‘Untuk apa kehidupan ada?’
Dari penjelasan lontar-lontar tentang penciptaan dunia, saya melihat ada mata rantai yang putus. Selain karena penjelasan yang rumit, tentu karena gagal memahami manfaat dari diciptakannya kehidupan ini oleh sesuatu yang abstrak yang kita sebut Tuhan. Bila benar dunia ini diciptakan oleh Tuhan, saya tidak menemukan jawaban untuk apa Tuhan repot-repot menciptakan dunia dengan segala kemelutnya. Toh, pada akhirnya segala ciptaan ini akan dikembalikan kepada muasalnya. Saya tidak ingin menduga, kalau Tuhan sebenarnya hanya kurang kerjaan. Oleh sebab itu, hipotesa saya atas pertanyaan tadi adalah pengabdian.
Di dalam praktik-praktik ritual, semisal caru, saya melihat banyak hal yang diabdikan. Menurut saya, penghargaan yang setinggi-tingginya harus diberikan kepada binatang-binatang yang dicabut jiwanya untuk pengabdian ini. Binatang-binatang itu adalah ayam, sapi, kerbau, angsa, bebek, anjing, dan sebagainya. Kelengkapan caru yang demikian ialah gambaran caru yang dilakukan di Bali sampai saat ini. Caru paling simple yang saya kenal sampai sekarang adalah caru abrumbunan yang menggunakan seekor ayam. Namun, bila kita sedikit rajin membaca, ada satu caru yang dilakukan tanpa menggunakan binatang.
Caru ini disebut caru skul dinyun. Caru ini berupa nasi yang dimasukkan ke dalam kendi dan ditanak dengan susu. Nantinya, nasi itu akan dimasukkan ke dalam tungku [kunda] sebagai bentuk pemujaan kepada Brahma. Informasi caru skul dinyun bisa kita temukan dalam prasasti Lintakan yang dikeluarkan oleh raja Tulodong pada tahun 841 Saka [919 Masehi]. Informasi lainnya tentang caru tanpa darah, bisa kita temui dalam teks Adi Parwa sebagaimana dijalankan oleh seorang Brahmana yang bernama Jaratkaru. Ini berarti, upacara caru selain menggunakan binatang, juga dapat menggunakan tumbuhan semata. Di dalam sumber-sumber yang kebetulan pernah saya temui, belum ada caru dengan mempersembahkan gambar. Begitulah saya memandang hidup dan kehidupan sementara ini.
Hal lain yang di-highlight oleh editor dalam buku ini, adalah perihal swadharma. Editor mengatakan bahwa “sebagaimana disuratkan dalam Sastra, melaksanakan swadharma, meskipun tidak sempurna, lebih baik dari pada melakukan dharma orang lain dengan sempurna”. Jelaslah Sastra – yang ditulis dengan italic dan huruf kapital – yang dimaksud oleh editor adalah Bhagawadgita, Adiyaya III, sloka ke-35. Kitab yang semasa saya menempuh pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, disebut-sebut sebagai kitab Weda yang kelima [Pancama Weda].
Saat diajarkan tentang Pancama Weda, saya tidak bertanya mengapa disebut demikian, bukan karena tidak berani bertanya, tapi karena bodoh. Waktu itu, Bhagawadgita yang saya baca adalah terjemahan yang dikerjakan oleh Agus S. Mantik [2007]. Buku ini sebenarnya berisi ‘cap’ tidak diperdagangkan, karena merupakan bagian dari Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pengadaan buku seperti ini barangkali adalah cara Pemerintah melakukan pengabdian. Sekali lagi, pengabdian.
Lanjutan dari sloka ke-35 itu ialah “lebih baik kematian [di dalam memenuhi] kewajiban sendiri, sebab menekuni tugas orang lain sesungguhnya berbahaya” [BG.III.35; hlm.196]. Dengan kata lain, melaksanakan kewajiban sendiri [swadharma] sedemikian pentingnya, meskipun harus mati. Namun, sebelum mati, tugas paling awal adalah mengenali swadharma. Memahami kewajiban sendiri. Bagaimana caranya? Sayangnya, dalam ingatan saya yang sangat samar tentang Bhagawadgita, sepertinya di dalamnya tidak tersedia jawaban.
Oleh sebab itu, saya mencari jawabannya di tempat lain, tepatnya di dalam Sastra yang lain. Dalam geguritan Salampah Laku, IPM Sidemen menyebut guna dusun [ilmu desa]. Hemat saya, yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu yang berlaku atau yang bermanfaat secara praktis di masyarakat. Hal-hal yang dapat digunakan di masyarakat kita jadikan pekerjaan [gina] dengan belajar terlebih dahulu agar mendapatkan pengetahuannya [guna]. Kata kuncinya adalah guna-gina. Meskipun, di dalam alam bawah sadar – orang Bali khususnya – sebenarnya tidak pernah menganggap pengetahuan apapun adalah milik sendiri. Mereka menganggap pengetahuan adalah milik dewa-dewi, sedangkan manusia hanya pelayan [sewaka] yang melayani [sewanam]. Tubuh manusia hanya dipinjam untuk mengalirkan pengetahuan-pengetahuan itu. Sekali lagi, untuk pengabdian.
Terakhir, editor menyatakan harapannya agar dapat “mewujudkan kehidupan bersama yang Indonesiawi, manusiawi, dan dilimpahi karunia Tuhan.” Dua kata yang diakhiri oleh sufiks -wi di depan, menggambarkan negarawan dan kemanusiaan [humanis]. Sedangkan harapan terakhir jelaslah sekali lagi menunjukkan religiusitas, keber-Tuhan-an. Tiga hal yang sebenarnya bisa kita tarik ke dasar Negara.
Tetapi, saya tidak ingin menarik benang merah ini ke arah sana. Saya justru ingin mengulur benang merah ini agar lebih panjang dan bisa ditarik ke segala penjuru oleh para pemikir-pemikir yang terus berjuang mengurai benang merah yang terlanjur kusut ini. Dengan begitu, kita bisa melihat kelindan yang awalnya tidak kelihatan meski samar-samar karena mabelat kelir. Dasar usaha untuk mengurai benang merah yang kusut ini adalah pengabdian. Jñāna yajña, toch?. [T]