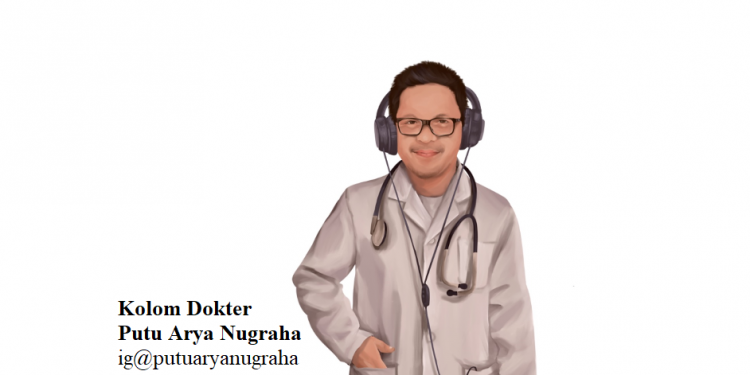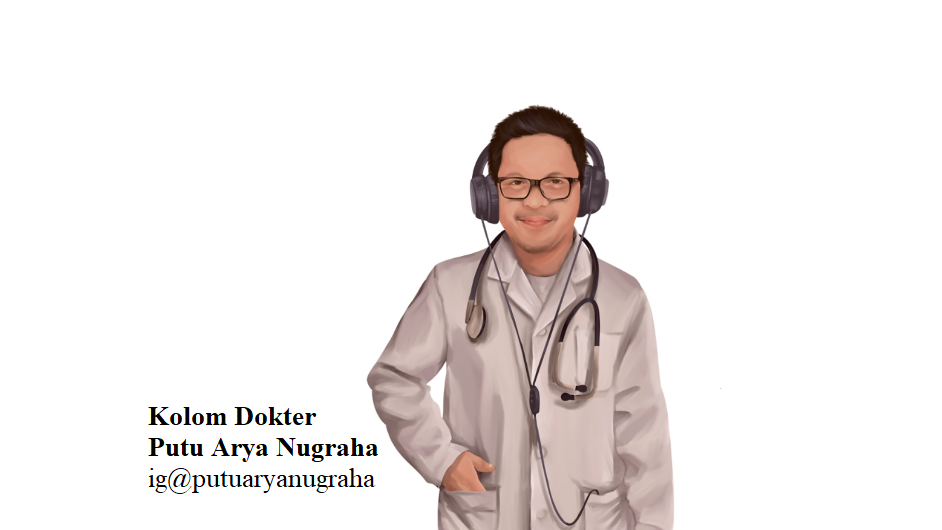“Tuhan bersemayam dalam hati setiap insan, usah lagi berkelana untuk mencarinya.”—- (Jalaludin Rumi)
Akankah sabda sederhana sang pujangga ini akan pernah menjadi pegangan hidup setiap insan di bumi? Berkali-kali alam memberi kode kepada kita, hal-hal sederhana telah menentukan yang vital. Oksigen (O2) dan airlah (H2O) yang menjaga kehidupan mahluk hidup bukannya C2H5OH (alkohol) atau C8H15 (bensin).
Tapi apa yang telah kita lakukan selama ini? Sangat terang, memusnahkan sumber oksigen dan air yang vital dengan merusak hutan belantara secara membabi buta. Tepatlah sindiran ahli astrofisika Hubert Reeves, “Manusia adalah makhluk yang paling gila. Mereka memuja Tuhan yang tidak terlihat dan merusak alam yang terlihat tanpa menyadari bahwa alam yang sedang mereka rusak sebenarnya adalah manifestasi Tuhan yang mereka puja.”
Kelahiran yang ditunggu-tunggu misalnya, sesungguhnya tak menuntut perayaan apapun, ia hanya butuh tangisan. Maka untuk bayi baru lahir, tangisan adalah kehidupan. Ini sebuah prototype betapa kehidupan begitu sederhana. Lalu kita membuatnya sedemikian rumit dan menyusahkan, bahkan tak sedikit mengundang bencana dan kehancuran.
Suriah dan mungkin juga beberapa bangsa lain di Timur Tengah adalah satu model yang sangat baik bagaimana agama menjadi pemusnah masal. Dari mana pujangga-pujangga besar yang telah menggugah kebijaksanaan kita berasal, Jalaludin Rumi atau Kahlil Gibran. Di negeri-negeri yang indah dan kaya itu, manusia memang telah menciptakan praharanya sendiri, dalam konflik sosial berkepanjangan atas nama agama, bahkan dengan yang seiman.
Maka tepat rasanya ucapan Gandhi, sang jiwa agung, “Orang yang berkata bahwa agama tidak ada kaitan sama sekali dengan politik, tidak tahu apa sebenarnya arti agama.” Gagasan ini terasa menjadi begitu visioner jika kita amati fenomena politik saat ini, tidak hanya di Timur Tengah, pun di dalam negeri.
Apakah kemudian cuma agama Islam yang oleh segelintir pemeluknya dibawa menciptakan kerumitan? Tentu saja tidak, hampir setiap pemeluk telah menyeret agama dan keyakinannya untuk menjadi bengis.
Kita pasti masih ingat betapa mengerikannya pembantaian warga muslim yang sedang beribadah di sebuah masjid oleh seorang ekstremis Kristen di kota Christcurch yang tenang di Selandia Baru.
Di India, tanah kelahiran sang jiwa agung Mahatma Gandhi pun tak luput dari prilaku intoleransi sekelompok militan Hindu. Dan yang paling fenomenal tentu saja pernyataan-pernyataan provokatif anti Islam seorang biksu radikal di Myanmar bernama Ashin Wirathu hingga ia dijuluki sebagai “Buddhist bin Laden”.
Mungkinkah sejak awal kelahirannya, agama adalah sebuah kekeliruan? Kecemasan ini mudah dimaklumi, misalnya kenapa hingga kini agama telah begitu banyak menciptakan tangisan. Bukankah bagi seorang bayi, untuk sebuah kelestariannya, tangisan sudah cukup saat kelahirannya saja? Sepertinya romantisme spirit pertarungan dalam melahirkan agama-agama manusia ini, tanpa disadari telah diwariskan kepada sejumlah penganutnya.
Spirit inilah yang menurut Gandhi kemudian mudah diinfiltrasi oleh motif politik kekuasaan. Secara primordial agama memang telah membatasi dirinya dengan penganut yang lain, lalu politik meninggikan tembok berduri kawatnya. Sekali keluar, bukan lagi untuk hangat berjabatan tangan, namun terbakar untuk menyerang yang lain dalam spirit glory, kemenangan agama. Politik memanfaatkan identitas dan tradisi yang berbeda antar agama, bahkan yang sering kali bertolak belakang. Inilah yang hari ini secara vulgar disuguhkan terang-terangan sebagai pertarungan suci yang harus dimenangkan.
Sudah saatnya identitas, simbol dan tradisi agama dikembalikan ke ruang-ruang hening pribadi kita semua. Cukuplah esensi-esensi agama yang kita sebut sebagai spiritualitas untuk disajikan dalam kehidupan bersama.
Nilai-nilai spiritual, karena ia esensi dalam setiap agama, maka ia akan mudah melebur dan menyatu dalam denyut nadi kehidupan semua manusia di bumi, universal. Jika Hindu merayakan Galungan dan Nasrani menyambut Natal, atau Muslim pergi ke Masjid dan Budha sembahnyang di Wihara, itu adalah warna-warni keindahan pelangi agama-agama di Indonesia. Di atas keindahannya ada kekuatan spiritual yang sama yaitu kebaikan.
Dalai Lama mengatakannya dengan, “Agamaku adalah kebaikan.” Atau boleh juga cara pandang sederhana budayawan Cak Nun, “Agama itu letaknya di dapur. Tidak masalah mau pakai wajan merk apa di dapur, yang utama adalah makanan yang disajikan di warung sehat. Maka ukuran keberhasilan orang beragama bukan pada sholat atau umrohnya, melainkan pada perilakunya.” Sedemikian menyentuh, mendasar dan universal.
Kita rindu ruang-ruang hening agama yang telah lama kita tinggalkan. Tumpah ruah hingar bingar kita bawa agama ke jalan-jalan layaknya perayaan karnaval. Ia perlu dipamerkan untuk mendapat riuh tepuk tangan. Jika mungkin bahkan perlu like dan subscribe sebanyak-banyaknya, demi juara atau pendapatan. Untuk itu kita butuh agresivitas, intimidasi bahkan kebohongan, demi kompetisi dan persaingan ini.
Kita rindu ruang-ruang hening agama yang telah lama kita tinggalkan karena seperti tangisan bayi baru lahir, agama adalah kesederhanaan vital yang lain. Ia meminta kita untuk berhenti, karena hanya dengan diam kita punya kesempatan mendengarkan dan melihat hati kita. Lalu bersepakat dengan Jalaludin Rumi, Tuhan ada di sana. [T]