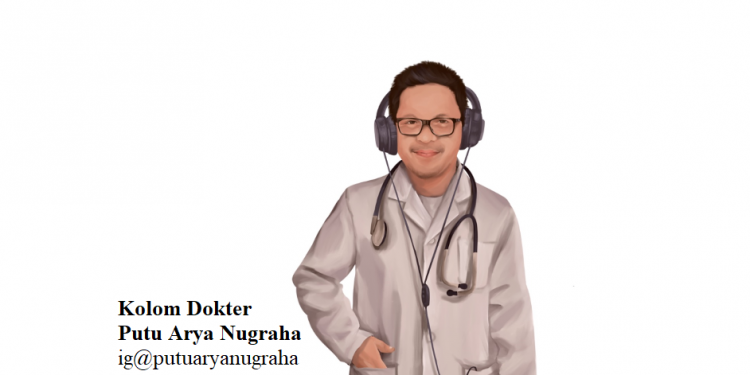“Teman-teman lama pergi, teman-teman baru datang. Hal ini sama seperti hari. Hari yang lama berlalu, hari baru tiba. Yang penting adalah untuk membuatnya berarti, seorang teman yang berarti atau sebuah hari yang berarti.” (Dalai Lama)
Rangkaian kata-kata Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso ini, rasanya relevan di masa pandemi Covid-19 yang telah mengombang-ambingkan perasaan sebagian besar manusi di bumi. Hingga kini, jumlah kematian global akibat pandemi SARS-Cov-2 ini telah mendekati 1 juta jiwa dan sepertinya akan terus terjadi. Tak terhitung sudah, gundukan kesedihan dan derai air mata yang menyertainya. Namun, Dalai Lama berpendapat sedemikian sederhana soal kematian. Mungkin saja inilah sesungguhnya realitas yang selama ini kita tampik dan ingkari. Kehidupan dan kematian, kedatangan dan kepergian, teman-teman, hari dan waktu, sepenuhnya semua dalam ketepatan sebuah perhitungan, namun sedikit pun tak bisa kita intip dalam tabir misteri yang abadi. Bahkan melampaui ketinggian negeri atap dunia, negeri bangsa Tibet, hingga mereka pun mengikhlaskannya segala takdir berputar meluncur pada orbit keniscayaannya. Lalu, Tibet pun tak tersentuh pandemi dan globalisasi.
Akan globalisasi, seakan kota Lhasa yang bisu menggugat, sepenting apakah globalisasi? Betulkan dengan globalisasi kalian bahagia, lebih dari kebahagiaan kami? Masyarakat Tibet yang seakan berputar di sekitar titik nol memang hampir tidak ambil pusing dalam dinamika hubungan transnasional yang mendalam dan sangat saling mempengaruhi. Bahkan mereka cenderung diam saat pemerintah RRC nyata-nyata telah menindas dan merampas kebebasan mereka. Tak ada pemberontakan seperti di Mindanao, Filiphina atau Palestina di Timur Tengah. Dalai Lama, sebaliknya melakukan perjuangan non kekerasan yang hingga saat ini hidup dalam pengasingannya di Dharmasula, India. Apakah sebaliknya mereka lebih baik dan bahagia? Terdapat beberapa fenomena yang sangat menarik untuk diketahui, karena sama-sama terjadi baik di dalam masyarakat liberal barat atau masyaraakat terbuka di timur maupun di dalam masyarakat konservatif Tibet, namun semuanya dikunci pada perspektif yang sangat berbeda. Misalnya dalam perkawinan dan hubungan seks atau ritual penguburan jenazah.
Masyarakat Tibet menerapkan praktek poliandri. Fenomena ini mengingatkan kita pada kontroversi kisah Mahabrata. Diceritakan, kelima anak Kunti berbagi seorang istri, Drupadi. Secara harfiah, kisah ini takkan pernah kita bisa terima atau dapat kita cerna dengan baik dan melegakan. Selamanya ada rasa risih dan keinginan untuk melawan drama yang janggal ini. Namun faktanya, dalam kehidupan sehari-hari yang terselubung dalam kabut gelap hipokrit masyarakat timur, setiap hari ada perselingkuhan seksual. Kaum lelaki yang diam-diam telah berbagi wanita. Bahkan di dalam masyarakat liberal barat, adegan persetubuhan seorang wanita dengan banyak lelaki pun adalah hal jamak dijadikan lahan bisnis hiburan. Keduanya, seakan mengalir normal biasa saja. Sebaliknya, masyarakat Tibet memang serius menjalankan tradisi poliandri ini, saat seorang wanita memiliki suami lebih dari seorang dan dapat melahirkan anak-anak dari kedua suaminya. Dan mereka hidup bersama. Bukan dalam kisah-kisah gelap yang disembunyikan atau hanya sebagai hiburan belaka. Manakah yang lebih bahagia? Rasa ngeri-ngeri sedap tabir perselingkuhan yang setiap saat bisa terkuak? Atau wanita-wanita yang dibagi kaum lelaki yang erotis digandrungi namun dicibir? Atau poliandri yang berjalan kalem setara dengan poligami? Poliandri bisa jadi merupakan sebuah fakta penaklukan diri sendiri lelaki Tibet, yang sebaliknya bagi lelaki di dunia lain dituntut untuk menaklukkan orang lain, terutama wanita.
Dalam tradisi dunia barat dan timur pada umumnya, masyarakat sangat menghormati jenazah dan diwujudkan dalam penatalaksanaannya. Coba lihat misalnya, sebuah pemakaman mewah di Los Angeles, bernama Westwood Village Memorial. Pemakaman ini meski terletak di pusat kota namun mengesankan suasana sangat asri pedesaan. Perlu merogoh kocek puluhan juta rupiah untuk dapat dikubur di sana. Atau yang dekat-dekat di kampung kita sendiri di Bali, upacara Ngaben untuk pemakaman jenazah dapat menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah dengan berbagai sarana yang sarat seni dan ritual. Nah, bandingkan sekarang dengan tradisi masyarakat Tibet yang terkenal ekstrim bernama “Pemakaman langit”. Prosesi ini diawali dengan mendoakan jenazah, kemudian membawanya ke puncak gunung tempat dimana banyak burung pemakan bangkai berada. Di puncak gunung, jenazah ditelungkupkan, kemudian disayat-sayat oleh seorang petugas agar mengundang burung pemakan bangkai datang dan menghabiskannya hingga tulang belulang orang mati tersebut. Bukankah tradisi ini terasa mengerikan dan seakan-akan tak etis maupun brutal alih-alih spiritual?
Masyarakat Tibet percaya, mereka akan tetap bahagia, tanpa globalisasi. Buktinya, mereka pun tak dihampiri pandemi Covid-19. Hanya ada laporan satu orang pasien terkonfirmasi yang itu pun adalah pelancong dari China dan sudah dinyatakan sembuh sekitar bulan Pebruari yang lalu. Wabah global yang merisaukan ini sepertinya mengingatkan kita semua, ambisi akan kejayaan dan kemenangan memang selamanya berada di bawah ancaman kejatuhan dan kekalahan. Ambisi menguasai dunia dan menginvasi antariksa, dengan sedemikian enteng diluluhlantakkan oleh seuntai RNA SARS-Cov-2 yang bagaikan imajinasi. Virus ini memastikan pada dasarnya kita semua sama, satu dalam rasa takut dan ketidakberdayaan. Satu-satunya terapi yang paling mujarab saat ini adalah, melihat semua kekacauan ini dengan cara sederhana seperti Dalai Lama, “Seberapa pun kesulitannya, seberapa pun sakitnya pengalaman tersebut, jika kita kehilangan harapan, saat itulah bencana yang sesungguhnya.” [T]