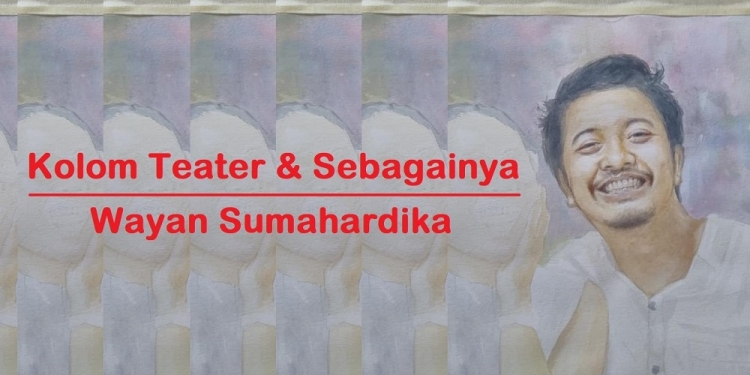Bicara soal fotografi, tentu perbincangan tak jauh-jauh tertuju pada yang namanya kamera. Saat melihat orang menenteng kamera, khususnya ketika saya memikirkan bagaimana membuka tulisan kali ini, entah kenapa ingatan jadi tertuju pada pengalaman masa kecil. Betapa saat itu, saya merasa kamera menjadi barang mahal yang tak sembarang orang bisa memakainya. Jika bukan wartawan, pastilah ia fotografer. Jika ia fotografer, tentu foto-foto yang dihasilkan bukan sembarang foto.
Memang, begitu naif pikiran saya kala itu, hampir sama naifnya dengan pikiran yang beranjak dewasa kini, ketika kian lazim menatap orang penantang-penenteng membawa kamera. Entah memang bisa membidik dengan benar atau hanya sekadar gaya. Namun pada mereka yang menenteng kamera dalam acara teaterlah saya masih meyakini, bahwa orang-orang ini pasti benar-benar fotografer. Bagaimana tidak? Jika cuma fotografer sekadarnya, dijamin 100% ia takkan memilih teater sebagai objek foto. Jangankan memoto, datang saja belum tentu ingin.
Misal ia adalah fotografer sekadar pingin cari cewek, cewek seperti apa yang bisa difoto dalam pertunjukan teater yang kebanyakan ditutupi make up? Iya, kalau memainkan karakter perempuan pesolek, kalau memerankan tokoh nenek-nenek? Betapa sial nasib mereka. Lain lagi dengan fotografer sekadar cari uang, teater tentu tak akan mampu memberi mereka peluang materi selain hanya ucapan terima kasih. Apalagi fotografer sekadar eksis di instagram. Jelas, teater bukanlah pilihan objek yang tepat jika dibandingkan dengan view pemandangan, acara budaya dan tradisi yang mahapariwisatanya bagi kelestarian Bali.
Dari sekian banyak fotografer yang bertebaran ini, adalah Agus Wiryadhi Saidi salah satu fotografer yang senantiasa hadir secara sukarela untuk mengabadikan pentas teater. Pada 28 November lalu, pada diskusi ‘Pertimbangan Fotografis dalam Pentas Teater’ acara Parade Teater Canasta 2019, kami cukup beruntung menyimak Guswier ngobrol ihwal proses kreatifnya selama 15 tahun dalam mendokumentasikan pertunjukan teater.
Secara implisit, Guswier menjelaskan bahwa foto teater bukanlah sebatas foto dokumentasi atau foto berindah-indah yang menggambarkan kegarangan atau kegantengan wajah aktor di atas panggung. Lebih dari itu, foto teater adalah foto peristiwa di atas peristiwa yang melahirkan peristiwa. Artinya, teater yang notabene merupakan pemanggungan peristiwa sehari-hari, bertransformasi jadi peristiwa baru baik di mata penonton dan fotografer. Ketika dibekukan dalam mata kamera, ia hadir sebagai bentuk peristiwa tersendiri lagi.
Dalam konteks ini, kerja fotografi teater sebenarnya beda tipis dengan fotografi jurnalistik yang kerap diungkapkan sebagai satu gambar sejuta kata. Foto teater juga berupaya untuk melahirkan sejuta kata atau narasi lain di luar apa yang ‘tampak’ dalam fotonya. Bagaimana posisi bidik foto jurnalistik misalnya, yang fokus pada sepatu tentara dan senjata api dengan berjubel rakyat yang duduk saling peluk sebagai latarnya, begitu pula kualitas yang hadir dalam pertimbangan fotografer teater dalam menentukan pilihan bidiknya di tengah permainan aktor, set properti, dekor dan komposisi pentas.
Lebih khusus lagi, pada kerja fotografi teater, hadir tawar-menawar fotografer dalam menyesuaikan cahaya, desain panggung, penonton dan durasi pentas. Jika diumpamakan, fotografi teater merupakan seni melukis cahaya dalam medan perang berdurasi, sesuai durasi pentas teater. Sementara dalam fotografi jurnalistik, perang bisa berhari-hari lamanya, disertai kemungkinan tewas yang senantiasa menghantui sang fotografer. Sedang pada foto teater, tewasnya fotografer adalah selama pentas berlangsung, ia tak mendapatkan foto yang membuat dirinya puas. Lebih-lebih setelah pentas, ada pemain teater yang minta foto kepadanya, ‘Pak.. tadi bapak foto saya, kan?’
‘Ha? Ehm… ah.. ehm.. coba ta cek dulu di kamera, ya..’
Lalu…..
Tewas.
Demikianlah, foto jurnalistik dan foto teater punya kecenderungan yang mirip namun tak sama. Yang paling berbeda mungkin adalah apresiasinya di ruang publik. Hingga kini, kian banyak penghargaan yang dibuka untuk kerja-kerja foto jurnalistik, seperti Pulitzer, NPPA, Picture of The Year International dan lain sebagainya. Ini tentu jauh berbeda dengan foto teater yang notabene seringkali disikapi sama dengan foto dokumentasi biasa. Bukan hanya oleh penikmat foto saja, bahkan oleh seniman teater dan pihak penyelenggara pentas sendiri. Buktinya, seberapa banyak sih digelar acara yang khusus mendiskusikan fotografi dalam teater atau memberi ruang karya seni fotografi teater untuk berhadapan pada panggung publik?
Dalam ingatan saya sendiri, sedari tahun 2011, hanya ada dua acara yang secara khusus menghadirkan karya fotografi teater di Bali. Pertama adalah pameran foto pentas ‘Kereta Kencana’ karya Iuginne Iunesco yang diselenggarakan oleh Teater Kampus Seribu Jendela Undiksha. Pameran foto yang bertempat di Kampus Bawah Undiksha Singaraja ini menyajikan foto-foto karya fotografer yang sempat membidik pentas Kereta Kencana dalam acara Parade Teater Arti Foundation 2011. Hardiman Adiwinata, sebagai sutradara pentas sekaligus inisiator pameran saat itu meyakini, bahwa teater tak boleh hanya berhenti pada panggung semata. Fotografi justru merupakan satu medium yang berpotensi melahirkan narasi-narasi lain di luar konteks pertunjukan teater itu sendiri.
Kedua adalah pameran Fotografi “Teater Kita: Panggung Baru” pada tahun 2014 yang diinisai oleh tiga fotografer Bali, yakni Agus Wiryadhi Saidi, Phalayasa Sukmakarsa dan (alm) Ida Bagus Darma Suta. Pameran yang digelar di Six Point Restaurant & Bar, Denpasar ini jadi penting artinya dalam konteks fotografi teater Bali saat itu, mengingat pilihan ruang restorant yang tak biasa dipilih sebagai tempat pameran. Justru pada ruang restaurant inilah, hadir semacam interaksi liyan di luar penonton yang pernah menyaksikan teater dalam foto yang dipamerkan.
Lain daripada itu, event fotografi pertunjukan hanya hidup pada lomba-lomba saja. Parahnya, lomba-lomba ini justru hanya sebatas lomba, yang tak jauh beda penyelenggaraannya dengan lomba fashion show, karaoke, atau mc tingkat sekolah. Hanya mengejar piala, tanpa ada gagasan dan wacana. Event yang tampak begitu gagap berhadapan dengan publiknya. Bagaimana tidak gagap? Jangankan ada kurasi dan pertanggung jawaban lomba, jurinya pun tak jelas siapa. Tiba-tiba saja ada lomba, tiba-tiba saja nama-nama juara terpampang di instagram, tiba-tiba saja penyerahan piala dan tiba-tiba saja hilang. Lalu apa yang bisa diharapkan dengan penyelenggaraan event yang tiba-tiba saja semacam itu?
Makin ironis kiranya jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kerja teater yang berkembang hari ini, seperti program teater arsip yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Jakarta yang mengeksplorasi arsip sebagai bahan pertunjukan dan acara teater. Ada pula kerja berbasis fotografi seperti yang dilakukan Radar Panca Dahana. Yang dalam salah satu esai pertunjukannya, sempat menggunakan foto sebagai sumber data dalam rangka membedah pentas tanpa pernah sekalipun melihat pertunjukannya secara langsung. Atau pada kerja seniman teater Riyadhus Shalihin dengan naskah Cut Out-nya yang ditulis berdasar pada dokumentasi foto sejarah dan lukisan Indonesia. Dari kerja-kerja ini, teater tak lagi dibatasi pada kepentingan membuat pertunjukan semata, melainkan mewujud dalam berbagai produk kerja seni seperti pameran, workshop, diskusi pun sebagai metode menciptakan pertunjukan baru yang berdasar pada arsip. Salah satu arsipnya, ya fotografi tadi.
Kini, sudah lima tahun berlalu sejak pameran foto terahkir “Teater Kita: Panggung Baru” digelar. Saya yakin, foto-foto di kantung kawan-kawan fotografer teaterpun banyak yang sudah berbiak lagi. Demikian pula dengan kehadiran fotografer muda yang kian marak menghadiri dan mengabadikan acara-acara teater, seperti Putu Sayoga, Syafiudin Vifick, Wayan Martino, Dodik Cahyendra, Hadhi Kusuma, dan kawan-kawan lainnya. Dalam diam dan kesenyapannya, mereka senantiasa mengisi ruang-ruang kosong dalam pertunjukan teater. Tentu jadi pertanyaan yang penting kemudian untuk diajukan pada hadirin, penyelenggara, dan khususnya seniman teater yang kerap diabadikan pertunjukannya. Tak adakah yang bisa direspon dari kerja-kerja fotografi teater kita sampai hari ini? Atau jangan-jangan memang sudah cukup puas oleh kerja fotografi teater, yang hanya berhenti pada tanda jempol di FB dengan komentar, ‘toooooopppp’ saja? [T]
Denpasar, 2019