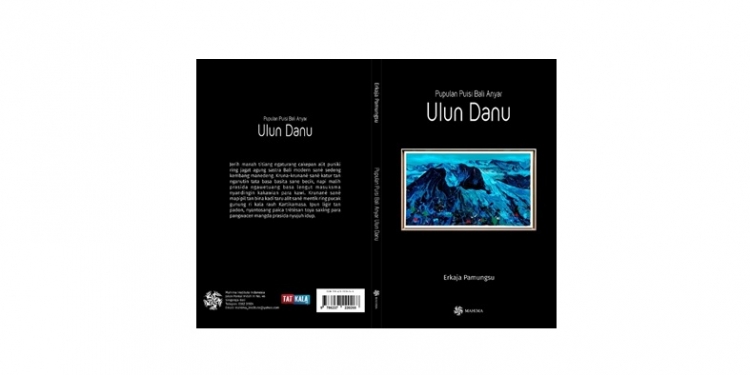- Judul Buku : Ulun Danu
- Penulis : Érkaja Pamungsu (IK Eriadi Ariana)
- Penerbit : Mahima Institute Indonesia
- ISBN : 978-623-7220-26-8
- Jumlah Halaman : viii + 105
I Ketut Eriadi Ariana atau biasa dipanggil Eriadi, laki-laki yang lahir 16 Juli 1994 di Batur ini, aktif menulis sejak terdaftar menjadi mahasiswa di Universitas Udayana pada tahun 2013. Puisi pertamanya yang dimuat dalam media berjudul “Purwa [Ha Na Ca Ra Ka]” di media massa Pos Bali. “Pupulan Puisi Bali Anyar Ulun Danu” ini merupakan hasil karya pertamanya dan sekaligus sebagai debutnya menjadi penulis professional. Bagi saya, buku ini merupakan kumpulan puisi berbahasa Bali yang pertama saya baca dan tentu meninggalkan kesan tersendiri bagi saya. Walaupun saya adalah orang Bali asli, tetapi tetap saja saya mendapatkan beberapa kesulitan dalam mengartikan puisi ini, karena tentu saja sang penulis tidak menyuratkan maksud sesungguhnnya dalam setiap puisi yang dituliskan. Namun, tentu hal ini semakin membuat saya tertantang untuk menyelesaikan membaca buku ini dan setidaknya menarik kesimpulan dari keseluruhan puisi yang dituliskan sang penulis.
Buku kumpulan puisi Bali modern Ulun Danu ini terdiri dari 100 judul puisi yang dituliskan Eriadi sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Melalui puisi-puisi yang tersaji dalam buku ini saya dapat merasakan kegelisahan sang penulis terhadap alam di kampung halamannya. Cara sang penulis dalam mengangkat permasalahan disekitarnya sangatlah “cantik” bagi saya, karena penulis menuangkan keresahannya melalui karya dan dengan rangkaian kata-kata indah. Keresahan-keresahan tersebut dapat kita lihat dalam beberapa judul seperti Ulun Danu #2 (hal: 7), terlihat dalam kutipan berikut.
Ulung!
Campuhané mamungkah
Dumun Mangening mangkin tan éning
Sangkaning kramané tan pada éling
Selain judul puisi tersebut, ada beberapa judul puisi yang menggambarkan keresahan dari penulis terkait kelangsungan alam di Kintamani. Hal ini tersurat dalam puisi yang berjudul Alas Arum (hal: 14) di bait terakhir, terlihat dalam kutipan berikut.
Alas arum sampun kapandung
Ilang pundukan ilang kaluhuran
ilang alas ilang makejang
Keresahan yang dirasakan oleh penulis sangatlah wajar terjadi, hal ini dikarenakan banyak perubahan terjadi mengarah ke arah kurang baik, seperti semakin maraknya pencemaran danau Batur dengan sampah, begitu juga kalderanya yang sejak tahun 2012 ditetapkan menjadi Global Geopark Network (GGN) UNESCO yang dapat dilihat dari puncak Gunung Batur. Selain Danau dan Kalderanya, Gunung Batur juga mengalami perubahan yang signifikan. Saya pun merasakan perubahannya pada bulan Juni lalu dimana puncak Gunungnya terasa lebih luas dan menurut penulis, hal itu sengaja dilakukan oleh warga untuk memberi kenyamanan kepada pendaki yang ingin berfoto atau menikmati alam Batur dari puncak Gunung Batur. Namun, bagi saya pribadi hal ini akan menimbulkan dampak negative yaitu merusak topografi alam. Mari kembali kita bahas kumpulan puisi Bali modern Ulun Danu dari Eriadi.
Selain memunculkan keresahan, penulis juga menuliskan kekagumannya terhadap alam Bali yang ia nikmati kala itu. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa judul puisi seperti Tegeh (hal: 35), terlihat dalam kutipan tersebut.
Cemara ngarokot makilit
Di belahan embidan batu
Makrama nyarengin Sang Bunga Kasna
Matinggah di muncuk utama
Gelung agung Hyang Udara Parwata
Puisi ini ditulis oleh penulis saat mendaki Gunung Agung pada tahun çaka 1939 atau tahun 2017 yang dimaksudkan untuk mengagumi keindahan panorama yang disuguhkan oleh Gunung Agung dari puncaknya. Selain itu, kekaguman juga dapat ditemukan dalam puisi berjudul Ratu Brutuk (hal: 65).
Hyang Ratu Brutuk masolah tan punah
Ring Kahyangan Pancering Jagat I Ratu munggah
China panunggalan sang rwa purusa-pradana
Ngamedalang bhuana agung alit jagadhita
Menurut saya, puisi ini mewakil rasa kagum dan bangga sang penulis terhadap tanah kelahirannya yang memiliki salah satu tradisi yang luar biasa unik. Barong Brutuk merupakan tarian yang ditampilkan setiap dua tahun sekali pada saat piodalan atau upacara Ngusaba Kapat di Pura Pancering Jagat di desa Trunyan.
Tidak hanya keresahan, kekaguman, dalam buku ini juga saya melihat adanya beberapa puisi yang lekat dengan kehidupan sang penulis, seperti yang tertuang pada salah satu puisi yang berjudul Kelir (Katur ring Arsaning Hyang) (hal: 99).
jani ba palas mabatas kelir awak
ané makebat melat ngilehin
majajar tipis nyengkerin angkihan
nguwatan bates manyama di gumi
Jika kita membaca isi puisi ini secara utuh, maka kita akan mengetahui bahwa puisi ini menunjukkan rasa kehilangan yang teramat dalam terhadap seorang saudara yang sangat disayangi.
Dari beberapa puisi yang saya coba bahas dalam tulisan ini, tentu masing-masing memiliki makna yang begitu dalam oleh sang penulis dan ditulis dengan analogi yang dalam pula. Namun, ada satu puisi yang saya temukan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Puisi ini mengisahkan seorang pemuda yang menikmati suasana memilah cengkeh di desa yang berada di punggung pulau Bali yakni Desa Sembiran. Puisi ini berjudul Wukir Samirana (hal: 31).
Di beten
Buin kapikpik pada sibakin
Padasan nak cenik pada ibuk mangempok
Anteng macanda ngajak timpalné saling sogok
Ngelésang Bungan cengkéh uling bantang cenik
Kapilpil lan kampihang
Jemuh menék tuun di langgatan
Kanti layu
Kanti tuh
Untuk menutup ulasan saya kali ini, saya akan mengutip bait terakhir dari salah satu puisi yang menjadi favorit saya dari 100 puisi yang ditulis oleh Érkaja Pamungsu. Puisi ini berjudul Lahru Tan Pegat (hal: 39). Kutipan sebagai berikut.
Ulian pongah
Gerut kayu ngantos ka akah
Pelut isin alas pakpak kanti telah
Énteb urek pang kanti benyah
Yén sube telah mara nyumunin malajah
Puisi ini menggambarkan realita kehidupan manusia hari ini yang terlalu congkak bersikap diatas alam yang menghidupinya. Melakukan eksploitasi secara berlebih demi keuntungan kelompok saja tanpa diimbangi dengan berbagai kegiatan merawat alam. Manusia hari ini terlalu dimanjakan dengan apa yang disediakan oleh alam tanpa menyadari bahwa kekayaan alam ini sejatinya akan habis suatu saat nanti, dan manusia pun akan termangu, bingung melakukan apa untuk bertahan hidup. Itulah manusia.
Sesungguhnya tidak memerlukan waktu yang banyak untuk membaca kumpulan puisi ini secara penuh satu buku. Namun, untuk menerjemahkan arti yang dimaksud oleh penulis itulah yang memerlukan waktu “meditasi” yang cukup lama. Hal yang membuat buku ini menarik adalah dengan membaca buku ini, kita selaku pembaca secara tidak langsung menelusuri perjalanan hidup sang penulis setidak-tidaknya selama lima tahun kebelakang dan apa saja yang telah penulis lewati dalam kurun waktu tersebut.
Buku yang ditulis menggunakan bahasa Bali ini sangatlah baik untuk menggugah kesadaran generasi muda Hindu untuk kembali mempelajari bahasa Ibu mereka yakni bahasa Bali. Namun, hal ini tentu memerlukan banyak waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, langkah perlahan dengan menggunakan bahasa Bali yang mudah dimengerti bagi saya penting jika ingin memperluas segmentasi penikmat buku ini, sehingga hal ini bisa saya jadikan masukkan utama dalam ulasan saya.
Hal tersebut saya sampaikan dikarenakan generasi muda masih teramat malas untuk berimajinasi atau ber”abstraksi” terhadap suatu fenomena dalam hal ini adalah tulisan (karya sastra). Tetapi, sebagai debutnya sebagai penulis, Eriadi mampu untuk merangsang pemuda lainnya untuk bersemangat dalam membangun budaya literasi, setidaknya membangun dalam dirinya sendiri. Saya tunggu karya selanjutnya untuk kemajuan ekosistem literasi di Bali. [T]