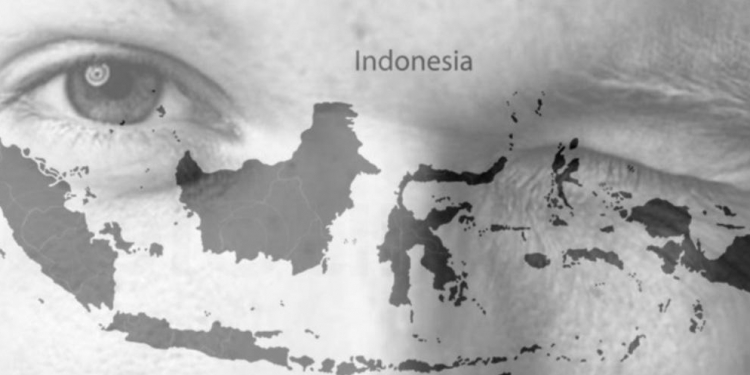SABTU hingga Minggu, 1-2 September 2018, kami, Keluarga Besar Jurusan Pendidikan Sejarah, Undiksha Singaraja, mengadakan Ramah Tamah Jurusan atau biasa disebut “Clio Anjangsana” yang berlokasi di Monumen Puputan Jagaraga, Desa Jagaraga Kecamatan Kubutambahan, Buleleng-Bali.
Dipilihnya tempat ini sebagai lokasi ratam tentu dilatarbelakangi spirit bahwa tanah tempat kami berpijak itu adalah saksi bisu perang yang dalam buku sejarah lokal disebut “perang heroik” melawan penetrasi Belanda. Di Bali sendiri secara keseluruhan hanya terdapat tiga perang puputan, Puputan Jagaraga salah satunya, sisanya Puputan Badung 1906 dan Puputan Klungkung 1908. Pasca Puputan Klungkung, secara de facto dan de jure Belanda telah berhasil menguasai Bali secara keseluruhan.
Kegiatan awal mahasiswa baru Jurusan Pendidikan Sejarah di tahun 2018 yang berjumlah 26-3 (3 orang mengundurkan diri) orang ini adalah “lintas alam” dengan menyusuri petak-petak sawah dan kebun milik penduduk dan dibagi menjadi empat pos. Di setiap pos, para panitia telah siap dengan masing-masing tantangan. Tujuan kegiatan ini tidak lain adalah melatih kerjasama, dan lebih dari itu adalah usaha membaurkan atau sederhananya mengakrabkan senior dengan junior, adik tingkat dengan kakak tingkat.
Kira-kira pukul 20.00 WITA, saya telah tiba di lokasi ratam. Kegiatan sarasehan setelah lintas alam pada siang harinya terpaksa tidak saya ikuti sampai tuntas karena harus mengajar. Saat itu, acara spontanitas kesenian telah usai dan tengah berlangsung kegiatan “nonton bareng” film dokumenter Puputan Jagaraga. Momen malam minggu menambah animo peduduk untuk meramaikan nobar yang digelar sebagai hasil kerjasama Jurusan kami dengan Badan Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Adanya aktivitas dagang kaki lima menyebabkan lokasi ratam yang ramai lalu lalang penduduk menjadi lebih mirip “pasar malam” ketimbang nobar.
Pukul 21.00 WITA, kegiatan nobar usai. Satu persatu penduduk mulai meninggalkan lokasi ratam meski beberapa muda-mudi masih terlihat bergerombol. Saat itu saya sedang duduk santai di pendopoan, ditemani sebuah gitar, kopi pahit tanpa gula dan ubi rebus. Sesekali saya melempar guyonan kepada mahasiswa di sebelah yang ikut ngumpul. Beberapa yang lain, terutama mahasiswa “veteran” (semester lawas) datang menghampiri sekedar salim dan basa basi menanyakan kabar.
Awalnya situasi masih wajar, lalu berubah riuh setelah secara tiba-tiba salah seorang mahasiswa memutar lagu “genjer-genjer”. Kontan saja hal tersebut menimbulkan kegaduhan. Namun justru dari kegaduhan itulah diskusi singkat saya dengan beberapa mahasiswa di lokasi ratam berlangsung hingga pagi dan mengilhami tulisan ini.
Di masa Orde Baru, lagu genjer-genjer diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia dan menjadi musuh bersama yang harus dilenyapkan atas sebuah jargon politik yang mereka bangun sendiri, yakni “bahaya laten komunis”. Saya mewanti mahasiswa bersangkutan agar berhati-hati memutar lagu itu di ruang publik. Sebab, meski hari ini kita telah berada di jaman reformasi, tetapi manusia yang hadir sekarang masih tetap mewarisi mentalitas Orde Baru, termasuk pengkultusan bahaya laten komunisme. Akibatnya akan mudah timbul gesekan-gesekan di dalam masyarakat. Pun demikian dengan ajaran-ajaran “kiri” yang telah dilucuti itu perlahan kehilangan panggungnya dalam memori kolektif bangsa.
Dunia pendidikan Indonesia kontemporer sepertinya masih tetap mentabukan Marxisme (moyangnya komunis) untuk diajarkan di ruang-ruang kelas. Khususnya di dunia kampus yang regime of truth-nya adalah pendidikan, ajaran-ajaran Marx diharamkan. Jangankan mengajar Marx, sastrawan Lekra yang karyanya melegenda seperti Pramoedya Ananta Toer saja jarang disebut. Alih-alih mempopulerkan Tetralogi Pulau Buru yang tersohor itu, mahasiswa saya lebih fasih dengan pemikiran Tere Liye dan Raditya Dika ketimbang Pramoedya.
Kemenduaan sikap dunia pendidikan kita ketika dihadapakan pada marxisme via literatur kiri mendapat sindiran keras dari Max Lane, seorang Indonesianis yang menaruh minat akademis khusus mempelajari Indonesia.
Dalam sebuah acara peluncuran bukunya, “Indonesia Tidak Hadir di Bumi Indonesia” (suara.com tertanggal 2 Juli 2018), bertempat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Ia menyatakan bahwa banyak sarjana maupun kaum muda Indonesia yang fasih berbicara sejarah pemikiran Yunani Kuno hingga Eropa modern.
Namun, ketika membicarakan sejarah bangsanya sendiri, mereka “gagap” atau cuma mengikuti teks-teks historis maupun sastra arus utama sehingga gagal mengenali negerinya sendiri. Max menyebut pemerintah “takut” jika generasi muda mengenal Pram maupun karya-karya sastrawan besar Indonesia lainnya, rakyat akan sadar mengenai perlawanan dan sejarah bangsa yang sebenarnya.
Minimnya pengetahuan mahasiswa tentang sastra “kiri” seperti Pram yang tulisannya berguna membaca nasionalisme Indonesia sejalan dengan ketidaktahuan mereka terhadap Indonesianis “kiri” yang tulisan-tulisannya sempat dibredel di era Orde Baru. Benedict Anderson misalnya, merampungkan “imagined communities” di tahun 1983 dan dicetak ulang di tahun 1991.
Ketakutan Orba terhadap bertumbuhnya sikap kritis melalui bacaan “kiri” membuat buku itu dilarang beredar meskipun setting nya Vietnam. Penulisnya pun sempat mendapat pencekalan. Seperti halnya Marx yang menulis Das Capital dengan setting Inggris Raya tetapi sebenarnya ditujukan utuk menyentil bangsanya, Jerman, begitu pula yang dilakukan Ben, setting Vietnam hanya metafora sosial untuk menyentil nasionalisme Indonesia yang dianggap “sakral” dan “suci” itu, namun memiliki kerapuhan-kerapuhan di dalamnya.
Ben menawarkan suatu gagasan pokok untuk menjelaskan fenomena nasionalisme. Mengapa orang yang belum pernah bertemu bisa merasakan nasib yang sama, bersaudara. Dalam kasus Indonesia, pemikiran Ben bisa dipakai untuk menelusuri bertumbuhya nasionalisme Aceh, nasionalisme Jawa, nasionalisme Borneo, dan nasionalisme Celebes menjadi “nasionalisme Indonesia”. Padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya.
Pada tahap ini Ben menyatakan bahwa karena rasa persaudaraan Indonesia itu tidak bisa dialami secara langsung maka harus dibayangkan terlebih dahulu. Ben menyebut kapitalisme cetak seperti koran, majalah dan buku sastra yang baru mucul pada akhir abad XIX sebagai pihak yang paling bertanggung jawab mendorong sesuatu yang dibayangkan itu menyeberangi batas etnik, agama dan ras. Meski kemudian Ben juga menawarkan alternatif lain seperti kehadiran transportasi massal, namun perhatian terbesarnya adalah media cetak.
Dengan mengarahkan perhatian ke media cetak sebagai arus utama pembentuk nasionalisme Indonesia, Ben menyindir anakronisme Yamin dalam bukunya “6000 Tahun Sang Merah Putih” (terbit 1958), bahwa identitas nasional Indonesia bukan sesuatu yang alamiah melainkan konsep baru yang dapat dibayangkan melalui kehadiran teknologi cetak sebagai pengedar gagasan bangsa sekaligus bukti untuk memungkinkannya.
Aktualisasi teknis pemikiran Ben lebih lanjut dikembangkan oleh Rudolf Mrazek dalam bukunya “The Engineers of Happy Land. Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni”. Tulisan Mrazek ini ingin menunjukkan adanya penanda modernisasi dalam masyarakat Hindia Belanda. Kata-kata teknologi yang digunakan lebih mengacu pada sekumpulan budaya identitas dan bangsa.orang-orang di Hindia Belanda merasa “gagap” tekonologi baru. Ketika menjumpai teknologi yang tidak biasanya, mereka bergerak, berbicara dan menulis dengan cara memasuki prilaku dan bahasa mereka. (T)