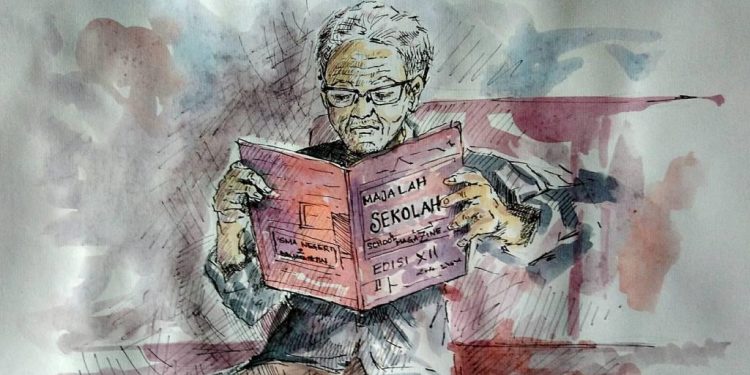KAWAN saya, seorang aktivis perempuan, mengeluhkan berita-berita di media massa yang menurut dia menyudutkan perempuan. Pemberitaan kasus pemerkosaan dan penangkapan perempuan pekerja kafe misalnya. Judul berita ditulis dengan kata-kata yang heboh seperti “Gadis di Bawah Umur Dijos” atau “Cewek Kafe Diciduk”.
Bagi teman saya pemberitaan tersebut bias jender, merugikan perempuan. Perempuan digambarkan sebagai barang mainan atau kriminal, yang dengan gampang “dijos” atau diciduk aparat. Maka itu dia sangat setuju ketika salah satu kelompok media di Bali mengadakan pelatihan kepada para wartawan (yang kebanyakan laki-laki) agar lebih peka jender sehingga pemberitaan mengenai perempuan tidak malah memposisikan perempuan sebagai objek seksual atau penyebab sebuah kejahatan.
Saya memahami kegalauan kawan saya. Budaya patriarki, budaya yang menganggap laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan memang tidak gampang dihilangkan begitu saja. Semenjak dini dalam pelajaran menulis di sekolah dasar kita telah diajarkan bahwa laki-laki (bapak) adalah sosok pekerja luar rumah, pencari nafkah keluarga dan perempuan (ibu) adalah pekerja domestik yang hanya bertugas menanak nasi dan memasak di dapur. Pemahaman yang ditanamkan sejak usia dini ini secara tak langsung membentuk pola pikir kita, bahwa laki-laki adalah makhluk kelas satu dan perempuan adalah mahkluk kelas dua. Apalagi negara kemudian melegitimasi pemahaman tersebut.
Saya Sasaki Shiraishi, antropolog asal Jepang dalam bukunya yang berjudul “Young Heroes; The Indonesian Family In Politics” diterjemahkan menjadi “Pahlawan-Pahlawan Belia; Keluarga Indonesia dalam Politik” (Ajidarma, 2001) menulis bahwa Indonesia pada masa Orde Baru adalah dunia koneksi yang maha besar. Dunia koneksi ini dibangun berdasar gagasan keluarga.
Dalam dunia koneksi ini, hanya ada satu hubungan hierarkis: hubungan bapak-anak. Indonesia mengukuhkan kemerdekaannya dalam revolusi gaya Indonesia, ketika si anak bangkit melawan bapaknya. Orde Baru diawali dengan datangnya bapak yang baru, Soeharto, dalam kontra-revolusi melawan hubungan bapak-anak yang revolusioner demi mempertahankan kebahagiaan keluarga.
Apa yang dikemukakan Shiraishi sangatlah menarik. Pencitraan bapak sangatlah kental. Secara politis bapak adalah pusat segala. Bapak perlu dihormati karena bapak-tahu-segala. Shiraisihi menulis, para pemimpin atau bos berusaha keras menghidupkan citra bapak sebagai seorang ayah yang penuh perhatian sekaligus mampu memenuhi harapan tanpa batas anak-anak atau bawahannya.
Seperti kita saksikan sekarang ini, menjadi orang tua itu sama dengan memanjakan tanpa syarat. Bapak harus bermurah hati dan melindungi keinginan anak-anaknya, sebaliknya, anak-anak harus menerima apa yang diberikan oleh bapak dengan rasa hormat dan terimakasih. Karena itu, seorang bos, baik di pemerintahan ataupun swasta, harus menyeimbangkan perannya sebagai seorang eksekutif yang bertanggungjawab atas jalannya birokrasi modern, dan sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak dan memelihara organisasi keluarga mereka agar bahagia dan harmonis.
Saya teringat Shiraishi ketika karena urusan pekerjaan saya mesti keluar-masuk kantor pemerintahan dan takjub melihat orang-orang yang begitu hormat (kadang berlebihan) pada atasannya, pada sosok bapak yang kebetulan mengepalai bidang tertentu pada departemen tertentu. Ah, Bapak! (T)