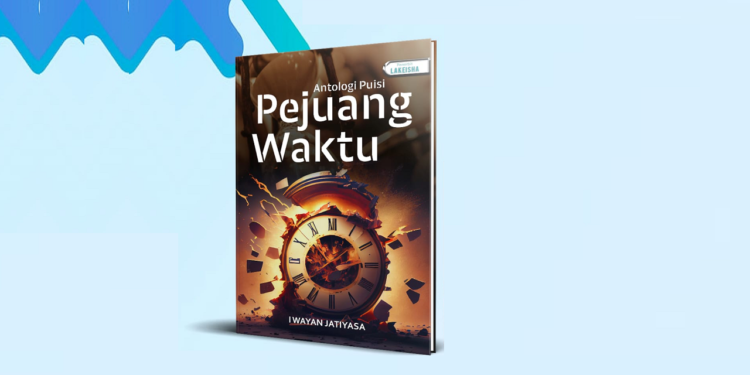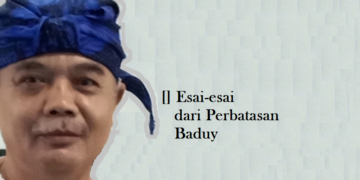ANTOLOGI ini memuat 91 karya. Dari kata-kata penulisnya, I Wayan Jatiyasa, seorang dosen di STKIP Agama Hindu, Kota Amlapura, menunjukkan bahwa sumber puisi-puisinya adalah pengalaman. Terutama di dunia kerjanya selaku dosen. Tidak dapat ditampik lagi jika pendekatan mimetik dan ekspresif dapat digunakan sebagai metode membaca karya-karya ini.
Puisi selalu bersentuhan dengan pengalaman sebagai mimesis yang merupakan keniscayaan abadi dalam sastra dan seni. Pemilik pengalaman ini tiada lain adalah sastrawan yang lewat media sastra, mengekspresikan semua itu secara indah. Maka puisi tidak bisa dipahami sebatas imajinasi. Puisi adalah konstruksi ekspresif penyair atas hal-hal dalam hidup yang dijumpai. Pun 91 puisi dalam antologi Pejuang Waktu yang tengah ada di tangan pembaca ini. Setidaknya hal ini diakui oleh I Wayan Jatiyasa, seperti pada kutipan bait berikut.
Aku belajar menulis bukan untuk sombong
Tapi untuk menemukan diri, mengekspresikan jiwa yang merindu
Hanya ingin diingat dalam lembaran waktu sebagai bagian dari alam semesta
Yang pernah mencoba menyampaikan cinta, kebenaran, dan keindahan lewat kata
(puisi ”Bukan Sombong!”)
Sederetan antologi: Karena Kau, Hujan: Tentang Rasa yang Menghujam, Beranda, Ungkapan Rasa dalam Kata untuk Ibu, Rumah, adalah bukti produktivitasnya sebagai penyair mengingat seluruh karya ini ditulis pada tahun yang sama, 2019. Lilin Harapan yang ditulis tahun 2022 menunjukkan bahwa I Wayan Jatiyasa konsisten berkarya di bidang sastra puisi. Di samping itu, tetap pula menulis teks-teks baku akademik dan book chapter. Teks-teks yang terakhir tentu saja sangat pragmatis bagi seorang dosen. Lalu puisi? Berhubungan dengan pragmatisme ekspresif!
Produktivitas dan apa alasan seseorang menulis, entah puisi atau teks lainnya, tidak selamanya karena keinginan untuk mendapat sambutan pembaca. Dari aspek ini, pandangan yang mengatakan bahwa peranan pembaca sangat penting bagi penyair adalah omong kosong. Pada mulanya adalah hasrat untuk mengungkapakan pikiran atau rasa dalam hening lewat huruf, tinta, dan kertas (atau kini layar). Pada zamannya juga terjadi secara lisan. Orang-orang di sekitar pun dengan sigap menangkapnya. Dengan cara ini sastra yang semula lisan diadopsi oleh masyarakat. Sastra pun menjadi milik kolektif. Sastra telah diadopsi. Ia kini menemukan orang tua angkat. Masyarakat!
I Wayan Jatiyasa memperpanjang contoh alamiah bahwa menulis tidak ada hubungannya dengan pembaca. Pembaca tidak memiliki sumbangan apapun bagi penulis atau sastrawan. Karena itulah, banyak sekali karya-karya berbagai genre lahir secara alamiah dari para penulis hebat atau penulis-penulis yang tidak bernama jauh di luar target pembaca. Maka menulis untuk diri sendiri mungkin satu alasan yang paling benar dan hebat. Untuk kesekian kalinya Gao Xingjian betul. Ia menyatakan dalam pidato pengantar anugerah Sastra Nobel yang diterimanya, “Saya hanya menulis untuk diri saya sendiri”.
Hal ini dapat terjadi dalam dunia menulis karena tidak diperlukan lawan. Atau jika itu terasa penting, maka Anne Frank menciptakan lawan ”bicara” dalam tulisan berupa buku harian perangnya, yaitu Kitty. Keadaan tidak dibutuhkannya lawan yang serta-merta atau simultan dalam ruang waktu, memberi peluang bagi siapapun untuk menulis terus. Hal ini kembali untuk menegaskan kalau pembaca sama sekali tidak dibutuhkan oleh para penulis.
Yang menarik pembaca ke dalam relasi pengarang dan karyanya adalah kaum kapitalis yang menanam modal di sektor ekonomi industri penerbitan buku. Mereka mengeksplorasi buah pikiran atau buah pena penulis untuk dijual. Tindakan ini murni komersil namun ditutupi dengan berbagai alasan kebudayaan. Kelak, cara-cara kaptalistik inilah yang selalu menjadi takaran atas sukses dan tidaknya karya seseorang. Pembaca dijadikan ukuran kualitas. Penerbit dengan jemawa mengklaim bahwa pihaknyalah yang berjasa menemukan sastrawan hebat. Jujur, di luar campur tangan penerbit, sastrawan hebat telah lahir jauh-jauh hari sebelumnya di dalam masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan banyak sastrawan tidak berlebel pasar (mayor) memiliki dan menyumbang karya yang hebat.
Sebelum membicarakan isi, dari beberpa puisi dalam Pejuang Waktu ini, adalah soal kuatnya konvensi baris dan bait dalam pilihan tipologi atau format penulisan yang dipilih oleh I Wayan Jatiyasa. Kecuali ”Ruanganku” (satu bait dua baris) dan ”Mahasiswa Idaman” (ditulis seperti tipe ”Tragedi Winka dan Sihka” karya Sutardji), seluruh puisi dalam antologi ini disusun dengan tipologi puisi lama. Ia konsisten dengan pembagian bait dengan empat baris. Format penulisan atau pengetikan ini adalah sebuah konvensi paling kuat dan paling populer dalam puisi lama Nusantara, terutama identik dengan pantun dan syair.
Hampir seluruh puisi ini memilih gaya prosa. Gaya prosa adalah paragrafis yang ditulis dalam pola bait. Untuk mengganti bentuk paragraf dalam prosa. Bentuk atau tipe rupa penulisan sama sekali tidak mereduksi suasana teks prosa. Teks prosa yang telah ditulis dalam bentuk puisi (bait dan baris pendek) tetap menyimpan rasa, jiwa, dan suasana prosa. Artinya, bentuk prosa atau puisi tidak pernah tunduk pada isi. Secara visual barangkali, “ya” tapi secara tekstual, tidak! Hal ini tentu ditopang oleh narasi yang cair, nyaris transparan, dan mengalir. Keadaan ini bisa dihubungkan dengan Pengakuan Pariyem, karya Linus Suryadi, sebagai referensi tekstual. Linus menggunkan tipologi puisi untuk menulis prosa Pariyem. Puisi-puisi dalam antologi ini juga realistis dan jujur. Namun terasa sangat lembut sehingga menghadiahi pembaca dengan suasana nyaman.
Sedemikian banyak tema yang ditulis dalam rupa teks puisi oleh I Wayan Jatiyasa, sejalan dengan konsep yang juga dijadikan kata-kata dalam judul ”waktu”. Hal ini membenarkan dua pendekatan M.H. Abrams, mimetik dan ekspresif. Dengan melihat tema-tema puisi yang telah ditulis oleh I Wayan Jatiyasa, yang sebagian besar berhubungan dengan dunia kerja, profesi (dosen), karier, mahasiswa, dan kampus; adalah akibat peristiwa mimetika atau mimesis. Puisi-puisi seperti:
Lembur, Menulis, Tuntutan Profesi, Suka Cita, Rasa Hormat, Adu Domba, Penjara Kata, Jabatan adalah Peluang, Beban, Benci dan Cinta yang Menggantung di Kelas, Ulang Tahun Kampus, Dosen, Helm ku Hilang!, Ibu dan Calon Mahasiswi Pengejar Mimpi, Motor Tua, Kampus Dambaan Mahasiswa, Ruanganku, Mahasiswa Idaman, Mahasiswa Hebat, Simfoni Kebersamaan di Kampus, Beasiswa Malang, Asa Dosen Doktor, Kasih Kuliah Kerja, Upacara Saraswati, Kampus Berseri , Demi Profesi, Tinggalkan Anak-Istri Publikasi, Mengais Karir: Pejuang Perguruan Tinggi, Kampus yang Hilang, Pegawai dan Handphone, Purnabakti :Pegawai Sejati, Kekerasan Seksual, Perjalanan Karir, Diam dalam Ratapan, Pengabdian Tak Berbalas, Mau Dibawa Ke Mana Kampus Ini?, Nasib Dosen Kini , Naik Jabatan, Dilema Kampus, Temaram Dosen, Tipuan Atasan, Kerja Tak Bertepi , Babu, Aku dan Rinai Hujan;
yang jumlah paling banyak di dalam antologi ini adalah berhubungan kuat dengan kehidupan penyairnya. Hal ini diperkuat oleh biografi I Wayan Jatiyasa (pada bagian akhir dari antologi ini). Sekaligus dengan pendekatan ekspresif, dapat dijelaskan bahwa puisi-puisi yang terjadi secara mimesis itu adalah ekspresi pengalaman I Wayan Jatiyasa sendiri, selaku dosen di sebuah kota di ujung timur pulau Bali, Amlapura, tempat kampusnya berdiri, dimana ia selaku dosen.
Karena sebagai teks yang diikat oleh hukum sastra yang fiksi dan imajinatif, hubungan antara isi sastra (puisi) dengan penyairnya tabu diungkapkan. Padahal M.H. Abrams telah memberi ruang pendekatan ekspresif. Hubungan yang erat dan niscaya antara sastra dan sastrawannya. Dengan pendekatan ekspresif, pembahasan ini menegaskan bahwa puisi-puisi ini adalah berhubungan erat dengan pengalaman hidup I Wayan Jatiyasa. Seluruh puisi ini adalah konstruksi ekspresif I Wayan Jatiyasa. Bahan-bahan puisi didapat dengan menggunakan metode mimesis. Dengan kedua pendekatan ini terjelaskan hubungan konstelatif atas tiga spot: realitas, penyair, dan karya. Kejujuran puisi sebagai karya yang berakar pada suatu realitas dibangun lewat pendekatan mimesis.
Di luar metode mimesis dan konstruksi ekspresionistik itu, yang menarik adalah produktivitas I Wayan Jatiyasa yang sangat tinggi. Hal ini membutuhkan konsistensi yang andal dan kepekaan menangkap berbagai kondisi sehari-hari (nyaris komprehensif). Pada periode karya berikutnya, sikap seleksi tema puisi perlu dilakukan. Konsekuensinya akan mengurangi jumlah puisi yang dihasilkan. Secara ekspresif hal ini mungkin akan menjadi gangguan bagi I Wayan Jatiyasa. Tetap konsisten menulis sebanyak mungkin namun untuk kebutuhan publikasi atau penerbitan buku, perlu dilakukan pilihan karya. (Di sini) dibutuhkan editor atau tim kurator karya. Namun bisa dilakukan sendiri! Memang salah satu kerja penyair adalah memilih topik karya lewat pertimbangan tertentu.
Di samping puisi-puisi mimesis dunia kerja dan berbagai elemen atau infrastruktur sosial yang berkaitan dengannya, memang masih ada peluang ditemukan tema-tema lain meskipun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang tema dunia kerja, seperti dua puisi yang bernada ode atau pujian (”Pejuang Waktu” dan ”Tanda Jasa”). Walaupun I Wayan Jatiyasa menggunakan fokus terbesarnya pada mimesisme dunia kerja, masih sayang jika dilewatkan puisi-puisi dengan tema romantisme diri (”Berdamai dengan Diri”, ”Syukur”, ”Apa Salah pada Diri yang Kurang?”, ”Dalam Kesunyian Aku Bersandar”, ”Ambisius”, ”Derita dan Bahagia”). Puisi-puisi ini adalah teks yang mengarah ke dalam muara diri dan memiliki kemungkinan menjadi ruang refleksi. Hal ini mungkin lebih spesifik dapat dipahami dengan psikoanalisa (Sigmund Freud). Waktu adalah dunia besar. Di dalamnya I Wayan Jatiyasa hidup dalam tiga tataran kesadaran: id, ego, dan superego. Hal ini dapat dijadikan metode untuk melakukan kategori atas seluruh puisi dalam Pejuang Waktu. Terdapat puisi-puisi bawah sadar (emosionalisme diri); puisi-puisi tataran ego yang terjadi di ruang sosial (profesinya sebagai dosen); dan superego yang melahirkan puisi-puisi kritik pendidikan dan ode bagi gurunya.
Tidak hanya narasi dan suasana prosa yang natural, I Wayan Jatiyasa juga sekali waktu tertarik menulis puisi-puisi bernada kritik yang bisa dikategori puisi pendidikan (”Lulusan dalam Penantian”, ”Biaya Kuliah Mencekik”, ”Akreditasi”, ”Minat Baca, Bangkit!”, ”Kampus Swasta, Nasibmu Kini”, ”Kampus Inspiratif”, ”Mahasiswa yang Tidak Beradab”, ”Melawan Dosen”, ”Kampus: Dulu dan Sekarang”).
Antologi Pejuang Waktu juga diperkaya oleh puisi-puisi dengan tema yang lebih umum, yang dapat dijelaskan sebagai wilayah atau ”ruang” di luar dunia kerja penulisnya, yang di dalam analisis ini diberi kategori puisi dengan tema umum (”Genggam Dunia”, ”Bukan Sombong!”, ”Ikhlas Beramal”, ”Perdebatan”, ”Balada Toilet”, ”Kolam yang Merana”, ”Prestasi dan Sukses”, ”Kebahagiaan Palsu”, ”Kotoran Anjing”, ”Sandiwara Sedekah”, ”Apa kabar Perpustakaan?”, ”AI”, ”Nafsu”, ”Ladang Koruptor”).
Tema-tema lain yang juga masih menjadi jangkauan ruang dan waktu antologi Pejuang Waktu adalah hubungan antarmanusia (”Aku dan Kamu tak sama”, ”Kamu Berkelas, Aku yang Tertindas”, ”Bawahan Bukan Jajahan”, ”Mana Hormatmu Atasan?”); puisi-puisi emosionalisme (”Frustrasi”, ”Buat Apa Susah”, dan ”Bayangan Luka di Relung Jiwa”); puisi puisi pemikiran (satu-satunya puisi dengan teman emansipasi wanita); serta masih ada ruang dan waktu bagi puisi cinta (”Jangan Tutup Dirimu”, ”Cinta di antara Profesi”, ”Cinta Semu”, ”Balada Cinta Dosen dan Mahasiswa”, ”Cinta di PKKMB”). [T]
[][][]
BACA esai-esai lain dari penulis I WAYAN ARTIKA