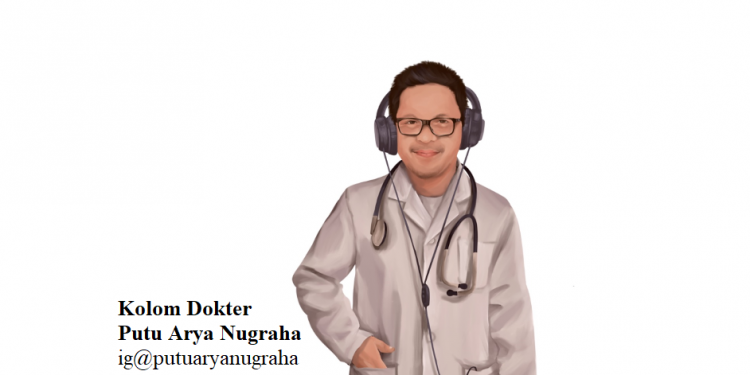“Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.”— (Sumpah dokter Indonesia No ke-11)
Istilah cuci otak selalu menarik. Entah itu pada makna harfiahnya maupun sebagai sebuah frase yang hari-hari ini menjadi populer sebagai satu tindakan medis yang tentu saja, kontroversial. Dalam makna harfiahnya, cuci otak kita ketahui merupakan sebuah proses yang tak biasa-biasa saja dan hasil prosesnya itupun acap kali luar biasa dan mencengangkan.
Istilah ini populer dalam dunia radikalisme-terorisme atau dalam kisah-kisah spionase. Akan mudah kita pahami, orang yang biasa-biasa saja takkan pernah menjadi seorang radikal, teroris atau agen rahasia. Ia perlu dicuci otaknya supaya memenuhi syarat.
Artinya, harus ditanamkan gagasan-gagasan baru yang ideologis, disebut juga indoktrinasi, untuk menggeser keyakinan lamanya yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebuah gerakan. Jika program cuci otak ini sukses, akan lahir individu-individu yang bersedia melakukan tindakan-tindakan ekstrim di luar nalar masyarakat pada umumnya dan tentu saja dampaknya pun tak main-main.
Ini bukti bahwa pikiran manusia sangat berbahaya walau ia tak tampak dan tak dapat dirasakan. Profil fisik manusia yang secara umum sama saja, terdiri dari kepala, badan, tangan dan kaki, dapat saja melakukan tindakan yang sangat beragam berkat kendali pikiran masing-masing. Kendali dari ruang gelap yang tak pernah dikenali.
Apakah ini sebuah kebetulan belaka, faktanya “cuci otak” yang dilakukan oleh dr Terawan Agus Putranto (TAP), juga telah menjadi polemik riuh saat ini. Polemik kian memanas saat TAP, dijatuhi sanksi pemecatan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akibat pelanggaran etik yang telah dilakukannya, atas rekomendasi dari sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).
Bagaimana kita melihat peristiwa ini? Saya akan berpijak pada prinsip-prinsip obyektifitas dalam menulis isu polemik ini. Pada artikel sebelumnya, saya pun pernah menulis sebuah otokritik terhadap IDI, organisasi profesi di mana saya bernaung.
Cuci otak ala TAP, memang menarik, sebab pada dasarnya hal itu merupakan satu prosedur medis biasa yang sudah diaplikasikan sejak lama, kemudian dimodifikasi oleh TAP. Prosedur medis tersebut dikenal sebagai Digital Subtraction Angiography (DSA) yang pada awalnya merupakan sebuah metode diagnosis, oleh TAP dimodifikasi sebagai sebuah terapi.
Yang dilakukan dari prosedur itu adalah, memasukan kateter (selang kecil khusus) ke dalam pembuluh darah otak disertai dengan penyemprotan zat warna yang kemudian dari pencitraan X-ray dapat dinilai keadaan dinding dalam pembuluh darah otak tersebut. Pada saat prosedur itu dilakukan, dilakukan pula penyemprotan satu obat bernama heparin untuk mencegah terjadinya pembekuan darah selama prosedur dilakukan.
Dari prosedur DSA tersebut, akan diketahui kemudian apakah pasien mengalami stroke, kelainan pembuluh darah lain atau sebaliknya pembuluh darahnya normal-normal saja. Itu kemudian menjadi dasar bagi seorang dokter ahli saraf (neurolog) untuk memberikan rencana terapi kepada pasien tersebut.
Nah, TAP kemudian mempromosikan prosedur ini sebagai satu pengobatan stroke kepada publik. Memang cukup banyak pasien yang memberikan testimoni, bahkan dari kalangan orang-orang penting dan tokoh nasional, merasa “lebih baik” setelah menjalani DSA atau “cuci otak” tersebut.
Namun ada beberapa hal mendasar yang harus publik ketahui. Pertama-tama, penyakit stroke sendiri adalah kompetensi seorang dokter ahli saraf, sementara TAP adalah seorang dokter ahli radiologi yang mendalami radiologi intervensi. Jadi, betulkah pasien-pasien yang di-”cuci otak” itu memang penderita stroke?
Kedua, prinsip dasar sebuah terapi medis adalah kedokteran berbasis bukti (KBB). Jadi bukan hanya atas dasar teori & testimoni. Sebab harus kita ketahui pula akan sebuah fenomena yang disebut sebagai efek plasebo yaitu suatu efek sugesti dari zat yang sebetulnya tak berkhasiat sama sekali. Ini dapat semakin mungkin dirasakan, apalagi kalau ternyata pasien tersebut memang bukan penderita stroke sebenarnya.
Sudahkah dilakukan pencitraan pembuluh darah pasien, baik sebelum dan sesudah “cuci otak”? KBB menuntut rangkaian riset uji klinis baku sebelum satu prosedur medis dapat disepakati (konsesus) oleh perkumpulan dokter ahli menjadi sebuah pilihan terapi. Ini semua demi melindungi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip praktek kedokteran yang baik.
Dalam riset tersebut, tidak hanya efektivitas terapi yang dipublikasikan, pun tingkat kegagalan dan efek samping yang ditimbulkan terapi tersebut harus disampaikan. Sebuah prinsip kejujuran dan kerendahan hati sedari awal.
Ketiga, TAP mempromosikan prosedur terapi yang menurut IDI belum memenuhi kaidah-kaidah KBB. Dalam etika praktek kedokteran, bahkan prosedur terapi yang telah disepakati menjadi sebuah standar terapi oleh perkumpulan dokter ahli pun, tetap tidak diizinkan untuk dipromosikan secara komersil kepada masyarakat.
Keempat, dalam perkembangannya, IDI telah memberikan ruang kepada TAP untuk melakukan klarifikasi atas apa yang dipertahankannya sebagai sebuah prinsip yang kemudian dikenal sebagai “Terawan Theory”, namun hingga kini TAP belum menanggapinya. Tentu saja jika TAP bersedia, beliau harus membawa data-data ilmiah sesuai KBB yang dapat menguatkan teorinya tersebut yang menjadi dasar terapi “cuci otak”-nya.
Kira-kira bagaimanakah akhir drama ini? Masih ada waktu yang cukup bagi TAP untuk guyub dengan organisasi yang menaunginya guna mencari titik temu. Saya meyakini, jika metode ini kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai KBB, IDI pasti akan siap membantu penelitian sesuai kaidah, terkait metode terapi kontroversial ini.
Untuk masyarakat luas, sudah sepatutnya selalu menguatkan literasi terkait isu-isu hangat agar menilai secara bias atau keliru tidak terlanjur menjadi budaya di era yang sudah sangat modern ini. Apalagi sampai menjadi korban cuci otak, hehehe! [T]