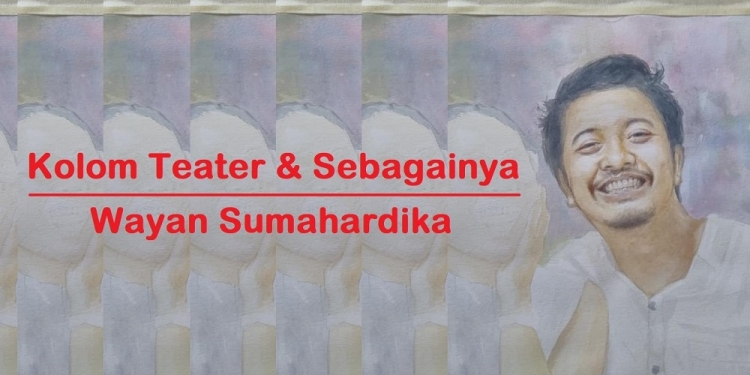Yen bendan zamane suba maju, raga sing perlu buin ngae penjor ajak banten. Tinggal klik dogen tombole, sruuutt! Pesu be penjor pedidi. Klik bin cepok, casss! Pesu be makejang soroh bantene. Cara hologram.
Yen pedanda ngantebang banten di pura, sing perlu ngeleneng buin. Pedanda cuma negak dogen. Klik tombol on di tape, pesu be puja Tri Sandya. Pedanda tinggal santai, ngeroko gen be klepus-klepus.
Pokokne aluh yen zaman suba maju!
Bagi orang Bali kebanyakan, saya yakin pernah meguyu seperti guyonan di atas. Tentang Tri Sandya, pedanda, hologram, dan kemajuan-kemajuan zaman yang menyertai, tentunya dengan beragam bentuk dan variasi tingkat lucu masing-masing. Pada masa SMA, saya dan kawan-kawan kerapkali berseloroh, membayangkan kemajuan zaman akan hadir untuk mempermudah kehidupan sehari-hari.
Seperti apa bentuk kemajuan itu, bagaimana rupanya, tak pernah terbayang jelas sejatinya di kepala. Ia begitu jauh. Begitu abstrak. Pun dengan definisi terhadap kemajuan itu sendiri. Tak pernah benar-benar kami pahami artinya. Yang terbayang tentang kemajuan hanyalah gambaran digital dengan sejumlah tombol yang sekali pencet, membuat segalanya jadi lebih sederhana dan efisien.
Entah kenapa, candaan akan kemajuan zaman cenderung dilayangkan tak jauh dari soal adat dan agama. Seingat saya, sedikit sekali guyonan tentang kemajuan zaman disangkutpautkan pada soal kemudahan mengerjakan PR misalnya. Mengapa kami tak membayangkan sebuah tombol yang sekali klik, PR akan selesai dengan mudah? Dengan sekali klik, akan muncul bakso, sosis, mie ayam, atau nasi bungkus di kelas tanpa harus repot ke kantin saling berdesakan? Padahal jika mau jujur, realitas sekolah dalam konteks kami masa itu sesungguhnya jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan persoalan adat dan agama, yang justru amat jarang kami ikuti apalagi kami pahami.
Adat dan agama juga kerapkali beririsan dalam konteks pentas teater. Pada banyak kecenderungan pentas di Bali, adat dan agama menjadi tema central cerita, bisa juga menjadi bahan sempalan. Menyentil kehidupan beribadat dan beragama masyarakat atau mempergunakannya sebagai bahan petuah. Kecenderungan ini seolah menyiratkan bahwa persoalan Bali tak boleh jauh-jauh dari adat dan agama. Ada kesan, jika pentas tak memakai framing adat dan agama maka pertunjukan jadi bukan Bali.
Mungkin di sinilah persamaan antara pertunjukan kawan-kawan teater Bali dengan guyonan anak-anak SMA tadi. Seringkali harus merasa dekat dengan adat dan agama. Seringkali gatal untuk berpetatah-petitih atau mengkritisi. Saking khusuknya kita pada adat dan agama, definisi tentang kemajuan zaman misalnya, jadi salah satu gagasan yang dibiarkan mengawang tak maju-maju dari dulu sampai sekarang.
Kemajuan zaman tak pernah dipergunakan sebagai ruang kerja baru dalam menatap kenyataan. Mempengaruhi pola pandang dan lanskap laku hidup manusia. Kemajuan zaman tetap menjadi entitas abstrak, yang naasnya cenderung dilekatkan pada oposisi biner baik buruk. Sebagai sebab goyahnya kehidupan adat dan agama orang Bali. Tak khayal, ada saja kita jumpai cerita-cerita naif semacam kemajuan zaman yang membuat orang tak lagi sembahyang, terjebak dalam perbuatan buruk lalu akhirnya terjerat hukum karma phala.
Dalam konteks penyusunan strategi pertunjukan, kemajuan zaman juga hanya dimanfaatkan sebagai spektakel. Menembakan proyektor bergambar pada backroud panggung, mengganti bentuk pencahayaan lampu sentir menjadi lampu warna-warni, atau mempergunakan teknologi mutakhir lainnya sebagai ornamen akrobatik para aktor di atas panggung. Sementara isi pentas tetap memakai kerangka kerja pertunjukan yang sudah-sudah. Berlandaskan adat agama dengan pola pikir yang sama. Seolah-olah adat dan agama adalah sesuatu yang ajeg. Entitas yang lemah dan lunglai. Maka tugas orang panggunglah yang mesti menegakan dan menjaganya.
Di tengah masa inkubasi corona ini, saat tak ada pentas yang terselenggara, saat masyarakat Bali suba telah gati olah-olahane, adat dan agama justru yang paling cair menyikapi keadaan. Waktunya odalan di Pura Batur, saya dan keluarga tetap bisa nunas tirta, tanpa harus nangkil ke pura. Saat menggelar upacara penguburan, joli tetap bisa diarak tanpa menimbulkan kegaduhan, bahkan di daerah Gianyar beberapa waktu lalu, saya dengar ada acara pengabenan yang digelar menggunakan iring-iringan mobil.
Dalam segala keterbatasannya, adat dan agama dapat serta merta beradaptasi seketika. Menyusun ulang pola kerja dan struktur dramaturgi peristiwa. Dari yang semula berbentuk kolektif, dimana masyarakat harus berkumpul bersama di pura, kini begerak secara estafet, dari pura ke pura, ke bale banjar, lalu ke rumah masing-masing. Dari yang dulunya riuh digelar, kini menjadi begitu sunyi. Atau pada kasus pengabenan di Gianyar yang mempergunakan iringan mobil. Mobil satu dengan lainnya dipertautkan menggunakan bentangan kain putih, seolah menjadi sekumpulan orang-orang yang mengiringi pengabenan. Maka mobil boleh jadi dapat diartikulasikan sebagai tubuh manusia Bali hari ini.
Kenyataan-kenyataan adat dan agama macam ini sangat bertolak belakang dengan yang biasa direpresentasikan pada panggung pertunjukan. Yang sekali lagi, selalu saja menganggap adat dan agama begitu rentan dengan perubahan-perubahan, dengan kemajuan zaman yang menggoyahkan esensi dan kebermaknaan adat dan agama. Benarkah adat dan agama yang lemah? Atau diri kita yang melemahkannya untuk mengaburkan keterbatasan pemahaman akan adat dan agama itu sendiri?
Di masa pandemi, rumah menjadi penjara yang mengekang ruang gerak manusianya. Sementara adat dan agama dengan bebas berkelindan. Lewat siaran televisi, Tri Sandya jadi penggenap hari-hari. Tiga kali sehari. Tetumbenan menonton televisi, pada jeda sejenak Tri Sandya, saya sendiri jadi merasa tengah melakukan Tri Sandya. Bisakah pada keterjedaan yang sejenak itu kita sebut sebagai ibadah? Bisakah kita meyakini bahwa Tuhan tengah berada di televisi, mengamini khusuk tatapan kita pada layar kaca sebagai doa kepada-Nya?
Pelan dan pasti Tri Sandya juga meranggas masuk hingga ke ruang digital. Memenuhi konten-konten media sosial semacam facebook, instagram dan youtube. Bersebelahan dengan tik-tok, youtuber, serta berta-berita yang meng-update berapa banyak yang terpapar dan meninggal karena corona. Tak hanya Tri Sandya, ada pula dharma wacana, piodalan, sampai Beghawad Gita yang jumlah penontonnya bisa mencapai puluhan bahkan sampai ratusan ribu. Yang kini, senantiasa diputar oleh ayah dan ibu sebagai pengisi jeda percakapan mereka yang telah habis.
Pada masa pandemi corona, saat panggung telah kehilangan penontonnya, saat panggung kehilangan kegarangannya mengkritisi dan berpetatah-petitih, saat diri teramat uring-uringan di dalam rumah, adat dan agama lempeng saja keluar masuk media. Saya bayangkan, seorang ida pedanda di suatu griya, kini sedang menyulut rokok klepus-klepus sembari mengontak kleneng Tri Sandya di HP. Sementara saya? Jangankan klepas-klepus, pis meli roko dogen suba tusing ada!
Ulian corona, telah gati suba olah-olahane! [T]
Denpasar, 2020